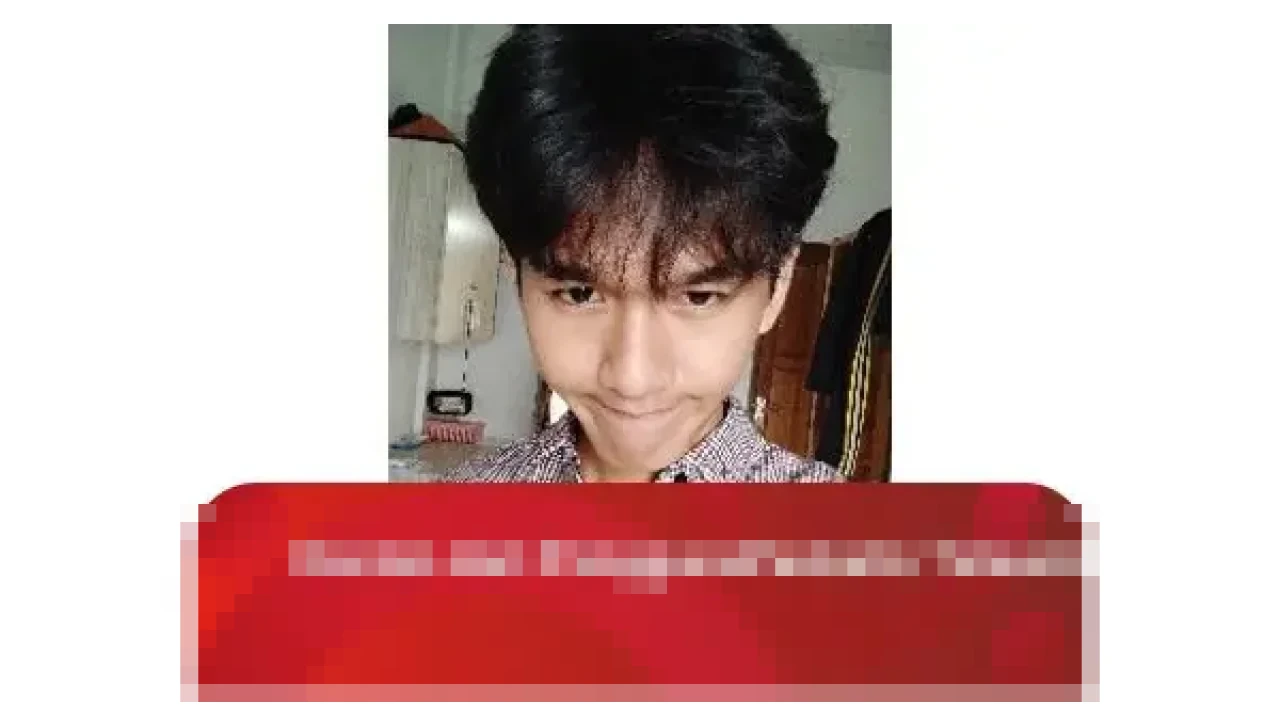Pembicaraan mengenai kesehatan mental kini semakin terbuka di berbagai platform, mulai dari media sosial, ruang akademik, hingga kebijakan publik. Namun, di tengah geliat kesadaran ini, satu realitas penting kerap terpinggirkan: pengalaman emosional pria.
Bukan karena pria tidak memiliki perasaan, melainkan karena sejak usia dini, banyak dari mereka tumbuh tanpa pernah diajari cara mengenali, memahami, dan mengungkapkannya secara sehat. Fenomena ini, menurut Mureks, menjadi akar masalah yang kompleks dalam kehidupan sosial dan personal.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Ketika Tangisan Dianggap Kelemahan: Akar Masalah Sejak Kanak-Kanak
Sejak masa kanak-kanak, banyak anak laki-laki dibesarkan dengan pesan yang seragam dan berulang. Menangis sering dianggap memalukan, sementara mengeluh dinilai sebagai tanda kelemahan. Ekspresi kesedihan kerap dipotong dengan kalimat singkat seperti “jangan cengeng” atau “laki-laki harus kuat.”
Pesan-pesan ini, meskipun terdengar sepele, secara perlahan membentuk hubungan yang rapuh antara pria dan emosinya sendiri. Alih-alih belajar memahami apa yang dirasakan, pria justru dilatih untuk menekan dan mengabaikannya. Emosi tidak dikenali sebagai bagian inheren dari kemanusiaan, melainkan sebagai gangguan yang harus disingkirkan.
Dalam jangka panjang, kebiasaan ini menciptakan jarak, bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri sendiri. Memasuki usia dewasa, jarak tersebut semakin terasa. Banyak pria kesulitan menjelaskan apa yang sebenarnya mereka alami ketika menghadapi tekanan hidup yang kompleks.
Maskulinitas dan Stigma: Menunda Pertolongan Hingga Krisis
Kelelahan emosional sering disamarkan sebagai kesibukan, kesedihan disembunyikan di balik diam, dan kekecewaan berubah menjadi kemarahan atau penarikan diri. Dalam relasi personal, pola ini kerap disalahartikan sebagai ketidakpedulian atau sikap dingin, padahal akarnya lebih dalam.
Budaya maskulinitas yang dominan turut memperkuat kondisi tersebut. Pria diposisikan sebagai penopang kepala keluarga, pengambil keputusan, dan simbol keteguhan. Dalam konstruksi ini, kerentanan tidak mendapat tempat. Pria diharapkan mampu memahami orang lain, tetapi jarang diberi ruang untuk dipahami. Mereka dituntut untuk selalu hadir sebagai solusi, bukan sebagai manusia yang juga bisa goyah.
Akibatnya, banyak pria hanya datang pada bantuan profesional ketika kondisi sudah berada di titik krisis. Berbagai laporan kesehatan mental menunjukkan kecenderungan bahwa pria lebih jarang mencari pertolongan, namun lebih rentan mengalami tekanan yang terakumulasi. Masalahnya bukan pada ketidaksadaran, melainkan pada stigma bahwa mengakui luka batin sama dengan mengakui kegagalan sebagai pria.
Dampak pada Relasi dan Kebutuhan Literasi Emosi
Dalam konteks sosial yang lebih luas, kondisi ini melahirkan kesalahpahaman kolektif. Pria sering dicap tidak peka, tidak komunikatif, atau tidak emosional. Padahal, yang terjadi adalah ketiadaan bahasa emosi yang sehat. Mereka tidak diajari cara menamai perasaan, apalagi menyampaikannya dengan aman. Diam menjadi mekanisme bertahan, bukan pilihan sadar.
Relasi personal menjadi ruang yang paling terdampak. Banyak konflik dalam hubungan bukan lahir dari kurangnya rasa, melainkan dari kegagalan komunikasi emosional. Ketika pria tidak mampu menjelaskan apa yang dirasakannya, jarak perlahan tumbuh. Pasangan merasa diabaikan, sementara pria merasa tidak dimengerti. Lingkaran ini terus berulang tanpa pernah benar-benar disadari akarnya.
Sejumlah pengamat sosial menilai bahwa persoalan ini bersifat struktural. Literasi emosi belum menjadi bagian yang setara dalam proses pendidikan anak laki-laki. Kecerdasan emosional sering dianggap penting bagi perempuan, sementara pria didorong untuk mengasah logika dan ketahanan. Ketimpangan ini melahirkan generasi yang kuat secara peran, tetapi rapuh secara batin.
Memperluas Makna Kekuatan
Mengajarkan pria untuk memahami perasaannya bukanlah upaya melemahkan maskulinitas. Sebaliknya, hal tersebut justru memperluas makna kekuatan itu sendiri. Pria yang mampu mengenali emosinya cenderung lebih stabil dalam mengambil keputusan, lebih sehat dalam relasi, dan lebih siap menghadapi tekanan hidup yang kompleks.
Selama masyarakat masih memelihara anggapan bahwa pria harus selalu kuat tanpa boleh rapuh, luka emosional akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pria akan terus bertahan, tetapi jarang benar-benar pulih. Dan di sanalah persoalan mendasarnya: bukan pada ketidakmampuan pria untuk merasa, melainkan pada ketidaksediaan kita untuk mengajarkan mereka caranya.