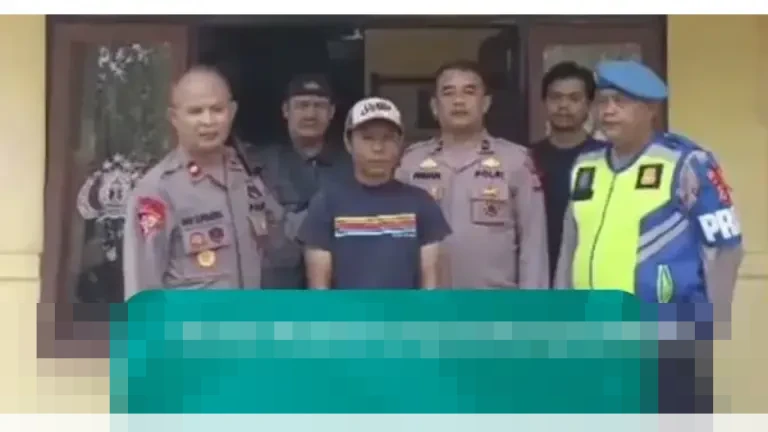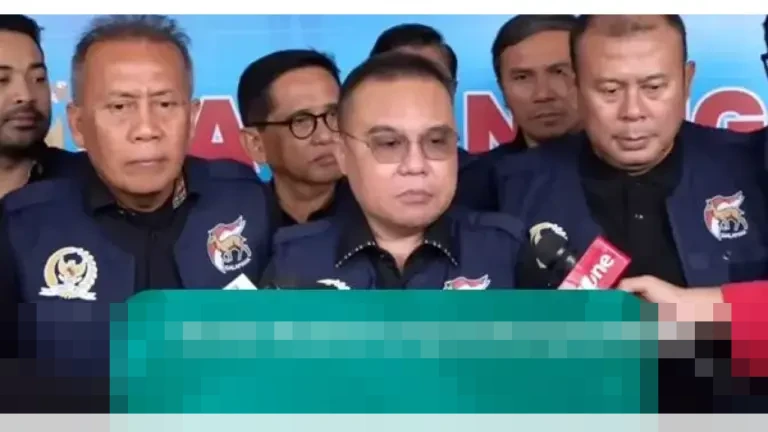Buku, yang seharusnya menjadi jembatan pengetahuan dan wawasan, kini kian sering dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara. Fenomena ini mengindikasikan adanya kecenderungan anti-kritik dan upaya menghidupkan kembali bayang-bayang rezim otoriter yang membatasi kebebasan berpikir, terutama melalui pengekangan kegiatan bedah buku dan diskusi literasi.
Secara universal, buku berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pengetahuan, wawasan, dan gagasan, yang kemudian dimaknai secara subjektif oleh setiap individu. Namun, seiring waktu, tindakan membaca buku justru dianggap sebagai ancaman bagi rezim tertentu. Sejarah mencatat, pada masa rezim Nazi di Jerman, Adolf Hitler melakukan pembakaran buku sebagai upaya melenyapkan narasi yang bertentangan dengan ideologi Reich Ketiga. Praktik serupa juga terjadi pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, yang memberlakukan penyitaan buku secara sistematis. Bukan hanya karya beraroma komunisme dan sosialisme, buku-buku dengan gagasan progresif pun turut disingkirkan dari ruang publik.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Trauma panjang dalam dunia perbukuan di Indonesia akibat rezim Orde Baru tampaknya masih membayangi hingga kini. Buku kerap diperlakukan bukan lagi sebagai sarana perluasan wawasan, melainkan sebagai objek yang mencurigakan. Alih-alih mendorong tumbuhnya daya kritis warga, negara justru cenderung membatasi akses terhadap bacaan. Padahal, demokrasi hanya dapat bertumbuh ketika rakyat diberi kebebasan untuk berpikir, berdialog, dan memperdebatkan gagasan secara terbuka.
Penyitaan Buku dan Pembubaran Diskusi
Fenomena penyitaan buku juga sempat terjadi di beberapa “lapak baca” yang digelar oleh penggiat literasi. Misalnya, pada aksi demonstrasi Agustus lalu, sebuah lapak baca harus berakhir diamankan aparat dengan dalih tidak mengantongi izin resmi. Tindakan menyita buku fisik semacam ini dinilai tidak relevan dan hanya melahirkan kesan bahwa negara merasa kalah oleh teks, seolah pemerintah berhadapan dengan “musuh” tak kasatmata. Pertanyaan pun muncul: mengapa negara begitu cemas terhadap keberadaan lembaran-lembaran kertas itu? Apakah persoalannya terletak pada pembaca, atau justru pada negara yang terlalu mengkonstruksi buku sebagai alat propaganda?
Ruang-ruang ekspresi pembaca yang hadir melalui forum-forum literasi pun tak luput dari sasaran kekuasaan. Pada Desember 2025, pembubaran kegiatan literasi kembali terjadi, kali ini dalam agenda bedah buku bertajuk “Reset Indonesia” di Madiun. Buku tersebut mengulas sejumlah persoalan yang tengah dihadapi Indonesia. Namun, sebelum diskusi berlangsung secara utuh, kegiatan itu terpaksa dihentikan oleh aparat bersama pemerintah setempat dengan alasan tidak memenuhi ketentuan perizinan.
Sebagai pembanding, Bupati Trenggalek justru menunjukkan sikap berbeda. Ia secara terbuka mengajak masyarakat untuk membaca dan mendalami gagasan dalam buku “Reset Indonesia”. Kegiatan ini berlangsung pascakejadian pembubaran diskusi di Madiun, menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat merespons wacana kritis secara konstruktif. Alih-alih membatasi, pemerintah daerah hadir sebagai fasilitator ruang dialog publik. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam forum tersebut bahkan menegaskan bahwa birokrasi tidak harus alergi terhadap diskursus intelektual. Praktik semacam ini patut menjadi teladan bagi pemerintah daerah lain, sekaligus memberi harapan baru bagi iklim literasi dan dunia perbukuan di Indonesia.
Ancaman bagi Demokrasi
Penyitaan buku atau pembubaran forum literasi bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sinyal kemunduran demokrasi. Dengan berdalih keamanan, kebebasan sipil dipersempit, mengulang logika lama Orde Baru yang bertujuan menjaga stabilitas dengan membatasi cara berpikir. Padahal, sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa ide tidak pernah bisa disita. Mengadili orang karena membaca sama artinya dengan menghukum karena berpikir, sebuah praktik berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Pada titik inilah buku dipandang berbahaya, bukan karena isinya semata, melainkan karena kemampuannya menumbuhkan daya pikir kritis pada pembaca. Cara berpikir kritis inilah yang kerap dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan yang anti-kritik. Ketakutan tersebut sejatinya tidak lahir dari teks yang dibaca, melainkan dari bayangan negara bahwa masyarakatnya mampu mempertanyakan, bahkan melawan, cara berpikir yang selama ini mapan.
Merawat Akal Sehat Publik
Jika negara benar-benar percaya pada demokrasi, maka buku tidak seharusnya diperlakukan sebagai ancaman. Negara mesti berhenti memandang ruang baca dan diskusi literasi sebagai persoalan keamanan, dan mulai melihatnya sebagai ruang refleksi terhadap negara. Perizinan tidak boleh dijadikan alat membungkam, melainkan sarana memfasilitasi. Buku tidak sama dengan kekerasan; membaca dan berdiskusi adalah hak warga, bukan potensi kejahatan.
Kritik dan perbedaan pandangan justru merupakan tanda masyarakat yang sehat, bukan musuh negara. Negara yang kuat tidak akan takut dibaca dan diperdebatkan. Sebaliknya, dengan membuka ruang literasi, negara sedang merawat akal sehat publik dan menjaga masa depan demokrasi agar tidak kembali mengulang luka masa lalu.