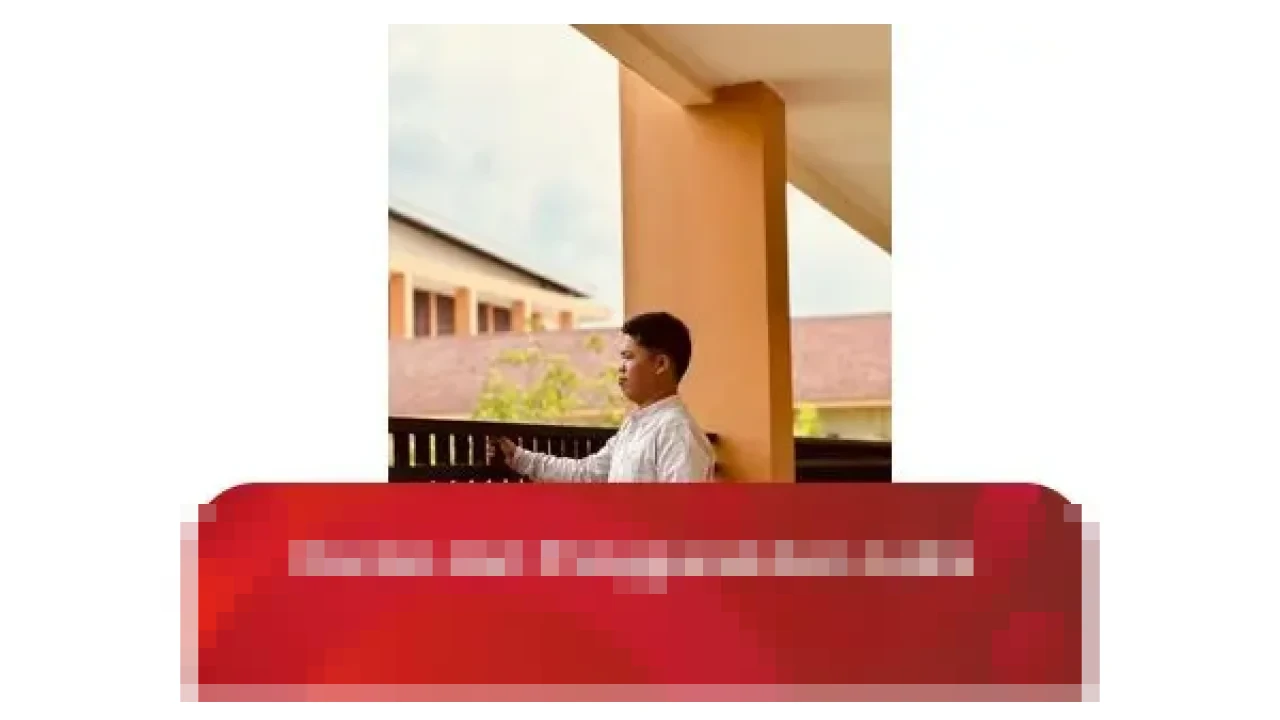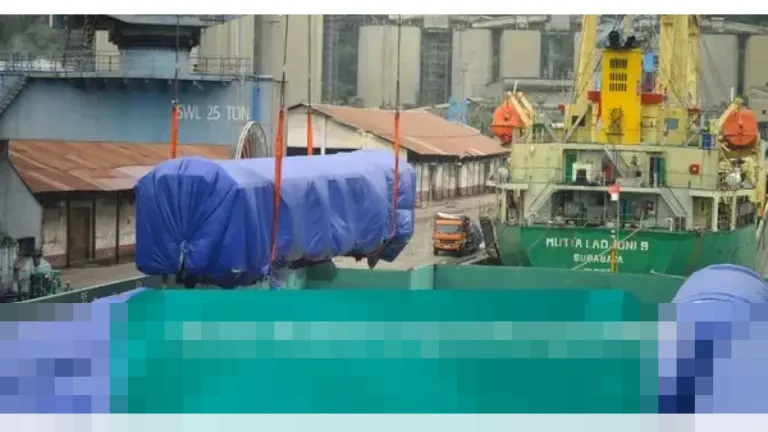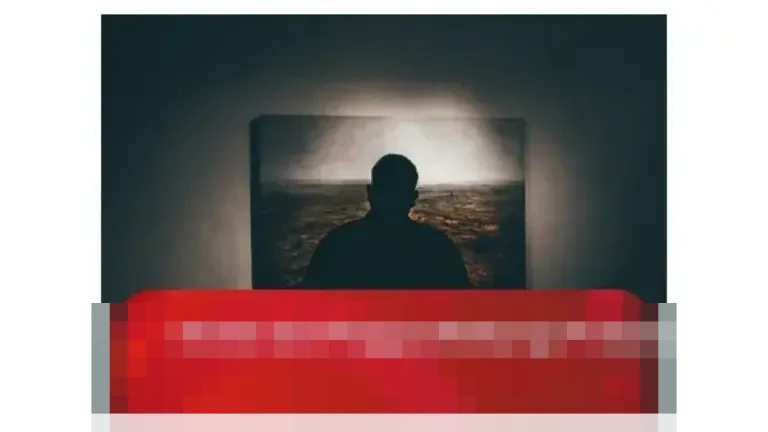Pergantian tahun kerap dirayakan dengan gemerlap angka pertumbuhan ekonomi, capaian kebijakan, dan laporan keberhasilan yang dibanggakan. Kalender boleh berganti, statistik pembangunan dikumandangkan, namun di balik hiruk-pikuk itu, sebuah pertanyaan mendasar jarang diutarakan secara tegas: apakah etika publik kita juga ikut berubah, ataukah kita hanya sibuk memperbaiki citra tanpa berani mengakui kesalahan?
Di tengah euforia akhir tahun, tradisi Batak yang dikenal sebagai mandok hata menawarkan cermin tajam. Tradisi ini, di mana anggota keluarga mengakui kekurangan dan meminta maaf, bukan sekadar ritual, melainkan praktik moral yang menempatkan perdamaian batin dan tanggung jawab personal di atas pencapaian materiil. Ketika budaya lokal mengajarkan kejujuran, ruang publik Indonesia justru menghadapi defisit etika yang nyata.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Tingginya Kepercayaan Publik, Minimnya Pengakuan Kesalahan
Data survei independen menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Indonesia relatif tinggi. Sekitar 69 persen masyarakat menyatakan mempercayai Pemerintah Indonesia pada pertengahan 2025, sebuah angka yang meningkat dibanding periode sebelumnya. Namun, angka ini hanya satu sisi cerita. Kepercayaan kepada institusi tidak serta-merta berarti kepuasan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keberanian pemerintah mengakui kesalahan.
Survei lain dari Litbang Kompas juga menemukan bahwa 78,3 persen responden yakin pemerintahan mampu menuntaskan kasus korupsi, dan sekitar 73,6 persen menyatakan puas dengan upaya pemberantasan korupsi. Persentase ini memang membanggakan, tetapi tidak menjelaskan sejauh mana bentuk tanggung jawab dan permintaan maaf disuarakan secara eksplisit oleh pemerintah ketika kebijakan atau program tertentu tidak berjalan sesuai harapan.
Krisis Etika dalam Respons Kebijakan
Krisis etika yang dimaksud bukan sekadar statistik kepercayaan, melainkan cara pemerintah merespons kegagalan publik. Di tahun terakhir, kita menyaksikan beberapa contoh nyata di mana perlunya keberanian moral lebih besar, bukan hanya klarifikasi informasi. Kebijakan yang semula diumumkan kemudian harus direvisi atau dibatalkan karena kurang sosialisasi, seperti rencana perubahan aturan elpiji yang memicu penolakan publik, menunjukkan lemahnya mekanisme pemeriksaan etika dalam penyusunan kebijakan.
Ketika klarifikasi itu berhenti pada penjelasan teknis tanpa pengakuan “kami salah dalam sosialisasi”, publik justru merasa diabaikan. Permintaan maaf bukan sekadar kata retoris. Ia adalah indikator keberanian pemerintah untuk mengakui bahwa kebijakan atau program tertentu berdampak buruk, bahkan jika dimaksudkan untuk kebaikan. Di negara demokratis besar sekalipun, pergeseran narasi dari pembenaran menjadi pengakuan kesalahan sering memerlukan proses panjang dan nyali politis yang kuat.
Realitas ini terasa ketika institusi hukum atau antikorupsi juga menghadapi dinamika kepercayaan. Tren penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi di periode sebelumnya menunjukkan bahwa publik mulai mengukur etika berdasarkan tindakan konkret, bukan sekadar label institusi.
Mandok Hata: Pelajaran untuk Pemimpin Publik
Tradisi mandok hata memberikan pelajaran sederhana: status, kekuasaan, dan capaian teknokratis tidak cukup bila tidak disertai kejujuran moral. Ketika seseorang secara pribadi mengakui salah di hadapan keluarga, penghormatan tumbuh. Sebaliknya, ketika pemimpin publik atau institusi enggan mengatakan “kami salah”, yang tumbuh justru adalah skeptisisme.
Tanpa itikad untuk bertanggung jawab, kebijakan yang baik sekalipun bisa memunculkan perasaan ditinggalkan oleh masyarakat yang melihat dampak riil di lapangan. Etika publik bukan sekadar slogan dalam pidato kenegaraan. Ia adalah praktik harian yang terukur—bagaimana pemerintah berkomunikasi ketika kebijakan gagal, bagaimana lembaga menanggapi kesalahan internal, dan bagaimana pejabat merespons kritik publik tanpa defensif.
Ini bukan soal citra, tetapi kepercayaan yang hidup. Jika kita terus menutup tahun hanya dengan angka dan klaim keberhasilan, sementara kesalahan dan dampaknya tidak diakui secara terbuka, maka yang berubah hanyalah tanggal di kalender. Etika kita, cara kita bertanggung jawab, dan cara kita meminta maaf terhadap publik tetap di tempat yang sama—sebuah tempat yang jauh dari standar moral yang ideal.
Kita boleh bangga pada pertumbuhan ekonomi, persentase kepercayaan publik, atau capaian tertentu. Namun jika etika dan keberanian moral tidak diukur sejajar dengan itu, kita hanya sibuk mengganti angka, bukan memperbaiki diri. Tahun boleh berganti, tetapi jika etika kita tidak ikut berubah, maka esensi peralihan tahun hanyalah sebuah ilusi.