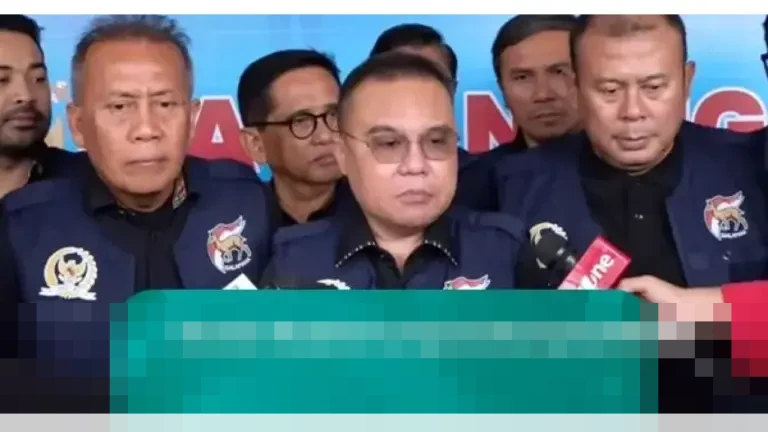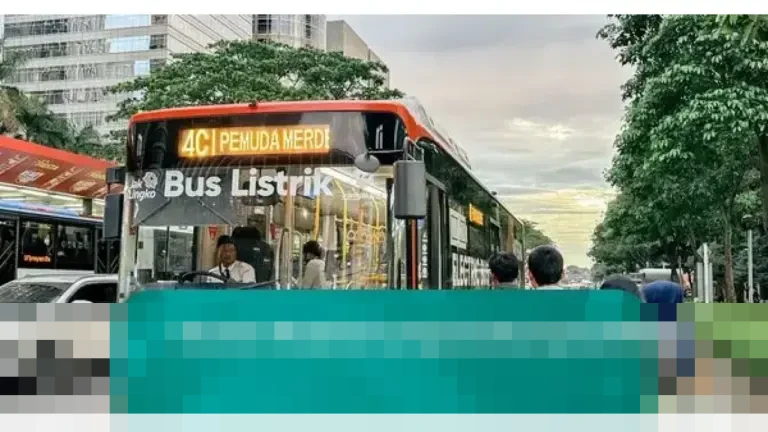Pada penghujung tahun 2025, kekhawatiran untuk menyuarakan kritik di ruang digital telah menjelma menjadi teror nyata. Jika pada tahun 2024 ketakutan semacam itu hanya menjadi materi komedi atau meme, kini ia bersemayam di benak masyarakat, memicu keraguan saat hendak menyampaikan pendapat.
Demokrasi, sejatinya, membutuhkan umpan balik atau feedback, bukan sekadar tepuk tangan atau upaya menciptakan trending topic di media sosial. Analogi sederhana dapat menggambarkan kondisi ini: negara adalah sebuah aplikasi, rakyat adalah penggunanya (user), dan pemerintah adalah pengembangnya (developer).
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Ketika sebuah aplikasi mengalami bug, sering crash, lambat, atau bahkan menyedot data pribadi tanpa izin, pengguna pasti akan melaporkan. Laporan tersebut, baik berupa rating bintang satu di PlayStore maupun keluhan di kolom komentar, merupakan data gratis atau bug report berharga yang memberi tahu pengembang letak kerusakan sistem agar segera diperbaiki.
Namun, di era pemerintahan Prabowo, respons yang terjadi justru berbanding terbalik. Alih-alih memperbaiki sistem, pemerintah justru “menangkap” pemilik akun media sosial yang mengkritik, bahkan mengirim polisi untuk menciduk mereka karena dianggap “mengancam developer aplikasi”.
Narasi usang yang mengidentifikasi aktivis sebagai dalang kerusuhan kembali digaungkan. Kasus Delpedro Marhaen dan sejumlah pengguna media sosial lainnya menjadi contoh nyata. Mereka diciduk bukan karena tindakan anarkis, melainkan dituduh “menghasut” melalui konten di media sosial. Penangkapan Delpedro sebagai tersangka, misalnya, didasari oleh paranoid aparat yang menganggapnya sebagai “provokasi demo Agustus 2025”.
Padahal, seperti diungkapkan Haji Siman bin Haji Naipin, “lembaran hitam demonstrasi Agustus 2025 itu terjadi bukan karena status medsos Delpedro. Bukan karena jempol netizen. Itu terjadi karena tabiat pejabat negara yang halu dan makin berani bersuara karena tewasnya Affan Kurniawan.”
Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat demonstrasi di depan Gedung DPR, menjadi martir atas brutalitas aparat. Ironisnya, alih-alih mengevaluasi insiden yang merenggut nyawa, negara justru sibuk membungkam mereka yang menuntut keadilan di media sosial.
Pola pembungkaman ini telah terkonfirmasi valid dalam laporan SAFEnet dan Amnesty International Indonesia. Kritik kebijakan dibalas serangan digital, pembela HAM dikriminalisasi, dan warga adat ditangkapi karena mempertahankan tanah dari proyek-proyek strategis nasional. Pola ini, yang tak banyak berubah sejak Orde Baru, menunjukkan hukum yang tajam terhadap pengkritik namun tumpul terhadap perusak lingkungan. Negara, alih-alih menangkap esensi kritik, justru menangkap individu yang mengkritik.
Akibat terlalu banyak gimik, pemerintah lupa bahwa memidanakan kritik tidak lagi menciptakan efek jera, melainkan justru memicu rasa tertantang. Semakin bau bangkai ditutupi dengan membungkam orang yang menciumnya, semakin besar rasa penasaran publik untuk mencari sumber bangkai tersebut.
Kondisi ini mengingatkan pada Catatan Akhir Tahun 2022 yang berjudul “Negeri Gimik”, yang menyoroti pemerintahan yang disusun berdasarkan kepentingan politik dan gemar gimik. Pada tahun 2025, gimik tersebut tidak hilang, melainkan berevolusi menjadi tone-deaf yang mengerikan. Jika dulu gimiknya adalah “kerja, kerja, kerja” atau blusukan ke gorong-gorong, kini gimiknya adalah “pencitraan dan klarifikasi di atas bencana”.
Banjir bandang yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, Kalimantan, dan daerah lainnya pada Desember ini menjadi contoh nyata. Saat rakyat membutuhkan logistik dan evakuasi, para pejabat justru melihatnya sebagai kesempatan untuk konten. Ada menteri yang cosplay menjadi kuli panggul beras di depan kamera, anggota DPR yang turun ke lumpur dengan rompi taktis ala militer, bahkan gubernur yang melempar bantuan dari helikopter, membiarkan beras berhamburan di tanah becek untuk dipunguti rakyat yang kelaparan. Tindakan ini bukan bantuan, melainkan penghinaan yang nir-empati.
Fenomena ini juga mengingatkan pada Catatan Akhir Tahun 2017 yang berjudul “Politik Pelintiran Kebencian”. Bedanya, jika dulu kebencian dipelintir untuk memenangkan Pemilu, kini kejadian nyata dipelintir untuk mematikan nalar. Pejabat sering berdalih kritik adalah hoaks, padahal ketidakpercayaan masyarakat lahir dari fakta ketidakadilan yang telanjang, tanpa sensor.
Rakyat melihat Affan tewas terlindas rantis, melihat beras dilempar dari langit, dan melihat aktivis ditangkap sementara koruptor mendapat diskon hukuman. Ini bukan hoaks, melainkan fakta yang menyakitkan. Keadilan, tampaknya, masih tersesat dalam kenikmatan kekuasaan. Semakin reaksioner pemerintah menyikapi kritik dengan label “makar”, semakin tebal tembok ketidakpercayaan publik. Public trust tidak dapat dibeli dengan bansos, MBG, apalagi dengan mengerahkan buzzer.
Tutorial Jadi Pemerintah yang Tidak Boomer di Era AI
Sebelum tembok kepercayaan ini benar-benar runtuh, ada beberapa saran gratis bagi para pejabat yang masih gagap menghadapi netizen di era AI:
- Anggap Kritik sebagai Dataset, Bukan Ancaman. Di era AI, data adalah “new oil”. Kritik rakyat adalah training data terbaik untuk memperbaiki algoritma kebijakan pemerintah. Jika ada ribuan orang berteriak, jangan kirim polisi atau ormas, apalagi intel. Kirimlah data analyst. Gunakan Sentiment Analysis. Jadikan amarah rakyat sebagai insight untuk mengetahui letak kekeliruan. Memenjarakan pengkritik sama saja merusak dataset yang dibutuhkan, yang pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan yang halu.
- Berhenti Pakai Buzzer. Mengerahkan buzzer untuk memuji pemerintah di tahun 2025 adalah tindakan norak. Rakyat semakin pintar membedakan akun organik dan akun ternakan. Pasukan siber berbayar hanya menciptakan noise, bukan voice. Buzzer hanya membuat pemerintah merasa dicintai oleh “cinta palsu, cintanya love scammer yang menyebar bujuk rayu demi cuan”.
- Jadilah Admin Negara, Bukan Admin Grup Chat Keluarga. Berhenti menggunakan bahasa birokrat kaku atau gimik cringe seperti memakai rompi perang di lokasi bencana. Rakyat memiliki radar pendeteksi kebohongan yang canggih, yaitu hati nurani. Jawab kritik dengan data dan solusi konkret, bukan dengan pasal karet di Undang-Undang.
Sebagai rakyat yang waras, kita tidak boleh berhenti mengkritik. Diam adalah pengkhianatan terhadap akal sehat. Kita hidup di era algoritma, di mana kebenaran akan mencari jalannya sendiri, sekecil apapun celahnya. Celah yang seringkali tak terlihat oleh penguasa yang duduk gelisah di singgasana, dibodohi bisikan para pembantu dan staf khusus yang menganut paham ABS: “Asal Bowo Senang”.
Yang seharusnya ditakuti pemerintah bukanlah linimasa yang penuh caci maki, melainkan ketika rakyat diam membisu. Benar-benar diam. Tak peduli lagi. Tetiba Angkat Bendera. Sebab, ketika rakyat sudah berhenti bicara dan berhenti mengeluh, biasanya itu tanda jempol mereka sedang beristirahat, dan berganti dengan pergerakan nyata mengembalikan keadilan yang telah lama tersesat.