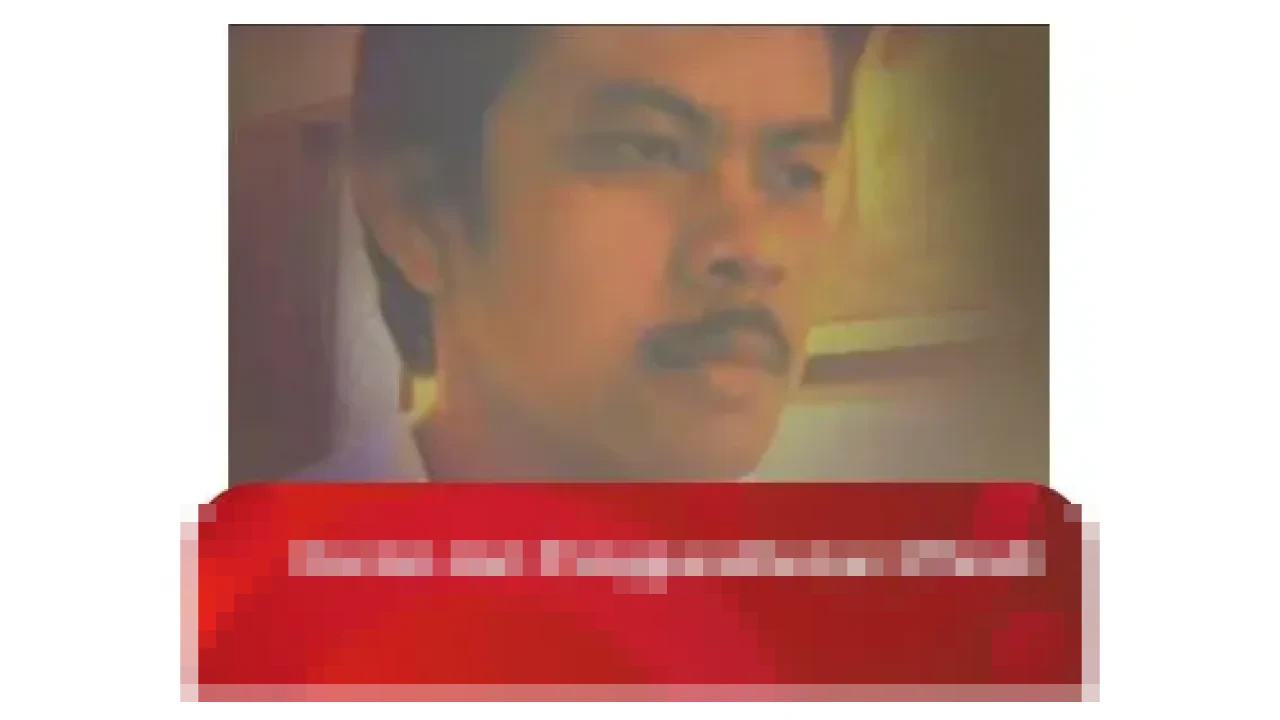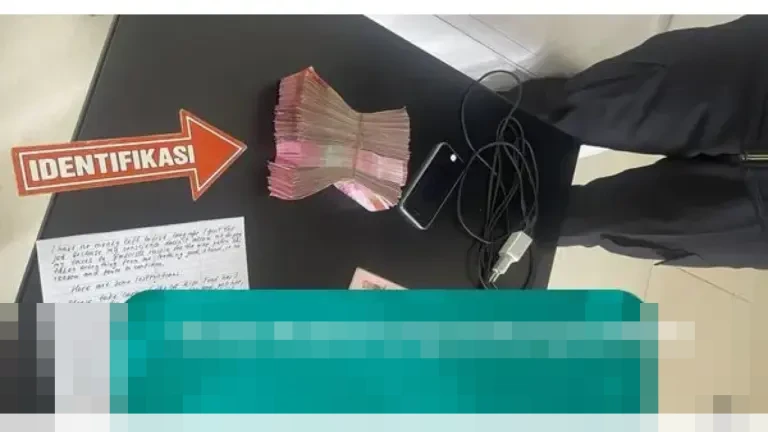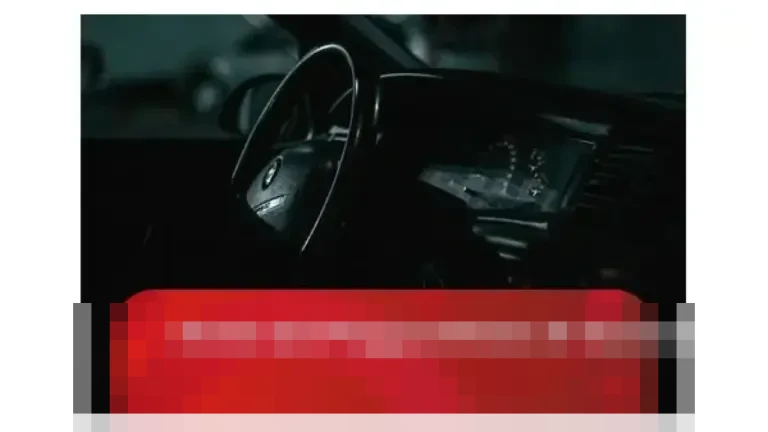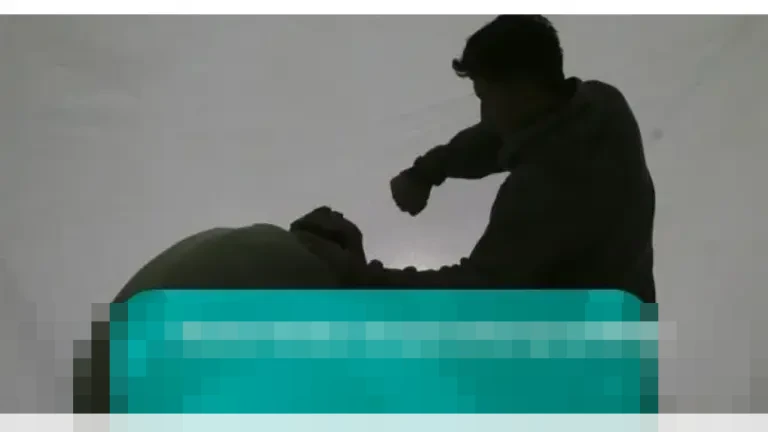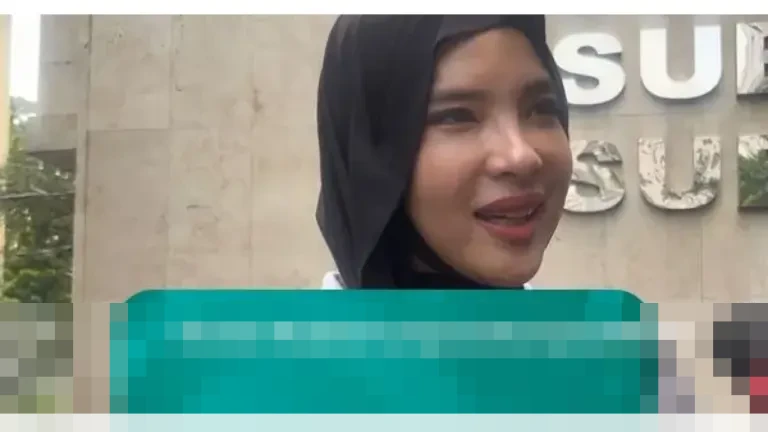Jumat, 02 Januari 2026 – Kebutuhan akan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 secara tegas menyatakan rumah sebagai hak dasar warga negara, menempatkan kewajiban pemenuhannya di pundak negara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya paradoks yang kompleks, di mana target ambisius pemerintah sulit terwujud.
Menurut analisis Ruslan Effendi, lulusan S3 Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Indonesia menghadapi backlog perumahan sekitar 27 juta unit. Sementara itu, pemerintah menargetkan penyediaan 10 juta rumah dalam rencana lima tahunan. Ironisnya, target kementerian yang membidangi perumahan hanya mencapai 3 juta unit, menyisakan 7 juta unit yang belum teridentifikasi bagaimana pemenuhannya. Paradoks ini muncul akibat benturan antara logika pasar, keterbatasan fiskal, dan tata kelola multi-lapisan yang rumit.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Konsep Ideal Kewargaan yang Sulit Diterapkan
Negara-negara Skandinavia seringkali dijadikan contoh ideal dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat, termasuk perumahan. Di sana, rumah dipandang sebagai bagian integral dari hak kewargaan (Citizenship) yang menjamin akses setara ke kota, pekerjaan, dan fasilitas umum. Peran negara bukan sebagai pembangun utama, melainkan penjamin melalui instrumen jangka panjang dan regulasi sewa serta lahan yang kuat. Pembangunan rumah banyak dilakukan oleh organisasi nirlaba dengan pendanaan negara, menerapkan tarif berbasis biaya, dan menginvestasikan kembali surplus untuk menciptakan komunitas perumahan yang inklusif, terintegrasi, serta menghindari segregasi sosial.
Model ideal ini sulit diterapkan di Indonesia karena beberapa faktor. Pertama, pemerintah daerah (pemda) tidak memiliki kendali kuat atas tanah, yang sebagian besar sudah dikuasai pengembang swasta atau organisasi profit. Kedua, kapasitas fiskal pemda terbatas untuk menyediakan lahan bagi perumahan sosial. Ketiga, Indonesia belum memiliki institusi pengembang nirlaba yang profesional. Keempat, kebijakan pembiayaan masih berorientasi pada kredit individu, yang tidak efektif membangun stok perumahan jangka panjang.
Pergeseran Logika Pembangunan Perumahan
Sejarah pembangunan perumahan di Indonesia juga mencatat pergeseran logika yang signifikan. Sebuah studi tentang proyek Pulomas menunjukkan bagaimana pada awal 1960-an, proyek ini dirancang sebagai perumahan terjangkau bagi kelompok menengah ke bawah, terinspirasi model koperasi ala Skandinavia. Pulomas direncanakan sebagai komunitas terintegrasi dengan pengelompokan hunian dan ruang bersama untuk menopang kohesi sosial.
Namun, memasuki tahap implementasi pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an, terjadi perubahan arah. Karena kesulitan dana pemerintah dan pergeseran paradigma politik pembangunan Orde Baru, pembangunan dialihkan ke swasta. Konsekuensinya, korporasi swasta lebih mengejar keuntungan daripada membangun perumahan sosial. Perumahan yang semula ditujukan untuk kelas menengah dan bawah, berubah menjadi hunian bagi kalangan atas, mengikuti logika pasar yang memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan.
Tata Kelola Multi-Lapisan yang Terlalu Rumit
Salah satu penghambat paling krusial dalam kebijakan perumahan di Indonesia adalah tata kelola multi-lapisan yang sangat kompleks. Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seringkali memiliki agenda pembangunan yang beragam dan tidak terkoordinasi. Pemerintah Pusat mungkin menargetkan jutaan rumah, namun izin lokasi sepenuhnya berada di tangan pemda.
Mureks mencatat bahwa banyak daerah tidak menyiapkan stok lahan murah di area yang terintegrasi, sehingga pilihan pembangunan seringkali jatuh pada daerah pinggiran yang jauh dari pusat kota. Dari sisi pendanaan, Pemerintah Pusat menyediakan pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tapera, atau subsidi KPR. Namun, pembangunan tidak dapat segera berjalan tanpa adanya izin prinsip, lokasi, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang seringkali berlarut-larut. Akibatnya, dana tersedia, tetapi rumah tidak terbangun.
Pemerintah provinsi, yang diharapkan mampu mengoordinasikan pembangunan lintas kabupaten/kota, tidak memiliki kendali penuh untuk memaksa kabupaten/kota membuka lahan, memberi perizinan, atau mengatur pengembang. Persoalan pun bergeser dari isu perumahan menjadi administratif yang berbelit.
Mendesak Reformasi Kebijakan Perumahan
Tidak adanya satu aktor tunggal yang secara efektif memastikan pembangunan rumah rakyat yang terintegrasi dan layak huni, membuat target perumahan seringkali hanya berhenti pada angka statistik, bukan menjadi komitmen bersama yang mengikat. Untuk mengatasi paradoks ini, Ruslan Effendi menekankan perlunya reformasi kebijakan perumahan.
Rumah tidak hanya harus dipandang sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai hak dasar warga negara. Perumahan rakyat tidak boleh hanya menjadi komoditas, melainkan harus menjadi hak kewargaan. Rencana pembangunan perumahan yang terpadu, dengan aktor-aktor yang memiliki pertanggungjawaban jelas, menjadi solusi untuk mewujudkan rumah yang berkeadilan sosial dan kesetaraan akses. Rumah layak huni tidak hanya dilihat dari aspek fisik dan sanitasi semata, tetapi juga bagaimana ia menjadi tempat tinggal yang memberikan akses pekerjaan dan kehidupan yang bermakna bagi penghuninya.