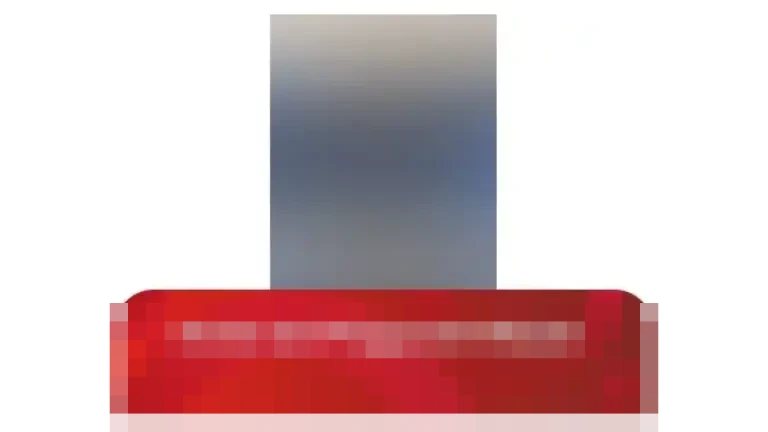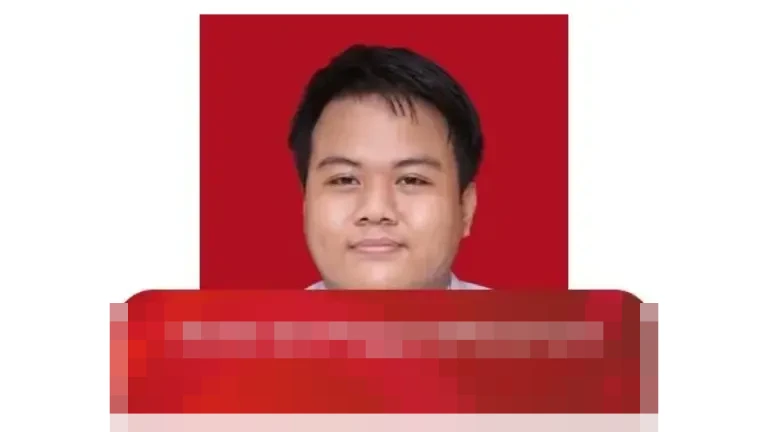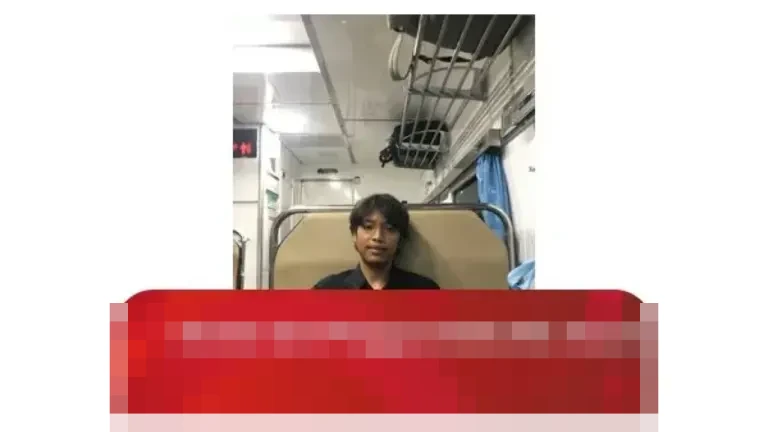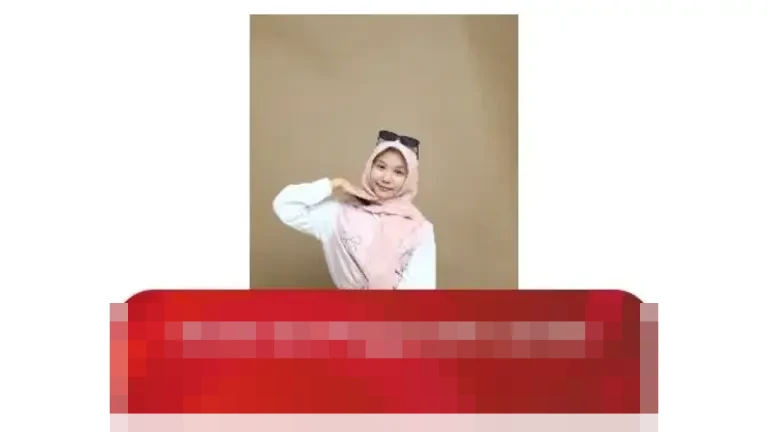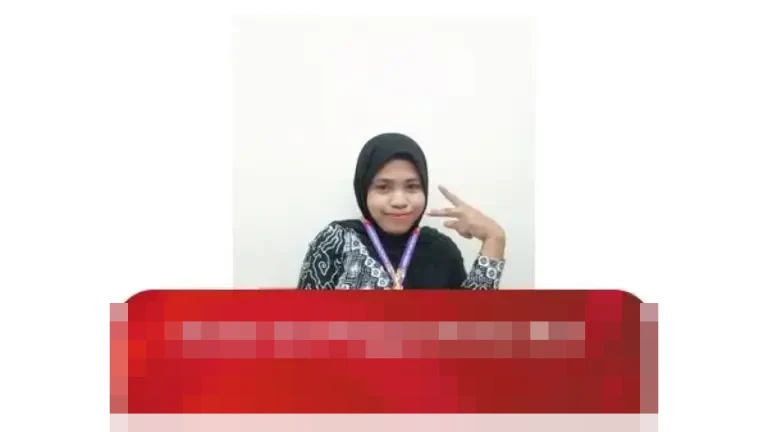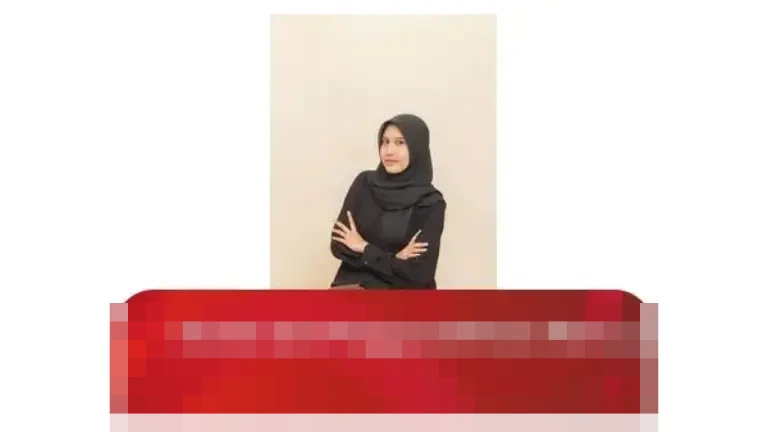Fahruddin Fitriya, seorang jurnalis, mengenang pengalamannya saat pertama kali ditugaskan ke Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Penugasan pada tahun 2011 itu, yang awalnya ia bayangkan sebagai petualangan ala Indiana Jones, justru membawanya pada pelajaran kemanusiaan yang mendalam di Palangka Raya.
Natal tahun 2011 menjadi momen debut Fitriya merasakan atmosfer Kristiani di tanah Dayak. Kala itu, era BlackBerry Messenger (BBM) masih mendominasi komunikasi, jauh sebelum kehadiran WhatsApp dengan segala fitur dan grup keluarganya.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Sebuah undangan dari mentornya, Almarhum Topan Nanyan, yang akrab disapa Bos Top, menjadi pemicu perjalanan tersebut. Bos Top, yang kala itu menjabat General Manajer dan sedang meroket karirnya dari desk kriminal, menyampaikan titah, “Kalau ke Palangka, datang ke rumah. WAJIB!”
Bagi Fitriya, Palangka Raya bukan sekadar ibu kota provinsi. Kota ini telah menjadi rumah keduanya setelah kampung halaman di Pati, Jawa Tengah. Maka, begitu libur tiba, ia segera bertolak menuju Jembatan Kahayan.
Perjalanan dari Buntok ke Palangka Raya pada tahun itu merupakan ujian kesabaran. Jika kini jalannya mulus, dulu lintasannya lebih mirip medan tempur yang bisa berubah menjadi bubur kacang hijau raksasa setelah diguyur hujan. Delapan jam di dalam mobil travel, Fitriya harus bergoyang ke kiri dan kanan menghindari lubang jalanan yang begitu dalam.
Setibanya di Palangka Raya, Fitriya singgah di kantor WALHI Kalteng untuk membersihkan diri, sebelum memulai safari Natalnya. Sebagai seorang Muslim yang tumbuh di lingkungan yang mungkin kurang terpapar keberagaman, ia sempat bertanya-tanya mengenai hidangan yang akan disajikan. “Nanti di sana makan apa ya? Apa saya harus bawa biskuit cadangan di saku?” pikirnya.
Namun, kekhawatiran itu segera sirna. Rumah pertama yang ia kunjungi adalah kediaman Bang Anchu, seorang redaktur. Di sana, Bang Anchu langsung mengumumkan, “Fit, nanti makan yang di meja sana ya. Ayamnya halal, disembelih tetangga yang Muslim tadi sore.”
Fitriya tertegun. Baginya, ayam itu seolah telah ‘bersyahadat’ demi menyambut kedatangannya. Momen ini menunjukkan bahwa toleransi di Palangka Raya bukan sekadar slogan atau materi pidato, melainkan praktik nyata yang memastikan kenyamanan dan kebutuhan kawan yang berbeda keyakinan terpenuhi.
Pemandangan di luar rumah pun mencerminkan hal serupa. Palangka Raya adalah kota di mana Masjid Al-Azhar dan Gereja Nazaret berdiri berdampingan, hanya dibatasi satu sisi dinding yang menyatu, seolah saling berbisik menjaga kedamaian. Tidak ada tatapan curiga, yang ada hanyalah senyum ramah dan ajakan untuk menikmati hidangan.
Di kota ini, perbedaan agama justru menjadi alasan untuk saling menjaga, bukan menjauh. Natal di Kalimantan Tengah bagi Fitriya bukan hanya tentang pohon plastik berlampu kelap-kelip atau lagu-lagu Natal, melainkan tentang bagaimana Bang Anchu dan rekan-rekannya melampaui batas dogma demi sebuah nilai persaudaraan.
Malam itu, di bawah langit Palangka Raya, Fitriya belajar satu hal penting: jika jalanan Buntok-Palangka yang keras bisa menjadi selembut bubur, maka ego manusia pun seharusnya bisa selunak itu saat berhadapan dengan kasih sayang antar-sesama.