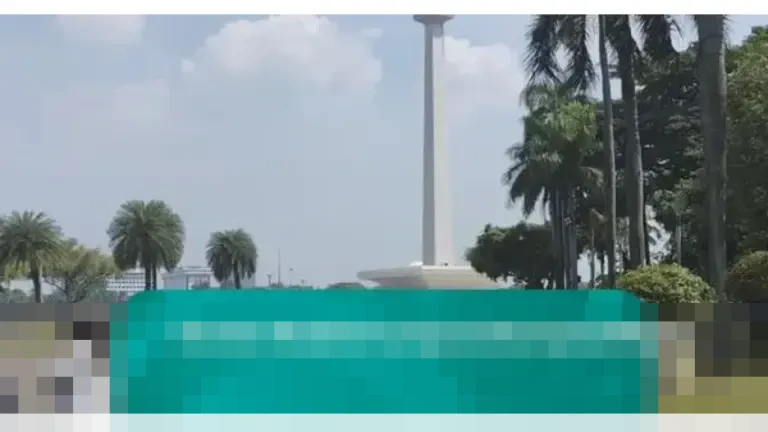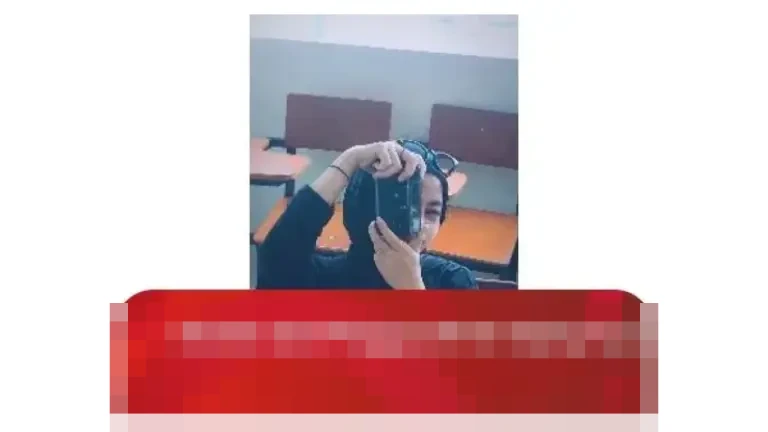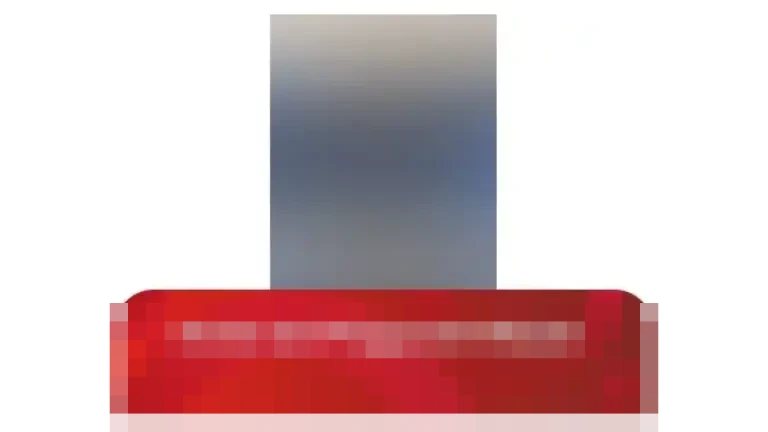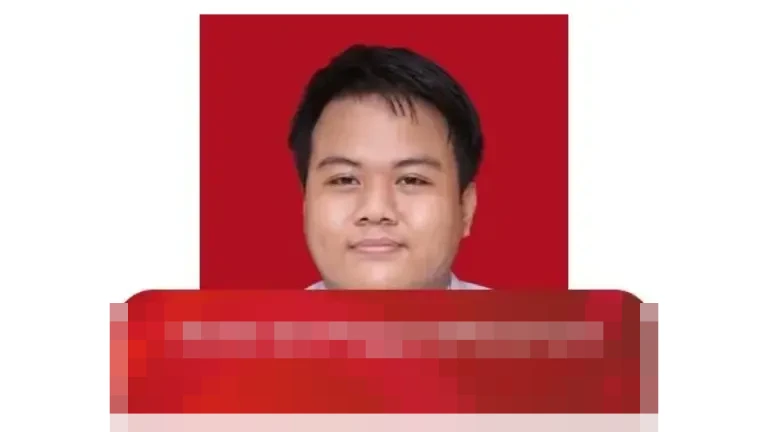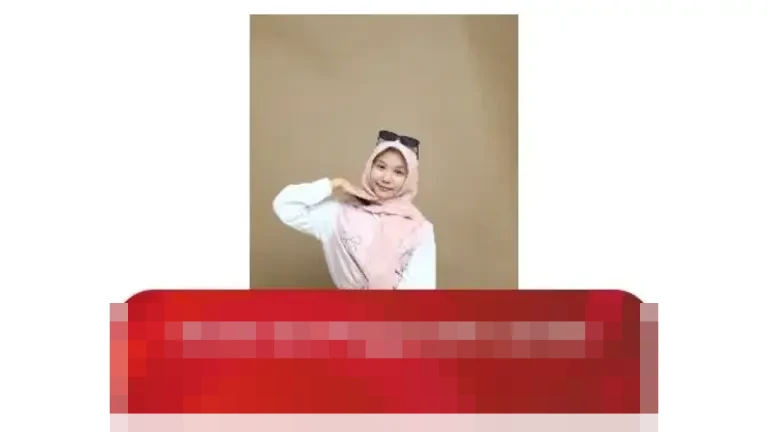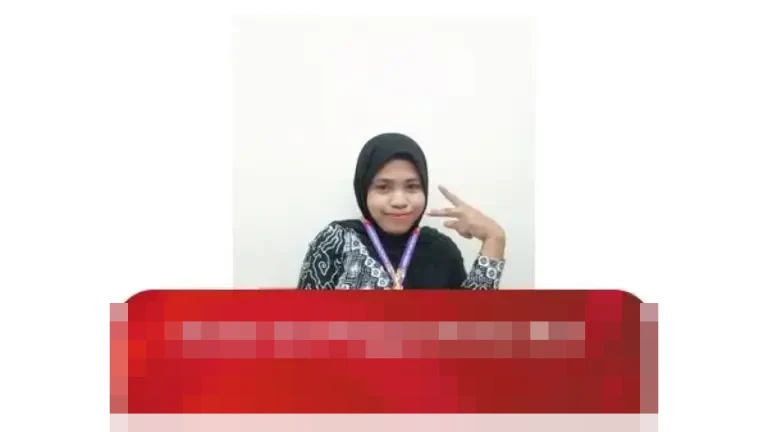Pada dekade kedua abad ke-20, keresahan sosial di kalangan rakyat Tegal telah bertransformasi dari bisikan di sawah-sawah menjadi gelombang perlawanan yang terorganisasi. Di balik hamparan perkebunan tebu yang menjadi tulang punggung ekonomi kolonial Belanda, tersembunyi kenyataan pahit eksploitasi ruang dan tenaga rakyat di daerah perkebunan dan pabrik.
Tegal saat itu tengah memasuki era modernisasi dengan menjamurnya perkebunan dan pabrik gula di berbagai wilayahnya, sebagaimana dicatat oleh Wijanarto (2016). Namun, alih-alih membawa kesejahteraan, perubahan sosial dan ekonomi ini justru membebani rakyat pedesaan. Konteks makro kebangkitan nasional menunjukkan bahwa akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan masa transisi dari sistem ekonomi tradisional menuju ekonomi liberal (Firdiyansyah, 2025). Liberalisasi ini dipicu oleh Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada akhir abad ke-19 (Zulyanti et al., 2025), yang mengalihkan ekonomi Hindia Belanda pada akumulasi kapital.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Akar Eksploitasi dan Keresahan Sosial
Tanah-tanah subur yang seharusnya ditanami padi beralih fungsi menjadi perkebunan tebu. Sawah-sawah petani dirampas paksa oleh kolonial untuk mendirikan pabrik gula, menjadikan gula komoditas ekspor paling berharga bagi pemerintah kolonial.
Pertumbuhan perkebunan tebu dan pabrik gula di Jawa dan Madura sangat pesat antara tahun 1870-1895. Jumlah pabrik gula melonjak dari 97 pada tahun 1870 menjadi 265 pada tahun 1895 (Lucas, 2004). Peningkatan jumlah pabrik ini diiringi dengan eksploitasi lahan petani yang masif. Petani menjadi pihak yang paling dirugikan karena alat produksi mereka direbut secara legal.
G. R. Knight (1993) bahkan menyebut Karesidenan Pekalongan-Tegal sebagai penghasil gula terbaik di Hindia Belanda sejak masa tanam paksa, berkat kesuburan tanahnya. Pada tahun 1914 saja, terdapat 18 pabrik gula di wilayah ini (Mutiara, 2016), enam di antaranya berlokasi di Tegal, meliputi Pangkah, Kemantran, Pagongan, Kemanglen, Dukuhwringin, dan Balapulang (Lindblad, 2002).
Kapitalisme perkebunan ini, meskipun mengandalkan korporasi swasta, justru menciptakan masalah baru. Kolaborasi antara praktik swasta dengan birokrasi pribumi, mirip dengan sistem cultuurstelsel, menjadi lahan subur bagi eksploitasi di Tegal (Lindblad, 2002). Akumulasi kemuakan rakyat pun tak terhindarkan. Ketika lahan pertanian diambil alih secara eksploitatif, keresahan sosial mulai mengemuka. Surat kabar Neratja pada November 1918 melaporkan keluhan petani di Adiwerna, Tegal, mengenai penarikan pajak sewa tanah untuk penanaman tebu sebesar 17%.
Dari Pembakaran Sporadis Menuju Gerakan Terorganisir
Kemuakan rakyat Tegal memuncak dalam aksi pembakaran perkebunan tebu, yang menjadi momok menakutkan bagi kaum kapitalis perkebunan. Merebaknya keresahan ini mendorong kaum kapitalis untuk memasang iklan perekrutan opsir militer di Soerabaijasch Handelsblad guna mengatasi masalah tersebut (McVey, 2017). Pada 18 Februari 1919, atas inisiatif Residen Pekalongan, sebuah rapat digelar untuk mengamankan perkebunan dari gangguan.
Pembakaran perkebunan tebu menjadi pemicu awal dalam sejarah pergerakan nasional. Selanjutnya, perlawanan terhadap industri gula di Tegal mulai digencarkan oleh kaum pergerakan nasional melalui organisasi yang lebih terstruktur. Hadirnya industri gula juga melahirkan kelas pekerja baru. Namun, sektor kerja formal tidak mampu menampung seluruh kelas pekerja, menciptakan masalah pengangguran.
Di Tegal, berbagai serikat buruh mulai berdiri, seperti Sarekat Boeroeh Goela, Sarekat Pegawai Pelaboahan Laoetan, serta Sarekat Boeroeh Bingkil dan Electric (Winarto, 2016). Jauh sebelum itu, Vereniging Spoor Transweg Personeel (VSTP) telah eksis sejak 1918. Beberapa organisasi ini, menurut Si Tetap (Juni 1918), merupakan serikat buruh beraliran kiri. Di lingkungan pedesaan, Sarekat Ra’jat Tegal berkembang dengan sekitar 5.000 anggota (Wijanarto, 2016).
Terbentuknya organisasi-organisasi ini menandai transformasi gerakan perlawanan rakyat Tegal dari spontanitas menuju organisasi, sekaligus menggambarkan situasi pedesaan Tegal pada masa pergerakan nasional. Puncak perlawanan rakyat Tegal di tahun 1920-an adalah Perlawanan Karangcegak, yang melibatkan berbagai organisasi, khususnya Sarekat Ra’jat Tegal.
Warisan Perlawanan dan Benih Nasionalisme
Perlawanan Karangcegak pada akhirnya menemui kegagalan, terutama karena ketergantungan pada tokoh-tokoh kunci dan tekanan pemerintah kolonial yang lebih terorganisasi (Wijanarto, 2016). McVey (2017) bahkan menyebut pemberontakan rakyat Tegal “mati pada saat lahir”, sehingga pemerintah kolonial untuk sementara waktu terhindar dari revolusi.
Meskipun gagal, perlawanan rakyat Tegal sekitar tahun 1926 ini setidaknya berhasil menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan di kalangan rakyat Tegal sebagai kaum tertindas. Pembayangan akan kesamaan nasib ini, menurut penulis artikel ini, Abdullah Azzam Al Mujahid, turut menyumbang tumbuhnya jiwa nasionalisme di lingkungan pedesaan sebagai warga negara Indonesia. Ia menilai, bukan karena pemantiknya adalah orang-orang kiri, melainkan karena pembayangan rasa senasib sepenanggungan itulah yang menyemai benih-benih nasionalisme.