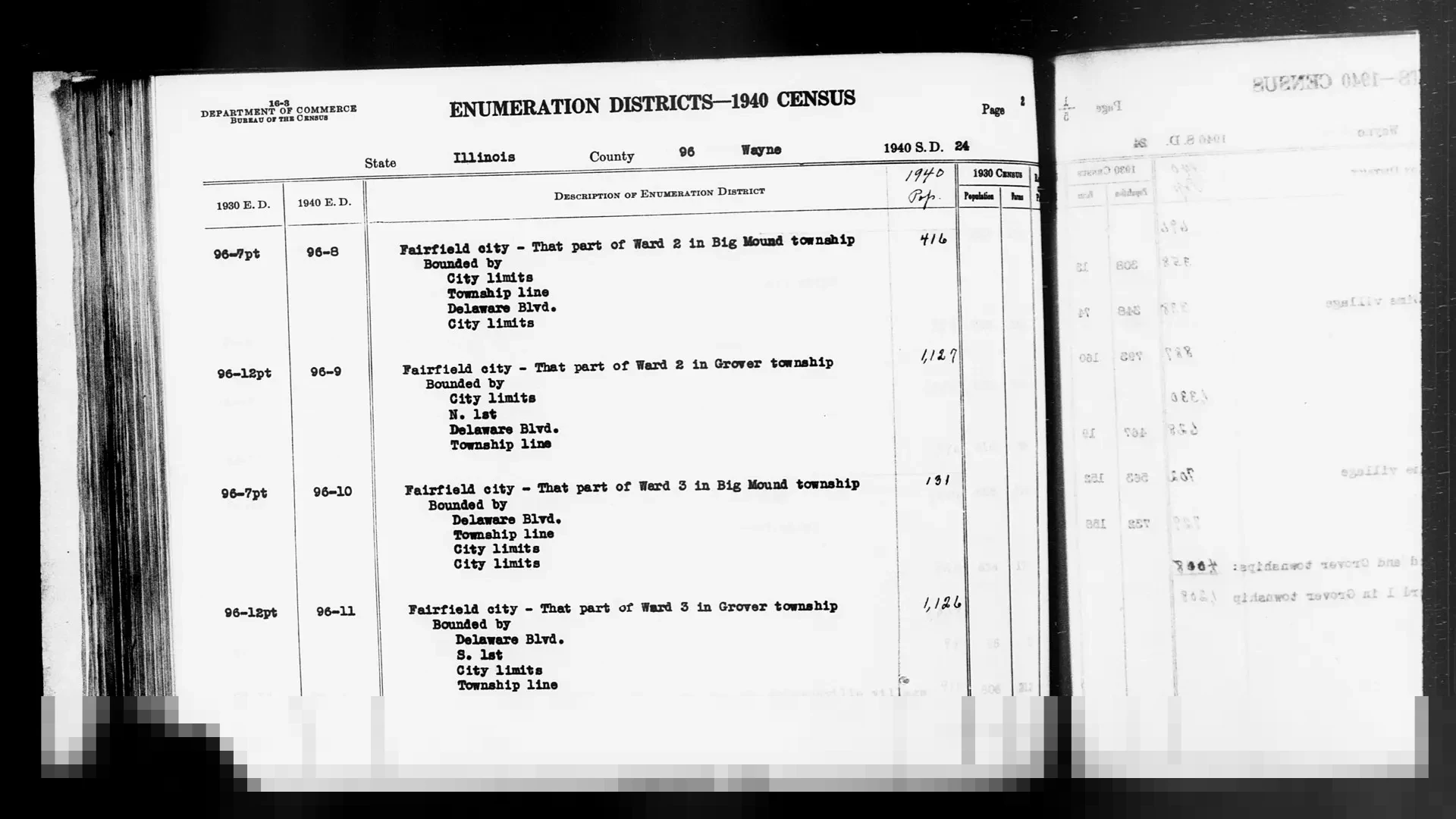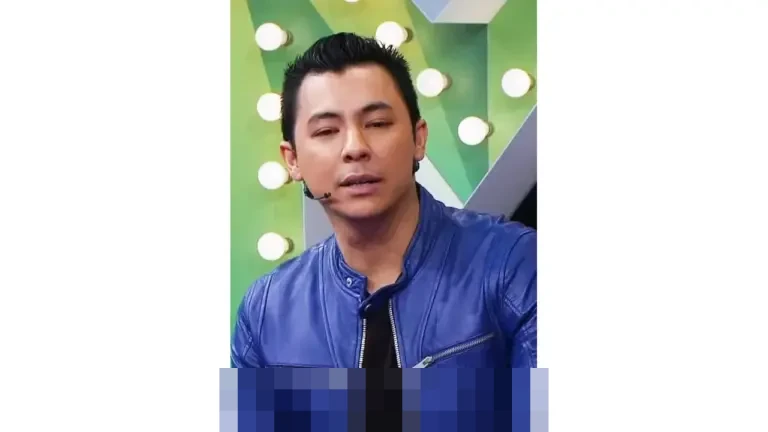Program perumahan rakyat yang digagas pemerintah kerap dihadapkan pada tantangan serius: hunian yang dibangun tidak selalu memenuhi standar kelayakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Meskipun pembangunan fisik rumah telah rampung, banyak di antaranya justru ditinggalkan penghuni.
Fakta di lapangan, seperti yang Mureks pantau, menunjukkan bahwa rumah-rumah bersubsidi seringkali mangkrak atau tidak dihuni. Berbagai alasan melatarbelakangi kondisi ini, mulai dari kualitas fisik bangunan yang buruk, minimnya infrastruktur dan fasilitas umum, hingga lokasi yang terlalu jauh dari pusat aktivitas ekonomi atau tempat kerja warga.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan bukan sekadar kekurangan unit rumah, melainkan berakar pada desain dan implementasi kebijakan yang kurang tepat. Setidaknya, ada empat faktor mendasar yang menjadikan rumah-rumah tersebut tidak selalu layak huni.
1. Rumah Dipahami sebagai Bangunan Fisik, Bukan Hak Dasar Warga
Kebijakan perumahan di Indonesia cenderung berorientasi pada aspek fisik semata. Pembangunan difokuskan pada penyediaan struktur dasar seperti atap, lantai, dinding, pintu, dan jendela. Pendekatan ini, menurut analisis, gagal memastikan bahwa rumah tersebut mampu mendukung kehidupan yang stabil dan produktif bagi penghuninya.
Padahal, rumah seharusnya lebih dari sekadar tempat berteduh. Ia mesti menjadi fondasi bagi keluarga untuk mencari nafkah, mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta membangun hubungan sosial dalam komunitas. Rumah juga berperan sebagai tempat merencanakan masa depan.
Fokus pada bangunan fisik semata juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Setelah bangunan fisik dinyatakan selesai, seluruh administrasi dianggap tuntas. Proses monitoring lebih banyak berpusat pada jumlah unit terbangun, penyerapan anggaran, dan ketepatan waktu, tanpa evaluasi mendalam terhadap kebermanfaatan riil bagi MBR.
2. Kebijakan Perumahan Terjebak Logika Komoditas dan Pasar
Meskipun konstitusi dan undang-undang secara jelas menempatkan rumah sebagai hak dasar warga negara, kebijakan yang diterapkan justru cenderung menyerahkan penyediaannya kepada mekanisme pasar. Akibatnya, rumah diperlakukan sebagai komoditas.
Ketika rumah menjadi komoditas, fokus utama adalah bagaimana agar “barang dagangan” tersebut laku di pasaran. Untuk menarik minat keluarga kurang mampu, pemerintah memberikan berbagai bantuan seperti subsidi, diskon, atau fasilitas pembiayaan. Namun, desain kebijakan ini justru membuka ruang lebar bagi pasar untuk menentukan hasil akhir.
Penyediaan perumahan rakyat didorong oleh sisi permintaan melalui subsidi pembiayaan dan kredit, sementara pasokan sepenuhnya ditentukan oleh pengembang dan perbankan. Dalam kerangka berpikir ini, rumah dipandang sebagai aset finansial, dan keterjangkauannya sangat bergantung pada kemampuan bayar calon penghuni.
Ironisnya, jika setelah disubsidi pun MBR masih tidak mampu membeli, batasan kriteria MBR kerap dilonggarkan agar unit rumah tetap terjual. Tim redaksi Mureks mencatat, kondisi ini seringkali berujung pada keluarga non-MBR yang justru membeli unit tersebut, lalu menyewakannya kembali.
Selain itu, skema perbankan yang menjadi tulang punggung pembiayaan juga berisiko tinggi bagi MBR. Persyaratan kredit dan cicilan bulanan yang kaku tidak mempertimbangkan fluktuasi kondisi keuangan MBR, sehingga rentan memicu gagal bayar.
3. Tata Kelola Kebijakan yang Berserakan dan Tumpang Tindih
Permasalahan lain yang krusial adalah tata kelola kebijakan perumahan yang tidak terintegrasi. Hierarki kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah seringkali tidak mengalir dalam satu sistem yang terpadu.
Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih peran dan kewenangan antarlembaga, bahkan ada kebijakan yang tidak memiliki institusi pengawal yang jelas. Akibatnya, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan hasil pembangunan menjadi tidak efektif.
Ketiadaan integrasi sistematis ini menghambat pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan sejak awal, menciptakan inefisiensi dan ketidakpastian dalam implementasi.
4. Kebijakan yang Abai terhadap Realitas Kehidupan MBR
Pendekatan pembangunan perumahan rakyat seringkali terlalu mengutamakan aspek teknis dan mengabaikan konteks sosial, budaya, serta ekonomi MBR. Kebijakan disusun dengan asumsi bahwa selama hunian terbangun, pasti akan laku dan MBR akan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.
Asumsi ini keliru, sebab MBR sangat bergantung pada sektor ekonomi informal dan kedekatan dengan komunitasnya. Mereka tidak bisa dengan mudah berpindah-pindah atau mengubah cara hidup secara drastis.
Jika kedua faktor fundamental ini terabaikan, tidak mengherankan jika MBR pada akhirnya memilih untuk meninggalkan hunian tersebut atau bahkan menjualnya. Ini menunjukkan adanya ketidakcocokan yang signifikan antara desain kebijakan dan realitas sosial ekonomi masyarakat sasaran.
Keempat faktor mendasar ini, yakni paradigma, kelembagaan, pasar, dan sosial politik, saling terkait erat dan membentuk lingkaran masalah dalam program perumahan rakyat. Cara pandang yang keliru sejak awal akan melahirkan kebijakan yang salah arah.
Kondisi ini diperparah dengan tata kelola yang tidak rapi serta ketergantungan yang berlebihan pada mekanisme pasar. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran ulang secara fundamental agar kebijakan perumahan tidak hanya sebatas intervensi pemerintah untuk membangun rumah, melainkan intervensi yang benar-benar berfondasi pada kesejahteraan rakyat.
Keberhasilan kebijakan harus diukur dari kebermanfaatannya bagi MBR, stabilitas mereka dalam bermukim, kedekatan dengan sumber penghasilan, serta kontribusinya dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Tanpa perhatian serius pada keempat aspek ini, program perumahan rakyat berisiko tinggi untuk terus menjadi “ilusi keberhasilan”, di mana rumah dibangun namun tidak memiliki makna dan fungsi optimal bagi penghuninya.