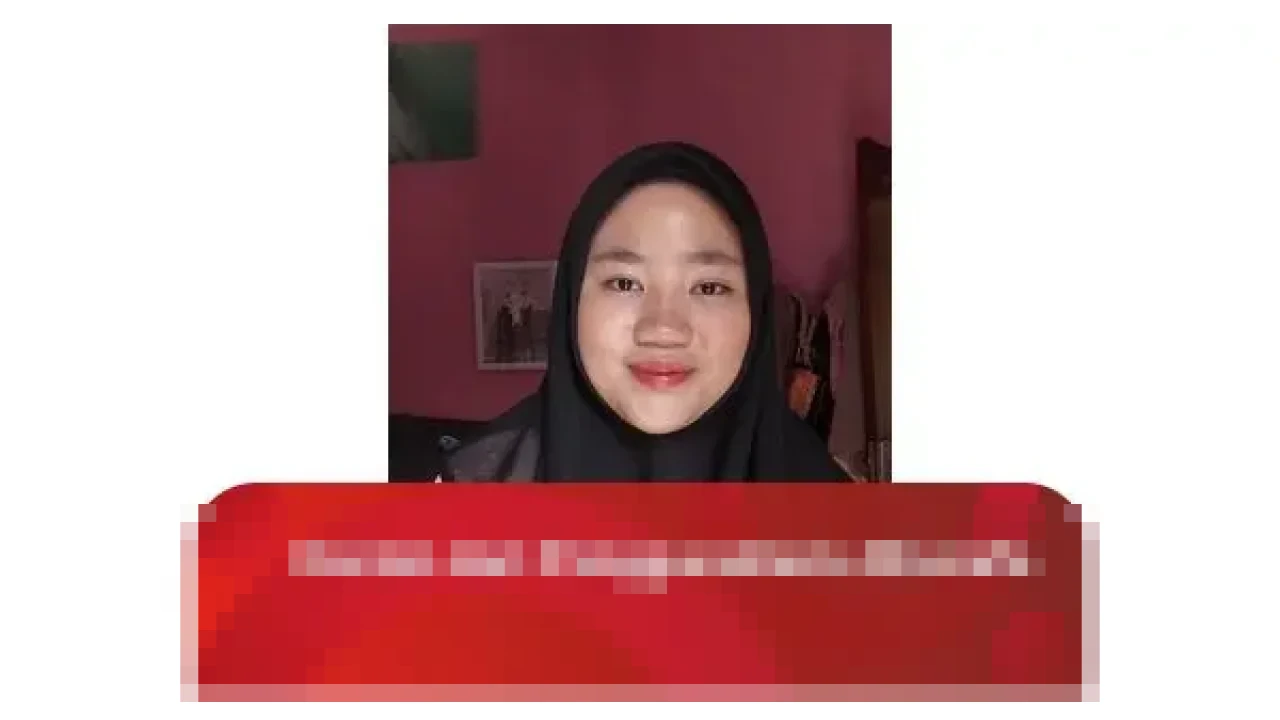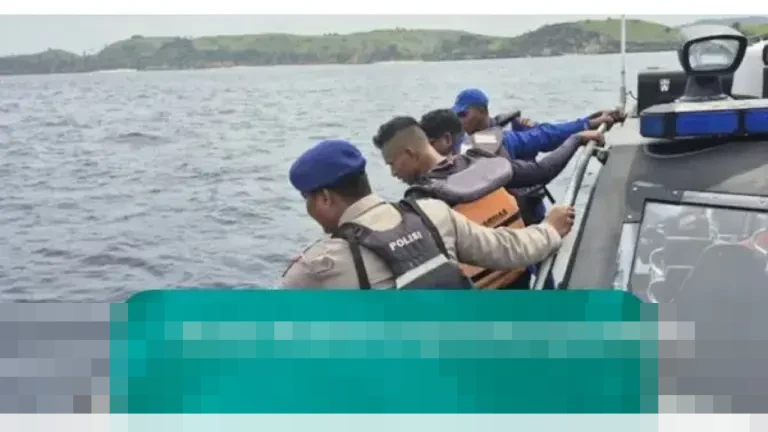Masyarakat Indonesia kerap membanggakan diri dengan keramahannya. Senyum mudah tersungging, sapaan hangat terdengar di mana-mana, dan frasa “tidak apa-apa” sering terucap, bahkan saat hati menyimpan keberatan. Namun, di balik citra tersebut, muncul pertanyaan krusial yang jarang diulas secara jujur: apakah keramahan ini cerminan sopan santun sejati, atau sekadar kepiawaian dalam berpura-pura?
Sejak dini, sopan santun telah diajarkan sebagai pilar moralitas dan tolok ukur kedewasaan serta kecerdasan sosial. Sikap halus, kemampuan menahan emosi, dan upaya menjaga perasaan orang lain kerap dipandang sebagai kebajikan luhur. Dalam kadar tertentu, nilai-nilai ini memang esensial. Tanpa sopan santun, hubungan sosial rentan retak akibat ego dan emosi yang tak terkendali.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Namun, dalam praktiknya, sopan santun sering kali bergeser menjadi tuntutan sosial yang membebani. Individu kerap merasa terpaksa bersikap ramah kepada pihak yang meremehkan, tertawa demi menjaga suasana, atau memilih diam agar tidak dicap “bermasalah”. Pada titik ini, sopan santun kehilangan fungsi etisnya dan berubah menjadi sebuah topeng. Penyesuaian diri dilakukan bukan atas dasar rasa hormat, melainkan karena ketakutan akan pengucilan.
Fenomena kepura-puraan sosial ini sering kali dilegitimasi dengan dalih profesionalisme atau kedewasaan. Padahal, implikasinya tidaklah sederhana. Penekanan perasaan secara terus-menerus menciptakan jurang antara realitas emosi dan ekspresi yang ditampilkan. Akibatnya, kelelahan emosional menjadi hal yang lumrah, bahkan dianggap sebagai harga yang harus dibayar demi penerimaan sosial.
Kehadiran media sosial semakin memperparah fenomena ini. Setiap individu dituntut untuk selalu tampil baik, santun, dan positif di setiap kesempatan. Kritik kerap disalahartikan sebagai kebencian, sementara ketidaksetujuan dianggap sebagai drama. Kondisi ini mendorong banyak orang memilih jalur aman: bersikap manis di permukaan, namun menyimpan keresahan secara personal. Ruang diskusi pun bergeser menjadi panggung pencitraan semata.
Kendati demikian, kejujuran bukanlah antitesis dari sopan santun. Permasalahan utama bukan terletak pada kejujuran itu sendiri, melainkan pada cara penyampaiannya. Kejujuran tanpa empati memang dapat melukai, namun sopan santun tanpa kejujuran hanya akan menciptakan relasi yang semu. Keduanya seharusnya tidak dipertentangkan, melainkan diseimbangkan secara harmonis.
Sopan santun yang sehat dan otentik lahir dari kesadaran, bukan dari kepura-puraan. Ia memberikan ruang bagi individu untuk menyatakan ketidaksetujuan tanpa merendahkan, serta untuk bersikap jujur tanpa harus melukai. Dalam sebuah masyarakat yang matang, perbedaan pendapat tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai indikator hidupnya sebuah dialog.
Maka, mungkin sudah saatnya kita menggeser pertanyaan dari “Apakah saya cukup sopan?” menjadi “Apakah saya masih jujur pada diri sendiri?”. Sebab, sopan santun sejati tidak pernah menuntut kita untuk mengorbankan kejujuran; justru, ia berfungsi untuk menjaganya agar tetap berada dalam koridor kemanusiaan.