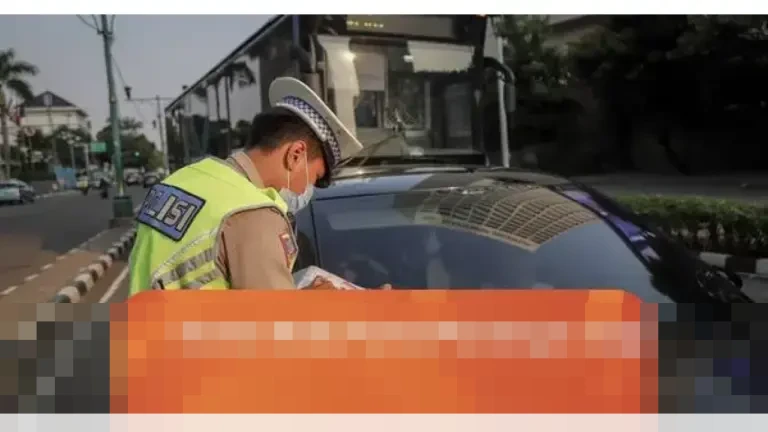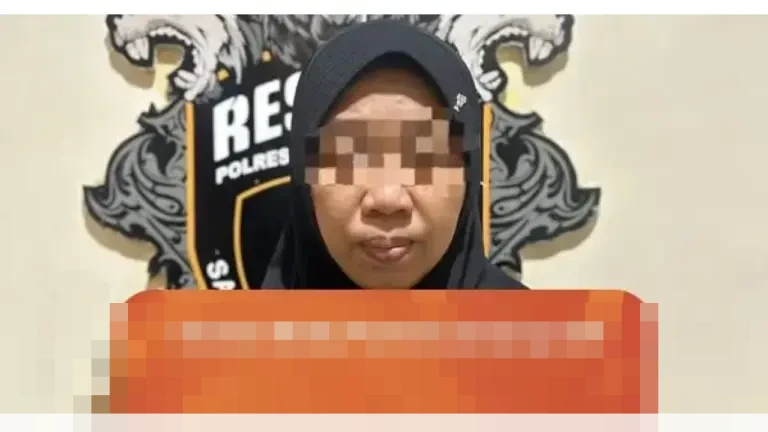Bencana alam tidak hanya merenggut tempat tinggal dan rutinitas harian, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan anak-anak di pengungsian. Mereka kehilangan akses sekolah, ruang bermain, dan aktivitas belajar yang terstruktur. Kondisi serba terbatas ini menuntut perhatian lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan fisik.
Negara umumnya hadir melalui bantuan logistik dasar seperti pangan, sandang, dan layanan kesehatan. Namun, kebutuhan anak-anak di pengungsian melampaui aspek fisik semata. Mereka juga memerlukan aktivitas sosial yang terkelola untuk menjaga keseharian tetap berjalan selama masa darurat.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Di tengah keterbatasan pengungsian Desa Ujung Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh, sebuah inisiatif berhasil menghadirkan kembali rutinitas bagi anak-anak. Melalui kegiatan membaca bersama, Satgas Senyar, TDMRC, dan Universitas Syiah Kuala (USK) menempatkan literasi sebagai aktivitas sosial sederhana yang menjaga hari-hari anak tetap terstruktur. Pendekatan ini menunjukkan bahwa buku dan kegiatan membaca bersama dapat menjadi sarana aktivitas sosial yang mudah diterapkan di pengungsian.
Tulisan ini secara spesifik menyoroti literasi sebagai bagian dari respons kemanusiaan, bukan sebagai pendekatan psikologis atau terapi klinis. Pengalaman penanganan bencana di Aceh mengindikasikan bahwa literasi belum terintegrasi dalam desain respons darurat. Kegiatan membaca lebih banyak muncul dari inisiatif relawan, bukan dari rancangan kebijakan yang jelas.
Literasi sebagai Kebutuhan Sosial Anak
Dalam situasi darurat, fokus utama memang tertuju pada pemenuhan kebutuhan fisik. Namun, bagi anak-anak, kebutuhan sosial menjadi bagian krusial untuk keberlanjutan hari-hari mereka di pengungsian. Ketiadaan aktivitas terstruktur membuat anak-anak menghabiskan waktu tanpa arah, dengan sekolah yang terhenti dan ruang bermain yang terbatas.
Literasi dapat berperan signifikan pada tahap ini. Membaca bersama, mendengarkan cerita, atau sekadar melihat buku merupakan kegiatan yang mudah diterapkan dan tidak memerlukan sarana rumit. Buku memberikan anak-anak aktivitas yang dikenali, dapat dilakukan secara berkelompok, mengisi waktu pengungsian, dan menjaga interaksi antar anak.
Dalam konteks ini, literasi berfungsi sebagai pengisi aktivitas harian yang sederhana dan aman, relevan diterapkan pada fase darurat. Namun, masalahnya adalah literasi belum diposisikan sebagai bagian dari respons resmi penanganan bencana. Tanpa desain yang jelas, kegiatan ini sulit berjalan secara berkelanjutan.
Keterbatasan di Lapangan: Pelajaran dari Aceh
Kegiatan literasi di pengungsian Aceh menghadapi banyak keterbatasan. Relawan bergerak dengan sumber daya yang minim, dan jumlah anak seringkali tidak sebanding dengan buku yang tersedia. Buku yang dibawa relawan seringkali hanya cukup untuk kegiatan singkat, sehingga pemanfaatannya harus bergantian dan tidak semua anak dapat terlayani secara bersamaan.
Akses ke sumber donasi buku juga tidak mudah, mengingat donatur umumnya berada di luar daerah terdampak. Dalam situasi darurat, distribusi dan komunikasi menjadi kendala serius. Kondisi ini diperberat oleh rusaknya sumber literasi lokal seperti taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa, dan perpustakaan sekolah di wilayah terdampak, dengan banyak koleksi yang terendam atau rusak.
Meskipun buku sebenarnya masih tersedia di daerah yang berdekatan dengan wilayah terdampak, koordinasi pemanfaatan lintas wilayah sulit terbentuk. Tidak adanya pihak yang memimpin koordinasi tersebut mengakibatkan ketersediaan buku tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari sini terlihat bahwa persoalan bantuan buku dalam bencana bukan terletak pada ketersediaan, melainkan pada kepemimpinan dan desain koordinasi.
Dilema Perpustakaan Pemerintah
Perpustakaan pemerintah berada pada posisi yang tidak sederhana dalam konteks bencana. Buku yang dikelola perpustakaan pemerintah merupakan Barang Milik Negara (BMN) dan diklasifikasikan sebagai aset tetap, bukan barang persediaan. Status ini memiliki konsekuensi langsung: buku tidak dirancang untuk dipindahkan secara cepat, dan pemanfaatannya terikat pada lokasi serta tujuan pengadaan.
Pengadaan buku pemerintah umumnya bersifat spesifik, dibeli untuk ditempatkan di perpustakaan tertentu atau didistribusikan sebagai bantuan langsung ke lokus tertentu. Dalam skema ini, hampir tidak tersedia stok cadangan untuk kondisi darurat. Kadang terdapat buku donasi yang tidak memenuhi kriteria koleksi, namun jumlahnya terbatas dan tidak dirancang untuk kebutuhan pengungsian skala besar.
Dalam situasi bencana di Aceh, permintaan bantuan buku untuk kegiatan literasi di titik pengungsian datang dari berbagai pihak, mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Namun, pada saat yang sama, banyak perpustakaan di wilayah terdampak juga mengalami kerusakan, sementara tata kelola buku pemerintah tidak dirancang untuk tanggap darurat. Hal ini menciptakan jarak antara kebutuhan lapangan dan desain kebijakan yang tersedia.
Bantuan Buku Bukan Bantuan Sekali Pakai
Dalam penanganan bencana, semua bantuan sering diperlakukan dengan cara yang sama. Buku yang tiba di posko satgas kerap diperlakukan seperti bantuan konsumsi: diterima, dimuat, lalu dibagikan. Pendekatan ini menimbulkan persoalan karena buku bukan barang sekali pakai dan tidak dirancang untuk dihabiskan dalam satu waktu.
Ketika buku langsung dibagikan kepada anak-anak, pemanfaatannya tidak terkelola. Tidak ada pendampingan membaca, tidak ada pengaturan penggunaan, dan kondisi buku tidak terjaga. Bantuan buku seharusnya diperlakukan berbeda; buku perlu dikelola sebagai alat kegiatan, digunakan dalam aktivitas membaca bersama, dan diputar pemanfaatannya.
Peran satgas menjadi penting dalam hal ini. Satgas tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mengelola penggunaannya. Buku dapat dibawa secara berpindah antar titik pengungsian atau ditempatkan di satu lokasi dengan relawan pengelola, memastikan manfaatnya menjangkau lebih banyak anak secara berkelanjutan.
Kerusakan Perpustakaan dan Pentingnya Pendataan
Bencana juga berdampak langsung pada perpustakaan. Banyak perpustakaan di wilayah terdampak mengalami kerusakan, mulai dari bangunan yang rusak, koleksi yang terendam, hingga layanan yang terhenti. Untuk perpustakaan pemerintah, jalur pemulihan relatif tersedia melalui skema anggaran, meskipun prosesnya tidak cepat.
Kondisi berbeda dihadapi perpustakaan non-pemerintah seperti taman bacaan masyarakat dan perpustakaan komunitas. Mereka tidak memiliki dukungan anggaran rutin, sehingga pemulihan menjadi lebih sulit ketika rusak. Dalam masa darurat, dorongan untuk segera merehabilitasi dapat dipahami, namun dari sisi tata kelola, langkah ini belum tepat karena data kerusakan belum lengkap dan kondisi lapangan belum stabil.
Pada fase ini, inventarisasi menjadi langkah penting. Pendataan diperlukan sebagai dasar perencanaan pemulihan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Penutup
Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa literasi belum menjadi bagian dari desain respons bencana yang terintegrasi. Kegiatan membaca di pengungsian masih sangat bergantung pada inisiatif relawan. Buku, sebagai alat kegiatan, perlu dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak anak. Pendekatan ini membutuhkan peran aktif satgas dan dukungan kebijakan yang sederhana.
Keberpihakan negara terhadap literasi masyarakat terdampak bencana tidak ditentukan oleh kecepatan membagi buku. Keberpihakan tersebut ditunjukkan melalui desain kebijakan yang memungkinkan literasi berjalan di masa darurat dan pulih secara berkelanjutan setelahnya.