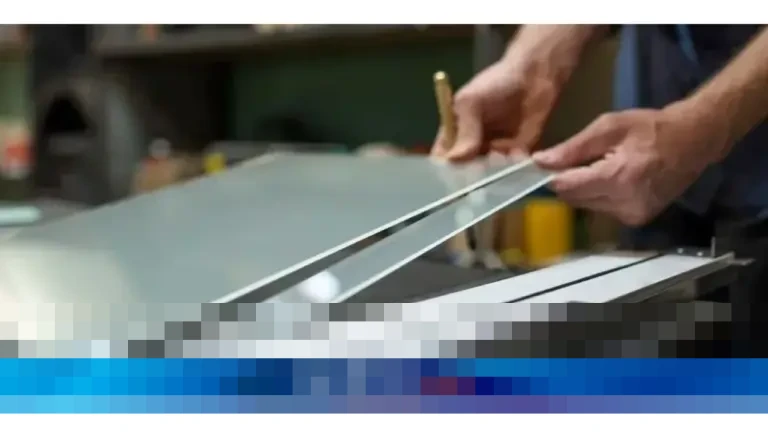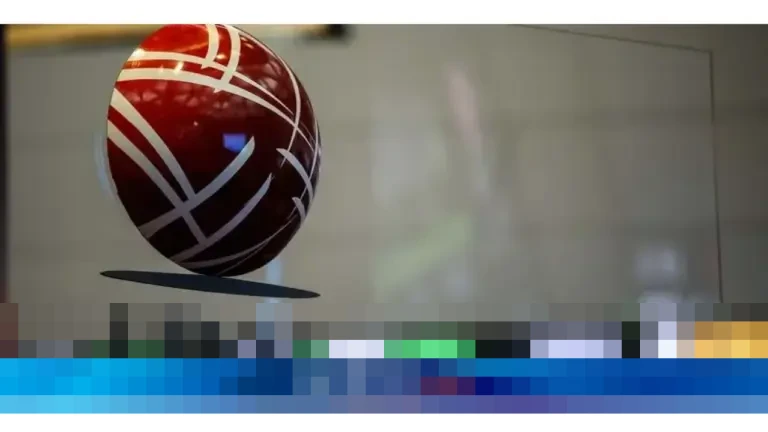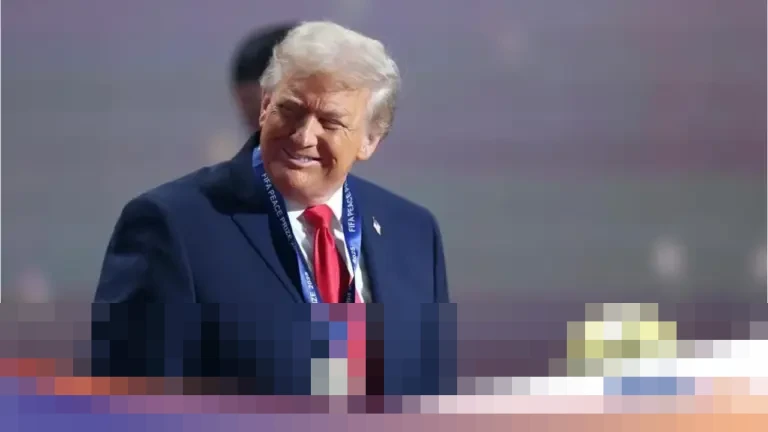Di era digital yang serba cepat ini, definisi kekayaan telah mengalami pergeseran signifikan. Jika dahulu kemapanan diukur dari isi rekening atau kepemilikan aset nyata, kini ia menjelma menjadi citra, narasi, dan tampilan visual yang dipamerkan di platform daring.
Fenomena inilah yang melahirkan istilah “fake rich” atau kaya semu, sebuah gejala sosial yang kian menguat melalui unggahan di Instagram, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Menurut Mureks, fenomena ini bukan sekadar pamer barang mewah, melainkan refleksi dari perubahan makna sukses, tekanan sosial di ruang digital, krisis literasi keuangan, serta problem etika dan nilai yang mendalam.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Media Sosial: Panggung Kompetisi Simbolik
Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekspresi diri, tetapi juga menjadi panggung kompetisi simbolik. Di sini, individu berlomba-lomba menunjukkan “keberhasilan” mereka, tak jarang dengan menutupi realitas finansial yang sebenarnya rapuh, bahkan terjerat utang dan kepura-puraan.
Logika visual yang dominan di media sosial turut memperkuat fenomena ini. Algoritma platform lebih mengedepankan hasil atau pencapaian yang tampak, bukan proses di baliknya. Unggahan foto mobil mewah, kopi mahal, jam tangan bermerek, atau liburan ke luar negeri jauh lebih “menjual” dan menarik perhatian dibandingkan cerita tentang menabung, kerja keras bertahun-tahun, atau gaya hidup sederhana.
Dalam konteks ini, kekayaan tidak lagi harus nyata, melainkan cukup terlihat kaya. Berbagai cara dilakukan untuk menciptakan ilusi ini: barang bisa disewa, uang bisa dipinjam, dan gaya hidup mewah bisa dicicil. Hal terpenting adalah citra kemapanan berhasil diproduksi dan divalidasi melalui “likes”, komentar, serta jumlah pengikut. Media sosial, dengan demikian, berfungsi sebagai mesin pembentuk ilusi, tempat simbol-simbol kemewahan dipamerkan tanpa harus didukung oleh fondasi ekonomi yang kuat.
Dampak Budaya Influencer dan Demokratisasi Flexing
Fenomena “fake rich” semakin diperkuat oleh budaya influencer. Banyak figur di media sosial menampilkan diri sebagai representasi kesuksesan instan: muda, modis, sering bepergian, dan tampak hidup tanpa beban. Narasi yang mereka bangun seringkali sederhana dan menggoda, seolah mengatakan bahwa “semua bisa sukses asal mau usaha.” Namun, realitas di balik layar, seperti utang, sponsor, tekanan menjaga citra, atau bahkan ketidakstabilan finansial, jarang sekali ditampilkan.
Aksi flexing atau memamerkan kekayaan sebenarnya bukanlah hal baru. Namun, di era media sosial, flexing mengalami demokratisasi. Jika dulu hanya orang kaya sungguhan yang mampu memamerkan kemewahan, kini siapa pun bisa melakukannya dengan bantuan teknologi dan instrumen keuangan. Mureks mencatat bahwa inilah titik di mana “fake rich” lahir; bukan sekadar pamer, melainkan penciptaan identitas palsu tentang kemapanan.
Ironisnya, individu yang “fake rich” seringkali justru mendapat apresiasi sosial. Lingkungan digital memberikan ganjaran berupa atensi dan pengakuan. Dalam masyarakat yang semakin mengukur nilai diri dari persepsi publik, pengakuan semacam ini terasa lebih berharga daripada stabilitas finansial jangka panjang. Akibatnya, seseorang bisa tampak “naik kelas” secara sosial, meski secara ekonomi justru sedang terjebak dalam tumpukan cicilan, tabungan minim, dan masa depan keuangan yang rapuh, semuanya tertutupi oleh unggahan yang tampak glamor.