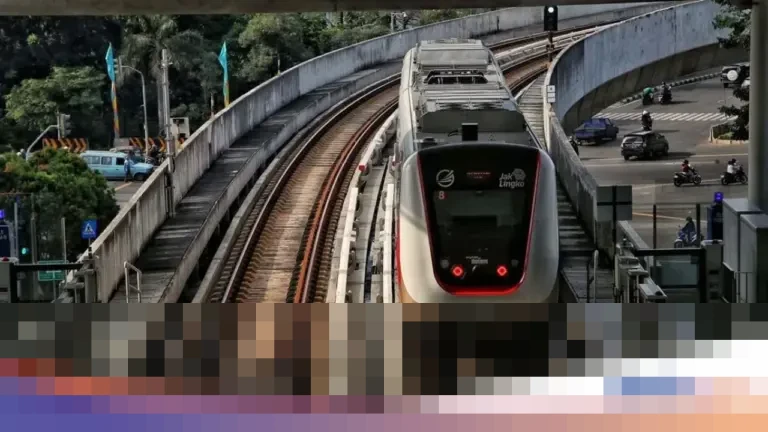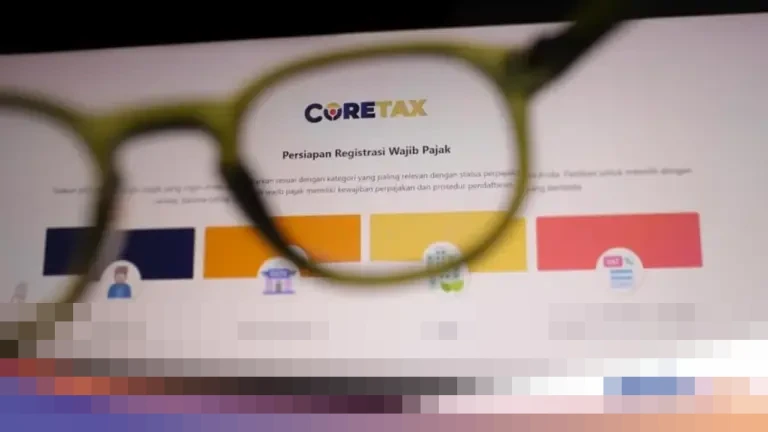Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, menyoroti kondisi ketenagakerjaan Indonesia sepanjang tahun 2025 yang dinilainya rapuh, meskipun pemerintah kerap menyampaikan narasi optimistis. Menurut Tan, terdapat jurang yang semakin lebar antara klaim kebijakan dengan pengalaman riil para pekerja di lapangan.
Dalam kolomnya yang diterbitkan pada Rabu, 31 Desember 2025, Aznil Tan menegaskan bahwa ketenagakerjaan adalah fondasi utama pembangunan sosial dan ekonomi. Sekitar 75 persen rumah tangga Indonesia menggantungkan hidupnya pada pendapatan sebagai pekerja. Oleh karena itu, isu pekerjaan tidak bisa dipandang sekadar masalah teknis ekonomi, melainkan menyentuh langsung keberlanjutan hidup mayoritas warga negara serta stabilitas sosial nasional.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Isu ketersediaan dan kualitas lapangan kerja bahkan menjadi janji politik utama dalam Pemilihan Presiden 2024. Harapannya, negara mampu menyediakan pekerjaan yang tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga layak, aman, dan berkelanjutan.
Optimisme Statistik Kontras dengan Realitas Lapangan
Aznil Tan mengamati adanya paradoks dalam wacana dan realitas ketenagakerjaan sepanjang 2025. Di satu sisi, pemerintah optimistis mengenai peningkatan jumlah penduduk bekerja dan potensi penciptaan jutaan lapangan kerja. Di sisi lain, pemerintah juga mengklaim bahwa kebijakan perlindungan terhadap kualitas pekerja Indonesia telah berjalan dengan baik.
Namun, optimisme statistik ini tidak selalu sejalan dengan kondisi kerja di lapangan. Realitas pekerja masih diwarnai oleh kontrak jangka pendek, ketidakpastian penghasilan, lemahnya perlindungan hak-hak pekerja, serta terbatasnya peluang peningkatan kesejahteraan dan mobilitas sosial. Ruang publik justru dipenuhi oleh berbagai fenomena yang mencerminkan keresahan pasar kerja, mulai dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), kekhawatiran atas kualitas lapangan kerja, perdebatan mengenai krisis ketenagakerjaan, hingga narasi tentang tergerusnya kelas menengah.
Kondisi ini, menurut Tan, menunjukkan bahwa indikator makro ketenagakerjaan belum sepenuhnya menangkap tekanan struktural yang dialami pekerja dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, klaim keberhasilan ketenagakerjaan tidak cukup dibaca dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau peningkatan jumlah penduduk bekerja semata.
Tiga Persoalan Kunci Kerapuhan Pasar Kerja
Evaluasi kebijakan ketenagakerjaan, lanjut Aznil Tan, harus menguji keselarasan antara statistik resmi, struktur pasar kerja domestik, kebijakan migrasi tenaga kerja, serta dampaknya terhadap kondisi kerja, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja—baik di dalam maupun di luar negeri. Pembacaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan Indonesia tidak terletak pada satu aspek tunggal, melainkan pada arsitektur pasar kerja itu sendiri yang tampak membaik secara angka, tetapi rapuh secara substansi.
Kerentanan ini bukan anomali, melainkan hasil dari pola struktural yang saling terkait dan berlangsung secara sistemik. Setidaknya terdapat tiga persoalan kunci yang menjelaskan mengapa perbaikan statistik ketenagakerjaan tidak berbanding lurus dengan perbaikan kondisi kerja di lapangan:
- Ilusi penciptaan lapangan kerja: Peningkatan jumlah orang bekerja tidak selalu mencerminkan bertambahnya posisi kerja baru secara bersih.
- Prekarisasi dan jebakan upah murah: Banyak pekerja tetap bekerja, namun tanpa kepastian, perlindungan, dan prospek mobilitas sosial.
- Migrasi tenaga kerja: Baik ke sektor informal di dalam negeri maupun ke luar negeri, muncul sebagai respons struktural atas kegagalan pasar kerja domestik dalam menyediakan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Evaluasi Kuantitas dan Ketersediaan Lapangan Kerja
Aznil Tan menekankan bahwa evaluasi ketenagakerjaan tidak cukup dilakukan dengan menghitung jumlah orang yang bekerja atau menurunnya tingkat pengangguran. Penilaian harus mencakup kuantitas penciptaan dan ketersediaan lapangan kerja, kualitas hubungan kerja dan kepastian kerja, serta berbagai penggerak struktural yang membentuk dinamika pasar kerja.
Pendekatan kuantitatif yang hanya menyoroti jumlah orang bekerja berisiko menimbulkan ilusi kinerja, karena tidak membedakan antara penciptaan posisi kerja baru, keberlanjutan pekerjaan lama, rotasi tenaga kerja, serta kehilangan pekerjaan akibat PHK, efisiensi, dan penutupan usaha.
Per Agustus 2025, jumlah penduduk bekerja tercatat mencapai 146,54 juta orang, meningkat sekitar 1,90 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah memproyeksikan penciptaan hingga 3,59 juta lapangan kerja sepanjang 2025. Namun, realisasi penyerapan menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut belum cukup untuk menjawab kebutuhan struktural tahunan.
Peningkatan penyerapan lebih berfungsi menahan lonjakan pengangguran, bukan menciptakan ekspansi lapangan kerja baru yang kuat dan berkelanjutan. Secara struktural, Indonesia membutuhkan sekitar 3,4–3,9 juta lapangan kerja baru setiap tahun hanya untuk menahan peningkatan pengangguran. Kebutuhan ini bersumber dari pertumbuhan penduduk usia kerja serta lulusan pendidikan menengah dan tinggi, dan merepresentasikan beban minimum tahunan yang harus dijawab kebijakan negara, terlepas dari kondisi ekonomi global atau siklus bisnis jangka pendek.
Lembaga keuangan global Morgan Stanley mencatat, tingkat pengangguran usia 15-24 tahun di Indonesia mencapai 17,3 persen, angka yang termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan Asia.
Pada titik inilah, kebijakan ketenagakerjaan perlu diuji bukan hanya dari niat dan desainnya, tetapi dari output yang benar-benar dihasilkannya: apakah mendorong kerja layak dan berkelanjutan, atau justru mereproduksi jebakan upah murah dan memperluas kerja rapuh (precarious work) di balik perbaikan angka statistik.