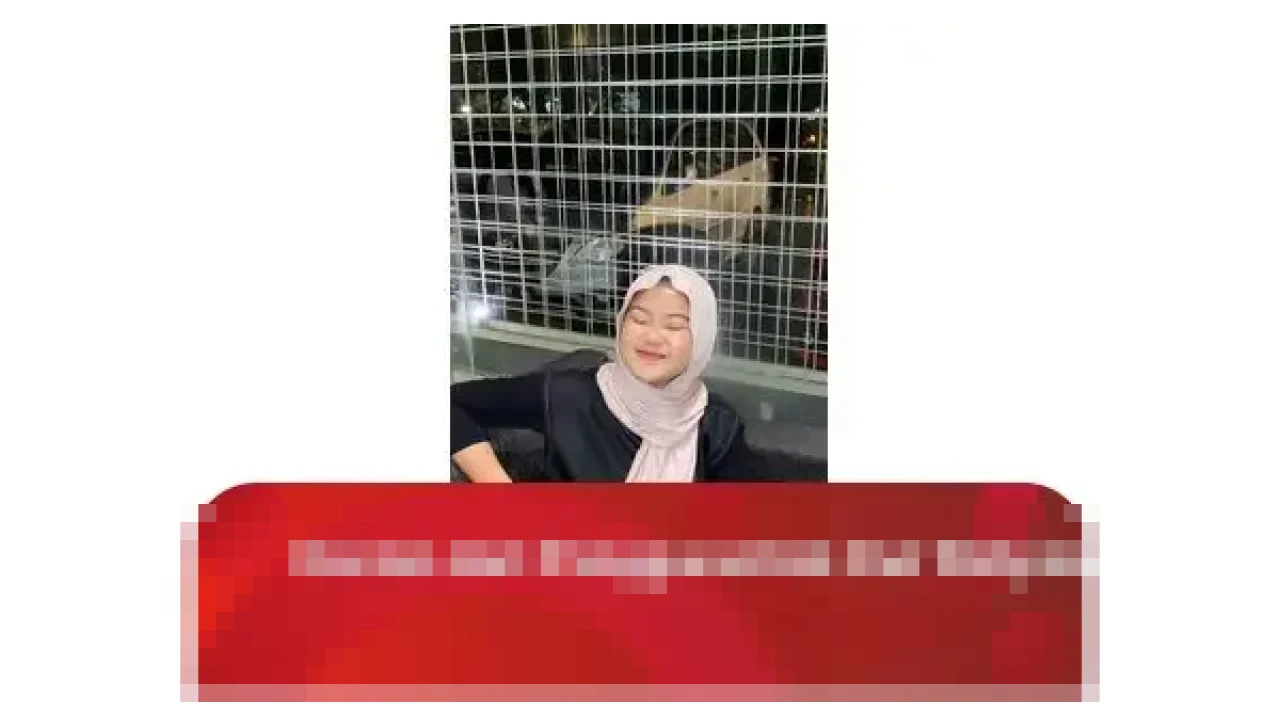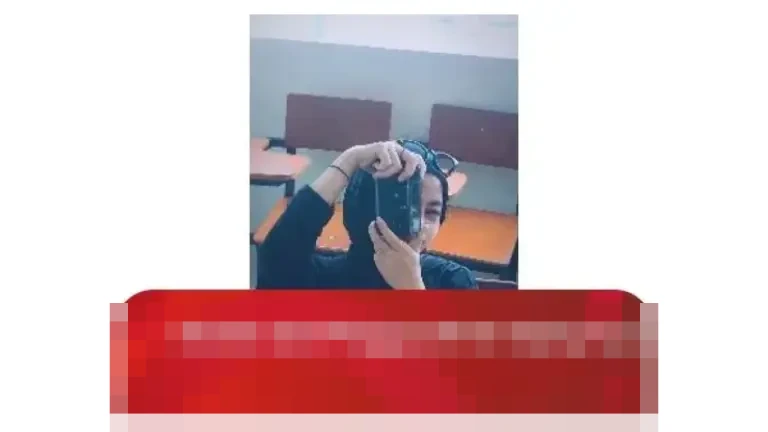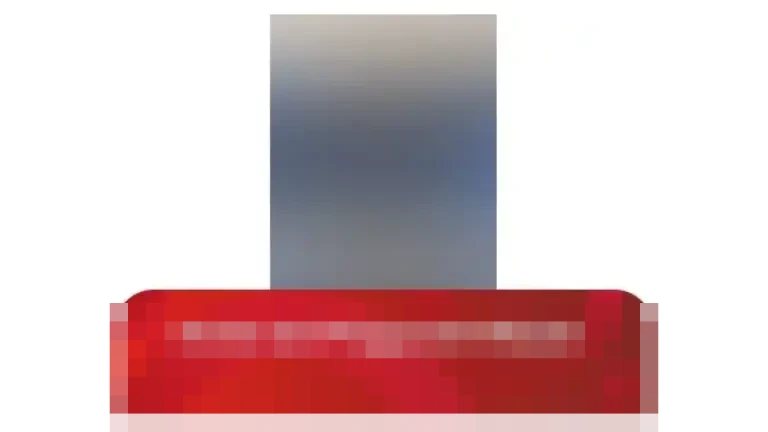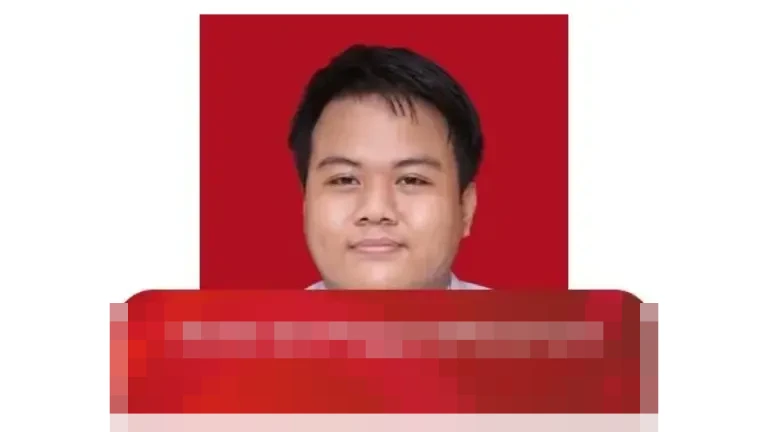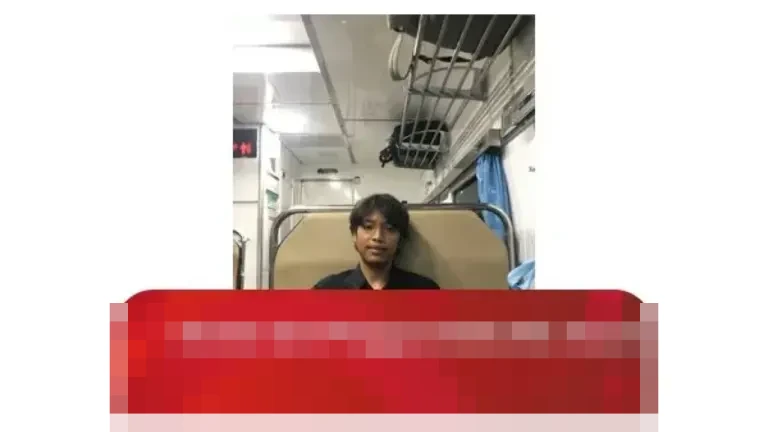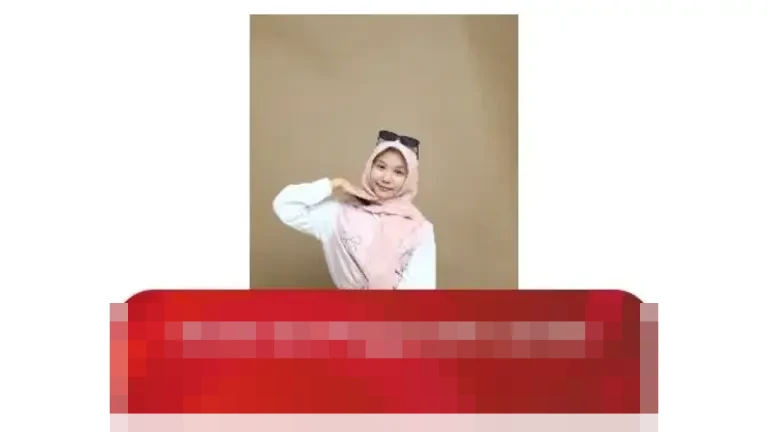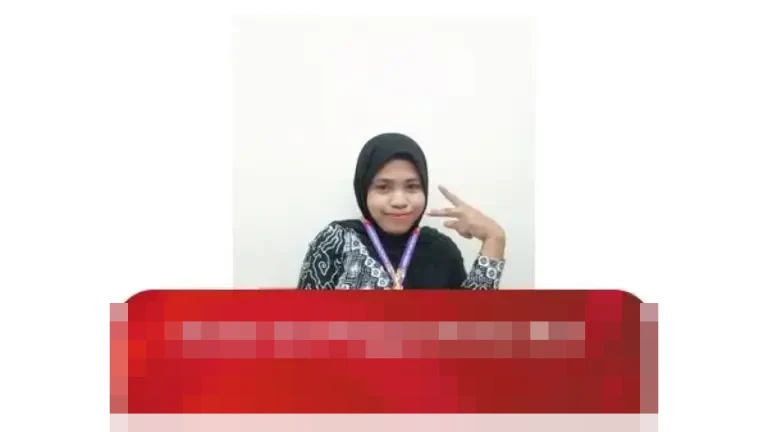Kehidupan remaja di Indonesia saat ini tak bisa dilepaskan dari gawai pintar dan berbagai platform digital. Aplikasi seperti TikTok, Instagram, hingga WhatsApp telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian mereka. Fenomena ini bukan tanpa alasan, mengingat survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2025 mencatat bahwa pengguna internet di Tanah Air mencapai 229,4 juta jiwa, dengan Generasi Z menjadi kelompok yang paling dominan dalam mengakses media sosial.
Dominasi penggunaan media sosial ini membawa pengaruh signifikan terhadap pembentukan kepribadian remaja, khususnya dalam fase pencarian identitas diri. Psikolog Vera Itabiliana dari Universitas Indonesia menyoroti bagaimana media sosial secara fundamental telah mengubah cara remaja mengenali diri mereka sendiri, sebuah proses krusial dalam perkembangan psikososial.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Dua Sisi Mata Uang: Manfaat dan Risiko Media Sosial
Media sosial menawarkan ruang ekspresi dan koneksi yang luas bagi remaja. Platform-platform ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi minat, berbagi kreativitas, dan bergabung dengan berbagai komunitas daring. Tak jarang, remaja menemukan dukungan emosional dari teman-teman virtual, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Hal ini secara positif mendukung perkembangan sosial dan meningkatkan rasa percaya diri mereka.
Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat pula risiko yang mengintai. Paparan terhadap konten-konten yang menampilkan kehidupan “ideal” sering kali memicu perbandingan diri yang tidak sehat, fenomena Fear of Missing Out (FOMO), serta tindakan perundungan siber atau cyberbullying. Berbagai riset menunjukkan adanya peningkatan kasus kecemasan dan depresi pada remaja yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial yang berlebihan.
Perspektif Erik Erikson: Krisis Identitas di Era Digital
Dalam teori psikososialnya, Erik Erikson menggambarkan masa remaja sebagai tahap “Identity vs Role Confusion” atau Identitas versus Kebingungan Peran. Pada fase ini, remaja secara aktif mencari jawaban atas pertanyaan fundamental “Siapa aku?” melalui eksplorasi berbagai peran dan nilai dalam hidup mereka.
Menurut Erikson, kondisi ideal bagi proses ini adalah melalui interaksi nyata dan autentik dengan keluarga, teman sebaya, serta masyarakat luas. Dukungan yang tulus dari lingkungan sekitar akan membantu remaja membentuk identitas yang kuat dan resilien, mampu menghadapi berbagai tantangan hidup.
Sayangnya, kondisi ideal tersebut kini menghadapi tantangan besar di era digital. Media sosial menggeser proses eksplorasi identitas ke dunia virtual. Validasi yang didapatkan dari “like” dan komentar di media sosial cenderung membuat identitas remaja menjadi rapuh dan bergantung pada pengakuan eksternal. Perbandingan diri yang konstan dan ancaman cyberbullying semakin memperburuk kebingungan peran yang mereka alami.
Akibatnya, remaja sering kali membangun “topeng” atau persona yang berbeda di dunia maya, yang dapat menyebabkan fragmentasi diri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah mental jangka panjang, karena mereka kesulitan menemukan jati diri yang autentik.
Mencari Keseimbangan: Peran Orang Tua dan Sekolah
Menyikapi kompleksitas ini, orang tua dan pihak sekolah memiliki peran krusial dalam mendampingi remaja. Literasi digital yang komprehensif serta dorongan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan offline perlu digalakkan. Guru Bimbingan dan Konseling juga dapat menerapkan pendekatan teori Erikson melalui lokakarya atau sesi refleksi diri, membantu remaja memahami dan mengelola proses pencarian identitas mereka.
Pada akhirnya, media sosial dapat menjadi alat yang positif jika digunakan secara seimbang dan bijak. Namun, tanpa pengawasan dan bimbingan yang memadai, platform digital ini berpotensi menghambat pembentukan kepribadian ideal remaja. Generasi muda membutuhkan arahan yang tepat agar dapat tumbuh menjadi individu yang autentik dan resilien di tengah derasnya arus informasi digital.