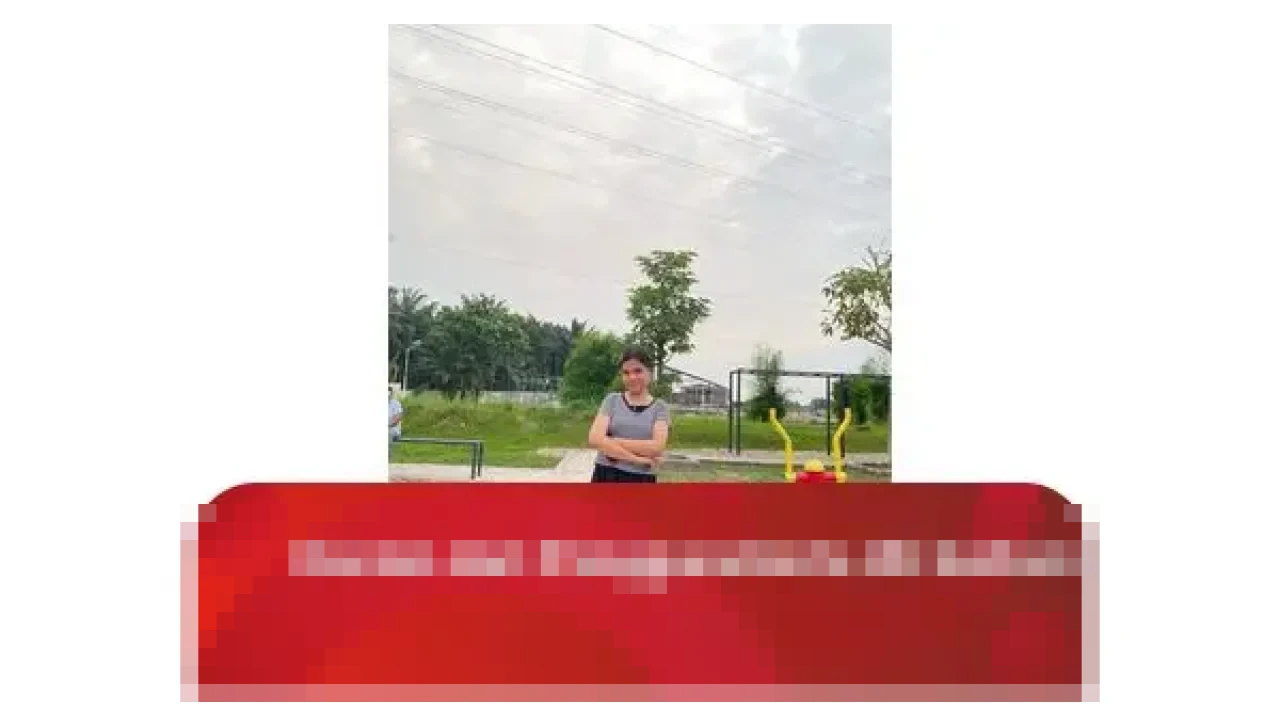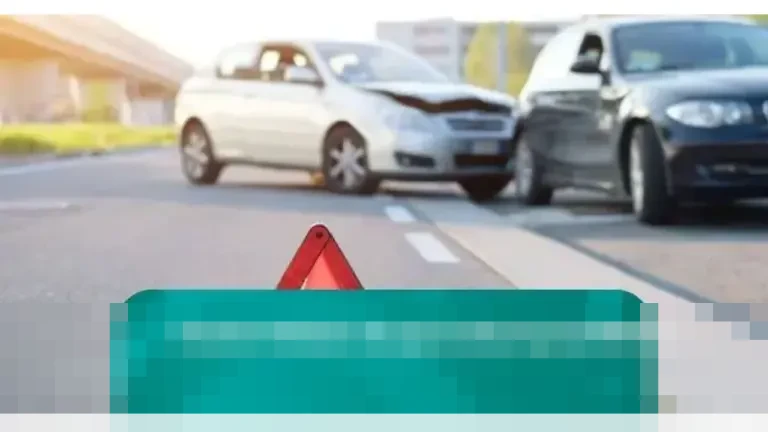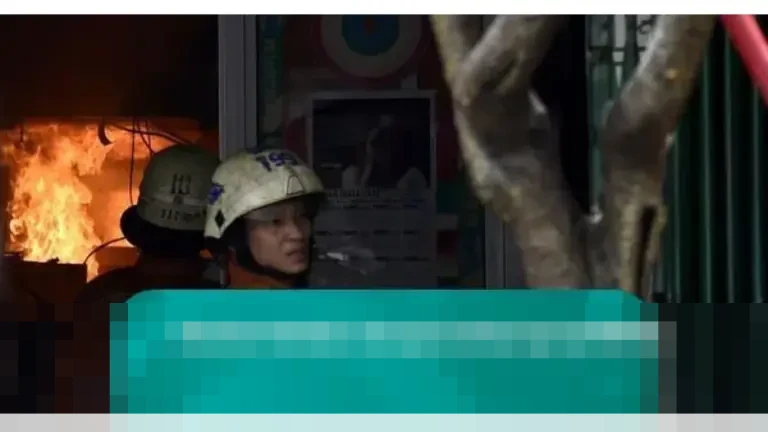Etika profesi, yang seharusnya menjadi kompas moral, kini kian retak diterpa ambisi dan kekuasaan. Fenomena ini tidak hanya mengikis nurani individu, tetapi juga mengancam fondasi kepercayaan publik serta masa depan demokrasi di Indonesia.
Kita hidup di tengah zaman ketika ambisi dan kekuasaan menjadi mata uang utama kesuksesan. Prestasi seringkali diukur dari jabatan, pengaruh, dan kekayaan, bukan lagi dari integritas. Dalam situasi seperti ini, etika profesi perlahan mengalami retakan. Ia terdesak oleh kepentingan pribadi, tekanan struktural, dan budaya permisif yang menormalisasi pelanggaran selama hasilnya menguntungkan.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia hadir dalam berbagai profesi, mulai dari hukum, kesehatan, pendidikan, jurnalistik, hingga birokrasi. Ketika profesional yang seharusnya menjadi penjaga nilai justru terlibat dalam penyimpangan, pertanyaan mendasar muncul: apa yang sedang rusak dalam sistem kita?
Ketika Etika Tak Lagi Menjadi Kompas
Etika profesi sejatinya adalah kompas moral yang menuntun setiap individu dalam menjalankan keahliannya. Ia bukan sekadar aturan tertulis atau sumpah jabatan yang diucapkan di awal karier, melainkan nilai yang hidup dalam keputusan sehari-hari.
Namun, dalam realitas sosial saat ini, etika profesi kian sering terdengar sebagai jargon normatif—indah diucapkan, mudah dilupakan. Retaknya etika profesi merupakan ancaman serius bagi kepercayaan publik dan masa depan demokrasi, serta tidak dapat diselesaikan hanya dengan sanksi individual tanpa pembenahan budaya dan struktur kekuasaan.
Etika Profesi: Fondasi yang Sering Dianggap Formalitas
Secara konseptual, etika profesi berfungsi untuk melindungi kepentingan publik, menjaga martabat profesi, dan memastikan bahwa keahlian digunakan secara bertanggung jawab. Kode etik profesi lahir dari kesadaran bahwa keahlian memberi kuasa, dan kuasa selalu mengandung potensi penyalahgunaan.
Namun dalam praktiknya, etika sering diperlakukan sebagai formalitas administratif. Ia hadir dalam modul pelatihan, dokumen akreditasi, atau pidato seremonial, tetapi absen dalam pengambilan keputusan nyata. Banyak profesional mengetahui apa yang benar, tetapi memilih yang menguntungkan.
Sebuah survei Transparency International menunjukkan bahwa rendahnya integritas profesional berkorelasi kuat dengan tingginya toleransi terhadap korupsi. Artinya, ketika etika tidak diinternalisasi, pelanggaran bukan lagi penyimpangan, melainkan kebiasaan.
Ambisi dan Kekuasaan: Dua Tekanan Utama Etika
Ambisi pada dasarnya bukan sesuatu yang keliru. Ia dapat menjadi pendorong inovasi dan kemajuan. Namun, ketika ambisi tidak dibingkai oleh etika, ia berubah menjadi dorongan tanpa batas. Dalam banyak kasus, profesional menghadapi dilema antara mempertahankan nilai atau mengejar posisi.
Kekuasaan memperparah situasi ini. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar godaan untuk memanipulasi aturan. Lord Acton pernah menyatakan, “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Ungkapan ini relevan dalam konteks profesi modern, terutama ketika mekanisme pengawasan lemah.
Dalam birokrasi, misalnya, jabatan sering menjadi alat transaksi politik. Profesional yang seharusnya netral terjebak dalam loyalitas struktural. Akibatnya, keputusan tidak lagi berbasis kepentingan publik, melainkan kepentingan elite.
Retaknya Etika dalam Berbagai Profesi
Profesi Hukum: Keadilan yang Tumpul ke Atas
Profesi hukum idealnya berdiri di garda terdepan keadilan. Namun, realitas menunjukkan bahwa hukum kerap tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kasus suap aparat penegak hukum, mafia peradilan, hingga kriminalisasi terhadap pihak lemah menjadi contoh nyata.
Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa penegak hukum termasuk kelompok profesi yang rentan terlibat korupsi. Fenomena ini mencerminkan bahwa pengetahuan hukum tanpa integritas justru menjadi alat legitimasi ketidakadilan. Ketika etika profesi hukum runtuh, keadilan berubah menjadi komoditas, publik kehilangan kepercayaan, dan hukum kehilangan wibawanya.
Dunia Kesehatan: Antara Pelayanan dan Kepentingan Bisnis
Dalam profesi kesehatan, etika berkaitan langsung dengan nyawa manusia. Prinsip nonmaleficence (tidak membahayakan) dan beneficence (berbuat baik) seharusnya menjadi pedoman utama. Namun, industrialisasi layanan kesehatan menghadirkan konflik kepentingan serius.
Kasus overdiagnosis, resep berlebihan, hingga praktik rujukan demi keuntungan finansial menunjukkan bagaimana etika dapat tergeser oleh logika bisnis. Pasien tidak lagi dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi, melainkan objek ekonomi. Situasi ini memperlihatkan bahwa ketika sistem mendorong keuntungan lebih dari kemanusiaan, etika profesi berada dalam posisi rentan.
Media dan Jurnalistik: Antara Kebenaran dan Klik
Jurnalisme memegang peran vital dalam demokrasi. Namun, tekanan industri media digital melahirkan praktik yang mengorbankan etika. Judul sensasional, berita tidak terverifikasi, dan framing manipulatif menjadi strategi bertahan hidup.
Dewan Pers berulang kali mengingatkan tentang pelanggaran kode etik jurnalistik. Sayangnya, sanksi sering kalah cepat dibanding dampak informasi keliru yang sudah terlanjur menyebar. Ketika media kehilangan etika, publik kehilangan panduan kebenaran.
Pendidikan: Keteladanan yang Memudar
Pendidikan seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter. Namun, kasus plagiarisme akademik, jual beli nilai, hingga kekerasan di institusi pendidikan menunjukkan adanya krisis etika.
Guru dan dosen bukan hanya pengajar, tetapi teladan moral. Ketika mereka terlibat dalam praktik tidak etis, kerusakan yang ditimbulkan bersifat jangka panjang karena menyangkut generasi masa depan.
Akar Masalah: Sistem, Budaya, dan Impunitas
Retaknya etika profesi tidak bisa dilepaskan dari sistem yang permisif. Budaya organisasi yang menormalisasi pelanggaran, minimnya perlindungan bagi pelapor (whistleblower), serta lemahnya penegakan sanksi menciptakan iklim impunitas.
Dalam banyak kasus, pelanggaran etika tidak berujung pada konsekuensi serius. Ini mengirim pesan berbahaya: bahwa pelanggaran dapat ditoleransi selama dilakukan oleh pihak berkuasa.
Mengapa Ini Berbahaya bagi Publik?
Ketika etika profesi runtuh, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik memburuk, ketimpangan melebar, dan kepercayaan sosial terkikis. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan kohesi sosial dan demokrasi.
Kepercayaan publik adalah modal sosial yang mahal. Sekali hilang, ia sulit dipulihkan.
Membangun Kembali Etika: Dari Individu hingga Sistem
Pemulihan etika profesi harus dimulai dari internalisasi nilai sejak pendidikan awal. Etika tidak cukup diajarkan, tetapi harus dicontohkan. Selain itu, sistem harus dirancang untuk menghargai integritas, bukan hanya capaian kuantitatif.
Penguatan lembaga etik independen, perlindungan pelapor, serta transparansi dalam pengambilan keputusan merupakan langkah penting. Di sisi lain, masyarakat juga harus aktif mengawasi dan bersuara.
Peran Publik: Tidak Diam terhadap Pelanggaran
Masyarakat bukan sekadar penonton. Kritik publik, literasi etika, dan partisipasi aktif dalam pengawasan menjadi kunci. Media sosial, jika digunakan secara bertanggung jawab, dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif. Diam terhadap pelanggaran berarti memberi ruang bagi kerusakan yang lebih besar.
Mengembalikan Etika sebagai Nafas Profesi
Etika profesi yang retak di tengah ambisi dan kekuasaan bukanlah keniscayaan. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan yang dibiarkan berulang tanpa koreksi. Jika etika terus dipinggirkan, profesi kehilangan martabat, dan masyarakat kehilangan perlindungan.
Sudah saatnya etika dikembalikan sebagai nafas profesi, bukan sekadar aksesori moral. Ini membutuhkan keberanian individu untuk berkata tidak, komitmen institusi untuk berbenah, dan kesadaran publik untuk tidak menormalisasi penyimpangan. Masa depan keadilan, kemanusiaan, dan kepercayaan publik bergantung pada satu hal sederhana namun mendasar: apakah kita masih mau menjadikan etika sebagai kompas, bukan penghalang.