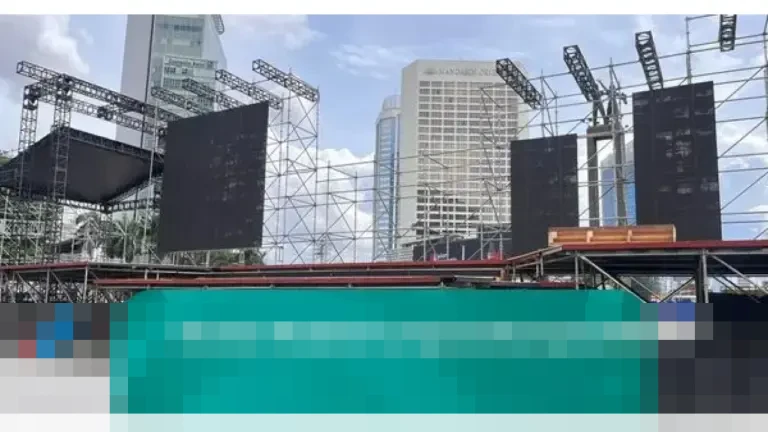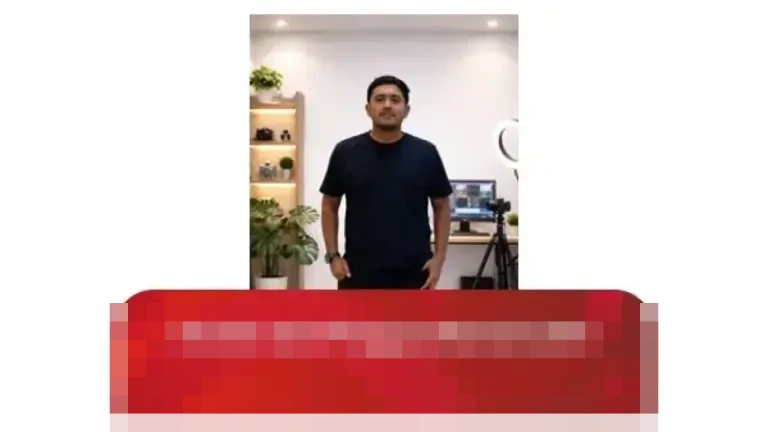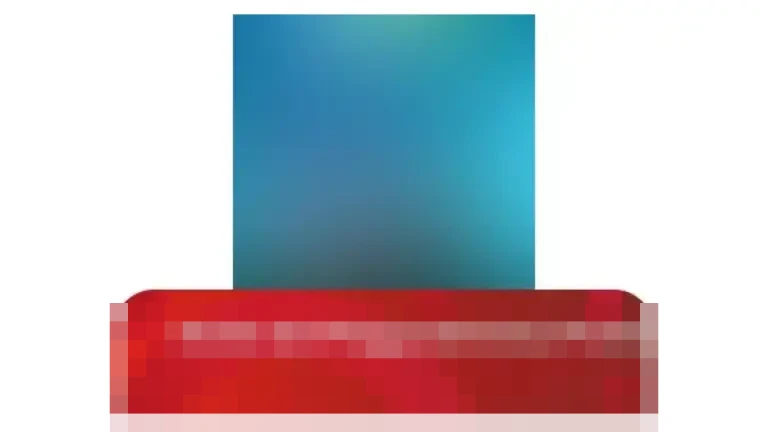Setiap kali bencana melanda, masyarakat dihadapkan pada dilema krusial: apakah bertahan di lokasi asal yang kini berstatus zona merah, atau pindah ke area relokasi yang belum tentu menjamin keamanan lebih baik? Pertanyaan ini, yang menyangkut kelangsungan hidup dan ikatan sosial, tidak pernah sederhana. Namun, ada satu pertanyaan fundamental yang kerap terabaikan: siapa sesungguhnya yang berhak menentukan pilihan tersebut?
Dilema Pilihan dan Peran Negara dalam Pemulihan Pascabencana
Dalam praktik penanganan bencana di Indonesia, keputusan mengenai jalur pemulihan acapkali diambil oleh pemerintah, lembaga kemanusiaan, atau bahkan kontraktor. Dalih yang digunakan seringkali adalah perlindungan dan percepatan proses. Akibatnya, warga terdampak seringkali ditempatkan sebagai penerima keputusan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memilih. Pendekatan semacam ini mungkin dapat dimaklumi dalam situasi darurat, namun menjadi sangat problematis ketika keputusan tersebut akan menentukan arah hidup seseorang selama bertahun-tahun ke depan.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Ironisnya, di tengah kompleksitas risiko bencana yang kian meningkat, ruang pilihan bagi warga justru seringkali dipersempit. Hunian sementara (huntara) di lahan relokasi, misalnya, kerap dibangun di lokasi yang belum dilengkapi fasilitas dasar memadai. Ketersediaan air bersih dan sanitasi terbatas, jaringan listrik minim, serta ketiadaan fasilitas umum dan sosial yang layak menjadi masalah umum. Banyak intervensi hunian sementara lebih berorientasi pada penyelesaian proyek fisik bangunan, ketimbang menciptakan tempat tinggal yang benar-benar aman, layak, dan bermartabat. Padahal, dalam kenyataannya, warga tidak hanya tinggal di huntara selama beberapa bulan, melainkan bertahun-tahun—bahkan tidak jarang lebih dari empat tahun.
Persoalan lain yang sering luput dari perhatian adalah biaya nyata pembangunan hunian sementara di lahan relokasi yang jauh lebih besar dari angka yang diumumkan ke publik. Biaya yang sering disampaikan umumnya hanya mencakup konstruksi fisik hunian, sementara berbagai komponen lain tidak diperhitungkan. Ini termasuk biaya lahan, penggunaan alat berat dan personel untuk persiapan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga biaya operasional dan pemeliharaan. Jika dihitung secara utuh, biaya tersebut dapat membengkak hingga 3-4 kali lipat. Anggaran sebesar ini, menurut Avianto Amri, sesungguhnya dapat membuka lebih banyak pilihan pemulihan bagi warga jika mereka diberi ruang untuk menentukan jalurnya sendiri.
Kondisi psikososial warga terdampak juga tidak seragam. Ada keluarga yang mengalami trauma berat sehingga enggan kembali ke lokasi asal, di mana suara air mengalir saja cukup memicu kecemasan akan kemungkinan bencana susulan. Namun, ada pula keluarga yang memiliki ikatan budaya dan sosial yang kuat dengan wilayah asalnya dan menolak direlokasi. Keragaman ini menunjukkan bahwa pendekatan satu solusi untuk semua tidak pernah memadai. Justru karena setiap warga memiliki jalur pemulihan yang berbeda, merekalah yang seharusnya berhak menentukan pilihan—dengan informasi yang jujur, dukungan yang memadai, dan perlindungan risiko yang jelas.
Mandat Negara: Antara Perlindungan dan Kontrol
Negara memang memiliki mandat konstitusional untuk melindungi warga negara dari ancaman bencana. Namun, mandat ini kerap salah diterjemahkan menjadi kewenangan sepihak untuk memutuskan apa yang dianggap terbaik bagi penyintas. Dalam praktiknya, perlindungan berubah menjadi kontrol, dan partisipasi warga seringkali hanya sebatas sosialisasi sepihak.
Padahal, perlindungan sejati bukanlah menghilangkan pilihan, melainkan memastikan pilihan yang tersedia aman, adil, dan bermartabat. Negara seharusnya menjamin bahwa warga memahami risiko, mengetahui opsi yang tersedia, dan mendapat dukungan untuk memilih jalur pemulihan yang paling sesuai dengan kondisi mereka masing-masing.
Indonesia Pernah Menjadi Teladan Global
Avianto Amri mengingatkan, Indonesia sebenarnya pernah menjadi rujukan global dalam pemulihan pascabencana yang berpusat pada manusia (people-centred). Pasca Tsunami Aceh 2004, Indonesia melakukan lompatan besar dalam tata kelola kebencanaan. Salah satu puncaknya terlihat pada respons Gempa Yogyakarta 2006 melalui pendekatan kelompok masyarakat (POKMAS).
- Bantuan perumahan tidak dimaksudkan untuk mengganti seluruh kerugian, melainkan sebagai insentif pemulihan.
- Dana disalurkan langsung ke kelompok warga, disertai pendampingan teknis.
- Keluarga diberi ruang untuk membangun sesuai kebutuhan dan kapasitasnya masing-masing.
Pendekatan ini mengakui satu hal mendasar: setiap keluarga itu berbeda. Tingkat kerusakan, sumber daya yang dimiliki, serta rencana hidup pascabencana tidak pernah sama. Dengan memberi pilihan, pemulihan berjalan lebih cepat, ekonomi lokal bergerak, dan martabat warga tetap terjaga. Model ini kemudian diadopsi dan dikembangkan di berbagai daerah lain, serta diakui luas sebagai praktik baik, baik secara nasional maupun internasional.
Pergeseran Paradigma: Ketika Pemulihan Menjadi Proyek
Sayangnya, dalam satu dekade terakhir, terjadi pergeseran pendekatan. Penanganan bencana semakin menyerupai manajemen proyek berskala besar. Hunian dirancang seragam, dibangun oleh kontraktor, dan ditempatkan di kawasan-kawasan terpusat. Bantuan yang dulu dimaknai sebagai pemicu pemulihan berubah menjadi anggaran tetap yang harus “cukup” untuk membangun rumah secara penuh—meski nilainya jauh dari nilai rumah yang hilang.
Hunian kolektif dan relokasi paksa kembali muncul, dengan seluruh konsekuensi sosialnya: keterputusan penghidupan, masalah perlindungan, ketergantungan bantuan, hingga terbentuknya kantong-kantong kemiskinan baru. Warga yang mampu akan pergi, sementara yang tidak mampu akan tertinggal. Dalam proses ini, warga kehilangan agensi. Mereka tidak lagi memilih jalur pemulihannya, tetapi mengikuti skema yang telah ditentukan.
Pendekatan Berpusat pada Manusia: Bukan Sekadar Jargon
Pendekatan berpusat pada manusia (people-centred approach) bukan sekadar jargon partisipasi. Intinya sederhana namun mendasar: memberi warga hak untuk memilih. Pilihan untuk tinggal sementara dengan keluarga, menyewa rumah, membangun bertahap di lokasi asal yang aman, pindah secara sukarela, atau—jika memang tak ada pilihan lain—menempati hunian kolektif.
Peran negara bukan menentukan desain rumah, melainkan memastikan keselamatan bangunan, pengelolaan risiko tata ruang, dan penegakan standar. Indonesia telah memiliki regulasi tata ruang dan kode bangunan yang fleksibel. Tugas kita adalah menegakkannya, bukan menggantinya dengan solusi seragam.
Pemulihan yang Bermartabat adalah Hak, Bukan Hadiah
Narasi bahwa warga terdampak harus bersyukur karena “sudah dibantu” adalah paradigma yang keliru. Bantuan kemanusiaan bukanlah hadiah, melainkan hak warga negara. Tujuannya bukan menumbuhkan rasa terima kasih, tetapi memastikan pemulihan yang aman, layak, dan bermartabat. Bencana memang menuntut kecepatan, tetapi kecepatan tanpa pilihan justru menciptakan krisis baru yang berkepanjangan.
Jika hidup kita sendiri hancur oleh bencana, kita semua tentu ingin didengar, diberi opsi, dijelaskan kekuatan dan kelemahan setiap opsi yang tersedia, dan dipercaya untuk menentukan masa depan kita sendiri. Indonesia tidak perlu kembali ke pendekatan komando dan proyek. Kita sudah pernah menunjukkan jalan yang lebih baik—jalan yang menempatkan manusia, martabat, dan pilihan di pusat pemulihan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita mau kembali mempercayai warga terdampak sebagai subjek, bukan sekadar objek, dalam setiap keputusan pemulihan pascabencana.