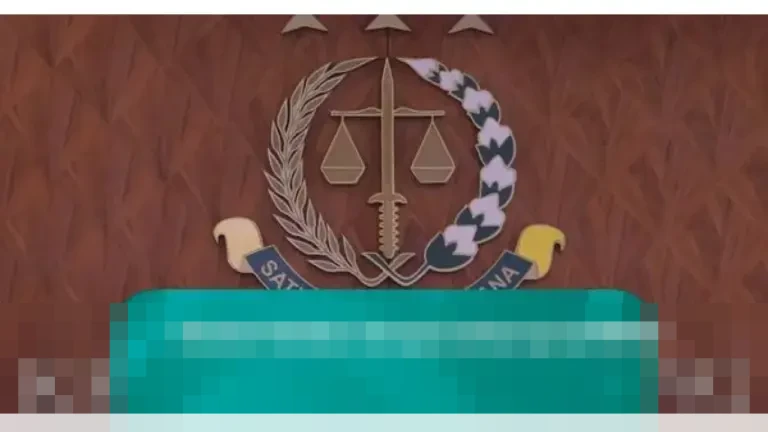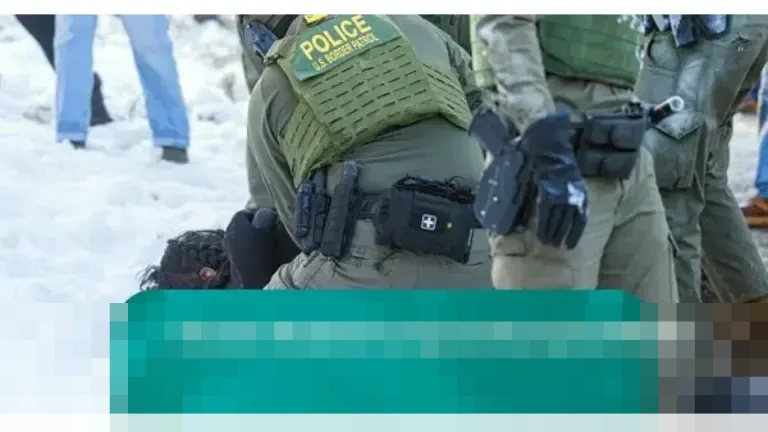Di penghujung tahun 2025, lini masa media sosial kembali diwarnai insiden yang ironisnya mulai dianggap biasa. Rekaman CCTV bom molotov di rumah DJ Donny serta pengiriman bangkai ayam dan coretan pylox di mobil influencer Sherly Annavita menjadi sorotan publik. Namun, respons netizen terhadap kejadian-kejadian ini justru memunculkan pertanyaan mendalam tentang empati dan nalar kolektif.
Penulis dan Pengamat Kebijakan Publik, Fathin Robbani Sukmana, menyoroti fenomena ini sebagai “Voyeunisme Teror”. Ia berpendapat bahwa masyarakat kini cenderung melihat kekerasan bukan sebagai ancaman kemanusiaan, melainkan sebuah pertunjukan yang layak dikritik aktingnya. Mureks mencatat bahwa pergeseran cara pandang ini jauh lebih mengerikan dibandingkan ledakan bom molotov itu sendiri.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Teror Molotov dan Matinya Rasa Gentar
Fathin Robbani Sukmana secara jujur mengakui bahwa saat melihat foto bangkai ayam yang dikirim ke DJ Donny atau mobil Sherly Annavita dicoret, saraf empati sebagian netizen tidak lagi bekerja secepat saraf “curiga”. Ini mengindikasikan hilangnya common sense untuk merasa ngeri terhadap tindakan kekerasan.
Menurut Fathin, fenomena ini terjadi karena di ruang digital, realitas telah mengalami apa yang disebut oleh Jean Baudrillard sebagai The Precession of Simulacra. Dalam teori ini, simulasi atau apa yang nampak di layar menjadi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Akibatnya, teror yang menimpa Sherly dan Donny tidak lagi dianggap sebagai peristiwa fisik yang menyakitkan, melainkan sebagai “produk narasi”. Netizen tidak lagi peduli pada bau bensin yang menyengat, tetapi lebih fokus pada apakah “skrip” teror ini masuk akal dalam skema politik tertentu. Cara berpikir ini, meskipun sakit, sering dijumpai di kolom komentar media sosial.
Kebenaran yang “Erotis”
Persoalan lain yang luput dari perhatian adalah bagaimana masyarakat mengonsumsi kebencian secara erotis. Netizen seolah menyukai konflik dan membutuhkan musuh untuk merasa “hidup”. Dalam konteks politik, hal ini sering menjebak kita dalam Tribalisme Digital. Jika korban bukan dari “kubu kita”, maka teror tersebut dianggap legal atau setidaknya layak ditertawakan.
Fathin Robbani Sukmana teringat pada pandangan Erich Fromm dalam bukunya The Anatomy of Human Destructiveness. Fromm membedakan antara agresi defensif (untuk membela diri) dan agresi nekrofilus (hasrat untuk menghancurkan yang hidup). Fathin mempertanyakan apakah masyarakat kita, tanpa sadar, sedang dipupuk menjadi massa yang nekrofilus. “Apabila Netizen senang melihat sesuatu yang mapan hancur, lalu kegirangan melihat orang yang vokal dibungkam, selama orang itu bukan bagian dari ‘kita’. Jika merasa demikian maka jawabannya adalah iya,” tegasnya.
Menjemput Nalar yang Tertukar
Lalu, bagaimana mengembangkan cara berpikir di tengah kepungan “asap molotov dan aroma bangkai ayam” digital ini? Solusinya, menurut Fathin, bukan sekadar menambah kuota internet untuk scroll media sosial, melainkan melakukan kurasi mental. Kita perlu beralih dari pola pikir “reaksi instingtif” ke “aksi reflektif”.
Fathin menekankan bahwa apabila ada kejadian teror, nalar pertama yang harus muncul adalah bahwa teror merupakan kejahatan terhadap manusia. “Titik. Urusan apakah kita setuju pendapat politik korban atau sebaliknya, itu adalah urusan paragraf kemudian,” ujarnya. Kita harus kembali terbiasa memisahkan antara subjek (manusia) dan objek (pendapat).
Sebagai penyimbang dari kegilaan massa ini, Mureks mencatat pentingnya merenungkan pemikiran Jose Ortega y Gasset, seorang filsuf dan esais Spanyol, dalam bukunya The Revolt of the Masses. Ia menulis, “Massa tidak pernah datang ke hadapan publik kecuali untuk menghancurkan. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk berdialog karena mereka merasa telah memiliki kebenaran yang mutlak tanpa perlu pembuktian.”
Pernyataan Ortega y Gasset ini menampar realitas kita. Jika hanya merasa sakit ketika “orang kita” diteror namun bersorak saat “lawan” yang dikirimi molotov, sejatinya kita sudah bukan individu yang berpikir. Kita hanyalah bagian dari “Massa” yang digambarkan Ortega y Gasset sebagai kumpulan orang yang merayakan kehancuran nalar demi kepuasan sesaat.
Jangan Jadi Penonton yang Jahat
Fathin Robbani Sukmana menyerukan pentingnya melakukan Digital Stoicism, yaitu berdaulat atas emosi kita sendiri. “Jangan biarkan algoritma atau kebencian partisan mendikte kapan kita harus empati dan kapan kita boleh mencaci,” pesannya.
Pada akhirnya, teror kepada DJ Donny dan Sherly Annavita adalah ujian bagi nalar publik. Apakah kita akan terus menjadi penonton bioskop yang sibuk mengomentari lighting dan plot hole dari sebuah teror nyata, atau kita kembali menjadi manusia yang tahu bahwa api di rumah tetangga—siapa pun dia—adalah ancaman bagi rumah kita juga?
Sebab, jika hari ini kita membiarkan api itu menyala hanya karena kita tidak suka pada wajah si empunya rumah, jangan kaget jika besok-lusa, saat api itu sampai ke daster atau sarung kita, orang-orang hanya akan menonton sambil sibuk mencari tahu: “Ini settingan atau bukan?”