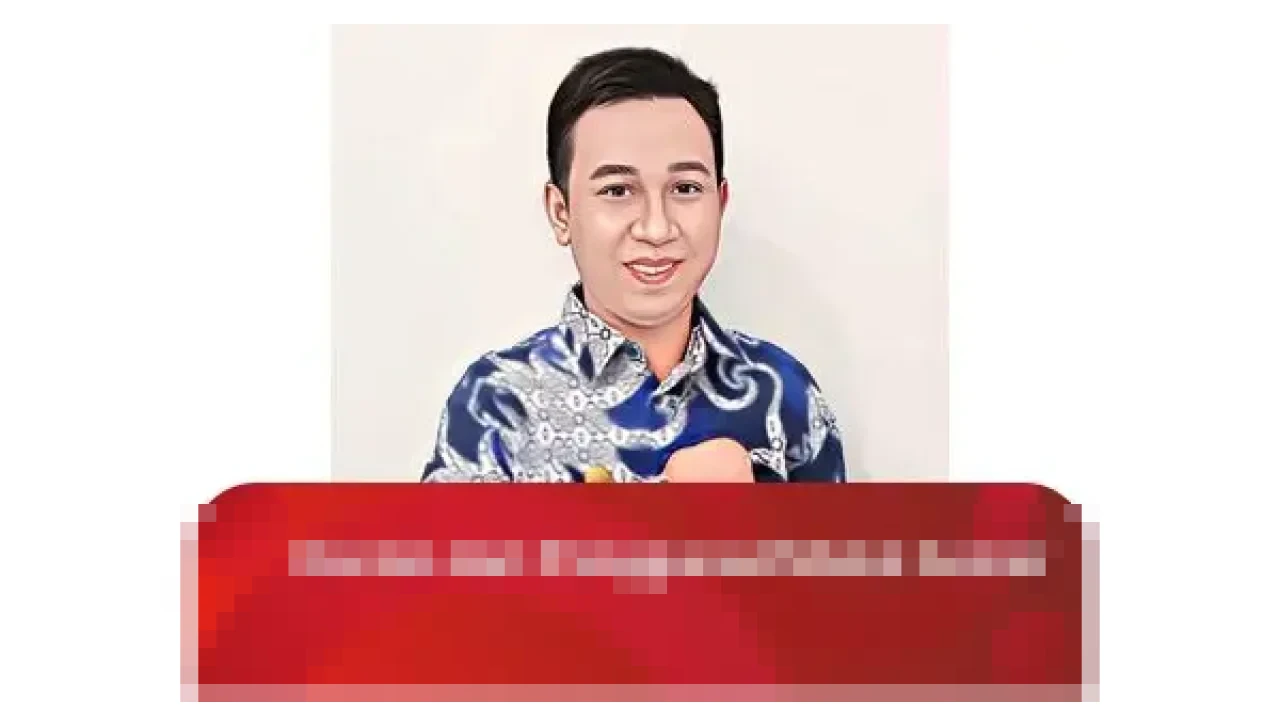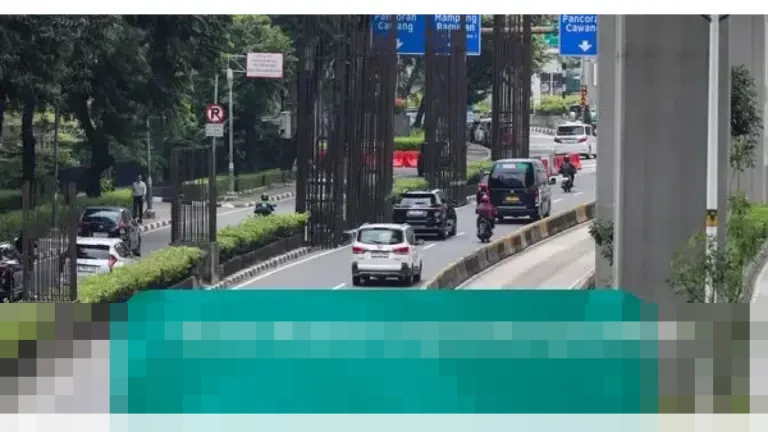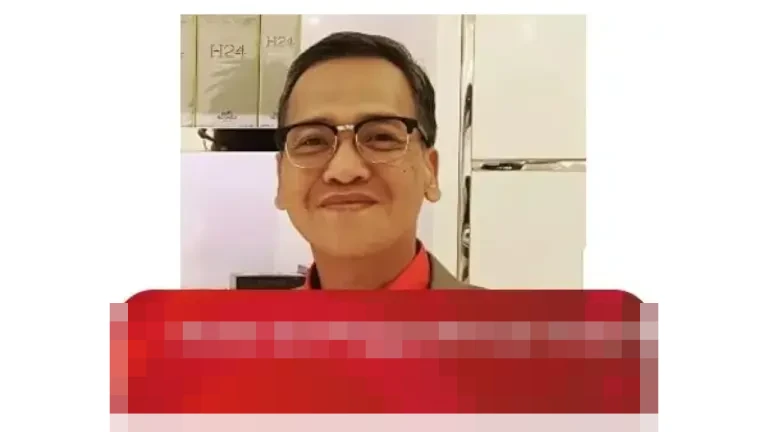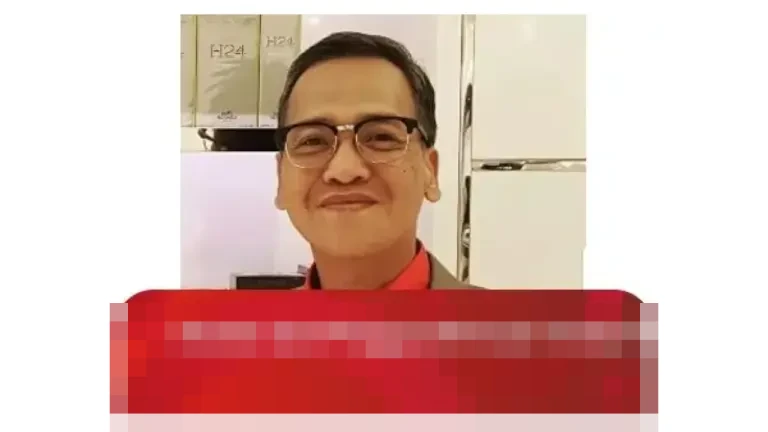Bulan Rajab, yang selalu datang dengan aura kesucian, seringkali dimaknai sebagai momentum spiritual untuk memperbanyak ibadah personal seperti puasa sunah, istighfar, dan doa. Namun, di tengah kesibukan spiritual ini, jarang sekali pertanyaan diajukan mengenai relevansi kesalehan Rajab dengan kondisi lingkungan kita hari ini: sungai yang tercemar, hutan yang digunduli, dan udara yang diracuni.
Akademisi Bidang Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Parepare, Afidatul Asmar, menyoroti ironi ini. Menurut Afidatul, Rajab seharusnya tidak hanya tentang relasi vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang etika horizontal manusia dengan semesta. Alam, dalam pandangan Al-Qur’an, bukanlah properti yang bisa dieksploitasi, melainkan sebuah amanah kosmik yang harus dijaga.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Alam sebagai Ayat Kauniyah dan Kritik Ekologis
Al-Qur’an secara berulang kali menyebut alam sebagai ayat kauniyah, yakni tanda-tanda kebesaran Tuhan yang terbentang di luar teks suci. Dalam Surah Ar-Rum ayat 41, ditegaskan bahwa “kerusakan di darat dan laut terjadi karena perbuatan tangan manusia.” Ayat ini, yang sering dibaca secara normatif, sesungguhnya merupakan kritik ekologis paling awal dalam sejarah peradaban manusia.
Para mufasir kontemporer menafsirkan ayat ini sebagai peringatan serius tentang ecological imbalance atau ketidakseimbangan ekologi. Manusia, dengan watak eksploitatifnya, kerap mengganggu mizan (keseimbangan) yang oleh Al-Qur’an disebut sebagai sunnatullah, sebagaimana termaktub dalam Surah Ar-Rahman ayat 7-9. Merusak alam, dalam konteks ini, berarti menentang tatanan ilahi, sebuah dosa struktural yang sering luput dari pembahasan khutbah Jumat.
Teladan Nabi dan Sahabat dalam Etika Lingkungan
Nabi Muhammad SAW tidak hanya dikenal sebagai pembawa risalah teologis, tetapi juga sebagai pendidik ekologi praktis. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi melarang menyia-nyiakan air, bahkan ketika berwudu di sungai yang mengalir. Ini bukan sekadar fikih air, melainkan prinsip keberlanjutan (sustainability) yang diajarkan jauh sebelum istilah tersebut populer dalam konferensi internasional.
Dalam hadis lain, Nabi bersabda: “Jika kiamat terjadi sementara di tanganmu ada benih, maka tanamlah.” Kalimat sederhana ini sarat makna, menegaskan bahwa harapan ekologis tidak pernah pensiun, bahkan di ambang kehancuran sekalipun.
Para sahabat juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Umar bin Khattab, yang dikenal tegas dalam urusan publik, melarang penggembalaan berlebihan yang dapat merusak padang rumput negara (hima). Ini merupakan bentuk awal kebijakan lingkungan berbasis keadilan sosial, di mana alam dijaga bukan hanya demi estetika, tetapi demi keberlanjutan hidup bersama.
Ali bin Abi Thalib bahkan mengingatkan bahwa bumi adalah titipan bagi generasi berikutnya. Pernyataan ini sangat relevan dengan konsep intergenerational ethics, sebuah istilah yang kini ramai dalam diskursus pembangunan berkelanjutan. Mureks mencatat bahwa pandangan para sahabat ini menunjukkan kedalaman pemahaman Islam tentang tanggung jawab ekologis.
Rajab sebagai Kritik Sosial-Ekologis
Jika Rajab adalah bulan mulia, maka merusak alam di bulan ini adalah ironi spiritual yang nyaris sempurna. Kita rajin berdoa agar dosa diampuni, tetapi tetap ringan tangan membuang sampah ke sungai. Kita memperbanyak istighfar, sambil menebang pohon tanpa merasa perlu menanam kembali. Kesalehan semacam ini, meminjam gaya satire klasik, adalah kesalehan yang tekun beribadah, tetapi enggan berpikir; khusyuk di sajadah, lalai di ruang hidup bersama.
Mahbub Djunaedi, seorang budayawan, kerap menyindir kesalehan yang kehilangan nalar publik. Jika ia masih menulis hari ini, barangkali ia akan berkata: “Umat berdoa minta hujan, tapi hutan ditebang sampai Tuhan bingung mau menurunkan hujan di mana.” Satire ini, meski terdengar jenaka, sesungguhnya adalah kritik ekologis yang tajam: doa tidak pernah salah, yang bermasalah adalah perilaku manusia yang memutus sebab-sebab rahmat itu sendiri.
Ironi ekologis ini juga menunjukkan kesenjangan antara teologi dan praksis sosial. Agama sering diperlakukan sebagai urusan langit semata, sementara bumi dibiarkan menanggung konsekuensinya. Padahal, dalam perspektif keislaman, merusak alam bukan hanya pelanggaran etika lingkungan, melainkan kegagalan memahami makna khalifah.
Dalam perspektif modern, manusia disebut sebagai khalifah fil ardh, yakni pengelola, bukan pemilik bumi. Konsep ini sejalan dengan teori environmental stewardship dalam ilmu ekologi modern. Para ahli lingkungan menyebut bahwa krisis ekologi hari ini bukan krisis sumber daya, melainkan krisis etika.
Teori ecotheology menegaskan bahwa agama memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran ekologis. Dalam konteks Islam, Rajab bisa dibaca sebagai bulan refleksi ekologis: sejauh mana ibadah kita berdampak pada keberlanjutan hidup?
Rajab seharusnya membuat kita lebih lembut bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada bumi. Sebab bumi, sebagaimana manusia, juga sedang lelah. Dan mungkin, ia sedang menunggu apakah kesalehan kita benar-benar punya akar, atau hanya daun-daun doa yang gugur tanpa makna. Jika Rajab tak mengubah cara kita memperlakukan alam, jangan-jangan yang mulia hanya bulannya, bukan perilaku kita.