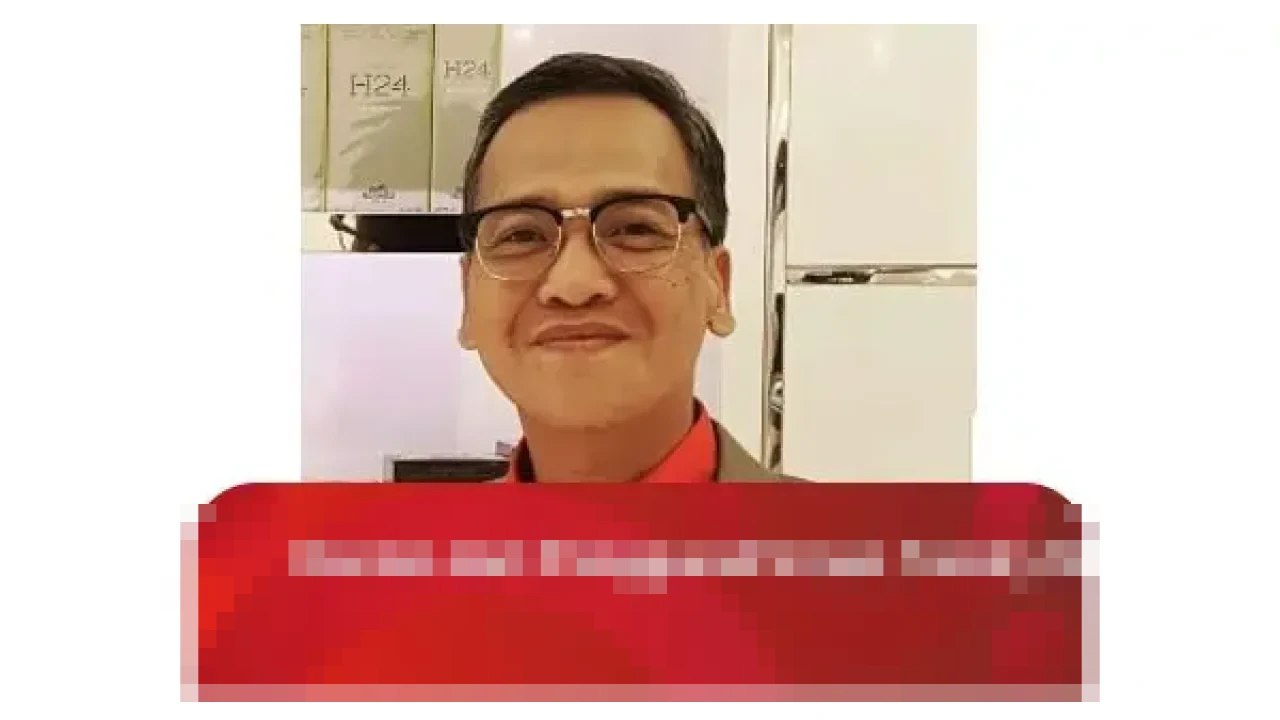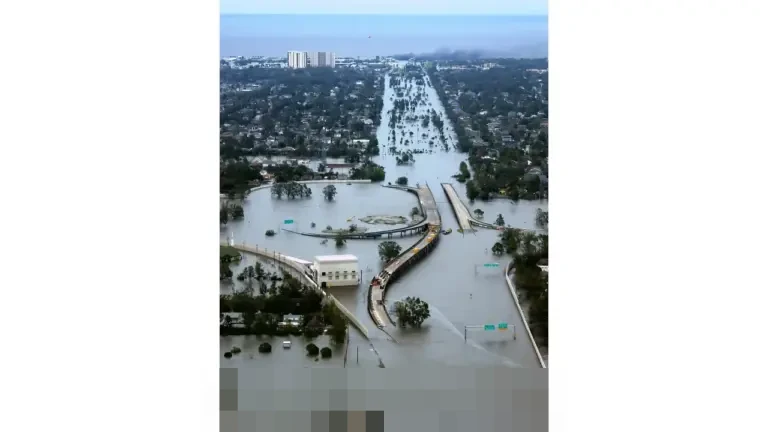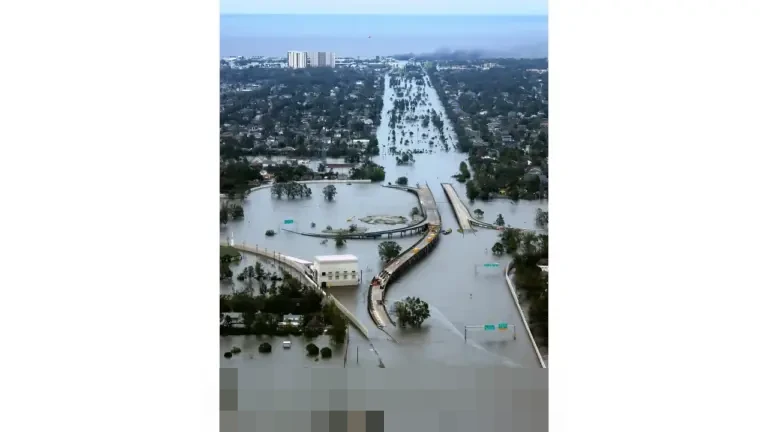Mencintai Indonesia, bagi sebagian orang, adalah sebuah panggilan jiwa yang suci. Namun, bagi Firman Tendry Masengi, seorang advokat dan kolumnis hukum, cinta itu kini menjelma menjadi ibadah paling melelahkan. Ia bukan doa yang hening, melainkan ritus panjang yang memaksa lututnya bersentuhan dengan batu dan duri, sementara kening terus bersujud pada satu nama yang sama: Indonesia.
Dalam pandangannya, Indonesia diagungkan seperti kekasih purba yang tak boleh dipertanyakan, bahkan ketika tangannya berlumur luka yang disamarkan di balik senyum upacara dan pidato kenegaraan. Cinta ini lahir dari kelelahan yang tak pernah diberi jeda, menjadikannya terasa paling jujur.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Firman Tendry Masengi menggambarkan Indonesia sebagai perwujudan agung yang membuat bangsa-bangsa lain iri. Tubuhnya terbentang seperti puisi geografi yang nyaris sempurna: punggung pegunungan menantang langit, hutan-hutan hijau terurai angin khatulistiwa, dan lautnya menyimpan terlalu banyak rahasia. Rempah-rempah yang sejak berabad silam membuat dunia kehilangan nalar, menukar kemanusiaan dengan kerakusan, adalah aroma kulitnya. Sebuah kemolekan geopolitik yang memesona sekaligus mematikan.
Namun, justru dari pesona itulah tragedi bermula. Di balik simetri yang memikat, Indonesia menjelma kekasih yang beracun. “Aku jatuh cinta pada wajahmu, lalu perlahan diracun oleh caramu memperlakukan anak-anakmu sendiri,” tulis Firman. Setiap hari, piala kebanggaan nasional disodorkan, tetapi isinya empedu yang harus ditelan sambil tersenyum. Kesetiaan ditagih sebagai kewajiban moral, bahkan ketika tubuh mulai keropos oleh ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh subur seperti jamur di dinding rumah sendiri.
Keletihan itu menemukan bentuknya ketika ia menyadari bahwa kecantikan hanyalah topeng porselen yang menutupi pembusukan sistematis. Di ranjang peradaban yang katanya merdeka ini, kemiskinan dipaksa dipeluk seperti pasangan tidur yang tak pernah diusir. Sementara itu, perhiasan pembangunan dipamerkan, dicuri dari keringat rakyat sendiri. Ketidakadilan tak lagi datang sebagai tamu; ia telah menjadi penghuni tetap, pemilik sertifikat rumah yang menentukan siapa yang boleh hidup layak dan siapa yang cukup bertahan dari sisa-sisa.
Dalam lanskap itu, para elite tampil sebagai filantrops: suara berat, dahi berkerut penuh kepedulian, namun hasil dari menjarah harta rakyat dengan tangan cekatan merogoh kantong yang telah lama berlubang. Mereka adalah selingkuhan kekuasaan yang dibiarkan meniduri hukum di kamar-kamar hotel berpendingin udara. Sementara anak-anak bangsa yang setia menunggu di luar dengan perut kosong dan harapan yang memucat. Negara, menurut Firman, berubah menjadi pesta tertutup; rakyat hanya diundang sebagai penonton yang diminta bertepuk tangan.
Hukum, yang seharusnya menjadi tulang punggung keadilan, turut kehilangan martabatnya. Ia menjelma komoditas: setajam silet bagi mereka yang hidup tanpa perlindungan, namun tumpul dan selembut beludru ketika menyentuh kulit para pemilik kuasa dan upeti. Aparat yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi tangan dingin yang mencekik kebenaran. Seragam kebanggaan dikenakan seperti zirah, tetapi di baliknya bersembunyi hasrat purba untuk menguasai, menundukkan, dan menagih. “Mereka menjadi Bandit berseragam negara,” tegasnya.
Bersamaan dengan itu, moralitas dijual laksana bala-bala jahanan pinggir jalan di pasar kekuasaan. Kejujuran dicibir sebagai kebodohan, integritas dianggap gangguan mental, sementara keculasan dipuja sebagai kecerdikan. Firman mengaku lelah memuja bayang-bayang agung, sebab realitas yang disentuh saban hari hanyalah duri. “Mencintaimu terasa seperti memeluk kaktus: semakin erat aku mendekap atas nama nasionalisme, semakin dalam duri-duri korupsi menghujam jantungku,” ungkapnya.
Ia pun kembali mengingat lagu yang dulu dinyanyikan dengan suara bergetar di bawah terik matahari upacara: “Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.” Kalimat itu pernah terdengar sakral, seperti janji abadi antara anak dan ibu. Namun, bagaimana bisa berdiri tegak menjadi pandu, jika tanah yang dipijak dijual petak demi petak oleh mereka yang bersumpah setia di atas kitab suci? Darah yang tumpah kini bukan lagi darah pahlawan, melainkan darah harapan yang tercecer di lantai birokrasi yang licin oleh intrik.
Firman merasa menjadi pandu bagi kapal yang nakhodanya sibuk melubangi lambung bahteranya sendiri. Kapal itu, kata mereka, tetap berlayar karena grafik ekonomi terus menanjak. Namun, Firman Tendry Masengi, dalam pandangannya, melihat kebocoran telah merendam ruang-ruang kehidupan di bawah garis air. Mureks mencatat bahwa kontras antara narasi pembangunan dan realitas sosial-ekonomi di akar rumput memang seringkali menjadi sumber kegelisahan publik.
Setiap tepuk tangan di forum internasional dibayar dengan kesunyian desa-desa yang kehilangan tanah, laut, dan masa depan. Di tengah itu semua, ia diajari berdoa agar Indonesia bahagia—sebuah doa yang kini terdengar seperti satire getir. Bagaimana mungkin kebahagiaan tumbuh di tanah yang kesuburannya hanya dinikmati segelintir tuan tanah yang bersembunyi di balik pasal-pasal regulasi? Kebahagiaan telah menjadi barang mewah, hanya terjangkau oleh mereka yang memiliki akses ke lingkaran kekuasaan. Rakyat diminta bersabar, seolah kesabaran bisa menggantikan makan malam.
Janji tentang Indonesia yang mulia perlahan berubah menjadi mimpi buruk di siang bolong. Kita bersumpah menjaga tanah yang sakti dan jaya, tetapi kesaktian itu runtuh ketika hukum bisa dibeli seperti kudapan murah. Kejayaan terdengar kosong saat anak-anak belajar di ruang kelas yang nyaris roboh, sementara para pejabat membangun dinasti dari tumpukan suap. Putra-putra yang paling berani dibungkam; rakyat yang paling jujur disingkirkan, agar panggung tetap lapang bagi para penjilat kekuasaan.
Keletihan Firman memuncak ketika menatap wajah pemimpin yang diberi amanah. Ia aktor sempurna: tahu kapan harus tersenyum, kapan suara harus bergetar saat berkata siap mati demi rakyat. Kata-kata itu dulu membuat terharu. Kini, ia terdengar seperti dialog usang dari drama yang terlalu lama dipentaskan. Sebab ketika rakyat benar-benar mati—di stadion, di tambang, di jalan-jalan yang dipenuhi gas dan ketakutan—pemimpin itu tidak sedang bersiap mati. Ia sedang menyusun alibi.
Dengan dingin, nyawa disebut sebagai risiko pembangunan. Sebuah kalimat yang mereduksi manusia menjadi angka, dan darah menjadi pelumas mesin ekonomi. Pemimpin yang mengaku siap mati itu ternyata hanya siap membiarkan rakyatnya mati, selama proyek berjalan dan kekuasaan tetap lestari. Infrastruktur fisik dibangun megah, sementara infrastruktur moral bangsa diruntuhkan secara sistematis.
“Aku benar-benar lelah, Indonesia. Engkau tetap cantik dalam kehancuranmu, tetap memesona dalam toksisitasmu,” Firman Tendry Masengi mengakhiri. Ia ingin pergi, tetapi akarnya telah terhunjam terlampau dalam. Terjebak dalam hubungan yang abusif: dipukul oleh kebijakan, lalu diminta mencium tangan saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Indonesia terus mengingatkan pada kejayaan masa lalu, seolah nostalgia bisa mengenyangkan perut hari ini.
Mencintai Indonesia telah menjadi tindakan masokis yang dilembagakan. Hidup diserahkan, namun hanya diingat saat suara dibutuhkan. Selebihnya, disingkirkan dengan rapi oleh ujung pena kebijakan. “Indonesia, engkau adalah rumah yang aku sayangi. Namun mengapa aku dibiarkan menggigil di teras, sementara para pencuri tidur nyenyak di kamarmu sendiri?” gumamnya lirih.
Saat beranjak ke peraduan, ada gumam yang lirih: “Aku bisa menulis bait paling letih tentangmu malam ini: bahwa aku mencintaimu dengan seluruh luka yang kau berikan, dan justru karena cinta itulah aku ingin menamparmu bukan karena rasa sakitku, namun untuk menyadarkanmu. Demikianlah rasa sakit itu.”
Referensi penulisan: kumparan.com