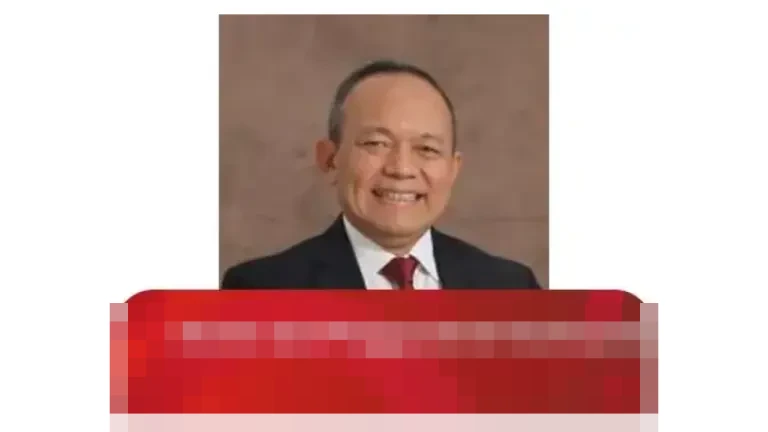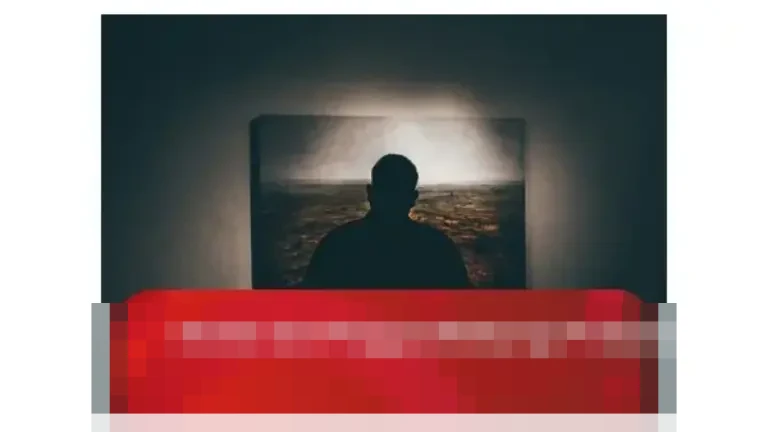Menyebut Indonesia lelah, terbelah, dan rapuh bukanlah sebuah pesimisme, melainkan kejujuran etis yang fundamental. Dari kejujuran inilah, harapan untuk membangun Indonesia sebagai rumah bersama yang adil dan berkelanjutan dapat lahir. Dalam beberapa bulan terakhir, publik disuguhi ironi yang berulang: bencana ekologis silih berganti, tekanan ekonomi terus menekan rumah tangga, ruang digital dipenuhi pertengkaran identitas, sementara kepercayaan pada institusi publik menurun.
Indonesia tampak tetap bergerak maju, bahkan merayakan berbagai capaian pembangunan. Dengan dalih demi rakyat, pemerintah terus bekerja, seringkali tanpa menghiraukan masukan atau kritikan sebagian warga. Namun, bagi banyak warganya, hidup terasa semakin berat. Di sinilah paradoks Indonesia hari ini mengemuka: bergerak maju, tetapi secara sosial lelah, secara politik terbelah, dan secara ekologis rapuh. Mengakui kenyataan ini bukan sikap pesimistis, melainkan langkah awal untuk memulihkan arah bersama. Situasi ini menuntut lebih dari sekadar kebijakan teknis; ia menuntut tanggung jawab etis bersama untuk menjaga masa depan Indonesia.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Indonesia Lelah
Kelelahan Indonesia bukan sekadar kelelahan fisik atau ekonomi, melainkan kelelahan sosial dan moral yang mendalam. Warga terus diminta beradaptasi dengan krisis—tekanan ekonomi, kerja yang makin tidak pasti, dan bencana yang berulang—sementara perlindungan sistemik sering tertinggal. Krisis demi krisis seolah dinormalisasi. Dalam kerangka pemikiran Zygmunt Bauman, kondisi ini mencerminkan kehidupan liquid: ketidakpastian menjadi permanen, dan risiko hidup dialihkan dari negara kepada individu. Ketika sistem gagal mengelola risiko secara adil, warga dipaksa menanggungnya sendiri, dan kelelahan menjadi pengalaman kolektif.
Kelelahan ini berbahaya karena perlahan melumpuhkan kepekaan etis. Hannah Arendt (1963) mengingatkan bahwa krisis terbesar dalam kehidupan publik bukanlah kebencian terbuka, melainkan ketiadaan refleksi moral—ketika orang berhenti berpikir dan merasa bertanggung jawab. Saat banjir, longsor, atau ketimpangan diterima sebagai “hal biasa”, masyarakat memasuki fase kelelahan moral. Nurani menumpul, dan ketidakadilan terasa wajar. Mureks mencatat bahwa fenomena ini menjadi indikator penting dalam dinamika sosial saat ini.
Indonesia Terbelah
Pada saat yang sama, Indonesia juga terbelah. Polarisasi politik dan identitas mengeras, diperkuat oleh ruang digital yang memonetisasi emosi. Demokrasi memang berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan kedalaman dialog. Kritik Jürgen Habermas (1996) relevan di sini: demokrasi hanya memiliki legitimasi jika ditopang oleh komunikasi etis—dialog yang jujur, setara, dan berorientasi pada pemahaman bersama. Tanpa etika dialog, demokrasi berubah menjadi arena saling meniadakan.
Keterbelahan ini semakin tajam karena ketimpangan struktural—antara pusat dan daerah, kota dan desa, elite dan rakyat. Banyak kebijakan diputuskan jauh dari pengalaman hidup mereka yang terdampak langsung. Pembangunan dirayakan, tetapi sebagian warga merasa tidak dilibatkan dan tidak dilindungi. Contoh tampak pada kebijakan pangan dan harga kebutuhan pokok. Saat stabilitas makro dinyatakan aman, petani di desa dan buruh di kota menghadapi kenyataan berbeda: biaya produksi naik, harga jual tidak stabil, dan daya beli melemah. Data dan indikator nasional terlihat baik, tetapi pengalaman hidup harian warga—antre pupuk, ongkos transport mahal, atau upah yang tertinggal—tidak sepenuhnya tercermin dalam pengambilan keputusan.
Ketimpangan pusat–daerah juga terlihat dalam penanganan bencana ekologis. Ketika banjir atau longsor terjadi di wilayah luar Jawa, respons awal sering bertumpu pada solidaritas warga dan pemerintah daerah. Negara hadir, tetapi terasa terlambat atau administratif. Akibatnya, warga membangun solidaritas sendiri, sementara rasa tidak dilindungi oleh sistem kian menguat. Pembangunan nasional tetap dipuji, tetapi ketahanan sosial di daerah rapuh.
Di ranah perkotaan, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang sering membawa konsekuensi sosial yang tidak kecil. Warga permukiman padat menghadapi penggusuran atau relokasi tanpa proses dialog yang memadai. Proyek dipromosikan sebagai kepentingan umum, namun partisipasi warga terdampak terbatas. Di sini, keterbelahan muncul bukan karena penolakan terhadap pembangunan, melainkan karena absennya keadilan prosedural dan empati kebijakan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa keterbelahan bukan semata persoalan perbedaan sikap, melainkan akumulasi pengalaman ketidakadilan. Pembangunan dirayakan dari pusat, tetapi sebagian warga di daerah, desa, dan lapisan bawah merasa tidak dilibatkan dan tidak dilindungi. Ketika jarak antara narasi kebijakan dan realitas hidup semakin lebar, kepercayaan pun menurun—dan ruang kebersamaan melemah.
Dalam pandangan Amartya Sen (1999), pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan substantif manusia, bukan sekadar pertumbuhan angka. Ketika warga bekerja keras tanpa kendali atas hidupnya, kelelahan dan keterbelahan menjadi tak terhindarkan. Di titik inilah pemikiran Indonesia sendiri memberi peneguhan. Franz Magnis-Suseno (1997) menegaskan bahwa etika publik bukan aksesori, melainkan syarat legitimasi kekuasaan. Negara yang efektif secara administratif tetapi abai pada keadilan akan kehilangan kepercayaan warganya. Senada dengan itu, Nurcholish Madjid (1997) menekankan pentingnya keadaban publik—bahwa hidup bersama hanya mungkin jika martabat manusia ditempatkan di atas kepentingan sempit kekuasaan dan identitas.
Indonesia yang Rapuh
Indonesia juga semakin rapuh, terutama secara ekologis. Kerusakan hutan, krisis air, dan bencana berulang menunjukkan fondasi kehidupan sedang terkikis. Guncangan kecil—hujan lebat atau pasang laut—mudah menjelma krisis besar. Dalam perspektif etika global, Paus Fransiskus (2015) menyebut krisis ekologis sebagai krisis moral: cara manusia memandang alam dan sesamanya. Ketika alam direduksi menjadi komoditas, manusia pun ikut terdegradasi.
Kerapuhan ini juga menyentuh martabat manusia. Martha Nussbaum (2011) menekankan capabilities dasar—hidup aman, sehat, berpendidikan, dan dihargai—sebagai ukuran keadilan. Jika sebagian warga kehilangan akses pada pendidikan bermakna, lingkungan sehat, dan perlindungan sosial, maka negara sedang gagal memenuhi tanggung jawab etis minimalnya. Benang merahnya jelas: kelelahan, keterbelahan, dan kerapuhan Indonesia berakar pada tersingkirnya etika dari politik, ekonomi, dan pembangunan. Keberhasilan terlalu sering diukur dengan kecepatan dan angka, bukan kualitas hidup dan keberlanjutan. Warga diposisikan sebagai objek kebijakan; alam diperlakukan sebagai sumber daya semata.
Tanggung Jawab Etis Negara
Karena itu, tanggung jawab etis perlu diterjemahkan ke dalam langkah kebijakan nyata. Pertama, negara harus menjadikan keadilan sosial dan ekologis sebagai tolok ukur utama kebijakan, melalui perlindungan sosial adaptif dan penegakan hukum lingkungan yang konsisten. Kedua, demokrasi perlu diperdalam dengan ruang dialog publik yang deliberatif dan beretika, agar polarisasi tidak terus direproduksi. Ketiga, pendidikan harus diarahkan untuk menumbuhkan kepekaan moral, literasi digital, dan kesadaran ekologis, bukan hanya keterampilan teknis. Langkah-langkah ini memang tidak instan, tetapi menjadi fondasi etis agar Indonesia pulih dan berdaya.
Seruan ini sejalan dengan seruan dan refleksi Reset Indonesia (2025), yang menegaskan bahwa krisis Indonesia bersifat sistemik dan membutuhkan keberanian untuk menata ulang arah. Reset bukan kehancuran, melainkan penyadaran—kesediaan untuk mengakui kelelahan, menjembatani keterbelahan, dan memperkuat fondasi yang rapuh melalui etika publik yang konsisten. Menurut Mureks, pemikiran ini krusial untuk mendorong perubahan fundamental. Menyebut Indonesia lelah, terbelah, dan rapuh bukanlah pesimisme. Itu adalah kejujuran etis. Dari kejujuran itulah harapan lahir—agar Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi menjadi rumah bersama yang adil, beradab, nyaman, dan berkelanjutan.