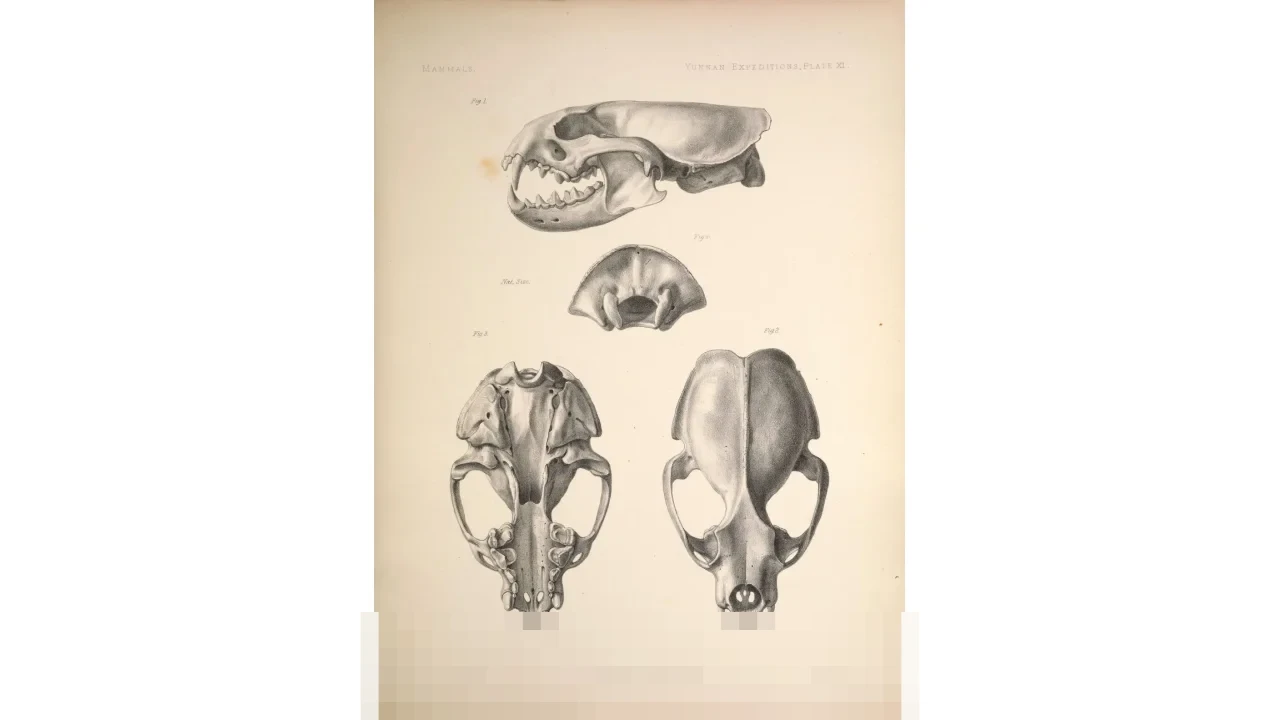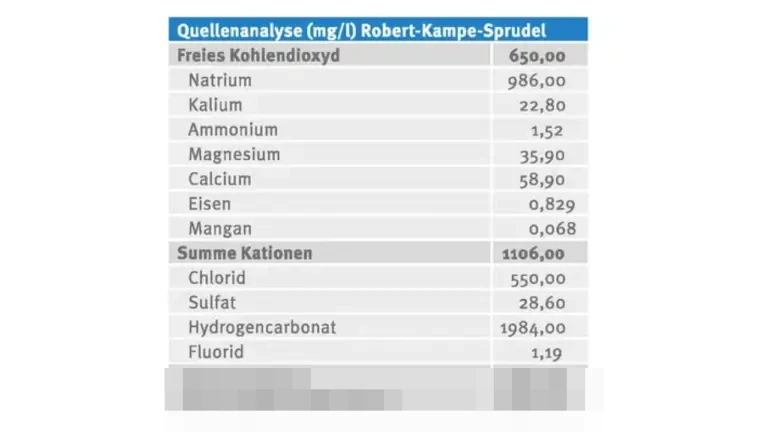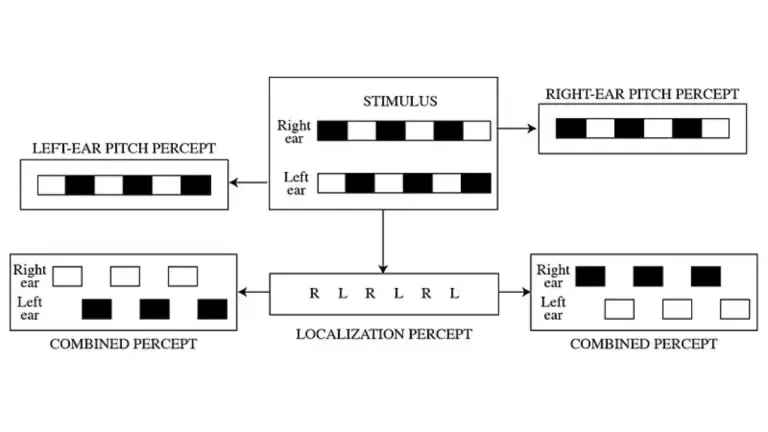Sebelum era jam mekanik dikenal luas, masyarakat Nusantara telah mengembangkan pemahaman waktu yang mendalam, terintegrasi erat dengan alam dan ritme kehidupan sehari-hari. Waktu tidak diukur dalam satuan detik atau menit yang kaku, melainkan sebagai rangkaian peristiwa yang berulang secara alami. Posisi matahari, peredaran bulan, kemunculan gugusan bintang, serta pergantian musim menjadi penanda utama yang membentuk sistem penanggalan lokal.
Konsep waktu yang demikian membuat setiap momen terasa hidup, sebab selalu terhubung langsung dengan berbagai aktivitas vital seperti bertani, melaut, berdagang, hingga pelaksanaan ritual adat. Pemahaman ini mencerminkan kearifan lokal dalam menyelaraskan kehidupan manusia dengan siklus alam semesta.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Pengukuran Waktu Harian Berbasis Alam
Pengukuran waktu harian paling fundamental dilakukan dengan mengamati pergerakan matahari. Masyarakat membagi hari menjadi pagi, siang, dan sore berdasarkan posisi matahari di langit. Alat sederhana seperti bayangan tongkat atau gnomon sering dimanfaatkan untuk penanda.
Di Jawa, dikenal pembagian waktu seperti eleh yang merujuk pada pagi hari, dan abueng untuk waktu menjelang siang, yang ditentukan dari panjang bayangan. Sementara itu, di kalangan masyarakat Bugis, pembagian waktu seperti ele dan tengngaesso digunakan bersama konsep Mattanra Wettu untuk menentukan waktu yang dianggap baik atau buruk dalam memulai suatu aktivitas.
Siklus Waktu yang Lebih Panjang: Jawa dan Bali
Selain hitungan harian, masyarakat Jawa dan Bali juga memiliki sistem perhitungan waktu dalam siklus yang lebih panjang dan kompleks. Kalender Jawa, misalnya, menggabungkan tujuh hari umum (Senin hingga Minggu) dengan lima hari pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Kombinasi ini menghasilkan siklus yang disebut weton, yang akan berulang setiap 35 hari sekali.
Dalam Jurnal Mengenal Istilah Bulan Dalam Kalender Jawa Pada Kehidupan Masyarakat Jawa: Kajian Etnolinguistik karya Iliya Ulva dan Uut Istianah, dijelaskan bahwa kalender Jawa juga memiliki sistem wuku. Sistem wuku ini terdiri dari 30 bagian, sehingga membentuk satu siklus waktu sepanjang 210 hari.
Perhitungan weton dan wuku masih relevan dan digunakan oleh masyarakat hingga kini, terutama untuk menentukan hari yang dianggap baik dalam pelaksanaan berbagai kegiatan penting dan upacara adat. Di Bali, sistem serupa dikenal dengan nama Pawukon, yang sampai saat ini tetap digunakan dan berjalan berdampingan dengan kalender Saka yang berasal dari tradisi Hindu.
Penanggalan Khas Bugis-Lontara dan Sasak
Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan memiliki kalender Lontara yang unik, memadukan unsur lunar, solar, dan Islam. Sistem ini juga mencakup pembagian waktu seperti lobbang yang berarti kurang baik, dan mallise yang dianggap baik untuk menentukan kegiatan harian, termasuk saat pergi ke ladang.
Di Pulau Lombok, masyarakat Sasak menggunakan Kalender Rowot. Sistem penanggalan ini sangat membantu dalam menentukan musim tanam yang optimal. Kalender Rowot memadukan pengaruh Hindu dan Islam Wetu Telu, sehingga tetap selaras dengan kondisi geografis dan sosial lokal.
Tanda Alam sebagai Penentu Musim dan Tahun
Pergantian musim menjadi penanda waktu yang sangat krusial bagi masyarakat Nusantara. Dalam sistem pranata mangsa Jawa, musim hujan dan kemarau dikenali melalui pengamatan arah angin dan posisi bintang-bintang di langit. Bulan-bulan Jawa, seperti Suro yang sarat makna ritual, merupakan hasil adaptasi kalender Saka yang kemudian dikenal sebagai Anno Javanico.
Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan juga membagi tahun berdasarkan fase bulan, menunjukkan pandangan waktu yang berulang dan terhubung dengan siklus alam. Catatan Mureks menunjukkan, adaptasi dan perpaduan berbagai sistem penanggalan ini mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal dalam memahami waktu.
Filosofi Waktu: Siklis, Bukan Linear
Berbeda dengan konsep Barat yang cenderung memandang waktu secara linear, waktu di Nusantara dipahami secara siklis. Masyarakat Jawa dan Bali, misalnya, meyakini bahwa peristiwa masa lalu dapat “hadir kembali” atau memiliki pengaruh pada masa kini melalui pelaksanaan ritual tertentu.
Perpaduan kalender Saka, Hijriah, dan unsur-unsur lokal telah membentuk sistem waktu Nusantara yang sangat lentur dan selaras dengan alam serta kehidupan sosial. Fleksibilitas ini memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan dan kebutuhan budaya.