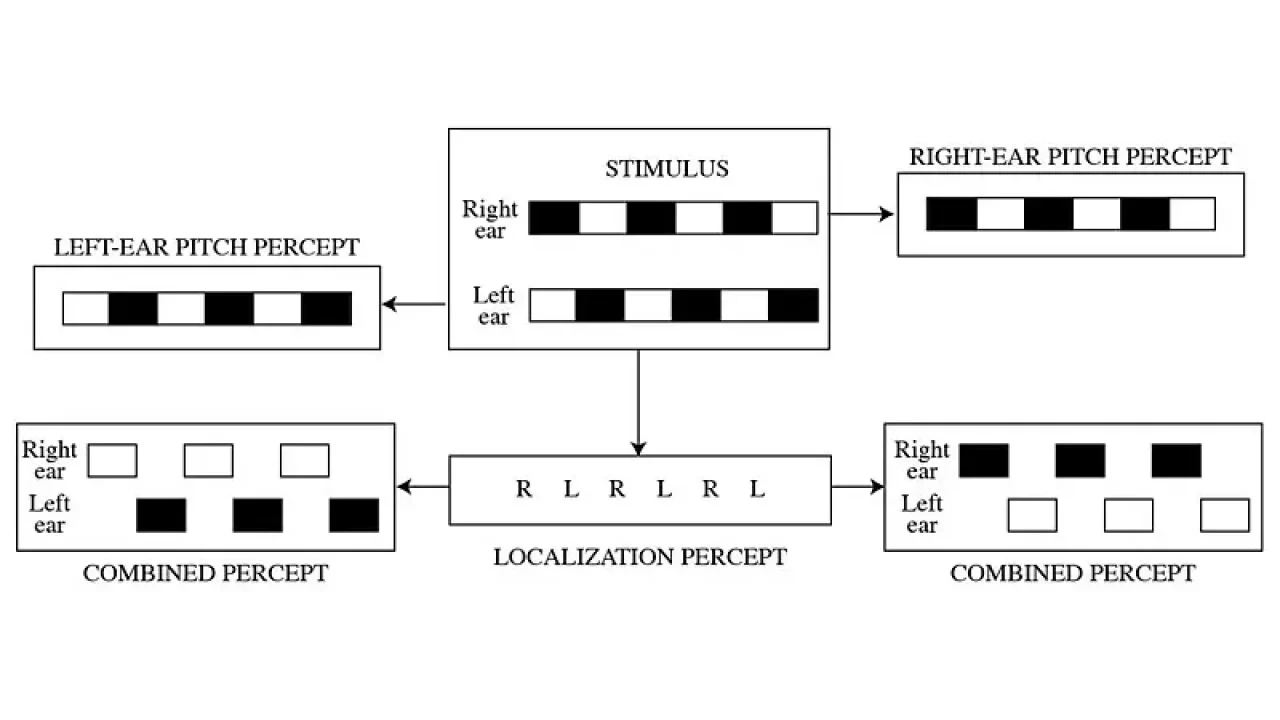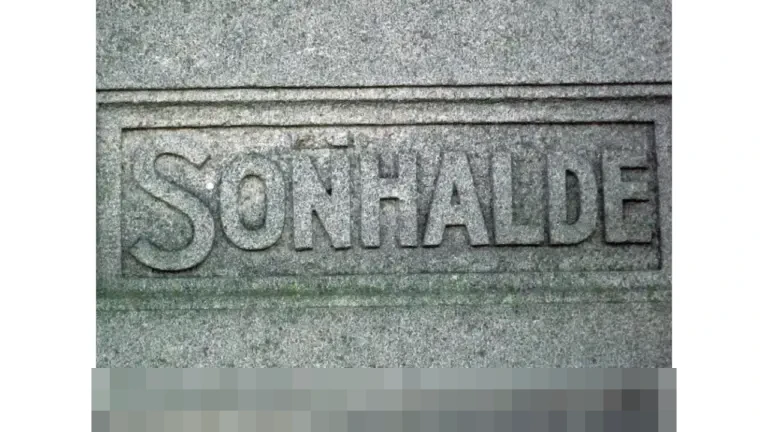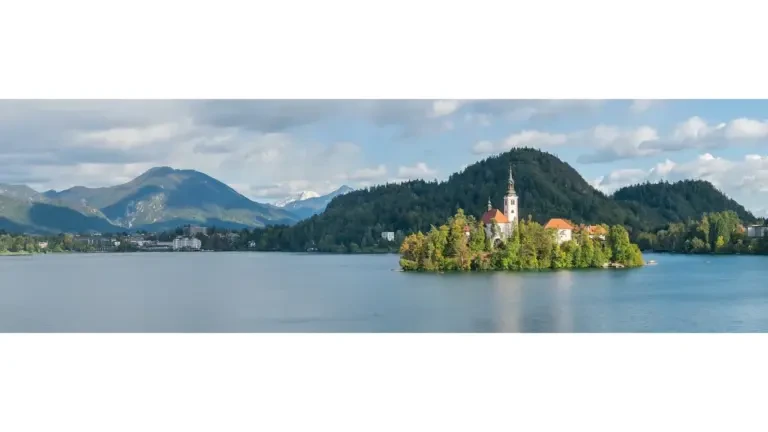Di atas kertas, banyak perpustakaan di Indonesia hari ini tampak baik-baik saja. Nilai akreditasi terpampang, laporan lengkap, dan berbagai indikator terpenuhi. Namun, realitas di lapangan seringkali berbeda: ruang baca sepi, koleksi jarang disentuh, dan kehadirannya nyaris tak terasa dalam kehidupan belajar masyarakat. Fenomena inilah yang disoroti Taufiq A Gani, seorang ASN di Perpusnas RI sekaligus Peneliti di IDCI, bahwa angka seringkali menciptakan ilusi tentang mutu.
Dalam banyak kebijakan layanan publik, mutu kerap direduksi menjadi sekadar skor. Kondisi ini membuat kita merasa aman ketika suatu capaian bisa diukur, diberi nilai, lalu diumumkan. Padahal, mutu bukanlah peristiwa administratif yang instan, melainkan sebuah proses kelembagaan yang dibangun perlahan. Ia melibatkan tata kelola yang baik, kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni, serta budaya kerja yang konsisten dan berkelanjutan.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Akreditasi: Antara Validasi dan Tujuan Semu
Akreditasi memang memiliki fungsi krusial sebagai bentuk pengakuan dan validasi eksternal. Ia menjadi sinyal bahwa sebuah perpustakaan telah memenuhi standar tertentu. Namun, masalah muncul ketika akreditasi diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai cermin sementara dari proses perbaikan yang sedang berjalan.
Akibatnya, muncul gejala yang jamak ditemui: perpustakaan mendadak “sibuk” menjelang penilaian, tetapi kembali sunyi setelahnya. Fokus utama tertuju pada pengisian borang dan pemenuhan instrumen, bukan pada pembenahan layanan yang substansial. Instrumen penilaian menjadi pusat perhatian, sementara standar yang seharusnya menjadi rujukan utama justru terlupakan. Pada titik ini, angka menggantikan makna, dan mutu dipahami sebagai hasil penilaian, bukan sebagai kemampuan institusi untuk terus belajar dan memperbaiki diri.
Standar dan Instrumen: Dua Hal yang Kerap Tertukar
Dalam tata kelola mutu, ada perbedaan mendasar yang kerap luput dipahami, bahkan oleh penyelenggara layanan itu sendiri. Standar adalah rujukan normatif, sebuah gambaran ideal tentang seperti apa perpustakaan yang bermutu. Ia memuat nilai, prinsip, dan tujuan yang hendak dicapai.
Sebaliknya, instrumen hanyalah alat ukur. Ia membantu melihat sejauh mana standar itu terpenuhi, tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan standar itu sendiri. Ketika instrumen diperlakukan lebih penting daripada standar, yang terjadi adalah pembalikan logika. Perpustakaan menjadi pandai mengisi formulir, tetapi gagap dalam membangun layanan yang relevan. Mutu pun berubah menjadi urusan administratif, bukan pengalaman nyata yang dirasakan oleh pengguna.
Mutu sebagai Proses, Bukan Sekadar Penghakiman
Penting untuk memahami bahwa penilaian dan pembinaan adalah dua fungsi yang berbeda. Penilaian diperlukan untuk menjaga akuntabilitas, namun tanpa pembinaan dan penguatan kapasitas, penilaian hanya akan menghasilkan label tanpa membawa perubahan berarti. Mutu yang sesungguhnya tumbuh dari dalam. Ia lahir ketika perpustakaan mampu mengelola dirinya secara mandiri, mulai dari menyusun prosedur kerja, mengevaluasi layanan secara jujur, memperbaiki kekurangan, hingga menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna. Proses ini tidak instan dan tidak selalu terlihat dalam satu siklus penilaian.
Oleh karena itu, sistem yang sehat adalah sistem yang tidak hanya rajin menilai, tetapi juga serius membangun kapasitas. Catatan Mureks menunjukkan, keberlanjutan mutu sangat bergantung pada keseimbangan antara evaluasi dan pengembangan.
Membangun Ekosistem Mutu, Bukan Sekadar Akreditasi
Perpustakaan yang hidup membutuhkan ekosistem mutu yang terintegrasi. Ada peran pembina yang membantu membangun pemahaman dan kemampuan. Ada penilai yang memastikan akuntabilitas eksternal. Serta ada pula fungsi analisis yang membaca data secara mendalam untuk memahami pola keberhasilan dan kegagalan.
Jika salah satu fungsi ini berdiri sendiri, mutu akan pincang. Penilaian tanpa pembinaan melahirkan kepatuhan semu. Pembinaan tanpa evaluasi berisiko kehilangan arah. Sementara analisis tanpa tindak lanjut akan berhenti sebagai laporan semata. Ekosistem mutu menuntut kerja yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Mengembalikan Mutu ke Pengalaman Pengguna
Pada akhirnya, publik tidak pernah bertanya berapa nilai akreditasi perpustakaan. Yang dirasakan warga adalah: apakah perpustakaan itu berguna, ramah, relevan, dan hadir dalam kehidupan mereka? Apakah ia membantu anak belajar membaca, mahasiswa meneliti, atau masyarakat mengakses pengetahuan yang mereka butuhkan?
Jika perpustakaan berstatus baik tetapi tidak digunakan, maka ada yang keliru dalam cara kita memahami mutu. Perpustakaan sebagai layanan publik tidak diukur dari angka, tetapi dari apakah warga datang untuk membaca dan memanfaatkan layanannya. Mutu hidup ketika perpustakaan hadir dan digunakan secara nyata.
Angka memang penting, tetapi ia tidak pernah cukup. Mutu bukan sekadar hasil penilaian, melainkan proses kelembagaan yang terus dibangun, dijaga, dan ditingkatkan. Tanpa kesadaran ini, kita akan terus terjebak dalam ilusi—merasa telah bermutu, padahal yang tumbuh hanyalah administrasi. Dan dalam urusan layanan publik, ilusi semacam itu adalah kemewahan yang terlalu mahal untuk terus dipelihara.