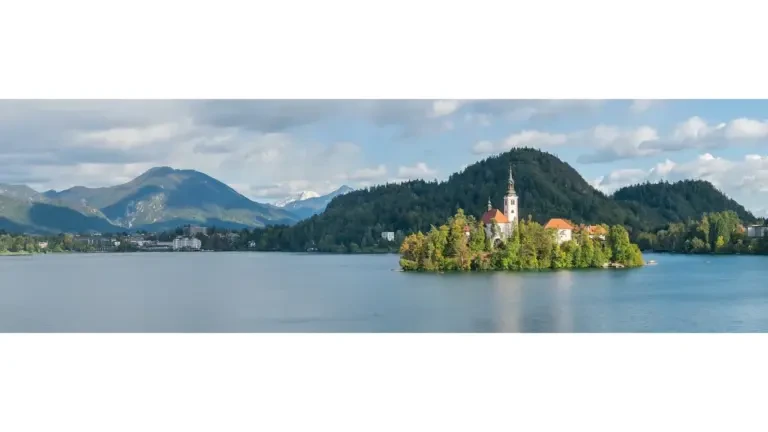Fenomena normalisasi pernikahan dini di linimasa media sosial belakangan ini memicu keprihatinan mendalam, bahkan kemarahan. Konten-konten tersebut kerap tampil dengan wajah yang tampak saleh, memadukan potongan dalil agama, cuplikan ceramah singkat, dan narasi ketakutan yang disederhanakan. Namun, di balik itu, terdapat pola berulang yang dinilai berbahaya: kemalasan berpikir yang dilegitimasi atas nama iman.
Ewia Ejha Putri, Pimpinan Lembaga PKBM Pahlawan Kerinci dan Anggota LHKP Muhammadiyah Jambi, menyoroti bagaimana logika ketakutan ini sering digunakan. Ia mencontohkan seorang ustaz di TikTok yang berujar, “Kalau anak semester dua kuliah sudah minta menikah, jangan dilarang. Nikahkan saja, daripada zina,” lalu menutupnya dengan kisah, “Tuh kan, dilarang nikah malah hamil.”
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Mengkritisi Logika Ketakutan dalam Pendidikan
Menurut Ewia, logika semacam ini keliru sejak awal. Ia berangkat dari asumsi bahwa anak muda tidak memiliki akal, tidak mampu mengelola dorongan, dan tidak layak dilatih berpikir jangka panjang. Padahal, inti pendidikan moral—baik dalam Islam maupun ilmu psikologi—justru terletak pada kemampuan menunda, mengelola, dan mengarahkan hasrat dengan akal serta nilai.
Psikolog perkembangan seperti Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg menegaskan bahwa kematangan pengambilan keputusan tumbuh melalui proses belajar, pengalaman, dan kedewasaan kognitif, bukan semata karena seseorang telah baligh atau siap secara biologis. Catatan Mureks menunjukkan, perdebatan mengenai kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan dini terus menjadi isu krusial di tengah masyarakat.
Pernikahan Dini sebagai Gaya Hidup Ideal yang Menyesatkan
Masalah ini semakin serius ketika narasi pernikahan dini tidak hanya dibenarkan, tetapi juga dijual sebagai gaya hidup ideal. Publik sering menyaksikan konten viral seorang perempuan berusia 19 tahun yang menikah muda, lalu dengan penuh percaya diri menyatakan, “Kuliah itu scam,” sambil memamerkan keberhasilan bisnis hijab syar’i yang ia kelola.
Ewia Ejha Putri menegaskan, ini bukan lagi sekadar pendapat pribadi. Ketika klaim semacam ini disebarkan ke ruang publik dengan jutaan penonton tanpa konteks, ia berubah menjadi racun sosial. Yang ditonton publik bukan keseluruhan realitas hidupnya—bukan fakta bahwa ia mungkin memiliki keluarga penopang, modal ekonomi, jaringan sosial, atau privilese tertentu.
Yang diserap mentah-mentah justru satu pesan sederhana namun menyesatkan: menikah muda adalah solusi, sementara pendidikan tinggi tidak penting. Sosiolog Pierre Bourdieu telah lama menjelaskan bahwa keberhasilan individu tidak pernah berdiri di ruang hampa; ia ditopang oleh modal ekonomi, sosial, dan kultural. Menghapus konteks ini sama saja dengan menyesatkan publik secara simbolik.
Dampak Pola Pikir Instan dan Reduksi Ketakwaan
Dari sinilah dapat dipahami mengapa kualitas umat terasa stagnan, mengapa literasi rendah, dan mengapa masyarakat mudah digerakkan oleh simbol agama tetapi miskin refleksi. Pola pikir yang terus direproduksi adalah pola pikir serba instan: yang penting sekarang. Kesalehan direduksi menjadi daftar centang—cepat berhijab, cepat menikah, soal ekonomi dianggap rezeki Allah semata, dan masa depan anak diserahkan pada harapan kosong. Selesai. Merasa aman. Seolah-olah telah lulus agama.
Padahal, menurut Ewia, ini bukan ketakwaan, melainkan kecerobohan yang dibungkus kalimat suci. Tawakal dalam Islam datang setelah ikhtiar, setelah perencanaan, setelah belajar, dan setelah kesiapan. Bukan tawakal sejak awal karena enggan berpikir. Imam Al-Ghazali menempatkan akal sebagai fondasi tanggung jawab moral manusia. Mengabaikan akal berarti meruntuhkan etika itu sendiri.
Pentingnya Akal dan Perencanaan dalam Islam
Tanpa disadari, pesan berbahaya sedang dikirimkan kepada anak-anak dan remaja: jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu lama sekolah, jangan banyak merencanakan hidup. Yang penting patuh dan cepat menikah, sisanya Allah yang mengurus. Padahal Al-Qur’an berulang kali memerintahkan manusia untuk berpikir (tafakkur), merenung (tadabbur), dan mempertimbangkan akibat jangka panjang.
- “Apakah kamu tidak berpikir?” (QS. Al-Baqarah: 44)
- “Agar mereka memikirkan akibatnya” (QS. Al-Hasyr: 18)
Ayat-ayat ini menjadi penegasan bahwa iman tidak pernah dipisahkan dari akal. Islam tidak pernah mengajarkan hidup asal berjalan lalu menyerahkan kekacauan pada takdir.
Misi Rasulullah SAW dan Tanggung Jawab Pernikahan
Ewia Ejha Putri menyampaikan dengan nada serius dan tegas: misi Rasulullah SAW bukan sekadar menjauhkan umat dari zina. Jika hanya itu, risalah Islam terlalu murah bagi peradaban sebesar ini. Misi beliau adalah mencerdaskan umat dengan perintah membaca, mematangkan akhlak—bukan sekadar ritual—serta menjadikan manusia berdaya dan bertanggung jawab.
Menikah dini semata-mata karena takut zina sering kali bukan tanda keimanan, melainkan tanda kegagalan mendidik. Mengapa tidak lebih banyak diajarkan bagaimana membangun relasi yang bermartabat? Bagaimana mengelola dorongan dengan akal dan nilai? Bagaimana menunda kesenangan demi masa depan yang lebih besar?
Tidak semua anak lahir dari keluarga dengan kondisi yang sama. Tidak semua pasangan muda memiliki jaring pengaman ekonomi. Bahkan ketika uang tersedia, kedewasaan mental dan emosional tidak bisa dibeli. Rumah tangga bukan konten romantis; ia adalah tanggung jawab panjang—kepada pasangan, kepada anak, dan kepada masa depan. Realitas sering kali jauh lebih kejam daripada narasi ceramah, seperti yang pernah disaksikan dalam kasus anak seorang ustaz terkenal yang menikah sangat muda hingga berujung pada persidangan dan pemberitaan publik.
Mencetak Generasi Emas atau Generasi yang Mencemaskan?
Jika hari ini masyarakat menormalisasi kemalasan berpikir atas nama agama, mengejek pendidikan sebagai scam, dan mencurigai perencanaan hidup sebagai tanda kurang iman, maka patut jujur pada diri sendiri: kita bukan sedang menuju generasi emas, melainkan mencetak generasi yang mencemaskan.
Padahal Al-Qur’an menetapkan standar tinggi: kuntum khaira ummah—umat terbaik—yakni umat yang menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah (QS. Ali ‘Imran: 110). Umat terbaik bukan yang paling cepat menikah, melainkan yang kuat ilmunya, matang akalnya, luhur akhlaknya, serta bertanggung jawab atas pilihannya.
Oleh karena itu, Ewia Ejha Putri mengajak untuk sekolah setinggi-tingginya, belajar selama mungkin, dan mengisi kepala serta jiwa sebelum meniru jalan hidup orang lain. Bukan karena anti-menikah, melainkan karena keinginan untuk menikah dengan kesiapan, martabat, dan masa depan. Pernikahan bukan pelarian dari ketakutan, melainkan keputusan sadar dari manusia yang berpikir.