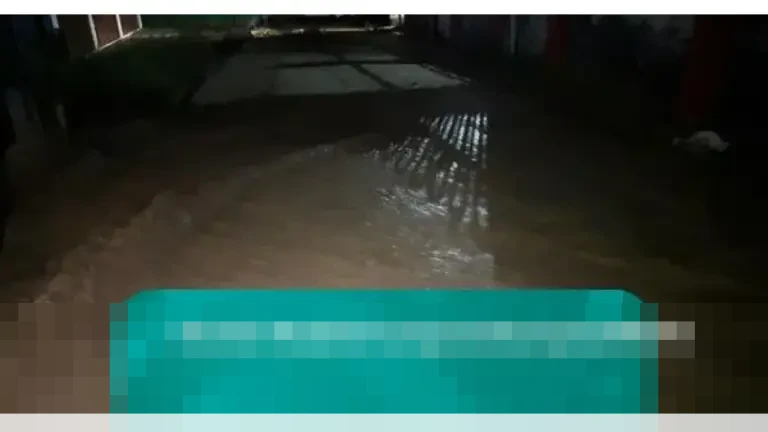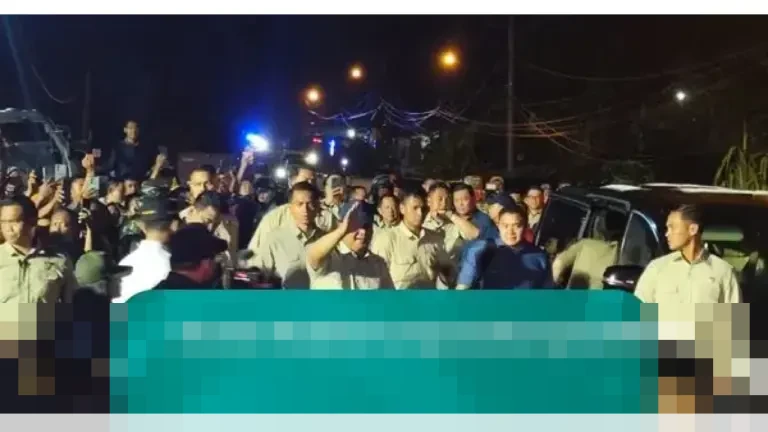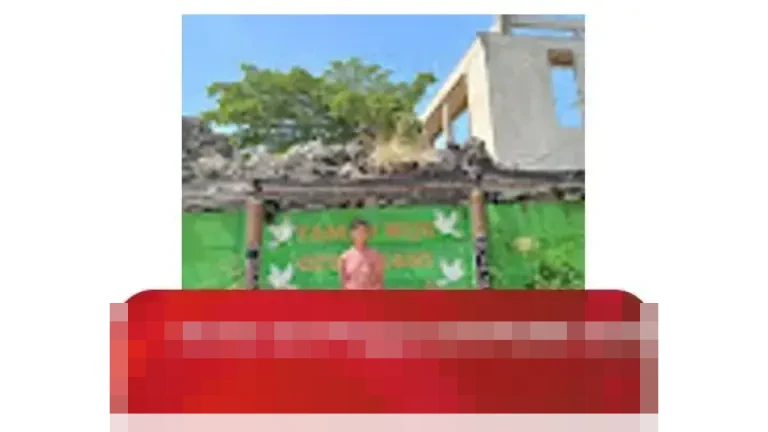Pada 2019, Sri Lanka mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan ekonomi yang puncaknya berujung pada krisis besar pada 2022. Krisis ini tercatat sebagai yang terburuk dalam tujuh dekade terakhir sejarah negara tersebut, menyeret jutaan penduduk ke dalam kesulitan, ketidakamanan pangan, dan kelaparan.
Data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dan Program Pangan Dunia PBB (WFP) pada 2022 mengungkapkan, sekitar 6,3 juta masyarakat Sri Lanka menghadapi krisis pangan akut. Situasi ini diperparah oleh penurunan produksi pertanian hingga 50 persen. Penyebab utamanya adalah kelangkaan impor biji-bijian pangan, pupuk kimia, dan pestisida, yang merupakan imbas dari menipisnya cadangan devisa negara.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Kelangkaan pangan dan melambungnya harga bahan pokok serta bahan pertanian menjadi konsekuensi langsung. Hal ini tidak hanya mengganggu sektor pertanian dan aktivitas komersial, tetapi juga memicu berkurangnya lapangan pekerjaan. Banyak tempat produksi terpaksa memecat karyawan untuk menekan biaya operasional yang tidak sebanding dengan hasil produksi.
Dampak Krisis yang Melumpuhkan Kehidupan
Inflasi yang terjadi telah mendevaluasi nilai rupee secara drastis, menyebabkan harga bahan pangan melonjak tak terkendali. Daya beli masyarakat pun merosot tajam, membuat makanan semakin tidak terjangkau, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Penurunan aktivitas ekonomi turut memukul pekerjaan dan sumber penghasilan masyarakat.
Sri Lanka juga menghadapi kebangkrutan dan kehabisan bahan bakar. Akibatnya, masyarakat harus mengalami pemadaman listrik berjam-jam setiap hari untuk menghemat energi, serta antrean panjang hingga berhari-hari untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Pemadaman listrik yang intens dan kekurangan obat-obatan vital turut menghancurkan sistem kesehatan negara.
Banyak rumah sakit terpaksa membatalkan jadwal operasi karena kekurangan obat. Operasi rutin ditangguhkan dan tes diagnostik laboratorium dikurangi di berbagai fasilitas kesehatan, menunjukkan betapa parahnya dampak krisis terhadap layanan dasar.
Akar Masalah: Kebijakan, Korupsi, dan Pandemi
Krisis ekonomi Sri Lanka sering kali dikaitkan dengan jebakan utang Tiongkok, namun analisis lebih dalam menunjukkan bahwa ini adalah krisis struktural yang dipicu oleh berbagai faktor kompleks.
Kemunduran ekonomi Sri Lanka berawal dari kesalahan implementasi kebijakan pada 2019. Saat itu, presiden Sri Lanka menerapkan pemotongan pajak bagi masyarakat dengan dalih menstimulus pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mencakup pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 15 persen menjadi 8 persen.
Kebijakan tersebut menuai kritik tajam dari ekonom dan lembaga think-tank seperti Advocata Institute. Murtaza Jafferjee, kepala Advocata Institute, berpendapat bahwa, "kebijakan pemotongan pajak tersebut merupakan misdiagnosis terhadap kondisi ekonomi Sri Lanka saat itu." Rancangan kebijakan ini dinilai sebagai upaya presiden Sri Lanka untuk meraih simpati rakyat pada pemilu 2019 dengan janji penurunan pajak besar-besaran.
Pada akhirnya, kebijakan ini terbukti tidak efektif. Alih-alih merangsang pertumbuhan, pemotongan pajak justru memperburuk defisit fiskal negara dan disubsidi dari utang negara yang terus membengkak. Selain itu, kebijakan pelarangan penggunaan pupuk kimia, yang bertujuan mendorong pertanian organik, justru menurunkan produktivitas pertanian secara drastis. Petani kesulitan beradaptasi karena kurangnya pengetahuan dan ketersediaan pupuk organik, menyebabkan hasil panen komoditas utama seperti beras, teh, dan rempah-rempah anjlok. Pemerintah akhirnya terpaksa mengimpor pupuk organik dari luar.
Korupsi dan Nepotisme yang Mengakar
Implementasi kebijakan yang buruk diperparah oleh budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah mengakar dalam pemerintahan Sri Lanka. Laporan Transparency International pada 2022 menempatkan Sri Lanka di peringkat 101 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Praktik nepotisme dan politik dinasti sangat kuat di negara tersebut.
Pada masa kepresidenan Gotabaya Rajapaksa, posisi perdana menteri diisi oleh kakaknya sendiri, Mahinda Rajapaksa. Jajaran kementerian juga banyak diisi oleh anggota keluarga Rajapaksa, memperkuat dinasti politik. Praktik korupsi dan nepotisme semacam ini menghambat efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah dan menghalangi upaya reformasi struktural yang sangat dibutuhkan. Korupsi pada akhirnya berkontribusi pada krisis utang, defisit fiskal yang besar, dan ketidakstabilan ekonomi yang dialami Sri Lanka.
Dampak Pandemi COVID-19
Faktor lain yang turut memperparah krisis adalah pandemi COVID-19. Sri Lanka, yang sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan terbesar ketiganya, merasakan dampak pahit pandemi yang membuat jumlah wisatawan anjlok drastis. Pada 2019, tercatat 2,3 juta wisatawan, namun pada 2020 angka itu turun drastis menjadi hanya 120 ribu, atau anjlok 73,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya akibat penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan.
Pandemi juga mengganggu aktivitas ekspor dan impor Sri Lanka. Negara ini bergantung pada ekspor komoditas pertanian untuk menghasilkan pendapatan. Dengan gangguan rantai pasokan global dan penurunan permintaan dunia, ekspor Sri Lanka turun 15,9 persen pada 2020, dari 11,9 miliar dolar AS menjadi hanya 10 miliar dolar AS. Di sisi lain, impor barang-barang esensial seperti bahan bakar, obat-obatan, dan bahan makanan juga terganggu, menyebabkan kekurangan pasokan. Meskipun pemerintah telah berupaya dengan stimulus fiskal, relaksasi kebijakan moneter, dan program bantuan sosial, langkah-langkah tersebut tidak cukup, sehingga Sri Lanka akhirnya meminta bantuan keuangan dari IMF.
Manajemen Utang yang Buruk
Krisis ekonomi ini tidak terlepas dari buruknya manajemen utang oleh pemerintah Sri Lanka. Namun, perlu dipahami bahwa jumlah utang luar negeri yang tinggi bukanlah penyebab utama, melainkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat. Rasio utang Sri Lanka terhadap PDB telah mencapai 114 persen pada 2022. Tingginya rasio ini mengindikasikan bahwa beban utang negara menjadi tidak berkelanjutan dan membahayakan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan dan pemanfaatan utang juga tidak dialokasikan ke sektor-sektor produktif yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara. Buruknya manajemen utang dan penggunaannya yang tidak tepat sasaran menjadi faktor signifikan dalam krisis ekonomi yang terjadi.