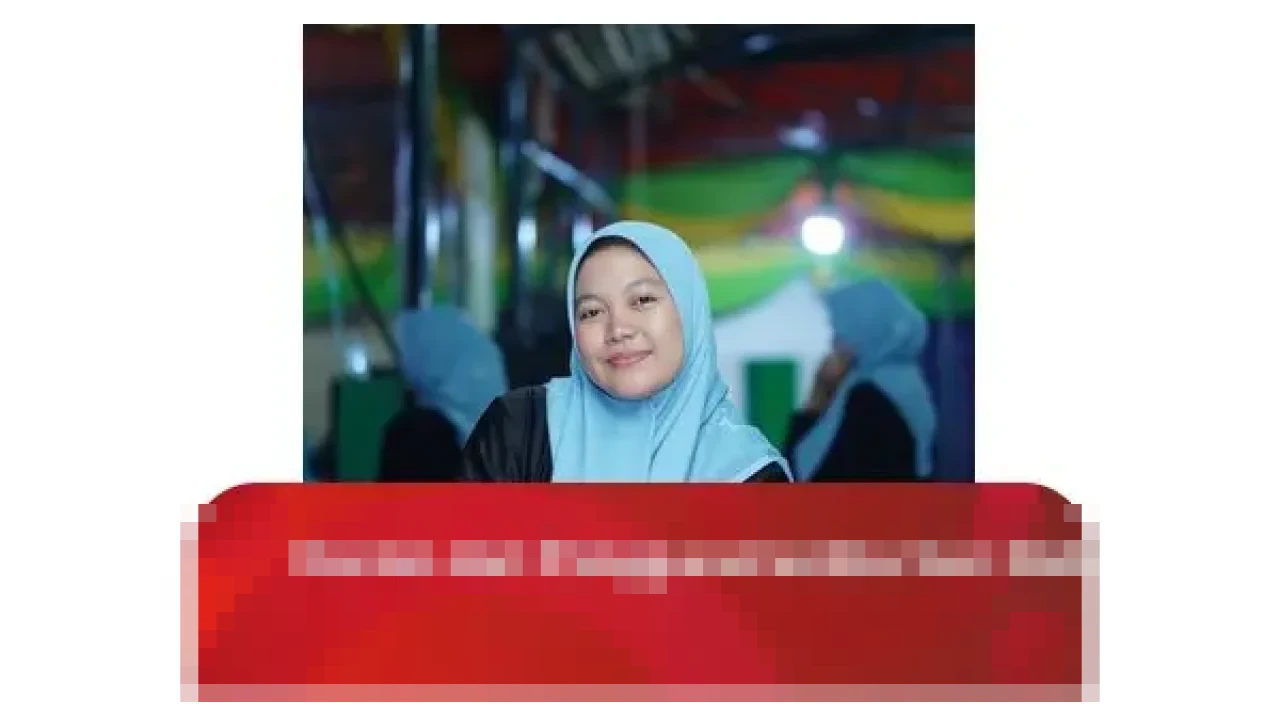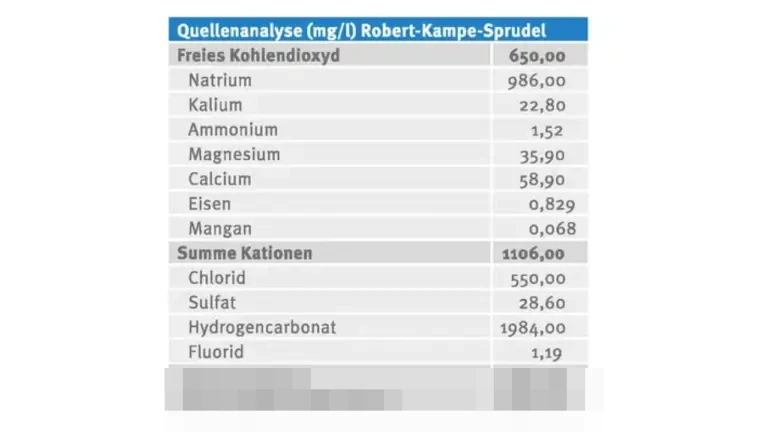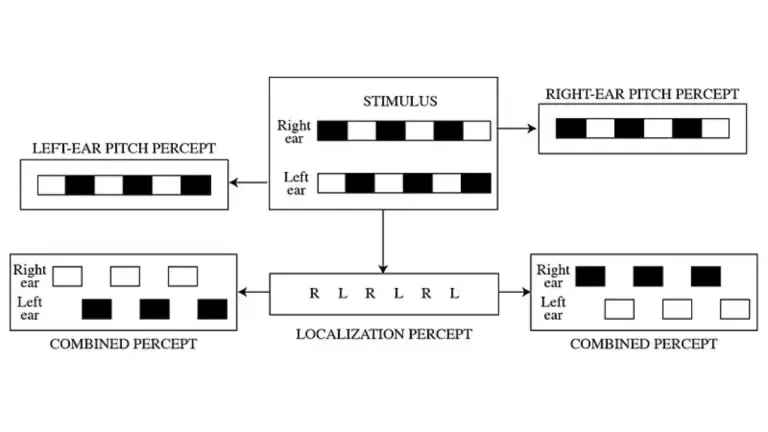Frekuensi bencana alam di berbagai wilayah Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan. Fenomena ini kerap dimaknai sebagai peringatan dari alam, namun analisis mendalam Mureks mencatat bahwa kelalaian manusia seringkali menjadi faktor pemicu utama di balik kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Memahami interaksi kompleks antara kekuatan alam dan tindakan manusia menjadi krusial untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.
Bencana alam acapkali menyapa tanpa permisi, mengganggu rutinitas harian, baik saat bekerja, bersekolah, maupun menikmati akhir pekan. Dalam hitungan jam, banjir dapat menenggelamkan permukiman, tanah longsor merobohkan bangunan, dan kebakaran melahap hutan yang membutuhkan puluhan tahun untuk pulih. Pasca-kejadian, seringkali terlontar frasa klise: “Ini peringatan dari alam.” Namun, tim redaksi Mureks mempertanyakan, apakah peringatan tersebut benar-benar diresapi atau hanya sekadar diucapkan lalu dilupakan?
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Alam Bekerja, Manusia yang Mengusik
Pada hakikatnya, alam beroperasi berdasarkan hukum-hukumnya sendiri. Air mengalir ke dataran rendah, tanah memerlukan akar pepohonan untuk stabilitas, dan hutan berfungsi vital sebagai penopang ekosistem, bukan sekadar lahan yang siap ditebang. Konflik muncul ketika manusia mulai memperlakukan alam sebagai entitas yang dapat dimanipulasi sesuai kehendak. Sungai dipersempit untuk proyek pembangunan, lereng bukit dibuka tanpa kajian mendalam, dan hutan ditebang atas nama kemajuan. Keyakinan berlebihan pada kemampuan teknologi untuk mengatasi segala dampak seringkali menutupi fakta bahwa alam memiliki batas toleransi.
Bencana yang Kerap Disebut “Tak Terduga”
Meskipun sering dilabeli sebagai musibah tak terduga, banyak bencana sesungguhnya memiliki rekam jejak panjang yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Banjir, misalnya, bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan juga dipicu oleh buruknya sistem drainase dan sungai yang tersumbat sampah. Longsor bukan hanya karena struktur tanah yang labil, melainkan dampak dari deforestasi yang menghilangkan penahan alami. Demikian pula kebakaran hutan, yang tak hanya disebabkan cuaca kering, tetapi juga praktik pembukaan lahan yang ceroboh.
Kasus banjir berulang di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, meski kerap dikaitkan dengan intensitas hujan, sejatinya jauh lebih kompleks. Alih fungsi lahan, penyempitan badan sungai, dan sistem drainase yang tidak memadai telah menghilangkan ruang alami bagi air. Konsekuensinya, curah hujan yang seharusnya dapat dikelola justru bertransformasi menjadi bencana tahunan.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas bencana di Indonesia didominasi oleh kejadian hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Jenis bencana ini memiliki korelasi kuat dengan kondisi lingkungan dan intervensi manusia terhadapnya.
Pola Berulang Pasca-Bencana: Empati yang Memudar
Pasca-bencana, masyarakat biasanya memasuki fase empati kolektif. Bantuan mengalir deras, relawan bekerja tanpa henti, dan media massa gencar memberitakan. Semangat kebersamaan terasa begitu kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, atensi publik cenderung memudar. Kehidupan kembali normal, janji-janji evaluasi hanya menjadi arsip, dan kebiasaan lama kembali terulang.
Ironisnya, bencana berikutnya seringkali terjadi di lokasi yang sama atau dengan pola serupa. Masyarakat kembali terkejut dan berduka, seolah melupakan bahwa kejadian serupa pernah menimpa sebelumnya. Di sinilah letak ironi terbesar: kita mengingat peristiwa bencananya, namun gagal meresapi pelajaran yang terkandung di dalamnya.
Mengapa Pelajaran dari Bencana Sulit Diresapi?
Salah satu faktor penyebab sulitnya masyarakat belajar dari bencana adalah jarak psikologis. Selama bencana tidak menimpa secara langsung, ia cenderung dianggap sebagai kisah orang lain. Simpati memang muncul, namun rasa keterlibatan yang mendalam baru benar-benar hadir ketika rumah sendiri terendam atau anggota keluarga menjadi korban.
Faktor lain adalah paradigma pembangunan. Kemajuan seringkali diukur dari infrastruktur fisik seperti beton, jalan tol, dan gedung-gedung pencakar langit. Dampak lingkungan kerap dianggap sebagai konsekuensi yang harus ditanggung. Padahal, harga yang harus dibayar atas kerusakan lingkungan seringkali jauh melampaui perkiraan, mencakup hilangnya nyawa, rusaknya ekosistem, dan penderitaan jangka panjang bagi masyarakat.
Belajar atau Sekadar Bertahan?
Jika alam diibaratkan sebagai guru, maka ia adalah pengajar yang tak pernah lelah mengulang pelajarannya. Namun, setiap pengulangan selalu datang dengan konsekuensi yang semakin berat: kerusakan meluas, dampak membesar, dan jumlah korban bertambah.
Belajar dari bencana seyogianya berarti melakukan perubahan fundamental. Bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, melainkan membangun dengan pendekatan yang lebih bijak. Ini mencakup penataan ulang ruang hidup, mendengarkan rekomendasi ilmiah, dan menghargai batas-batas alami lingkungan. Tindakan kecil pun memiliki signifikansi, mulai dari cara kita memperlakukan lingkungan sekitar hingga dukungan terhadap kebijakan publik yang berpihak pada keberlanjutan.
Pada akhirnya, esensi belajar dari bencana bukanlah untuk takut pada alam, melainkan untuk memahami dan hidup berdampingan dengannya. Alam bukanlah musuh yang harus ditaklukkan, melainkan sebuah sistem kompleks yang perlu dipahami dan dihormati. Selama manusia terus mengulangi kesalahan yang sama, bencana akan selalu menemukan jalannya kembali. Pertanyaan krusial kini bukan lagi kapan bencana akan datang, melainkan apakah kita bersedia berubah sebelum harga dari setiap pelajaran menjadi semakin mahal.