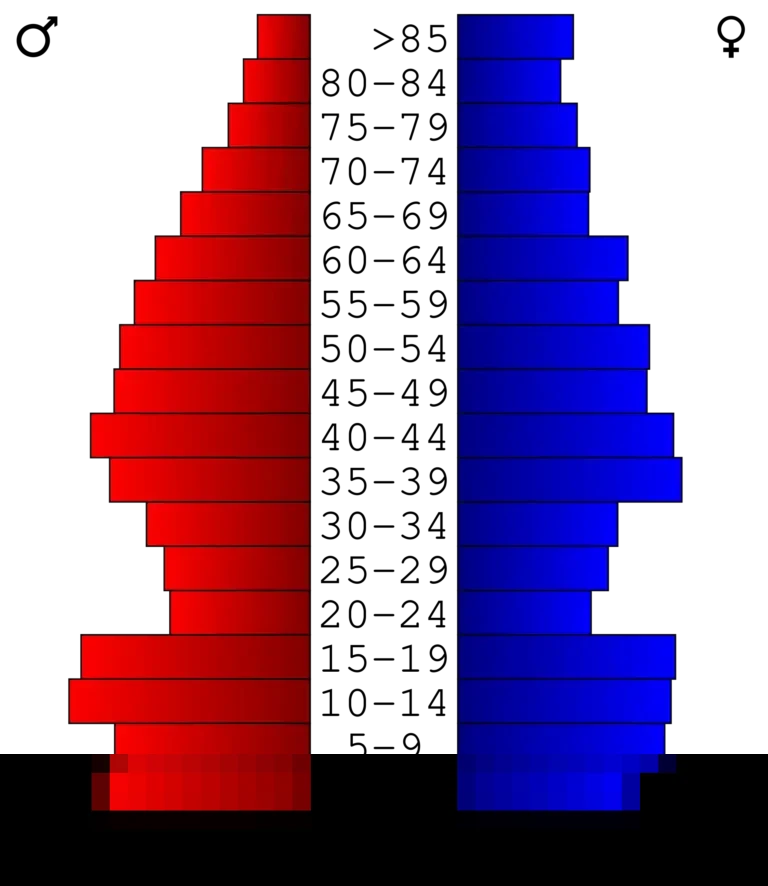Di tengah deru kendaraan Ring Road Utara dan riuhnya suara suporter dari Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta, tersimpan sebuah anomali sejarah yang kerap luput dari perhatian. Jika Candi Prambanan dan Borobudur berdiri megah, Candi Gebang justru memilih jalan sunyi, seolah merendahkan diri di hadapan zaman yang terus berlari. Situs kuno dari abad ke-8 ini bukan sekadar tumpukan batu andesit, melainkan saksi bisu perjuangan spiritualitas masa lalu yang bertahan di tengah kepungan perumahan elit dan modernitas kota.
Bagi mereka yang sengaja mencari jeda di Dusun Gebang, Kelurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman, candi ini menawarkan paradoks menenangkan. Ia menjadi ruang purba yang kini seolah menjadi halaman belakang bagi kehidupan suburban yang bising.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Menyusuri Jejak Kuno di Balik Perumahan Modern
Memasuki area Candi Gebang tidak seperti mengunjungi kompleks arkeologi pada umumnya. Pengunjung harus melintasi portal perumahan warga, menyusuri jalan konblok yang diapit pagar rumah modern, hingga tiba di sebuah gapura sederhana. Keunikan situs ini terletak pada posisinya yang berada di dataran rendah, bahkan lebih rendah dari permukaan tanah sekitarnya. Hal ini menciptakan ilusi optik; dari kejauhan ia tak tampak, namun begitu menuruni anak tangga, wujudnya yang mungil namun kokoh—berukuran sekitar 5,25 x 5,25 meter dengan tinggi 7,75 meter—menyambut dengan aura magis.
Kesunyian di sini terasa artifisial namun nyata, seakan dinding-dinding tanah di sekelilingnya sengaja diciptakan alam untuk memblokir suara bising knalpot dari jalan raya yang hanya berjarak beberapa kilometer.
Penemuan Tak Sengaja dan Identitas Shivaite
Sejarah penemuan Candi Gebang menyimpan narasi ketidaksengajaan yang berbuah manis bagi dunia arkeologi Indonesia. Pada November 1936, penduduk setempat menemukan batu andesit yang tertimbun lahar dingin Gunung Merapi saat beraktivitas. Penemuan patung Ganesha, dewa ilmu pengetahuan dan penolak bala, menjadi kunci pembuka sejarah ini.
I.R. van Romondt, seorang arsitek dari dinas purbakala Hindia Belanda saat itu, segera menyadari pentingnya temuan tersebut. Ekskavasi yang dipimpin oleh Prof. Dr. F.D.K. Bosch kemudian mengungkap bahwa Candi Gebang memiliki karakteristik unik dibandingkan candi-candi Hindu lainnya di Jawa Tengah maupun Yogyakarta. Ia tidak memiliki tangga masuk megah atau relief cerita rumit seperti Ramayana di Prambanan. Kesederhanaan ini justru menjadi kekuatan naratifnya; ia adalah tempat pemujaan bagi kaum resi atau pertapa, bukan tempat pamer kemegahan raja-raja.
Secara arsitektur, Candi Gebang adalah studi kasus tentang adaptasi dan fungsi. Kaki candi yang tinggi tanpa selasar keliling memberikan kesan ramping namun teguh. Menurut Mureks, yang paling menarik perhatian peneliti adalah keberadaan titik puncak atapnya yang tidak dimahkotai oleh Ratna (ciri khas candi Hindu) ataupun Stupa (ciri khas candi Buddha) secara murni, melainkan sebuah bentuk lingga yang diletakkan di atas seroja bantalan ganda. Ini menegaskan identitasnya sebagai candi Hindu yang memuja Siwa, namun dengan sentuhan lokalitas yang kental. Di dalam bilik candi yang sempit, hanya tersisa sebuah yoni dan lingga semu yang menjadi pusat orientasi spiritual. Kekosongan bilik ini memberikan ruang bagi imajinasi pengunjung modern untuk merenung; bahwa kekosongan adalah bentuk tertinggi dari kepasrahan.
Candi Gebang di Tengah Kepungan Modernitas
Tantangan terbesar Candi Gebang hari ini bukanlah ancaman letusan Merapi, melainkan tekanan demografi dan tata ruang kota. Wilayah Wedomartani yang dulunya hamparan sawah hijau, dalam dua dekade terakhir telah bermetamorfosis menjadi kawasan hunian padat, kampus, dan pusat olahraga. Candi Gebang kini terkepung. Jarak antara pagar situs dengan dinding rumah penduduk sangatlah tipis, menciptakan situasi canggung namun harmonis.
Di satu sisi, keberadaan perumahan melindungi candi dari vandalisme karena pengawasan warga menjadi lebih intensif. Di sisi lain, sakralitas situs ini terus diuji oleh aktivitas manusia modern di sekitarnya. Suara musik dangdut dari hajatan warga, teriakan anak-anak yang bermain bola, hingga gemuruh suara pesawat yang mendarat di Bandara Adisutjipto, menjadi latar suara abadi bagi situs tua ini. Candi Gebang dipaksa beradaptasi menjadi ruang publik yang cair, bukan lagi sekadar monumen mati yang dibekukan waktu.
Transformasi Fungsi: Dari Pemujaan Dewa ke Pemujaan Ketenangan Jiwa
Menariknya, justru dalam keterhimpitan itulah Candi Gebang menemukan relevansi barunya. Bagi generasi muda Yogyakarta, khususnya mahasiswa di kawasan ini, Candi Gebang bukan sekadar destinasi wisata sejarah, melainkan tempat pelarian (getaway) yang murah dan dekat. Sore hari di pelataran candi seringkali diisi oleh mahasiswa yang membaca buku, fotografer yang memburu cahaya matahari terbenam, atau pekerja kantoran yang melepas penat.
Rumput hijau yang terawat rapi di sekeliling candi menjadi karpet alami yang mengundang siapa saja untuk duduk dan diam. Dalam konteks ini, Mureks mencatat bahwa Candi Gebang telah bertransformasi fungsi; dari tempat pemujaan dewa menjadi tempat pemujaan ketenangan jiwa (healing) bagi manusia modern yang lelah. Ia menawarkan kesejukan visual dan batin di tengah panasnya persaingan hidup di kota pelajar.
Strategi Pelestarian yang Bersahaja
Pengelola candi, di bawah naungan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X, tampaknya menyadari betul potensi narasi