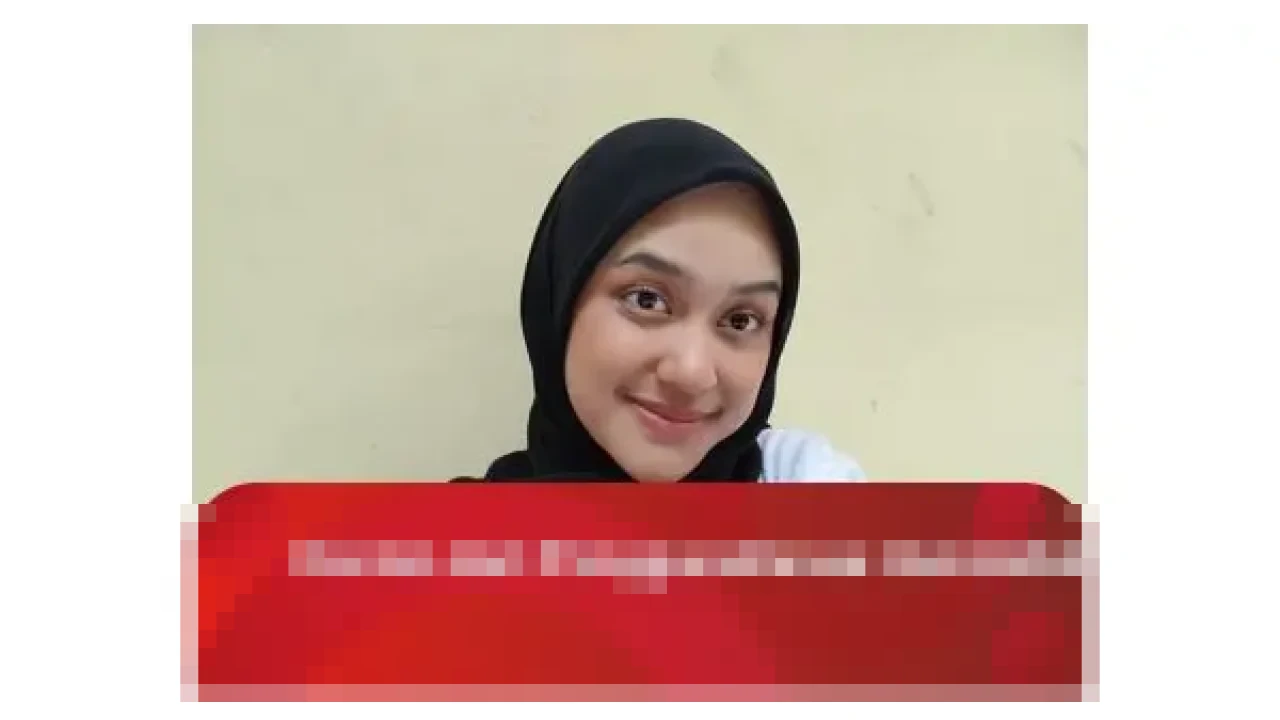Pemandangan seorang anak muda yang tetap duduk di tengah keramaian transportasi umum, sementara penumpang yang lebih tua berdiri di sekitarnya, bukan lagi hal asing. Seringkali, situasi ini berujung pada tatapan tidak nyaman, desahan pelan, bahkan teguran yang menempatkan anak muda sebagai pihak yang bersalah.
Budaya menghormati orang tua memang mengakar kuat di masyarakat Indonesia, menjadikan tindakan memberi tempat duduk sebagai bentuk empati dan kesantunan. Namun, persoalan muncul ketika penghormatan tersebut bergeser menjadi tuntutan mutlak, mengabaikan kondisi individu yang terlibat. Fenomena ini menyoroti ‘norma sunyi’ yang bekerja di ruang publik, khususnya transportasi umum.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Norma Sosial dan Asumsi Usia di Ruang Publik
Transportasi umum lebih dari sekadar sarana berpindah; ia adalah arena sosial tempat norma-norma tak tertulis beroperasi secara halus. Meskipun tidak ada aturan baku yang mewajibkan anak muda untuk berdiri, praktik ini terus direproduksi dan diperkuat oleh tekanan lingkungan. Anak muda yang memilih tetap duduk kerap merasa sungkan dan bersalah, bukan karena melanggar regulasi, melainkan karena tidak memenuhi ekspektasi sosial yang tak terucapkan.
Tuntutan untuk mengalah seringkali berlandaskan asumsi bahwa anak muda selalu memiliki kekuatan dan daya tahan lebih. Tubuh muda diasosiasikan dengan energi tak terbatas, sementara orang yang lebih tua dianggap lebih rentan dan otomatis membutuhkan tempat duduk. Namun, realitasnya tidak selalu demikian.
Anak muda juga rentan terhadap kelelahan setelah seharian bekerja, menempuh perjalanan jauh, atau bahkan memiliki masalah kesehatan yang tidak terlihat secara fisik. Sayangnya, dalam konteks transportasi umum, kondisi-kondisi ini kerap terabaikan, dengan usia menjadi satu-satunya tolok ukur.
Mengalah sejatinya adalah tindakan etis yang bernilai karena dilakukan secara sukarela, sebuah ekspresi empati yang tulus. Namun, ketika tindakan ini berubah menjadi kewajiban sosial, maknanya pun bergeser. Anak muda seringkali tidak diberi pilihan; konsekuensi dari tidak mengalah adalah penilaian negatif, dianggap tidak sopan atau kurang empati. Padahal, memilih untuk tetap duduk bisa jadi merupakan bentuk menjaga diri sendiri. Pada titik ini, empati kehilangan sifat kemanusiaannya, berubah menjadi standar perilaku yang harus dipatuhi, bukan lagi sikap saling memahami.
Empati Dua Arah: Kunci Keadilan di Transportasi Umum
Aspek yang sering luput dari diskusi adalah arah empati itu sendiri. Dalam keseharian, empati hampir selalu dituntut dari anak muda. Mereka diharapkan peka, sigap, dan siap mengalah tanpa banyak alasan. Sebaliknya, kondisi yang dialami anak muda—baik lelah, tidak enak badan, atau sekadar butuh duduk—jarang benar-benar dipertimbangkan.
Padahal, empati idealnya berjalan dua arah. Orang yang lebih tua pun dapat menunjukkan pengertian, misalnya dengan meminta tempat duduk secara baik-baik atau memahami jika seseorang belum bisa langsung berdiri. Komunikasi sederhana dan sikap saling memahami jauh lebih membantu daripada tatapan atau penilaian diam-diam yang justru menciptakan ketidaknyamanan.
Sebagai ruang publik, transportasi umum melayani beragam individu dengan latar belakang dan kebutuhan berbeda. Di dalamnya ada pekerja, pelajar, lansia, hingga penyandang disabilitas. Oleh karena itu, keadilan di ruang publik tidak dapat ditentukan hanya dari satu ukuran seperti usia. Kenyamanan seharusnya dipahami secara situasional, bukan hasil asumsi yang disamaratakan.
Beberapa transportasi umum memang telah menyediakan kursi prioritas bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Keberadaan kursi ini penting sebagai pengakuan terhadap kebutuhan khusus. Namun, fasilitas tersebut juga mengingatkan bahwa tidak semua kebutuhan dapat terlihat secara kasat mata. Interaksi antarpenumpang tetap membutuhkan kebijaksanaan. Memberikan tempat duduk akan lebih bermakna jika lahir dari kesadaran dan empati, bukan dari tekanan atau rasa takut dihakimi.
Persoalan tempat duduk di transportasi umum seharusnya mendorong kita untuk memandang sesama penumpang secara lebih holistik. Usia memang berperan, tetapi bukan satu-satunya acuan untuk menilai siapa yang lebih berhak atas kenyamanan. Kepekaan membaca situasi dan kesediaan untuk berkomunikasi menjadi kunci terciptanya keadilan di ruang publik.
Nilai menghormati yang lebih tua patut dipertahankan, namun tidak seharusnya mengabaikan keterbatasan fisik dan mental anak muda. Empati akan lebih bermakna ketika lahir dari kesadaran untuk saling memahami, bukan tuntutan sepihak. Transportasi umum sebagai ruang bersama menuntut sikap saling mengerti yang seimbang, di mana kesantunan diukur dari kesediaan setiap orang untuk bersikap adil sesuai kondisi yang dihadapi, menciptakan ruang publik yang manusiawi bagi semua penggunanya.