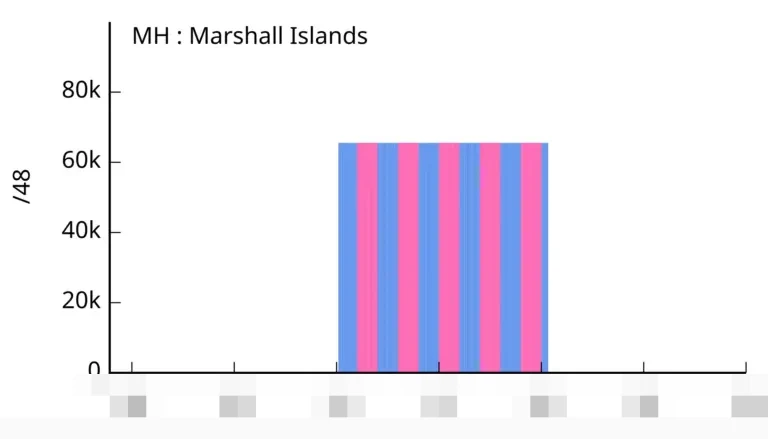Nama Venezuela kembali mencuat dalam pemberitaan global, namun bukan lagi tentang kisah rakyatnya, melainkan tentang dinamika kekuasaan dan justifikasi di baliknya. Krisis yang telah berlangsung lama di negara tersebut kini bertemu dengan narasi klasik: penertiban, penyelamatan, dan penegakan. Amerika Serikat, dengan retorika yang terkesan administratif, kembali memposisikan diri sebagai pihak yang datang untuk membantu—sebuah peran yang dalam catatan sejarah global seringkali terdengar wajar, meskipun dampaknya kerap kali jauh dari kesederhanaan.
Dalam rentang waktu yang panjang, Venezuela hari ini seolah menjadi titik kecil di mana pola kekuasaan lama kembali beroperasi. Kekuatan besar merasa perlu untuk campur tangan, dan dunia diharapkan untuk percaya pada alasan-alasan yang disodorkan.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Pola Kekuasaan: Dari Roma Kuno hingga Amerika Modern
Kekaisaran Romawi, ribuan tahun silam, memasuki wilayah-wilayah jauh dengan keyakinan yang hampir polos: dunia membutuhkan ketertiban. Jalan-jalan dibangun, hukum ditegakkan, dan jika ada penolakan, pedang menjadi solusi tanpa banyak perdebatan. Kekerasan bukan dianggap aib, melainkan prosedur yang sah. Konsep peradaban menjadi justifikasi yang memadai.
Dua milenium kemudian, Amerika Serikat datang dengan bahasa yang lebih halus. Mereka tidak membawa legiun, melainkan istilah-istilah seperti demokrasi, stabilitas, dan keamanan global. Kekerasan tidak lagi disebut kekerasan, melainkan “operasi.” Korban tidak lagi disebut manusia, melainkan “dampak.” Kata-kata kini bekerja lebih rapi daripada pedang; ia tidak meninggalkan jejak fisik yang mudah didokumentasikan.
Roma secara terbuka menyebut dirinya imperium. Sebaliknya, Amerika justru bersikeras menyatakan bahwa mereka bukan apa-apa—hanya penolong yang kebetulan memiliki kekuatan paling besar. Mureks mencatat bahwa, perbedaan dalam narasi ini menjadi kunci dalam memahami cara kerja kekuasaan modern.
Strategi Bahasa dan “Manufacturing Consent” ala Chomsky
Pemikir terkemuka Noam Chomsky pernah menulis bahwa kekuasaan modern bekerja paling efektif ketika ia menolak menyebut dirinya kekuasaan. Roma jujur dengan pedangnya, sementara Amerika lebih mengandalkan kekuatan bahasa. Bahasa yang menenangkan, mengaburkan, sekaligus mengarahkan cara berpikir publik. Dalam narasi tersebut, sanksi bukan lagi hukuman, melainkan “tekanan moral.” Serangan bukan agresi, melainkan “penegakan.”
Jika Roma membutuhkan “orang barbar” agar dirinya tampak beradab, Amerika membutuhkan “musuh” agar dirinya tampak bermoral. Musuh itu tidak harus baru; cukup diberi nama yang tepat. Istilah “negara bermasalah” atau “ancaman regional” seringkali cukup. Venezuela, seperti banyak negara lain sebelumnya, masuk ke dalam kosakata tersebut. Yang terpenting bukan siapa musuhnya, melainkan fungsi yang dimainkan oleh keberadaan musuh itu.
Chomsky menyebut fenomena ini sebagai manufacturing consent: persetujuan yang diproduksi, bukan diminta. Publik tidak perlu diyakinkan bahwa perang itu baik. Cukup diyakinkan bahwa perang itu perlu. Media massa, dalam konteks ini, turut membantu dengan memilih gambar yang “aman”—pidato, peta, pernyataan resmi—dan menyisihkan realitas yang sulit dijelaskan: kehidupan yang terhenti tanpa istilah teknis.
Akhir Sebuah Imperium: Kelelahan atau Hilangnya Kepercayaan?
Kekaisaran Romawi tidak runtuh karena satu serangan besar, melainkan karena kelelahan yang panjang. Perang yang tak kunjung usai, biaya yang tak pernah lunas, dan keyakinan yang perlahan menguap dari dalam.
Amerika Serikat mungkin tidak akan runtuh seperti Roma, tanpa ada tembok yang roboh. Namun, sebuah imperium tidak selalu berakhir dengan kehancuran fisik. Kadang, ia hanya berhenti dipercaya—oleh dunia yang terlalu sering mendengar alasan, dan oleh dirinya sendiri yang mulai sulit membedakan antara kepentingan strategis dan kebajikan moral.
Venezuela hari ini mungkin bukan Roma, dan Amerika tentu bukan seorang Kaisar. Namun, sejarah jarang mengulang peristiwa secara persis; ia lebih sering mengulang pola. Dan pola itu selalu sama: kekuasaan yang terlalu yakin bahwa ia datang untuk menolong, akhirnya lupa untuk bertanya apakah pertolongan itu pernah diminta. Sebuah imperium tidak selalu runtuh oleh perlawanan. Kadang, ia hanya ditinggalkan oleh kepercayaan. Dan sejarah, seperti biasa, mencatatnya tanpa perlu bertepuk tangan.
Referensi penulisan: m.kumparan.com