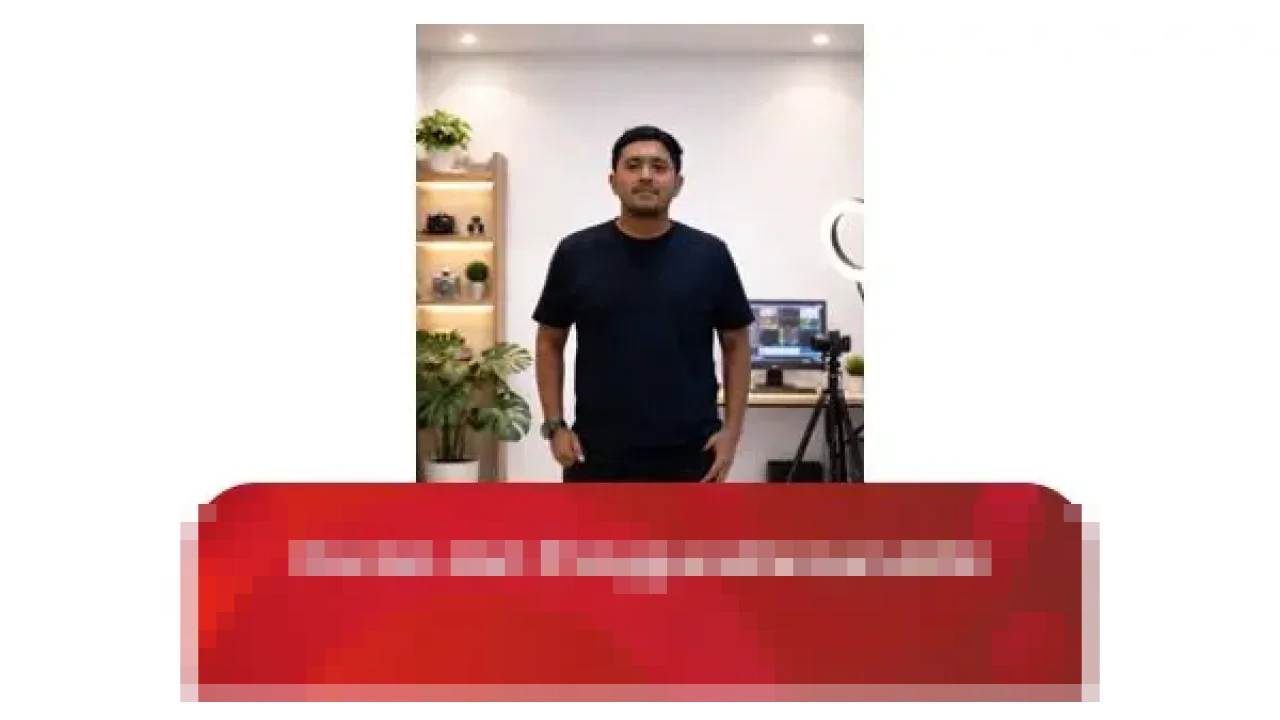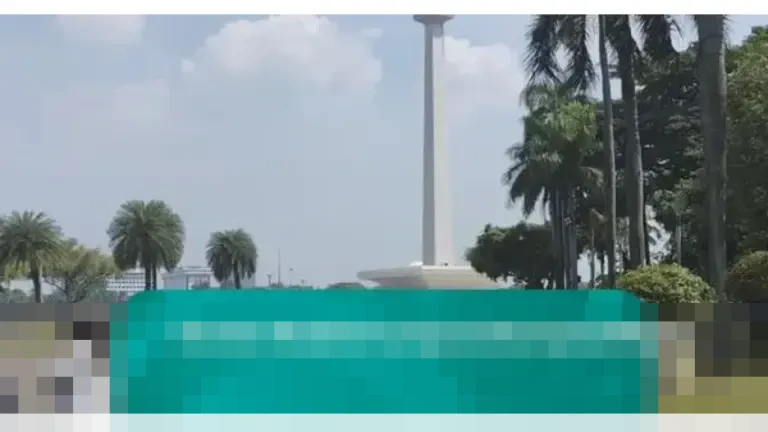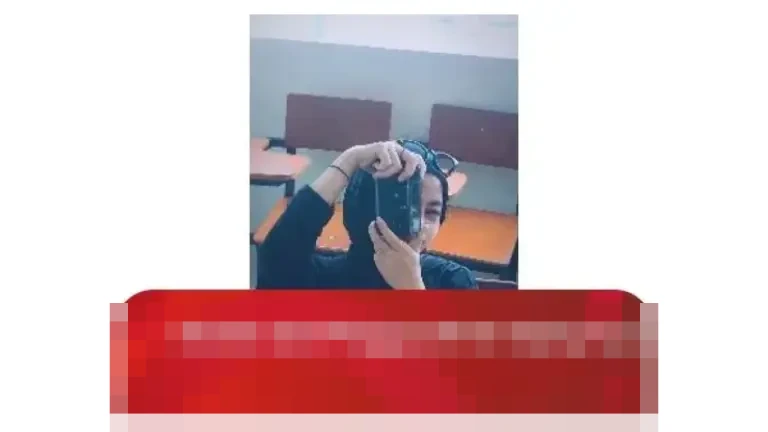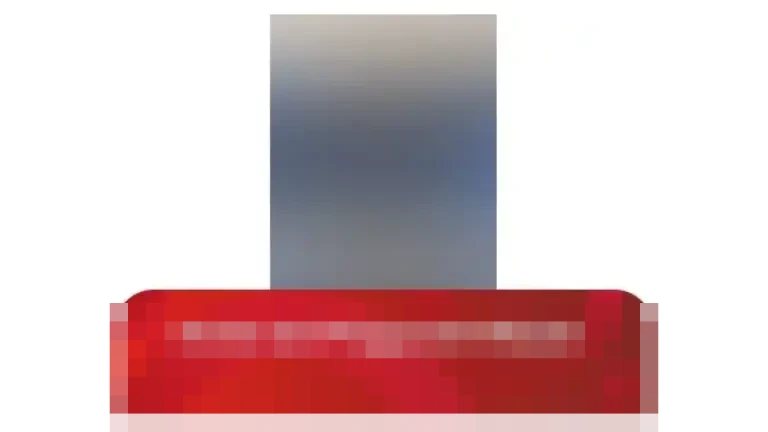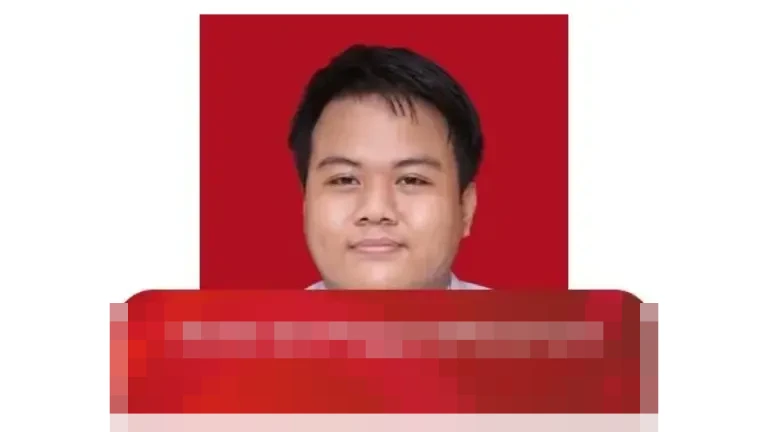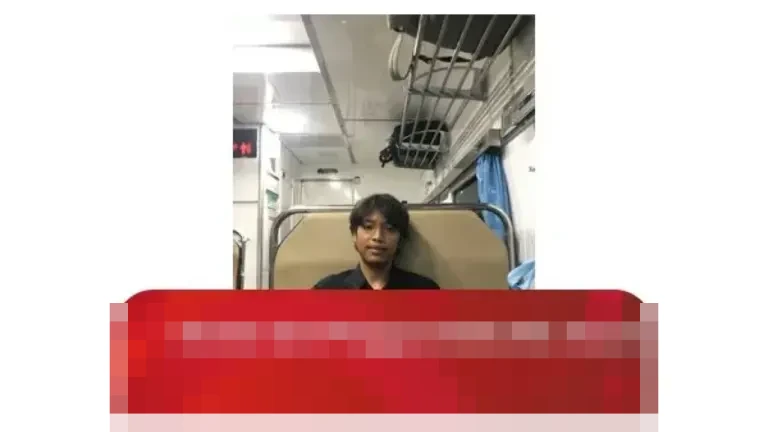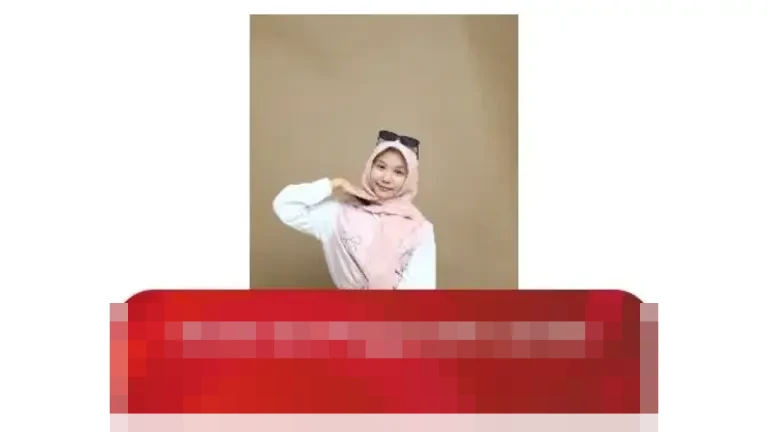Setiap 26 Desember, ingatan kolektif masyarakat Aceh kembali ‘diputar’ pada tragedi paling mematikan di abad ke-21. Tepat 21 tahun silam, gelombang tsunami dahsyat menyapu sebagian besar Serambi Mekkah, meninggalkan duka mendalam dan kisah-kisah heroik yang tak pernah usai diceritakan.
Tsunami Aceh 2004 tercatat sebagai bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah dunia modern. Amukan laut pada Minggu pagi itu telah mengumbar ketakutan, merenggut ratusan ribu nyawa, dan menenggelamkan harta benda dalam lumpur legam. Kini, yang tersisa tinggal cerita, namun roda kehidupan terus bergerak. Anak-anak yatim dan para janda syuhada telah reda dari deraan bencana, meski kegelisahan masih saja merundung hati. Semua itu tergambar dari kisah sedih dan heroik para penyintas yang tak bakal lekang dari ingatan.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Kisah Yuniar: Berjuang di Lantai Dua Rumah Tetangga
Pada Minggu, 16 Desember 2025, Yuniar, 54 tahun, ditemui di kediamannya di Jalan Bangau, Kampung Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Yuniar adalah saksi hidup keganasan tsunami Aceh. Hari itu, ia tidak berziarah ke kuburan massal, melainkan terlihat sibuk membereskan tanaman hias di pinggir rumahnya.
Rumah berlantai dua itu menjadi saksi bisu bagaimana air laut di ujung Banda Aceh pernah singgah sejauh kurang lebih enam kilometer ke darat. Bidang tanah rumahnya sedikit amblas, dinding-dindingnya mulai terkelupas dan tanpa cat. Saat tsunami, ketinggian air menutupi seng lantai bawah rumahnya, mencapai kurang lebih dua meter.
“Meski rumah saya lantai dua, tapi saat tsunami saya malah menyelamatkan diri di lantai dua rumah tetangga di depan. Kita tidak bisa berpikir saat itu. Saya, suami dan ketiga anak alhamdulillah selamat,” kenang Yuniar mengawali ceritanya.
Firasat buruk muncul sehari sebelum tsunami. Yuniar merasa ada yang janggal; suasana di sekelilingnya tampak sepi, tidak ada aktivitas. Kegelisahan itu merundung Yuniar, meskipun pada malam harinya, terdengar suara musik besar menyambut natal dan tahun baru dari gereja dekat rumahnya. Ia tetap merasa ada yang tidak beres.
Keesokan harinya, seperti Minggu pagi pada umumnya, Yuniar sebagai ibu rumah tangga disibukkan dengan pekerjaan rumah, mulai dari mencuci hingga memasak. Namun, baru saja memulai aktivitas, ia dikejutkan guncangan hebat, sebuah gempa. Yuniar sekeluarga bergegas keluar mencari perlindungan. Di jalan depan rumah, warga sudah berkumpul. Gempa sempat berhenti beberapa saat, sebelum akhirnya gempa susulan berguncang dengan kekuatan magnitudo 9,2 Skala Richter. Air laut dan gelombang besar pun naik ke daratan Aceh.
“Beberapa saat sempat tenang. Saya jemur kain tapi hati mulai tidak tenang. Kemudian ada orang teriak katanya air laut naik. Trus, ada mobil puskesmas yang masuk ke jalan di depan rumah, mengumumkan air laut naik,” cerita Yuniar.
Gelombang tsunami, kata Yuniar, setinggi tiang listrik dengan warna gelap. Tanpa pikir panjang, ia dan keluarganya mengikuti warga lain yang berlarian menuju lantai dua rumah tetangga. Tiga anak Yuniar, dua laki-laki dan satu perempuan, dirangkul sang ayah yang juga ikut naik ke lantai dua rumah tetangga, persis di depan rumahnya.
“Awalnya suami ajak keluar ke jalan utama ke Jalan Pocut Baren. Tapi saya menolak dan memilih untuk ke rumah warga. Saya gak tau gimana keadaan kami, jika saat itu mengikuti ajakan suami,” tutur Yuniar sambil mengusap air mata.
Dari lantai dua, Yuniar melihat ombak besar berwarna seperti lumpur. Air pecahan ombak berputar begitu kuat, bahkan mampu mengangkut kapal besar dari laut ke darat. Kapal itu membentang di persimpangan lorong, menahan air untuk masuk.
“Seketika air menjadi tidak sederas semula. Seandainya tidak ada kapal itu, sepertinya hancur semua rumah kami. Kapal itu membuat air pecah. Di dalam kapal ada satu orang, dia selamat,” ungkap Yuniar.
Ada satu hal yang membuat Yuniar sangat terpukul, yakni ketidakmampuannya menolong orang-orang yang saat itu membutuhkan pertolongan. “Mereka berteriak tolong-tolong, ada yang mengapung di air, ada yang di atas kasur terbawa air. Tapi saya tidak bisa menggapai tangan mereka untuk menolong,” kenang Yuniar.
Yuniar mengatakan suaminya sempat hendak turun menolong seorang bapak yang terduduk di atas kasur mengapung. Namun, niat baik itu tidak membuahkan hasil karena suaminya mengalami kesulitan saat turun. Setelah beberapa jam, air laut mulai surut. Yuniar bersama keluarga turun. Setiba di bawah, sejauh mata memandang, ia melihat mayat-mayat bergelimpangan. Langkahnya beberapa kali sempat terhenti sejenak karena menginjak mayat.
Terutama di rumahnya, banyak mayat terbujur kaku di luar dan dalam. Tanpa pakaian dan membengkak, bahkan ada yang beberapa hari tidak diambil. Anehnya, mayat itu tidak menimbulkan bau busuk sama sekali. “Mereka adalah syuhada yang mendapatkan pahala syahid,” kata Yuniar.
“Rumah di Kampung Keuramat memang tidak banyak yang hancur, akan tetapi mayat ada di mana-mana. Saat menuju arah pos kamling kampung, kami melihat mayat bapak yang tadinya minta tolong sama kami,” ungkap Yuniar sedih.
Setelah itu, Yuniar sekeluarga hidup berbulan-bulan di pengungsian kawasan Desa Siron, Aceh Besar. Di sana ia hidup berdampingan dengan para penyintas tsunami lainnya. Hari berganti hari, ketika malam datang tetap saja ketakutan menghampirinya. Selama beberapa bulan setelah tsunami, ia masih trauma.
Dian Febriansyah: Pertemuan Terakhir dengan Sahabat
Secara terpisah, Dian Febriansyah, 32 tahun, anak sulung Yuniar, menceritakan pengalamannya. Saat tsunami, Dian masih berusia sebelas tahun. Pagi Minggu sebelum tsunami, ia bersama seorang teman hendak pergi bermain bola ke Blang Padang. Keduanya menggunakan sepeda masing-masing. Namun, belum lagi setengah perjalanan, di simpang Pocut Baren (depan SD 20 Banda Aceh), terjadi gempa. Karena takut, Dian memutuskan kembali ke rumah, sementara temannya tetap melanjutkan perjalanan.
“Setelah hari itu kami tidak pernah bertemu lagi. Kalimat terakhir yang saya ingat dia bilang, ayok lek (panggilan akrab Dian) pergi terus, kita tanding hari ini. Aku tunggu di sana ya,” ucap Dian menirukan temannya. Pertemuan itu adalah pertemuan terakhir bagi Dian dengan teman akrabnya. Sejak saat itu, Dian tak pernah dapat kabar lagi tentang keberadaan temannya dan keluarga. Dian menduga temannya itu dibawa gelombang tsunami.
Cerita Zaharuddin: Kehilangan Kakak Tanpa Jejak
Pada hari yang sama, Zaharuddin, 60 tahun, warga Gampong Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, ditemui saat sedang berziarah di kuburan massal Ulee Lheue. Gampong Prada merupakan salah satu desa di Banda Aceh yang tidak parah saat tsunami, sehingga ia dan keluarga selamat.
Namun, kata Zahar, Tsunami Aceh 2004 menyisakan kabar kehilangan paling pahit baginya. Sekeluarga kakak kandungnya hanyut dibawa tsunami. Padahal, sehari sebelum tsunami, Zahar sempat singgah ke rumah kakaknya di Lampaseh Kota. Tidak ada yang janggal dari pertemuan itu, mereka bercerita layaknya biasa. Ia tidak menyangka pertemuan itu menjadi pertemuan terakhir dengan kakaknya.
“Sabtu saya sempat ke rumah ngomong-ngomong cerita sama dia. Besoknya sudah tidak bertemu lagi. Itulah momen terakhir yang saya ingat,” ucap Zahar.
Zahar mengatakan jenazah sekeluarga kakaknya hilang tanpa jejak, kecuali anaknya yang paling kecil perempuan, saat itu tersangkut di tangga. “Mereka tidak ada yang tertinggal, semua meninggal karena tsunami,” ungkap Zahar.
Meskipun tidak tahu di mana keluarga kakaknya itu dikubur, setiap tahun Zahar secara acak pergi ke kuburan massal Ulee Lheue dan Siron. “Yang terpenting mengirim do’a untuk mereka. Selain waktu salat, saya juga mengirim doa setiap 26 Desember. Itu rutin saya lakukan,” tutur Zahar.
Zahar mengaku sudah ikhlas. “Karena dia tinggal di Lampaseh, saya yakin dia dimakamkan di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan di tempat lain,” ujar Zahar sembari menyeka air matanya.
Kisah Ernawati: Bertahun-tahun Mencari Ibu
Berbeda dengan cerita Yuniar dan Zaharuddin, Ernawati, 54 tahun, bukan penyintas, bukan juga warga Kota Banda Aceh. Ernawati adalah warga Bireuen yang kehilangan ibunya saat tsunami 2004. Beberapa tahun sebelum tsunami, ia dan ibunya memang tinggal berjauhan. Biasanya setiap Lebaran, jika bukan ibunya yang pulang ke Bireuen, Erna yang menyusul ke Banda Aceh.
Erna mengatakan ibunya berjualan di Pasar Aceh. Karena merasa usia sang ibu sudah tua, ia sempat meminta ibunya untuk kembali dan tinggal bersamanya di Bireuen. Namun, ibunya selalu menolak, karena lebih senang berjualan di ibu kota provinsi.
“Terakhir Ibu pulang ke Bireuen saat lebaran bulan November 2004,” kata Erna.
Kepulangan tahun itu, kata Erna, berbeda dengan sebelumnya. Ketika hendak balik ke Banda Aceh, ibu meminta maaf ke semua orang di sekitar yang dikenal dan meminta dibuatkan kue khas Aceh ‘boh rom-rom’. “Ibu juga minta baju saya yang warna merah. Tapi baju tidak saya kasih karena saat itu saya berencana akan menjahit lain untuk Ibu. Bahkan ukuran badan ibu sudah saya ukur,” ungkap Erna. Isyarat itulah yang membuat Erna sangat terpukul.
Benar saja, kepulangan hari itu adalah kepulangan terakhir sang ibu. Ia mendapat kabar mengejutkan dari tetangga. “Banda Aceh sudah tidak ada,” kata salah seorang tetangga yang baru sampai di Bireuen dan selamat dari tsunami.
Mendapat kabar itu, Erna langsung bersiap untuk berangkat ke Banda Aceh. Namun, langkahnya sempat terhalang setelah mendapatkan informasi bahwa akses dari Bireuen ke Banda Aceh tidak bisa. Ia tidak menghiraukan itu, tetap melanjutkan perjalanannya, sampai akhirnya tiba di Banda Aceh.
“Bukan Banda Aceh yang saya pergi sebelumnya, semua menjadi rata. Hari itu saya langsung cari Ibu. Tapi setelah berhari-hari saya cari, gak dapat. Hingga, pihak keamanan berjaga di situ tidak di kasih lagi untuk cari,” ujar Erna.
Beberapa bulan setelah itu, Erna masih mencari. Namun, jangankan menemui jenazah ibunya, orang yang kenal dengan ibunya saja tidak ia temui, sehingga menyulitkannya. Baru setelah 16 tahun berlalu, pada tahun 2020, ia bertemu seseorang yang pernah tinggal di kompleks yang sama dengan ibunya.
“Saat tsunami, kata dia, mamak saya terkurung di kamar mandi, kesulitan untuk keluar,” cetus Erna. Sejak saat itu, ia merasa menemukan titik terang dari apa yang dia cari selama ini. Pencariannya bertahun-tahun bukan pada jenazah sang ibu, melainkan di mana posisi sang ibu saat tsunami.
Inilah setetes kisah dari lautan cerita tragedi tsunami Aceh yang bisa dinukil sepanjang masa. Bagi mereka yang syahid, bencana itu adalah pintu masuk kehidupan yang sesungguhnya; akhirat. Sebaliknya, bagi mereka yang berjuang dan selamat, juga bagi kita yang masih hidup di semesta alam ini, tsunami Aceh adalah jalan pembuka menuju pintu taubat. Karena kebenaran tentang datangnya kematian itu adalah pasti meski perkara menuju ke sana tak pernah serupa; gaib.