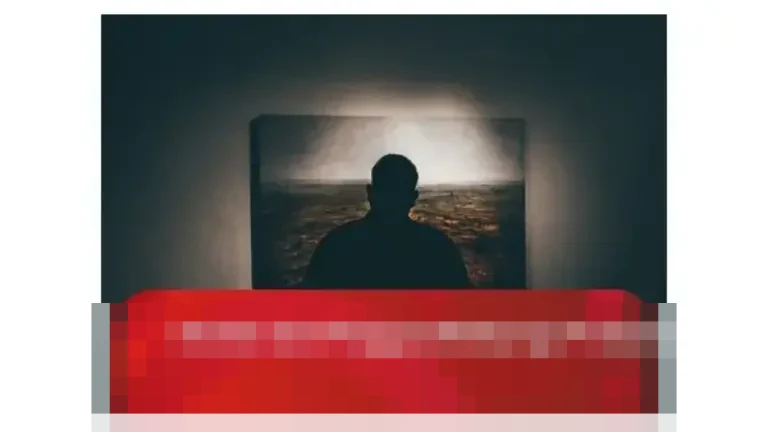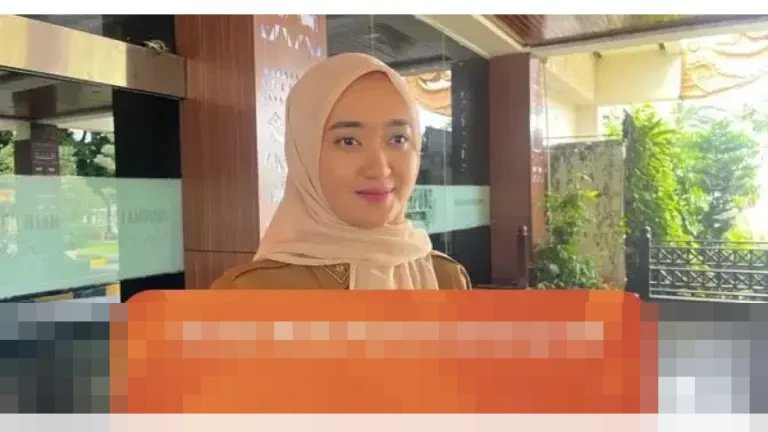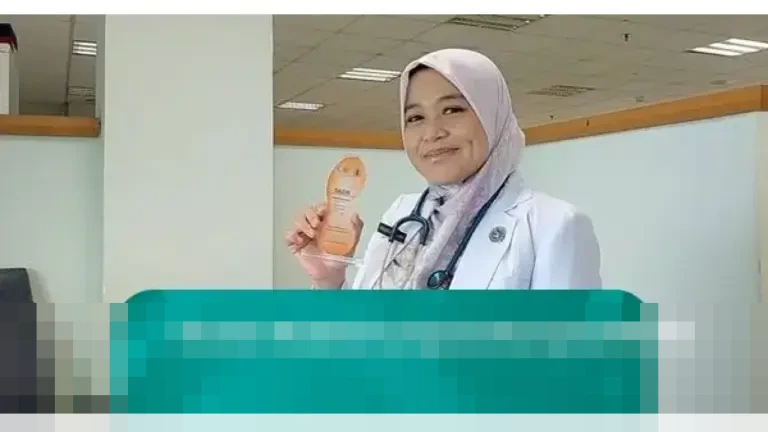Liburan Natal di Palangka Raya pada penghujung 2011 bukan sekadar perayaan bagi Fahruddin Fitriya, melainkan sebuah ‘sidang ajudikasi’ tanpa palu hakim. Situasi reflektif itu berlanjut hingga malam terakhir, sebelum ia kembali ke daerah penugasan di Buntok, Kabupaten Barito Selatan.
Saat kabut tipis mulai turun memeluk aspal, Fahruddin merapat ke kediaman mendiang Bos Top (Topan Nanyan) sekitar pukul 20.30 WIB. Ia sengaja datang lebih awal, mengantisipasi ‘dosis’ ilmu yang biasanya lebih pekat jika hari belum terlalu larut.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Di teras, Bos Top telah menanti dengan penampilan santai, namun tatapannya seolah mampu memindai isi pikiran siapa pun di depannya. Di meja, toples kue nastar sudah berganti posisi dengan kopi hitam yang kekentalannya mampu membuat sendok berdiri.
“Duduk, Fit. Besok kamu balik ke Buntok? Barito Selatan itu rimba bagi jurnalis manja. Kamu harus punya ‘senjata’ sebelum kembali lagi ke sana,” ucap Bos Top tanpa basa-basi. Fahruddin duduk tegak, mirip tersangka yang siap memberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pikirannya masih tertinggal pada debat semalam tentang konspirasi Elite Global hingga analisis takzim soal pencurian celana kolor warga yang dibahas Bos Top setara dengan membedah pasal makar.
Namun malam itu, Bos Top mematikan mode santai. Ia ingin bicara soal sanad keilmuan yang diperoleh langsung dari ‘Sang Imam Besar’ jurnalisme naratif, Dahlan Iskan.
Jurnalisme Bukan Sekadar Kartu Identitas
“Fit, jadi wartawan itu jangan cuma pamer kartu id card. Itu namanya delusi kompetensi,” ujarnya sambil menyulut rokok. Suaranya berat, mengandung vibrasi otoritas yang tak bisa dibantah. “Kamu harus keras pada diri sendiri. Jangan jadi jurnalis pemalas yang cuma memoles rilis humas. Eksekusi kata-katamu dengan bengis sebelum orang lain membacanya,” lanjutnya di balik kepulan asap rokok.
Bos Top kemudian menarik napas panjang, menatap jauh ke arah gelapnya jalanan. Di sinilah Fahruddin menyadari, Palangka Raya bukan lagi sekadar tempat singgah untuk mencari nafkah, melainkan rahim baru yang melahirkan sisi dewasanya.
Bersamaan dengan asap yang membumbung, Bos Top menanamkan prinsip jurnalisme mutakhir yang melampaui zamannya. Rahasia ini, menurut Fahruddin, tidak pernah dicicipi oleh mereka yang sudah berpuluh tahun di bawah asuhannya. Nubuat yang diucapkan empat belas tahun lalu itu kini telah menemukan bentuk aslinya.
“Zaman akan berubah, Fit. Nanti semua orang bisa nulis lewat HP. Tapi ingat doktrin dari Pak Dahlan, jangan jadi wartawan yang cuma mengejar speed tapi kehilangan substansi. Tulisanmu harus cair, mengalir seperti air sungai Barito, tapi kuat secara narasi. Kalau tulisanmu kaku kayak teks proklamasi, jangan harap ada orang mau baca!”
Di telinga Fahruddin, wejangan ini terasa seperti Lex Specialis, hukum khusus yang mengesampingkan segala aturan umum yang membosankan.
Integritas dan Investasi Moral
“Dan satu hal paling krusial,” suara Bos Top merendah, “Jaga integritasmu. Sekali kamu jual pena-mu buat kepentingan politik, itu sama saja kamu sudah melakukan penggelapan kepercayaan publik. Kamu itu wartawan, bukan alat peraga kampanye!”
Bos Top kemudian tertawa kecil, tawa yang terdengar agak sarkas namun hangat. “Mumpung kamu masih muda, habisi jatah salahmu sekarang. Jangan takut dicaci karena tulisan yang kritis. Lebih baik babak belur karena kejujuran di masa muda daripada jadi penjilat yang aman di masa tua. Itu investasi moral, Fit!”
Menjelang tengah malam, ia memberikan resep teknis yang hingga kini menjadi kitab suci Fahruddin, soal Lead dan Penutup.
“Fit, dalam menulis, pembukaan (lead) adalah pintu masuk. Kalau pintunya karatan, orang malas masuk. Tapi penutup… penutup adalah kesan terakhir. Kalau penutupmu hambar, tulisanmu cuma jadi sampah visual. Itu Ibarat pasangan yang kabur pas sayang-sayangnya,” tuturnya. “Tugasmu,” lanjutnya, “membuat pembaca merenung, tertawa, atau minimal mengumpat saking berkesannya tulisanmu”.
Malam itu, Fahruddin merasa seperti baru saja mendapatkan grasi intelektual. Genggaman tangan Bos Top saat ia pamit terasa begitu tegas. Ia kembali membelah sunyi malam di Jantung Kalimantan Tengah. Kepalanya terasa jauh lebih berat oleh ilmu, dan hati terasa lebih penuh karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar di tanah Dayak ini.
Peristiwa itu terjadi pada penghujung 2011, sebuah masa yang kini terasa purba namun abadi dalam ingatan. Meski percakapan di teras rumah itu sudah berlalu 14 tahun silam, ruhnya masih terasa sangat relevan hingga hari ini, tepat pada 30 Desember 2025.
Palangka Raya telah memberikan segalanya, dari drama absurd ‘ayam bersyahadat’, misteri klenik kolor hilang, hingga doktrin jurnalisme yang menuntut integritas mutlak. Fajar berikutnya, Fahruddin meluncur ke Barito Selatan bukan lagi sebagai jurnalis ‘casing’. Ia datang sebagai petarung kata-kata yang siap ‘salah’, dengan hati yang telah bulat bersyahadat pada kebenaran.