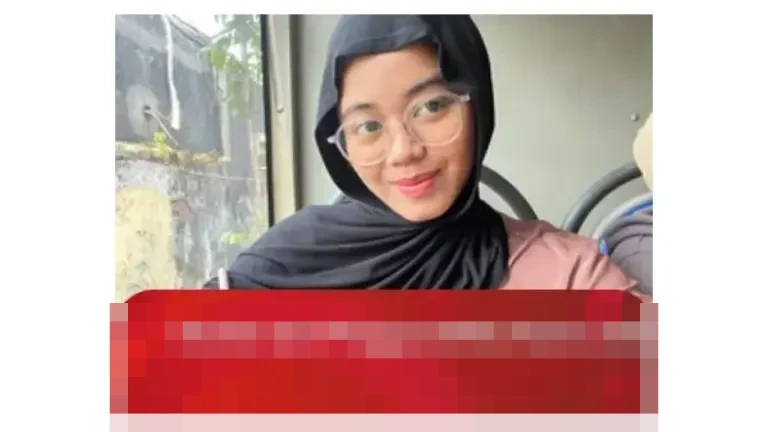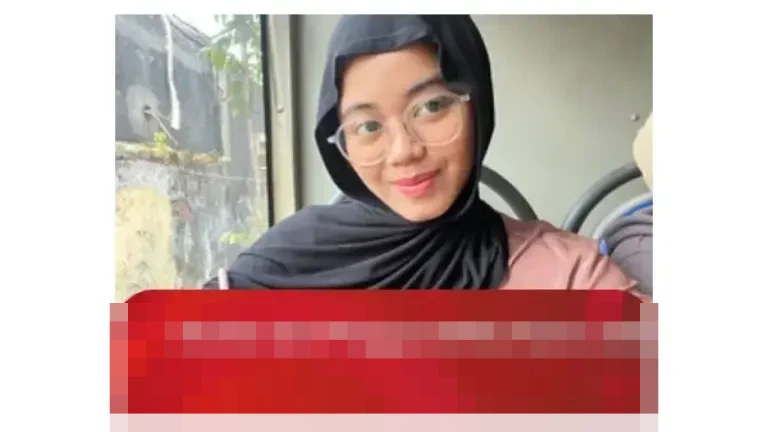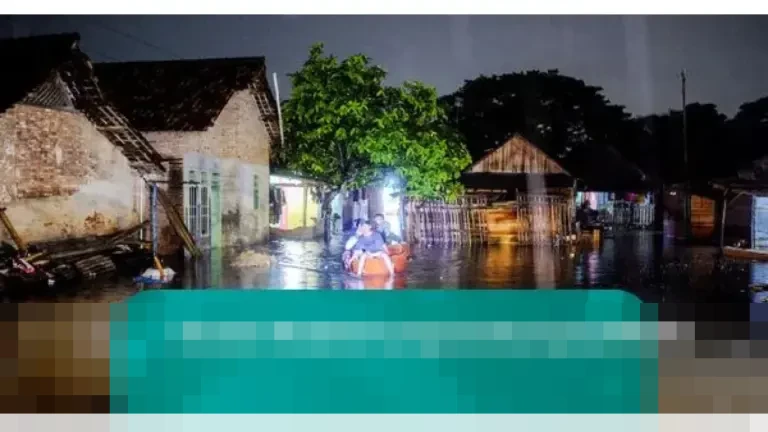Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah partai politik besar dilaporkan mulai membuka ruang diskusi untuk meninjau ulang mekanisme Pilkada langsung yang telah diterapkan sejak tahun 2005.
Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari tingginya biaya politik, potensi konflik horizontal, hingga maraknya praktik politik uang di tingkat akar rumput. Namun, di balik argumen-argumen tersebut, muncul pertanyaan fundamental: apakah demokrasi elektoral yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir memang harus dikembalikan ke tangan elite politik?
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Anggi Anggraeni Kusumoningtyas, seorang akademisi dari Universitas Pamulang sekaligus Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik UI, menilai wacana ini menimbulkan dilema politik serius. Ia tidak hanya mengundang perdebatan teknis pemilihan, tetapi juga menyentuh hakikat kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi modern.
Kedaulatan Rakyat yang Berjarak
Menurut teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau, kekuasaan yang sah hanya dapat lahir dari kehendak umum (general will) rakyat. Dalam konteks ini, pemilihan langsung merupakan manifestasi paling konkret dari prinsip tersebut, menempatkan rakyat sebagai subjek utama, bukan sekadar penonton, dalam menentukan pemimpin mereka.
Jika sistem Pilkada dikembalikan ke DPRD, proses politik berpotensi bergeser kembali dari partisipasi rakyat ke ruang tertutup elite. Hubungan antara warga dan pemimpinnya akan menjadi tidak langsung, bahkan berjarak. Ini dikhawatirkan akan mengikis wajah partisipatif demokrasi, menggantinya dengan model perwakilan yang lebih elitis dan rentan terhadap praktik patrimonial.
Legitimasi Kekuasaan: Dari Mandat Rakyat ke Negosiasi Elite
Dalam pandangan Max Weber, legitimasi kekuasaan bersumber dari rasionalitas prosedural dan kepercayaan publik terhadap sistem. Pemimpin yang terpilih secara langsung memperoleh legitimasi karismatik-elektoral, yakni dukungan moral yang lahir dari proses partisipatif rakyat.
Ketika legitimasi ini dipindahkan ke tangan lembaga perwakilan yang rentan terhadap kompromi politik, kekuasaan dapat berubah dari weberian authority menjadi patronage authority, dari mandat rakyat menjadi hasil negosiasi antar-elite. Mureks mencatat bahwa pergeseran ini berpotensi melemahkan akuntabilitas pemimpin terhadap konstituen.
Efisiensi atau Dominasi Elite?
Para pendukung wacana Pilkada melalui DPRD seringkali berargumen bahwa pemilihan langsung terlalu mahal dan memicu konflik sosial. Namun, menurut Anggi, alasan ini, meskipun tampak rasional, sesungguhnya mengandung logika berbahaya: mengorbankan partisipasi demi efisiensi.
Demokrasi memang bukan sistem yang murah. Akan tetapi, biaya politik yang tinggi seharusnya tidak menjadi pembenaran untuk menghapus partisipasi rakyat. Akar masalahnya, lanjut Anggi, bukan terletak pada bentuk pemilihan itu sendiri, melainkan pada tata kelola partai, pendanaan politik, serta lemahnya penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Mengubah sistem tanpa membenahi persoalan mendasar hanya akan memindahkan sumber korupsi dari ranah publik ke parlemen.
Dalam teori elite politik Vilfredo Pareto, setiap sistem kekuasaan memiliki “peredaran elite” (circulation of elites). Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, sirkulasi elite dikhawatirkan akan semakin tertutup, di mana pihak yang berkuasa akan cenderung memilih sesamanya. Demokrasi, pada titik ini, berhenti menjadi arena kompetisi ide dan bergeser menjadi permainan kuota kekuasaan.
Representasi Politik yang Pincang
Robert Dahl, melalui konsep polyarchy-nya, menekankan dua unsur utama demokrasi: partisipasi luas dan kompetisi terbuka. Pilkada langsung dinilai memenuhi kedua unsur ini, memberikan ruang bagi warga untuk menentukan pilihan serta membuka kesempatan bagi siapa pun untuk berkompetisi.
Sebaliknya, pemilihan melalui DPRD berpotensi mengurangi kedua aspek tersebut secara bersamaan. Warga akan kehilangan hak pilih langsungnya, sementara kompetisi calon kepala daerah hanya akan berlangsung di lingkaran elite politik. Pada titik ini, representasi dapat berubah menjadi kooptasi, di mana rakyat tidak lagi diwakili secara substantif, melainkan diatur atas nama efisiensi.
Kekuasaan yang lahir dari sistem tertutup semacam itu berisiko mengalami defisit legitimasi. Pemerintah daerah mungkin akan stabil secara administratif, tetapi rapuh secara moral. Ketika rakyat merasa tidak lagi memiliki suara, jarak antara pemerintah dan masyarakat akan melebar, membuka peluang bagi apatisme dan erosi kepercayaan publik.
Menata Ulang Demokrasi, Bukan Memundurkannya
Tidak dapat dimungkiri bahwa Pilkada langsung memiliki sejumlah kelemahan, seperti biaya tinggi, praktik politik uang, hingga polarisasi akibat politik identitas. Namun, solusi yang tepat bukanlah dengan mundur ke masa lalu, melainkan memperbaiki mekanisme partisipasi agar menjadi lebih sehat dan berkualitas.
Negara dapat memperkuat pendanaan partai politik secara transparan, memperbaiki regulasi kampanye, serta membangun sistem pendidikan politik yang berkelanjutan bagi warga. Pengawasan publik juga perlu diperluas dengan memperkuat lembaga-lembaga independen di tingkat daerah. Demokrasi, menurut Anggi, bukanlah sesuatu yang harus disederhanakan, melainkan disempurnakan melalui proses pembelajaran politik yang berkelanjutan.
Jean-Jacques Rousseau pernah mengingatkan, “Begitu rakyat berhenti memilih, maka ia berhenti menjadi rakyat.” Pernyataan ini menegaskan bahwa demokrasi akan kehilangan maknanya jika rakyat hanya diberi hak untuk disapa saat pemilu, tetapi tidak diikutsertakan secara substansial dalam menentukan arah kekuasaan.
Usulan Pilkada via DPRD, meskipun tampak pragmatis, berisiko besar menimbulkan kemunduran demokrasi. Sistem ini mungkin efisien secara biaya, namun mahal secara politik: menggerus legitimasi rakyat dan berpotensi menghidupkan kembali oligarki yang sempat dipangkas oleh gelombang reformasi.
Demokrasi tidak dapat diukur hanya dari seberapa murah biayanya, melainkan dari seberapa besar kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan yang dihasilkan. Jika partisipasi rakyat dikorbankan atas nama efisiensi, maka yang tersisa bukanlah demokrasi sejati, melainkan sekadar administrasi kekuasaan tanpa jiwa.