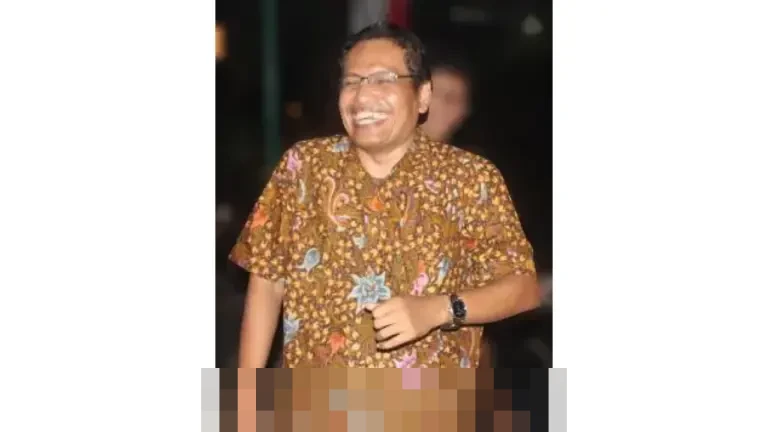Peristiwa yang melanda Venezuela pada awal tahun 2026, meski secara geografis jauh dari Indonesia, membawa implikasi politik internasional yang mendalam bagi ASEAN, Indonesia, dan negara-negara berkembang yang tergabung dalam Global South. Operasi militer Amerika Serikat di Caracas, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya, serta pernyataan Washington untuk “mengelola” Venezuela hingga transisi politik, bukanlah sekadar drama geopolitik Amerika Latin. Ini adalah sinyal keras tentang perubahan drastis arah dunia yang sangat relevan bagi kawasan kita.
Kasus Venezuela kembali menyoroti kenyataan pahit dalam hubungan internasional: hukum internasional semakin diterapkan secara selektif. Ia tidak lagi menjadi norma universal yang melindungi semua negara, melainkan instrumen yang dapat ditafsirkan dan ditegakkan sesuai kepentingan kekuatan besar. Bagi negara-negara Global South, termasuk Indonesia, ini bukan hanya isu moral, melainkan persoalan eksistensial yang mengancam jaminan keberadaan mereka dalam sistem internasional saat ini.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Dalam beberapa tahun terakhir, inkonsistensi penerapan hukum internasional semakin mencolok. Invasi Rusia ke Ukraina dikecam luas sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional, memicu sanksi ekonomi besar-besaran dan tekanan diplomatik. Namun, pada saat yang sama, pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun, disertai berbagai kejahatan kemanusiaan, terus dinormalisasi. Resolusi PBB diabaikan, korban sipil dianggap “kerusakan sampingan”, dan hukum internasional direduksi menjadi retorika semata.
Kini, kasus Venezuela menambah babak baru dalam sejarah politik internasional. Amerika Serikat membenarkan intervensinya dengan alasan penegakan hukum domestik, keamanan, dan perang melawan narkotika. Penangkapan kepala negara asing ini dilakukan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, disertai klaim sepihak atas legitimasi tindakan tersebut, bahkan di tengah kecaman luas dari publik domestik Amerika Serikat sendiri. Dari Ukraina, Palestina, hingga Venezuela, pola “tebang pilih” terlihat jelas: hukum internasional ditegakkan keras ketika sejalan dengan kepentingan geopolitik tertentu, dan dikesampingkan ketika dianggap menghambat.
Preseden Berbahaya bagi Kedaulatan
Berbeda dari sanksi ekonomi atau tekanan diplomatik, kasus Venezuela menciptakan preseden yang jauh lebih berbahaya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, seorang kepala negara asing ditangkap melalui operasi militer lintas batas, dengan pembenaran hukum sepihak. Preseden ini berpotensi mengubah pemahaman negara-negara dan masyarakat internasional tentang konsep kedaulatan. Selama ini, kedaulatan dipahami sebagai kewenangan mutlak suatu negara untuk mengurus urusan internal tanpa intervensi pihak lain.
Apabila dakwaan pengadilan domestik suatu negara, seperti Amerika Serikat, dapat dijadikan dasar untuk menangkap pemimpin negara lain, maka kedaulatan tidak lagi bersifat mutlak, melainkan kondisional. Ini berarti kedaulatan bergantung pada relasi kekuatan, di mana negara adidaya dapat memaksakan kebijakannya, bahkan secara militer, kepada negara lain. Praktik semacam ini jelas dapat mengikis, bahkan menghilangkan, konsep kedaulatan itu sendiri.
Lantas, apa sebenarnya dampak bagi negara Global South, termasuk Indonesia? Apakah keberadaan negara-negara ini benar-benar aman? Mureks mencatat bahwa negara Global South sangat rentan terhadap isu-isu yang sering dijadikan justifikasi intervensi oleh negara berkekuatan besar. Permasalahan seperti penegakan demokrasi yang belum optimal, kasus hak asasi manusia yang belum terselesaikan, hingga isu narkotika, bisa menjadi pintu masuk intervensi. Dalam konteks Venezuela, ini bukan lagi soal Maduro atau ideologi, melainkan normalisasi praktik di mana kekuatan besar dapat bertindak sebagai hakim, jaksa, dan eksekutor sekaligus dalam sistem internasional, tanpa mengindahkan hukum dan norma hubungan internasional.
Implikasi Nyata bagi ASEAN dan Indonesia
Bagi ASEAN, perkembangan ini bukan sekadar diskusi akademik. Asia Tenggara dibangun di atas pengalaman pahit kolonialisme dan intervensi asing. Oleh karena itu, prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan menjadi fondasi utama ASEAN. Namun, kasus Venezuela menjadi pengingat bahwa dunia hari ini tidak pernah ramah terhadap prinsip tersebut. Netralitas tidak lagi dihormati, melainkan dicurigai. Negara-negara yang mencoba menjaga jarak dari rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, misalnya, justru ditekan dari berbagai sisi untuk menunjukkan keberpihakan.
Jika kasus Venezuela dan presedennya diterima sebagai “normal baru”, maka ASEAN berisiko berada dalam posisi rentan. Prinsip non-intervensi bisa dianggap usang, sementara tekanan eksternal atas nama stabilitas, demokrasi, atau keamanan regional semakin kuat. Dalam skenario terburuk, Asia Tenggara bisa kembali diperlakukan sebagai arena kontestasi kekuatan besar, bukan sebagai subjek yang berdaulat. Kasus Venezuela memperlihatkan kontradiksi besar dalam tatanan global: prinsip yang sama ditegakkan keras di satu tempat, tetapi diabaikan di tempat lain.
Dalam situasi seperti ini, politik luar negeri bebas aktif Indonesia menghadapi tantangan serius. Apa arti bebas aktif jika hukum internasional hanya berlaku bagi negara tertentu? Apa makna sikap normatif jika norma itu sendiri diterapkan secara selektif oleh kekuatan besar? Jawabannya tentu tidak sederhana. Namun, satu hal yang pasti: Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan posisi moral secara individu. Tanpa dukungan kolektif dari Global South, suara Indonesia mudah tenggelam dalam hiruk-pikuk politik kekuasaan global. Artinya, Indonesia harus mampu kembali menjadi pelopor pemersatu negara-negara Global South, sebagaimana pernah dilakukan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika dengan Deklarasi Bandung-nya dan Gerakan Non-Blok.
Palestina, Ukraina, dan Venezuela tidak bisa diperlakukan sebagai isu yang terpisah. Khususnya bagi negara Global South, ketiganya adalah satu rangkaian pelajaran tentang bagaimana hukum internasional bekerja atau malah gagal bekerja dalam praktiknya. Di Palestina, hukum internasional mandek. Di Ukraina, ia bergerak cepat. Di Venezuela, ia dilewati. Perbedaan ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari ketimpangan kekuatan global. Bagi negara-negara berkembang, pengalaman ini seharusnya memicu kesadaran kolektif: ketergantungan pada “niat baik” dari negara kekuatan besar adalah strategi yang rapuh. Tanpa solidaritas dan posisi bersama, Global South akan terus menjadi objek, bukan subjek, dalam tatanan dunia.
Menyerukan persatuan Global South bukan berarti bersikap anti-Barat atau memusuhi negara tertentu. Ini adalah seruan untuk konsistensi dan universalisme hukum internasional. Prinsip yang sama harus berlaku di Gaza, Kyiv, maupun Caracas. ASEAN memiliki peran penting dalam upaya ini. Sebagai kawasan yang relatif stabil dan berpengaruh, ASEAN bisa menjadi contoh bahwa negara-negara berkembang mampu bersuara satu arah dalam menolak intervensi sepihak dan standar ganda.
Indonesia, dengan sejarah KTT Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok, sudah memiliki modal diplomatik untuk mendorong koalisi Global South yang lebih tegas. Konsistensi sikap, dan bukan hanya retorika politik sesaat, adalah kunci. Dunia sedang bergerak menuju tatanan baru yang semakin menyerupai politik imperium abad ke-19: zona pengaruh, tekanan koersif, dan hukum yang tunduk pada kekuatan. Dalam tatanan seperti ini, negara-negara Global South dihadapkan pada pilihan yang tidak nyaman, tetapi harus diakui sebagai keadaan yang tidak terelakkan.
Negara Global South bisa saja memilih diam dan berharap tidak menjadi target berikutnya. Atau mereka bisa bersatu, memperjuangkan kembali hukum internasional sebagai norma universal, bukan alat selektif. Kasus Venezuela adalah peringatan keras bahwa dunia sedang berubah lebih cepat dari yang bisa kita duga. Jika hukum internasional hanya hidup ketika negara kuat mengizinkannya, maka diam bukanlah bentuk netralitas. Diam adalah bentuk persetujuan terhadap pelanggaran hukum. Dan bagi Global South, persetujuan semacam itu sangat berbahaya, berisiko tinggi, dan terlalu mahal untuk dibayar.