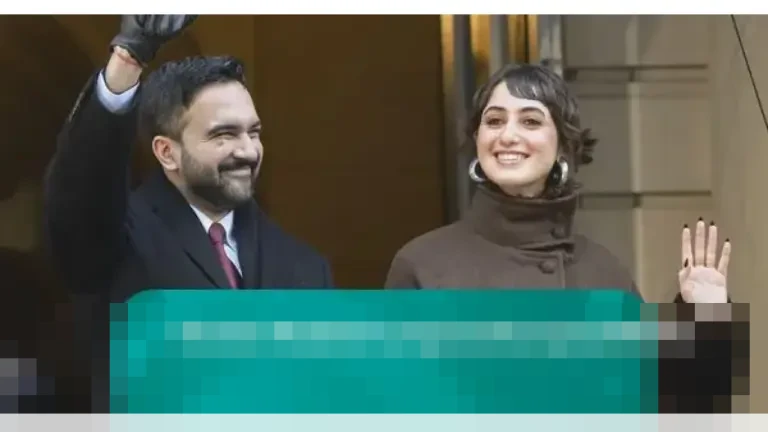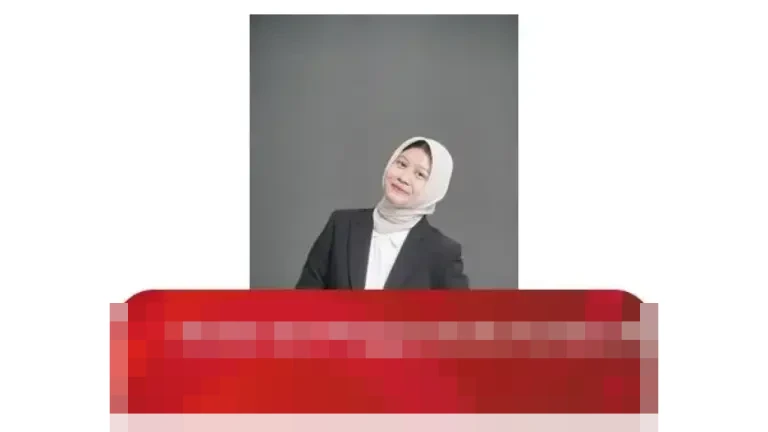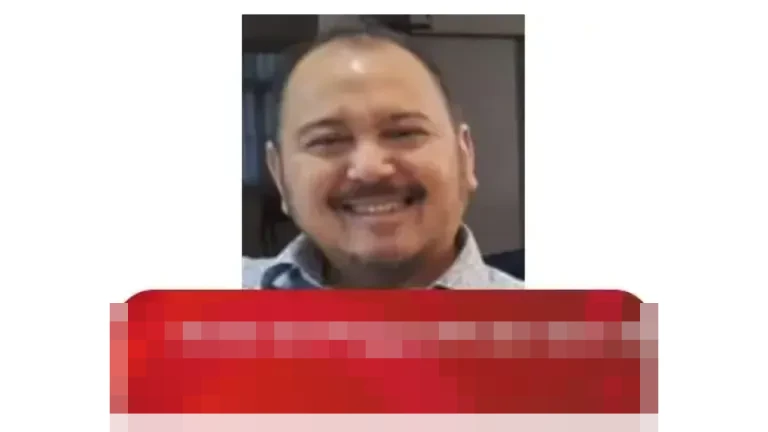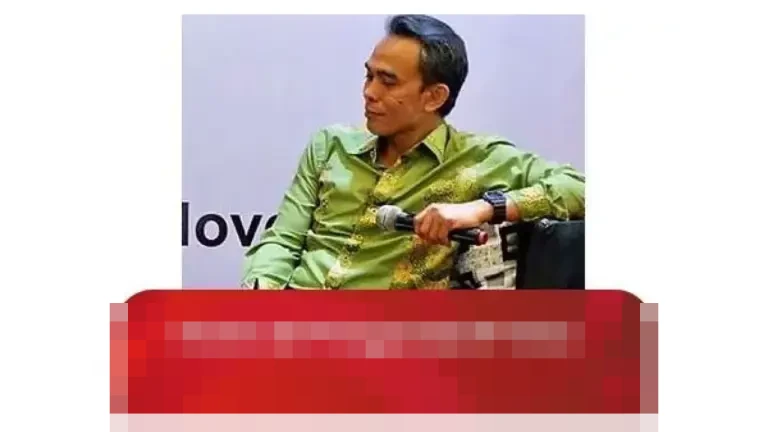Tahun baru 2026 diawali dengan suasana keprihatinan mendalam di berbagai wilayah Indonesia. Alih-alih kemeriahan, duka dan tangisan masih menyelimuti sebagian besar rakyat, terutama di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta beberapa daerah di Pulau Jawa, akibat serangkaian bencana.
Musibah yang tak terelakkan ini, menurut pandangan Mara Ongku Hsb, seorang Dosen Studi Islam di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan sunatullah yang menuntut kesabaran dan upaya bangkit. Peran seluruh komponen masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu korban bencana, mengingat hampir 1.000 orang diperkirakan meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Tantangan besar ke depan adalah bagaimana merawat ekosistem secara lebih baik demi keberlangsungan hidup manusia. Kerusakan alam, termasuk banjir, tidak lain merupakan ulah tangan manusia sendiri, bahkan seringkali disengaja demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Proses pemulihan pascabencana membutuhkan waktu yang sangat panjang. Banyak korban masih terombang-ambing tanpa kejelasan tempat tinggal. Beberapa laporan dari media nasional menyebutkan, pascabanjir, sebagian korban meninggal bukan karena langsung terdampak banjir, melainkan akibat kekurangan makanan dan gizi yang memadai. Bahkan, seorang ibu hamil dilaporkan kehilangan janinnya karena gizi buruk, sementara anak-anak terdampak penyakit kulit setelah terpaksa minum air banjir yang keruh akibat sulitnya akses bantuan.
Peribahasa “sedia payung sebelum hujan” seharusnya menjadi pegangan dalam menghadapi tahun 2026. Persiapan ketahanan pangan dan lingkungan sangat krusial agar praktik penggundulan hutan akibat kerakusan tidak terulang. Mureks mencatat bahwa bencana banjir di berbagai daerah seharusnya tidak lagi terjadi di tahun-tahun mendatang. Sebagai contoh, data dari Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menunjukkan bahwa bencana yang terjadi pada tahun 2007 terulang kembali pada tahun 2025, dengan jumlah korban yang jauh lebih banyak.
Selain itu, konflik agraria juga menunjukkan peningkatan signifikan, bahkan empat kali lipat sejak tahun 2010. Konsesi sawit dan tambang kerap menggusur komunitas lokal, sementara petani kecil justru sering dijadikan kambing hitam deforestasi, padahal kontribusi mereka kurang dari 10%. Ironisnya, konglomerat yang menguasai mayoritas konsesi (25%) justru mendapat perlindungan politik. Akibatnya, 70 juta masyarakat adat yang bergantung pada hutan kehilangan akses terhadap tanah leluhur mereka tanpa adanya konsesi yang adil.
Dalam konteks ini, pemegang kekuasaan di tahun 2026 dituntut untuk lebih berhati-hati dalam memberikan izin kepada konglomerat. Pengalaman menunjukkan bahwa setelah izin diberikan, tidak jarang mereka melewati batas demi kepentingan pribadi, sementara rakyat harus menelan pil pahit dan dampak beracun dari kerusakan lingkungan.
Tidak hanya pemerintah, seluruh komponen dan lapisan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga alam sekitar. Menghidupkan kembali budaya dan kearifan lokal, seperti yang diajarkan para leluhur yang menjadikan hutan sebagai sahabat, adalah langkah vital. Dahulu, hujan membawa rahmat, namun kini seringkali berubah menjadi bencana. Saling menghormati terhadap alam sekitar menjadi kunci, sebab alam juga merupakan makhluk hidup yang saling membutuhkan dengan manusia, menciptakan keseimbangan yang menjaga keduanya.
Persepsi terhadap banjir pun telah berubah drastis. Jika dahulu banjir disambut gembira karena banyaknya ikan yang bisa ditangkap, kini hujan lebat justru memicu kekhawatiran akan datangnya marabahaya. Margasatwa pun turut merasakan dampaknya, kehilangan habitat dan terpaksa mencari perlindungan, yang lambat laun dapat menyebabkan kepunahan akibat dosa dan keserakahan manusia terhadap lingkungannya.