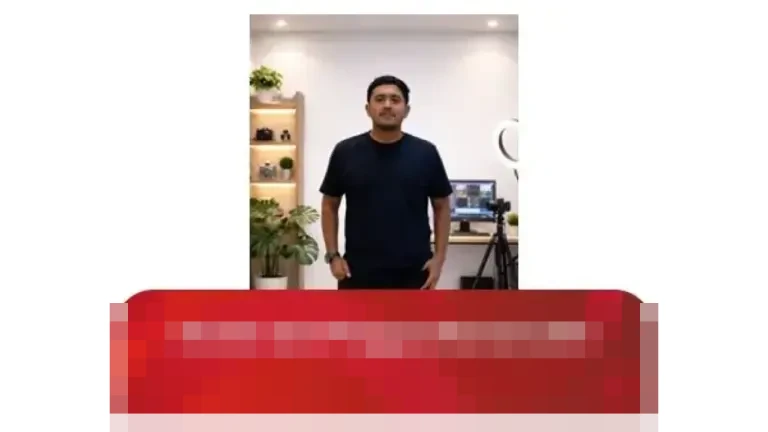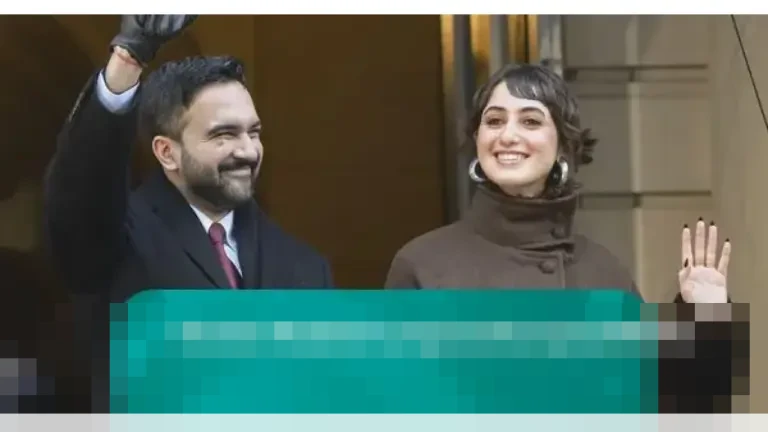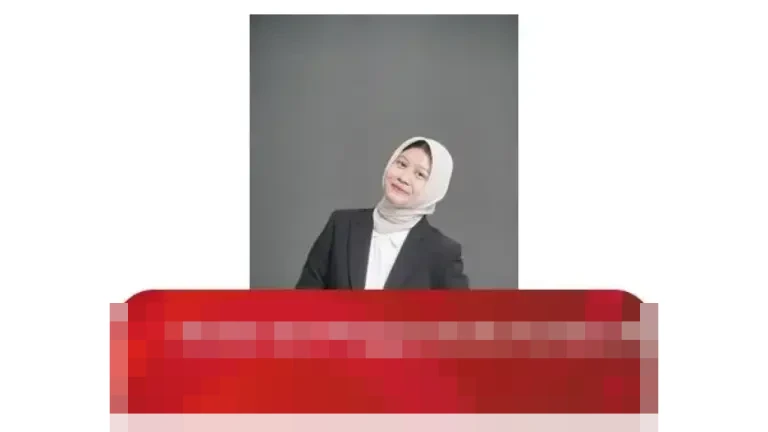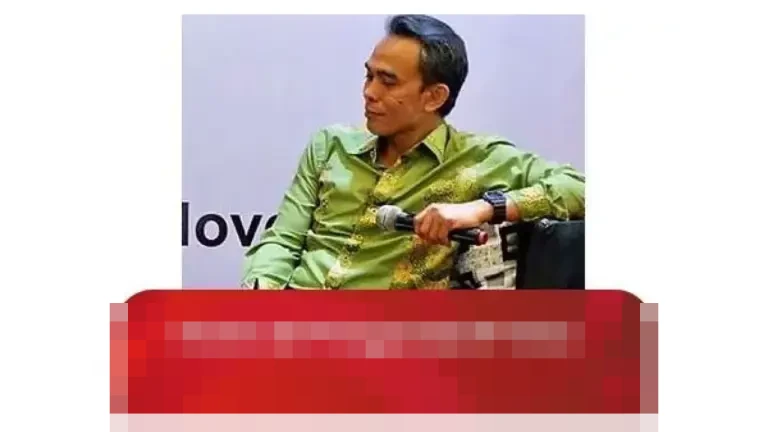Narasi historiografi cyborg yang kerap disajikan secara informatif dan reflektif, ternyata menyimpan problem mendasar. Menurut Dosen Filsafat Sains S3 di STEI ITB, Dimitri Mahayana, teks tersebut mengandung reduksionisme antropologis serius.
Pakar ICT lulusan Waseda University, Jepang, sekaligus pendiri konsultan ICT Sharing Vision, Bandung, ini menilai manusia direduksi menjadi sekadar sistem adaptif. Dimensi makna, kesadaran, dan pertumbuhan batin justru dipinggirkan dalam narasi tersebut.
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
1. Kritik Psikologi Humanistik: Manusia Bukan Proyek Adaptasi Teknis
Psikologi humanistik, yang digagas oleh tokoh seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Rollo May, lahir sebagai respons terhadap pandangan mekanistik tentang manusia. Tradisi ini menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mengaktualisasikan makna, nilai, dan kebebasan eksistensial, bukan sekadar bertahan hidup atau dioptimalkan.
Dimitri Mahayana menyoroti bahwa narasi cyborg membingkai manusia dalam logika adaptasi ekstrem, seperti modifikasi tubuh untuk lingkungan luar angkasa atau pengendalian fungsi biologis secara otomatis. Dari kacamata humanistik, ini merupakan bentuk dehumanisasi halus.
Ketika ‘ketidaksadaran’ (unconscious control) dipuji sebagai efisiensi, kita sedang menormalisasi hilangnya agency atau kehendak bebas, yang bagi Rogers adalah inti pribadi manusia. Maslow juga menekankan bahwa puncak perkembangan manusia adalah self-actualization, bukan peningkatan kapasitas teknis.
Pertanyaan bergeser dari “Siapa saya akan menjadi?” menjadi “Apa yang bisa ditingkatkan?”, sebuah pergeseran yang, menurut psikologi humanistik, menandai krisis kemanusiaan.
2. Kritik Psikologi Positif: Kesejahteraan Bukan Optimalisasi Algoritmik
Psikologi positif modern, yang dikembangkan oleh Martin Seligman, Ed Diener, dan Carol Ryff, berlandaskan pada data empiris tentang kesejahteraan manusia. Ironisnya, dari sudut pandang ini, narasi cyborg justru tampak naif terhadap janji teknologi.
Penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh kapasitas kognitif, melainkan oleh makna hidup, relasi yang bermakna, otonomi, dan kontribusi moral. Namun, narasi cyborg menggambarkan “cyborg kognitif” sebagai ekstensi memori dan pengambilan keputusan, seolah berpikir lebih cepat berarti hidup lebih baik.
Padahal, data justru menunjukkan sebaliknya. Ketergantungan kognitif pada sistem eksternal berkorelasi dengan peningkatan kecemasan, penurunan rasa kompetensi, dan erosi makna personal. Ini adalah illusory progress atau kemajuan semu, yang meningkatkan performa namun menggerus flourishing atau keberkembangan diri.
Lebih jauh, ketika algoritma mulai “menentukan apa yang kita lihat, baca, dan pikirkan”, salah satu pilar kesejahteraan, yaitu otonomi, terancam runtuh. Psikologi positif akan mempertanyakan dengan tegas: kesejahteraan siapa yang sebenarnya dioptimalkan? Individu, atau sistem?
3. Kritik Psikologi Transpersonal: Kesadaran Bukan Sekadar Fungsi Neural
Psikologi transpersonal, dengan tokoh seperti Stanislav Grof, Ken Wilber, dan Roberto Assagioli, melangkah lebih jauh. Aliran ini menolak asumsi implisit dalam narasi cyborg bahwa kesadaran identik dengan fungsi otak.
Dalam teks cyborg, pikiran diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat diperluas, disimpan, dan dimediasi teknologi, seolah kesadaran hanyalah komputasi kompleks. Bagi psikologi transpersonal, ini adalah kesalahan kategori ontologis.
Kesadaran bukanlah produk teknologi biologis semata, melainkan medan pengalaman yang melampaui ego dan identitas fungsional. Pengalaman mistik, transendensi diri, dan kesatuan eksistensial, yang telah diteliti lintas budaya, tidak dapat direduksi menjadi “cyborg kognitif”.
Ketika Ray Kurzweil berbicara tentang singularitas dan lenyapnya batas manusia-mesin, psikologi transpersonal melihatnya bukan sebagai puncak evolusi, melainkan sebagai krisis spiritual modern. Ini adalah upaya menggantikan transendensi dengan akselerasi teknis, di mana teknologi berfungsi sebagai substitusi makna, bukan sarana pendalaman kesadaran.
4. Kritik Etis Bersama: Siapa yang Mendefinisikan “Upgrade”?
Ketiga aliran psikologi ini, meskipun berbeda, bertemu pada satu kritik etis fundamental: narasi cyborg gagal mempertanyakan siapa yang berhak mendefinisikan kemajuan manusia. Ketika “upgrade” menjadi norma sosial, manusia yang memilih untuk tetap organik, lambat, reflektif, dan kontemplatif berisiko dianggap usang.
Psikologi humanistik menyebutnya sebagai penyangkalan martabat personal. Psikologi positif melihatnya sebagai ancaman terhadap kesejahteraan autentik. Sementara itu, psikologi transpersonal membacanya sebagai keterputusan manusia dari dimensi terdalam dirinya.
Penutup: Dari “Menjadi Cyborg” ke “Menjadi Manusia”
Narasi historiografi cyborg seringkali ditutup dengan pertanyaan: cyborg seperti apa yang ingin kita pilih untuk menjadi? Namun, menurut Mureks, dari perspektif psikologi humanistik, positif, dan transpersonal, pertanyaan itu perlu dibalik secara radikal.
Pertanyaan yang lebih relevan adalah: manusia seperti apa yang ingin kita pertahankan agar tidak hilang? Jika teknologi memperpanjang tubuh dan pikiran, tetapi memperpendek kesadaran, makna, dan kebebasan batin, maka kita bukan sedang berevolusi, melainkan kehilangan arah.
Dalam pandangan Carl Rogers, tantangan zaman ini bukan menjadi lebih canggih, melainkan tetap menjadi fully functioning human beings di tengah dunia yang semakin mesin.