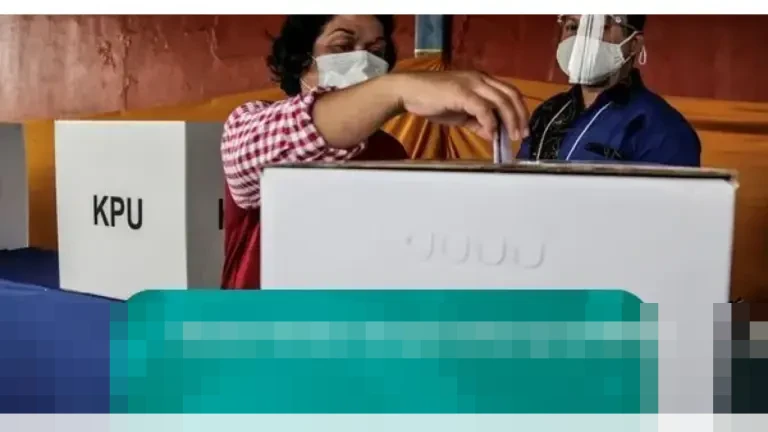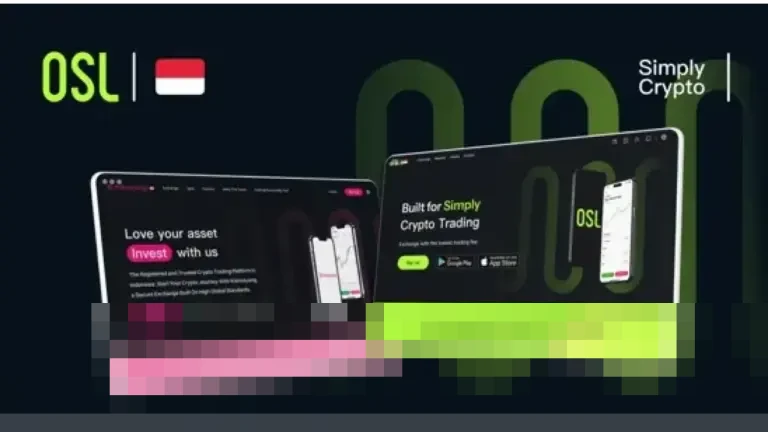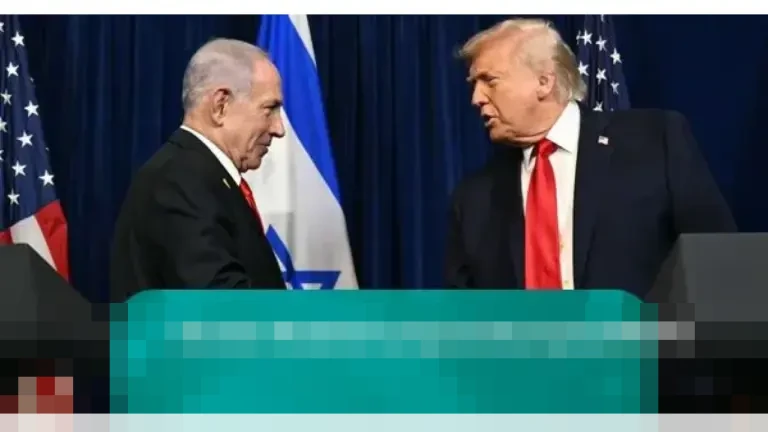Istilah cyborg—singkatan dari cybernetic organism—bukanlah produk fiksi ilmiah, melainkan lahir dari kebutuhan praktis di laboratorium sains. Pada tahun 1960, dua ilmuwan Amerika, Manfred Clynes dan Nathan S. Kline, memperkenalkan konsep ini dalam artikel mereka berjudul “Cyborgs and Space” yang diterbitkan di jurnal Astronautics.
Gagasan awal mereka sangat pragmatis: mencari cara agar manusia dapat bertahan hidup dalam misi luar angkasa jangka panjang. Alih-alih membawa “Bumi mini” ke luar angkasa, Clynes dan Kline mengusulkan modifikasi tubuh manusia agar mampu beradaptasi secara otomatis dengan lingkungan ekstrem.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Dalam pengertian ini, cyborg didefinisikan sebagai organisme yang sebagian fungsi biologisnya diatur oleh sistem teknologi internal. Sistem tersebut bekerja tanpa memerlukan kendali atau kesadaran terus-menerus dari subjeknya, menandai integrasi mendalam antara manusia dan mesin.
Dari Fiksi Ilmiah ke Realitas Medis
Meskipun berakar pada kebutuhan astronautika, gagasan cyborg dengan cepat melampaui dunia kedirgantaraan. Ia membuka horizon baru tentang relasi manusia dan mesin, memicu imajinasi publik jauh sebelum teknologi siap diwujudkan.
Kisah-kisah tentang automata dan mekanisasi manusia telah lama hadir dalam sastra, seperti Frankenstein di abad ke-19. Kemudian, film-film populer seperti Terminator, Blade Runner, dan RoboCop menampilkan figur cyborg sebagai simbol kecemasan modern: ketakutan akan hilangnya kemanusiaan, kaburnya identitas, serta masa depan yang dingin dan mekanistik.
Namun, di dunia nyata, perkembangan paling konkret justru terjadi di bidang medis. Alat pacu jantung, implan koklea bagi tunarungu, serta prostetik canggih secara perlahan mengaburkan batas antara tubuh biologis dan mesin. Jutaan manusia kini hidup dengan sistem teknologi yang menyatu langsung dengan tubuh mereka, bukan untuk memperoleh kemampuan super, melainkan untuk memulihkan dan menopang fungsi dasar kehidupan.
Cyborg sebagai Metafora Budaya dan Politik
Lompatan konseptual besar terjadi pada tahun 1985 ketika Donna Haraway menerbitkan esainya yang sangat berpengaruh, A Cyborg Manifesto. Di tangan Haraway, cyborg tidak lagi dipahami semata sebagai proyek teknologi, melainkan sebagai metafora politik dan budaya.
Haraway melihat cyborg melambangkan runtuhnya batas-batas lama: antara manusia dan mesin, alam dan budaya, serta laki-laki dan perempuan. Baginya, manusia modern yang hidup dalam jaringan teknologi pada dasarnya sudah bersifat “cyborgian”. Gagasan ini memberi pengaruh luas dalam studi feminisme, teori budaya, dan posthumanisme, meskipun juga menuai kritik karena dianggap terlalu optimistis terhadap potensi emansipatoris teknologi.
Eksperimen Integrasi Fisik dan Visi Futuristis
Dua dekade setelah Haraway, konsep cyborg benar-benar memasuki tubuh manusia secara harfiah. Pada tahun 1998, ilmuwan Inggris Kevin Warwick menanamkan chip RFID ke tubuhnya dalam proyek yang dikenal sebagai Cyborg 1.0. Kemudian, pada tahun 2002 melalui Cyborg 2.0, ia menghubungkan sistem sarafnya dengan komputer, memungkinkan sinyal saraf manusia berinteraksi langsung dengan mesin, bahkan dalam skala terbatas, dengan sistem saraf manusia lain.
Eksperimen Warwick memicu kekaguman sekaligus kontroversi, memicu perdebatan tentang batas antara terobosan ilmiah dan sensasi teknologi. Perdebatan ini menegaskan bahwa hingga kini, definisi tentang apa yang disebut “cyborg” belum pernah sepenuhnya disepakati.
Sementara itu, futurolog Ray Kurzweil membawa wacana cyborg ke arah yang lebih spekulatif. Ia memprediksi terjadinya Singularity—titik di mana kecerdasan mesin melampaui kecerdasan manusia—sekitar tahun 2045. Dalam visinya, cyborg hanyalah tahap peralihan menuju masa depan di mana batas antara manusia dan mesin semakin menghilang.
Era Cyborg Kognitif: Integrasi Tanpa Operasi
Hari ini, definisi cyborg tidak lagi terbatas pada implan medis atau eksperimen laboratorium. Seniman Neil Harbisson, yang memiliki antena tertanam di kepalanya untuk menerjemahkan warna menjadi suara, diakui secara administratif oleh pemerintah Inggris, bahkan diperbolehkan tampil dalam foto paspor resminya. Di sisi lain, komunitas body modification secara sukarela menanam magnet, chip RFID, dan sensor eksperimental ke tubuh mereka.
Namun, revolusi paling luas justru terjadi tanpa operasi apa pun. Ketika manusia bergantung pada Google Maps hingga kehilangan orientasi spasial alami, menyimpan ingatan di ponsel, atau mengandalkan sistem seperti ChatGPT untuk membantu berpikir dan menulis, kita memasuki era cyborg kognitif. Integrasi manusia dan mesin kini berlangsung di tingkat pikiran, bukan semata-mata tubuh.
Teknologi Kecerdasan Buatan (AI), terutama model bahasa besar, berfungsi sebagai ekstensi memori, persepsi, dan pengambilan keputusan. Berbeda dari cyborg klasik ala Warwick, bentuk integrasi ini bekerja secara implisit dan pervasif. Algoritma tidak sepenuhnya menentukan pikiran manusia, tetapi semakin kuat memengaruhi apa yang kita lihat, baca, dan cara kita membentuk penilaian.
Tantangan Etis dan Pilihan Masa Depan
Di sinilah pertanyaan etis paling mendesak muncul. Jika teknologi semakin menyatu dengan tubuh dan pikiran manusia, bagaimana dengan agensi, martabat, dan kebebasan memilih? Siapa yang bertanggung jawab ketika sistem gagal? Dan siapa yang akan tertinggal ketika “peningkatan” teknologi perlahan berubah menjadi norma sosial baru?
Sejak tongkat pertama yang memperpanjang jangkauan tangan manusia hingga kecerdasan buatan yang memperpanjang daya pikir, teknologi selalu menjadi bagian dari kemanusiaan. Yang berubah bukanlah kenyataan bahwa manusia bersifat teknologis, melainkan seberapa dalam dan intim relasi tersebut.
Maka, pertanyaannya bukan lagi: apakah manusia akan menjadi cyborg? Melainkan: cyborg seperti apa yang secara sadar ingin kita pilih untuk menjadi? Atau, seharusnya kita berpikir lebih kritis lagi?