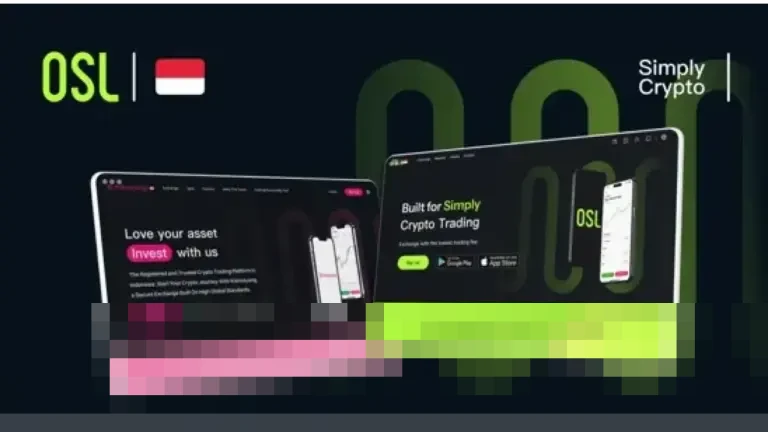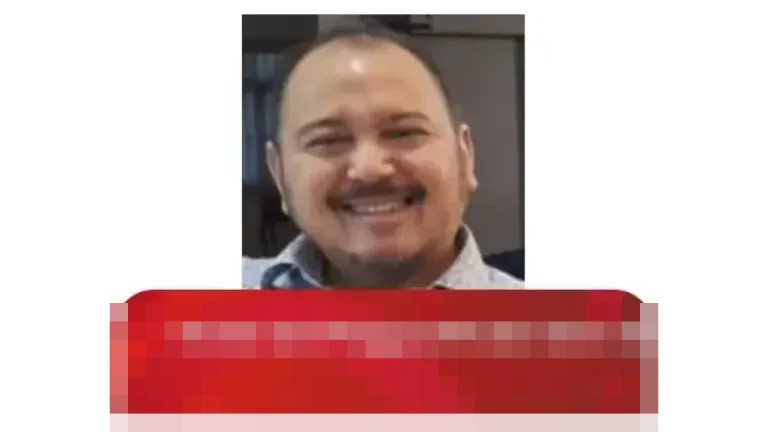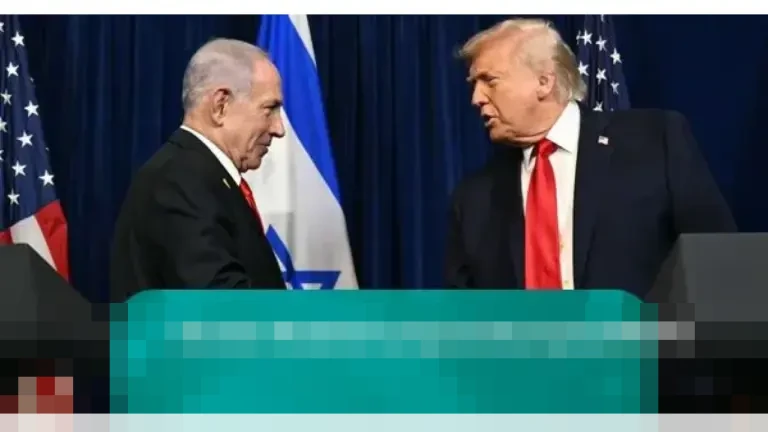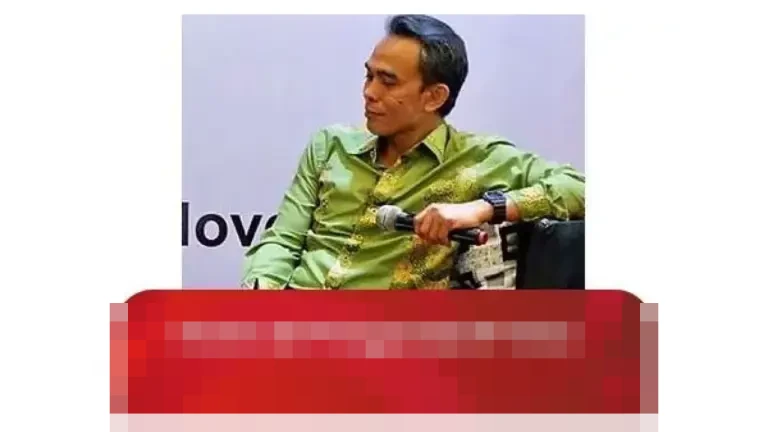Indonesia kembali dihadapkan pada serangkaian bencana alam yang datang silih berganti. Banjir, banjir bandang, dan tanah longsor melanda berbagai wilayah, dari Sumatera hingga Jawa, dari hulu sungai hingga perkotaan. Peristiwa-peristiwa ini, yang kerap dianggap sebagai kejadian alamiah tak terelakkan, sesungguhnya membawa pesan mendalam: alam sedang memberi isyarat agar arah pembangunan kembali selaras dengan batas-batas ekologis.
Menurut Yana Karyana, seorang aktivis lingkungan dan Ketua DPP Persaudaraan dan Kemitraan Pesantren (PK-Tren) Indonesia, hujan memang turun dari langit, tetapi banjir dan longsor lahir dari cara manusia memperlakukan alam. Di titik inilah, bencana tidak lagi semata peristiwa alam, melainkan cermin relasi timpang antara pembangunan dan daya dukung lingkungan. Pertanyaan mendasarnya, apakah kita akan terus bersikap reaktif menangani dampak, atau berani melakukan koreksi terhadap arah pembangunan yang selama ini mengabaikan batas-batas ekologi?
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Amanat Pendahulu yang Terabaikan
Jauh sebelum istilah krisis iklim atau pembangunan berkelanjutan populer, para pendahulu di Nusantara telah mewariskan pengetahuan ekologis yang praktis sekaligus etis. Dalam tradisi Sunda, dikenal ungkapan gunung kaian, gawir awian, lebak balongan—gunung harus berhutan, tebing ditanami bambu, dan lembah dijaga sebagai cadangan air. Ini bukan sekadar petuah budaya, melainkan panduan tata ruang berbasis ekologi.
Pesan di baliknya tegas: alam tidak boleh diperlakukan seragam. Setiap bentang alam memiliki fungsi yang saling menopang. Ketika fungsi itu diabaikan, kerusakan menjadi keniscayaan. Karena itu, peringatan leluhur terasa profetik: leuweung ruksak, cai beak, rahayat balangsak—hutan rusak, air habis, rakyat menderita. Ungkapan ini menemukan relevansinya ketika bencana datang dan yang paling terdampak adalah masyarakat kecil di wilayah rentan.
Ungkapan lain, mulasara alam, miara sasama—merawat alam dan memelihara sesama—menegaskan bahwa krisis lingkungan selalu berkelindan dengan krisis kemanusiaan. Kerusakan alam pada akhirnya adalah bentuk ketidakadilan sosial yang paling nyata.
Ketika Ilmu Modern Membenarkan Kearifan Lama
Menariknya, nilai-nilai yang diwariskan para pendahulu justru menemukan pembenarannya dalam teori pembangunan kontemporer. Konsep Doughnut Economics yang dikembangkan oleh Kate Raworth menekankan bahwa pembangunan harus bergerak di ruang aman antara dua batas: fondasi sosial yang menjamin kesejahteraan manusia dan langit-langit ekologis yang menjaga daya dukung bumi. Melampaui salah satunya akan melahirkan krisis, baik krisis sosial maupun krisis lingkungan.
Dalam konteks Indonesia hari ini, kita kerap melampaui kedua batas tersebut sekaligus. Alam dieksploitasi secara berlebihan, sementara manfaat ekonominya tidak terdistribusi secara adil. Banjir, longsor, dan kekeringan yang berulang bukan sekadar peristiwa alamiah, melainkan cermin kegagalan kolektif dalam menata pembangunan yang berkelanjutan.
Dari Pembangunan ke Pertanggungjawaban
Rentetan bencana seharusnya mendorong kita berhenti menyalahkan cuaca dan mulai bercermin pada kebijakan. Tata ruang yang longgar, pembukaan hutan di kawasan hulu, serta pembangunan yang mengabaikan daerah resapan air adalah bentuk pengingkaran terhadap amanat pendahulu. Alam diperlakukan sebagai komoditas ekonomi jangka pendek, bukan sebagai penopang kehidupan jangka panjang.
Di sinilah urgensi etika ekologis menjadi tak terelakkan. Alam bukan warisan nenek moyang untuk dihabiskan, melainkan titipan untuk generasi mendatang. Prinsip ini hidup dalam banyak kearifan lokal Nusantara, tetapi sering kali kalah oleh logika pertumbuhan yang sempit dan serba instan.
Penutup
Indonesia sejatinya tidak kekurangan pengetahuan untuk merawat alam. Kearifan lokal di berbagai daerah telah lama mengajarkan tentang batas, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam memperlakukan lingkungan. Tantangan kita hari ini bukan menemukan gagasan baru, melainkan keberanian menjadikan kebijaksanaan lama itu sebagai dasar kebijakan pembangunan modern.
Pepatah Sunda mengingatkan, gunung kanyahoan, laut kasabaan, jagat kasorang—gunung untuk dikuasai ilmunya, laut untuk diolah hasilnya, dan dunia untuk dijelajahi. Pesan ini menegaskan bahwa kemajuan menuntut pengetahuan, pengelolaan yang bijak, serta tanggung jawab moral. Tanpa etika ekologis, pembangunan hanya akan melahirkan bencana yang berulang. Merawat alam bukan pilihan moral tambahan, melainkan prasyarat keadilan sosial dan keselamatan bersama, agar masa depan Indonesia tidak terus dibayangi oleh krisis yang seharusnya bisa dicegah.