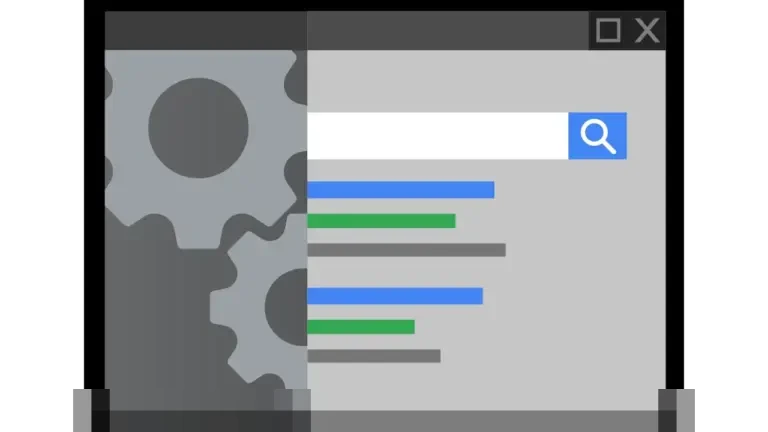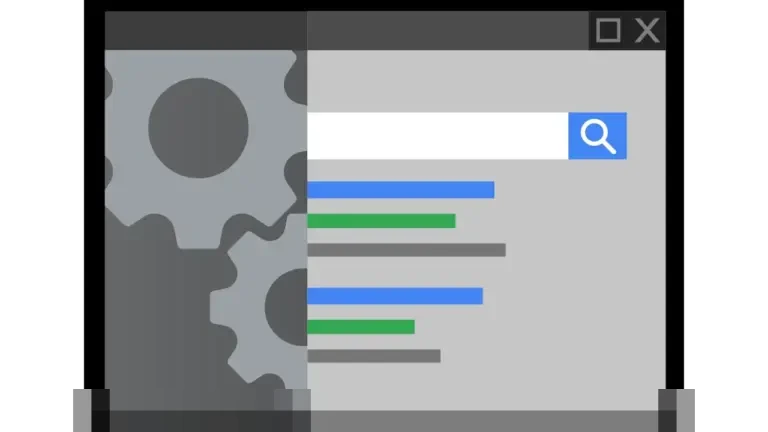Dunia pergerakan nasional Indonesia kerap diwarnai pidato-pidato heroik, namun di balik itu, kekuatan tinta juga menjadi senjata mematikan bagi kolonialisme. Salah satu tokoh yang konsisten menghunuskan penanya adalah Mas Marco Kartodikromo, atau yang lebih dikenal sebagai Mas Marco.
Lahir dari keluarga priyayi di Cepu, Blora, Hindia Belanda pada 1890, latar belakang sosialnya menempatkan Marco pada posisi unik. Ia bukan elite priyayi tinggi, namun cukup dekat dengan administrasi kolonial untuk menyaksikan langsung ketimpangan yang dialami kaum bumiputra.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Dari Juru Tulis Menuju Mimbar Jurnalistik
Perjalanan hidup Marco dimulai sebagai juru tulis di dinas kehutanan pada tahun 1905. Lima tahun berselang, ia memutuskan merantau ke Semarang. Di kota tersebut, ia bekerja di perusahaan kereta api Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) sambil mendalami bahasa Belanda melalui guru privat untuk memahami logika berpikir bangsa penjajah.
Titik balik hidupnya terjadi pada tahun 1911 saat ia pindah ke Bandung dan bergabung dengan surat kabar Medan Prijaji di bawah bimbingan Tirto Adhi Soerjo. Di bawah asuhan Tirto, Marco mengasah diri menjadi jurnalis yang tak hanya sekadar penyampai berita, tetapi juga aktivis pergerakan yang kritis.
Ketika Medan Prijaji bangkrut pada 1912, ia pindah ke Surakarta untuk mengelola koran Sarotomo sebagai editor sekaligus administrator. Pengalaman di Bandung dan hubungannya dengan tokoh seperti Soewardi Soerjaningrat semakin memperkuat komitmennya dalam menyuarakan ketimpangan sosial melalui jalur jurnalistik.
Student Hidjo: Romantisme Pelajar dan Kritik Tajam
Salah satu warisan intelektual terbesarnya adalah novel Student Hidjo yang diterbitkan pertama kali oleh Masman en Stroink di Semarang pada tahun 1919. Melalui tokoh utama bernama Hidjo, Marco memotret kegelisahan pelajar bumiputra yang menempuh studi ke Belanda namun terjebak dalam dualitas budaya.
Novel ini secara tajam membandingkan nilai tradisional Jawa dengan budaya Barat, sekaligus mengungkap tabir rasisme yang dialami kaum terpelajar pribumi. Melalui narasi tersebut, Marco berupaya menelanjangi keangkuhan serta perilaku tidak manusiawi para penjajah Belanda terhadap masyarakat Jawa yang berada di bawah kekuasaan mereka. Mureks mencatat bahwa novel ini secara eksplisit menggambarkan kontradiksi moral yang dilakukan oleh kaum kolonial saat itu.
Sebagaimana ditegaskan oleh Pramoedya Ananta Toer dalam novelnya yang berjudul Rumah Kaca,