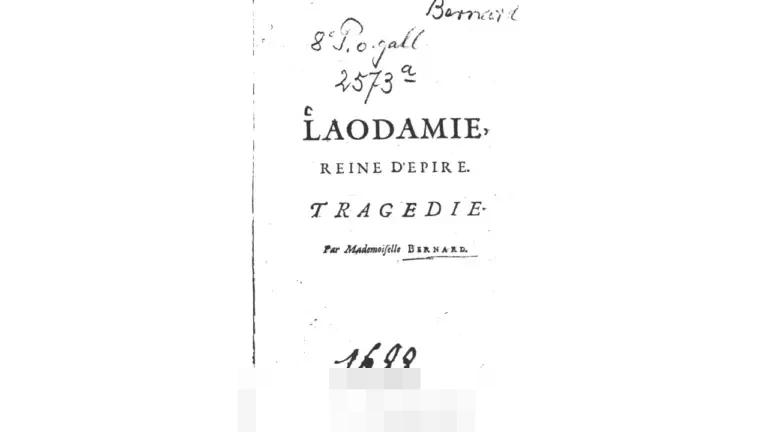Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai Jumat, 2 Januari 2026. Regulasi yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto ini membawa implikasi signifikan, khususnya terkait praktik kohabitasi atau yang dikenal dengan istilah kumpul kebo, serta aturan pidana perzinahan.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan seluruh jajarannya siap menegakkan ketentuan baru ini. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa sejak pukul 00.01 WIB pada tanggal tersebut, seluruh satuan kerja Polri, mulai dari fungsi reserse kriminal hingga lalu lintas, telah menyesuaikan proses penanganan perkara dengan regulasi terbaru.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
“Seluruh petugas pengemban penegakan hukum Polri telah mempedomani pelaksanaan dan mengimplementasikan pedoman tersebut, menyesuaikan KUHP dan KUHAP saat ini,” ujar Trunoyudo, dikutip dari detikcom, Jumat (2/1/2026).
Lebih lanjut, Bareskrim Polri juga telah merampungkan penyusunan panduan serta format administrasi penyidikan baru yang telah ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Syahardiantono.
Pasal 411 dan 412 KUHP Baru: Perzinahan dan Kohabitasi
Dalam KUHP baru, aturan mengenai perzinahan tertuang dalam Pasal 411. Pasal ini menyatakan, “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II.”
Sementara itu, praktik kumpul kebo atau kohabitasi diatur dalam Pasal 412. Pasal ini berbunyi, “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II.”
Meskipun mengatur sanksi pidana, kedua pasal ini bukan merupakan delik umum. Artinya, proses hukum hanya dapat dimulai berdasarkan pengaduan dari pihak-pihak tertentu. Untuk orang yang terikat perkawinan, pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istri. Sedangkan bagi orang yang tidak terikat perkawinan, pengaduan dapat diajukan oleh orang tua atau anak.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa ketentuan yang bersifat sensitif seperti hubungan di luar perkawinan dirumuskan sebagai delik aduan. “Ketentuan yang bersifat sensitif, seperti hubungan di luar perkawinan, dirumuskan sebagai delik aduan untuk mencegah intervensi negara yang berlebihan ke ranah privat,” kata Yusril.
Pengaduan terkait Pasal 411 dan 412 bahkan masih dapat dicabut kembali selama proses persidangan belum dimulai. Yusril menambahkan, penerapan KUHP dan KUHAP baru ini menandai lahirnya sistem hukum pidana nasional yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan. “Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan,” ujarnya, mengutip detikcom, Jumat (2/1/2026).
KUHP baru ini mengubah pendekatan hukum pidana dari retributif menjadi restoratif. Tujuannya adalah pemidanaan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Pendekatan ini diwujudkan melalui perluasan pidana alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan mediasi, termasuk penguatan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika.
Fenomena Kohabitasi di Indonesia
Praktik kohabitasi di Indonesia telah menjadi sorotan, terutama di kota-kota besar. Yulinda Nurul Aini dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam tulisannya yang dikutip The Conversation pada 22 Februari 2024, mengungkapkan bahwa kohabitasi dan kelahiran anak di luar pernikahan (nonmarital childbearing) menjadi fenomena demografi yang semakin umum. Menurutnya, generasi muda mulai mengalami pergeseran pandangan terhadap relasi dan pernikahan, di mana pernikahan dianggap sebagai institusi normatif yang kompleks, sementara kohabitasi dilihat sebagai hubungan yang murni dan refleksi cinta.
Pandangan ini sejalan dengan teori “Second Demographic Transition” (SDT) yang diajukan oleh Ron Lesthaeghe, profesor demografi dan sains sosial dari Belgia. Lesthaeghe berpendapat bahwa pernikahan telah kehilangan statusnya sebagai bentuk persatuan konvensional yang berdasar pada norma dan nilai sosial, dan sebagai gantinya, kohabitasi telah menjadi bentuk baru pembentukan keluarga.
Dalam ringkasan Mureks, studi tahun 2021 berjudul “The Untold Story of Cohabitation” mengungkap bahwa kohabitasi lebih umum terjadi di wilayah Indonesia Timur, yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Sebagai contoh, analisis data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menemukan 0,6% penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi.
Dari total populasi pasangan kohabitasi di Manado, catatan Mureks menunjukkan, 1,9% di antaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia kurang dari 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% lainnya bekerja secara informal.
Terdapat tiga alasan utama mengapa pasangan memilih melakukan kohabitasi, yaitu beban finansial, rumitnya prosedur perceraian, serta adanya penerimaan sosial terhadap pasangan kohabitasi di lingkungan tertentu.
Dampak Negatif dan Solusi yang Mungkin
Perempuan dan anak menjadi pihak yang paling terdampak secara negatif oleh praktik kohabitasi. Dalam konteks ekonomi, ketiadaan peraturan yang mengatur kohabitasi berarti tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu, berbeda dengan hukum terkait perceraian. Ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan dukungan finansial dalam bentuk nafkah (alimentasi). Ketika pasangan kohabitasi berpisah, tidak ada kerangka regulasi yang mengatur pembagian aset dan finansial, alimentasi, hak waris, penentuan hak asuh anak, dan masalah-masalah lainnya.
Dampak negatif kohabitasi juga meluas ke aspek kesehatan mental, yang dapat dirasakan melalui penurunan kepuasan hidup serta masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi akibat kurangnya komitmen, kepercayaan, dan ketidakpastian masa depan. Anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga sering mengalami dampak negatif, termasuk gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, dan emosional. Mereka dapat mengalami kebingungan identitas dan perasaan tidak diakui karena stigma “anak haram”, bahkan dari anggota keluarga sendiri, yang menyulitkan mereka menempatkan diri dalam struktur keluarga dan masyarakat.
Alih-alih hanya “menghukum” pasangan kohabitasi, pemerintah dan pembuat kebijakan disarankan untuk fokus mengurangi hambatan dalam melangsungkan pernikahan. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain melalui pembentukan gerakan komunitas yang berkolaborasi dengan pemimpin masyarakat (gereja, adat, atau lingkungan setempat) untuk mensosialisasikan pentingnya menyesuaikan mahar pernikahan dengan kemampuan ekonomi calon pengantin. Selain itu, edukasi mengenai dampak negatif kohabitasi dan anak di luar pernikahan juga penting untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dalam mempersiapkan kehidupan masa depan, termasuk merencanakan pernikahan.