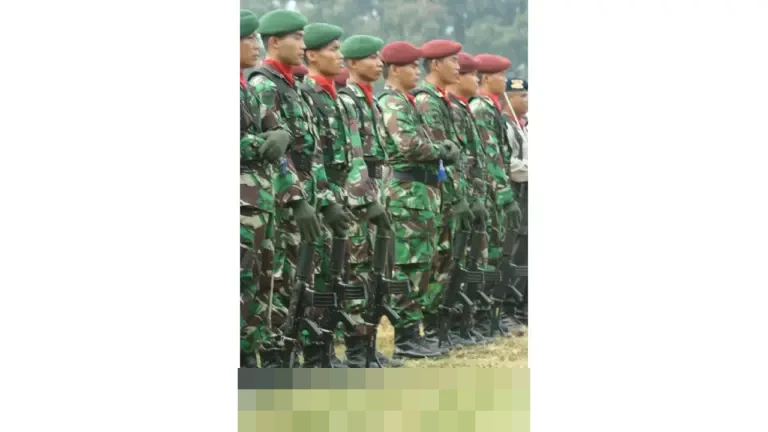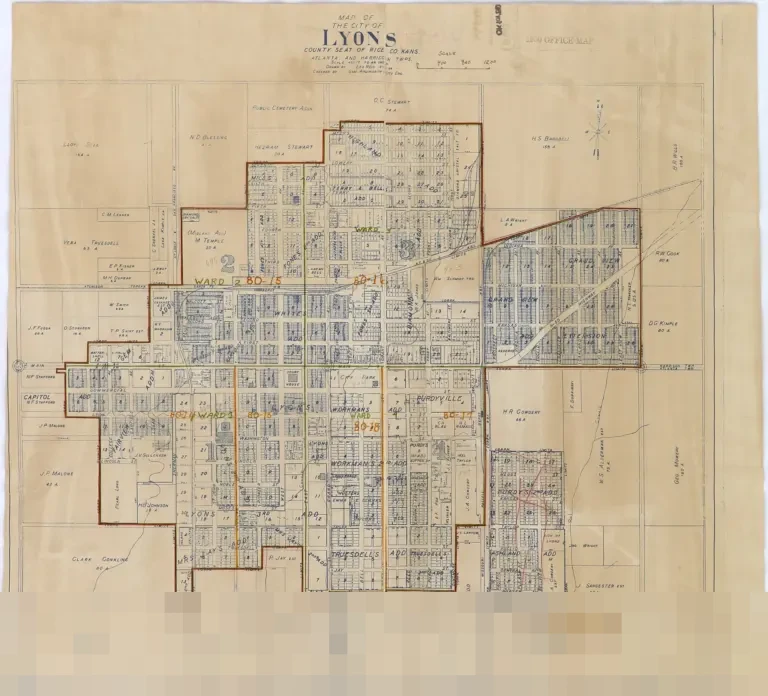Rilis Global Flourishing Study (GFS) 2024-2025 yang menempatkan Indonesia di urutan pertama dunia dalam hal “kesejahteraan utuh” telah menjadi sorotan. Predikat ini, menurut Presiden Prabowo Subianto, seolah-olah merupakan hasil nyata dari kebijakan pemerintah yang patut dirayakan secara luas.
Namun, Mureks mencatat bahwa ada kekeliruan logika yang mendasar ketika pemimpin negeri ini mengklaim kebahagiaan rakyat sebagai capaian politik. Pemerintah dinilai gagal memahami bahwa kebahagiaan masyarakat lebih banyak bersumber dari dimensi spiritual, seperti doa dan kehidupan bertetangga yang harmonis, ketimbang intervensi kebijakan politik dan ekonomi.
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Kebahagiaan Rakyat Bukan Output Birokrasi
Data GFS memang menunjukkan Indonesia di puncak, tetapi pendorong utamanya bukanlah indikator material seperti angka pertumbuhan ekonomi atau efektivitas birokrasi. Skor tinggi Indonesia justru ditopang oleh domain non-material, yakni religiusitas yang mendalam, makna hidup yang spiritual, serta hubungan sosial yang erat. Ini adalah aset organik yang telah melekat dalam kehidupan rakyat jelata secara turun-temurun, bukan hasil dari rapat-rapat kabinet.
Menganggap skor GFS sebagai prestasi pemerintah diibaratkan seperti seorang Gen Z yang berswafoto di lokasi wisata indah, lalu mengklaim keindahan pemandangan tersebut sebagai hasil dari kualitas kameranya.
“Wellbeing Washing” dan Romantisasi Kemiskinan
Fenomena ini memunculkan aroma “Wellbeing Washing”, sebuah upaya pencucian citra melalui narasi kesejahteraan yang tercium dari podium kepresidenan. Ketika Presiden memuji rakyat yang “tetap bahagia meskipun hidup sederhana,” secara tidak langsung ia sedang meromantisasi kemiskinan, mengaburkan realitas kesulitan yang dihadapi.
Survei GFS, pada dasarnya, berkonteks pada peri kehidupan rakyat, bukan kinerja pemerintah. Jika masyarakat Indonesia masih mampu tersenyum di tengah himpitan harga bahan pokok dan biaya pendidikan yang mencekik, hal itu bukanlah bukti keberhasilan pemerintah. Sebaliknya, itu adalah indikasi bahwa rakyat sudah terbiasa “nrimo” atau menggunakan mekanisme koping religius karena absennya jaminan sosial yang memadai dari negara. Budaya bersyukur, meskipun dalam penderitaan, telah tertanam kuat.
Delegitimasi Keluhan Publik
Ketika negara mendiktekan narasi bahwa “kita bangsa paling bahagia,” setiap keluhan tentang ketidakadilan, korupsi, atau bencana seperti banjir, dapat dengan mudah didelegitimasi sebagai sikap “kurang bersyukur.” Ini adalah taktik retoris yang sinis untuk mengabaikan ketidakpuasan publik.
Tugas pemerintah seharusnya bukan memuji ketahanan rakyat dalam menahan penderitaan atau menyesali 58% pemilih yang kecewa dengan kabinet, melainkan memastikan penderitaan dan frustrasi rakyat berakhir. Mengklaim posisi pertama dalam Global Flourishing Study sebagai pencapaian politik adalah kesimpulan yang “di luar nurul” dan berpotensi berbahaya.
Data GFS seharusnya menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang luar biasa kuat sebagai fondasi. Tugas pemerintah, yang digaji dari pajak rakyat, adalah membangun rumah ekonomi yang layak di atas fondasi tersebut. Jangan biarkan rakyat terus kepanasan dan kehujanan di luar, sementara para pejabat di ruangan ber-AC sibuk memuji ketahanan mereka sambil menunjukkan sertifikat penghargaan.
Pada akhirnya, sebrengsek apapun oknum pejabat negara atau sebebas apapun koruptor menggerogoti aset negara, rakyat tetap berusaha bahagia. Hal ini karena rakyat menyadari, menangis dan menjerit sekalipun, tidak akan serta-merta membuat negara berpihak pada mereka.