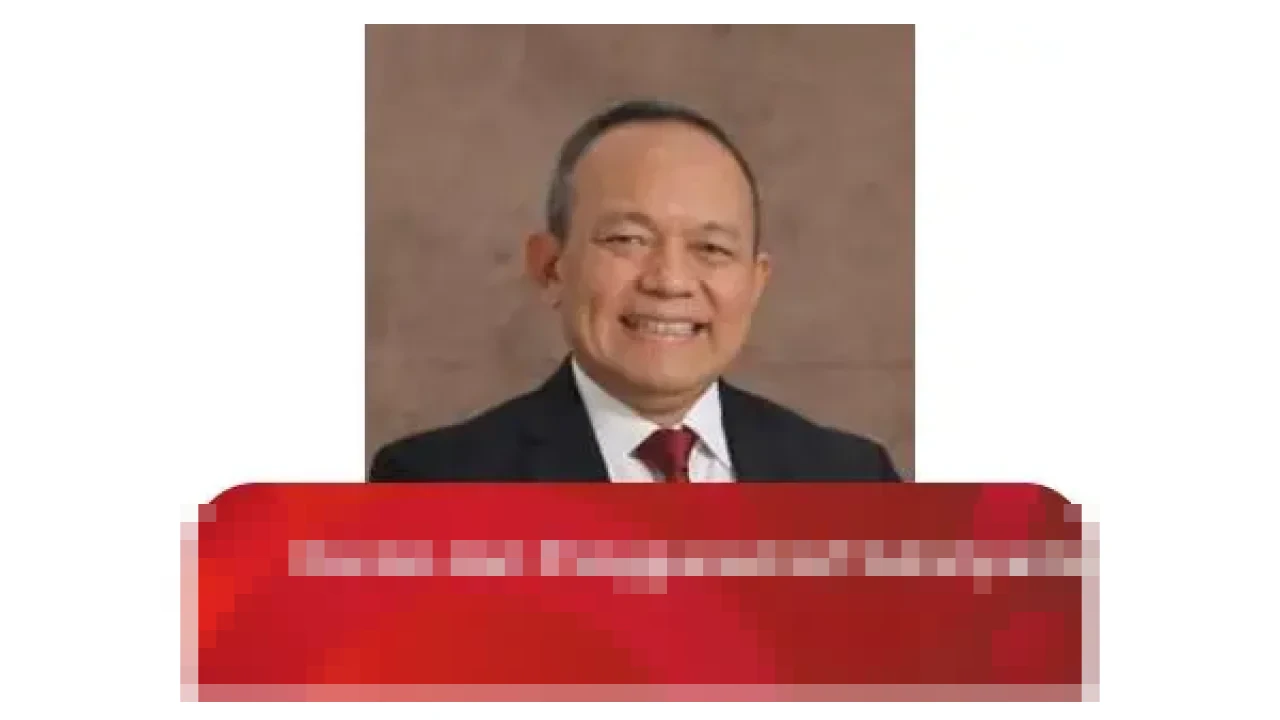Indonesia, sebuah negeri yang dianugerahi kekayaan alam melimpah, seringkali dihadapkan pada ironi mendalam. Di tengah karunia hutan, mineral, laut, dan tanah subur, kemiskinan dan ketimpangan masih terasa nyata, sementara bencana alam datang silih berganti. Menurut pemerhati kepemimpinan, etika publik, dan refleksi spiritualitas sosial, Arief Sulistyanto, persoalan ini bukan lagi sekadar teknis, melainkan telah mencapai titik moral.
Pola Kezaliman dalam Sejarah dan Masa Kini
Sejarah manusia berulang kali menunjukkan pola di mana kekuasaan menolak kebenaran. Kaum Nūḥ, ‘Ād, dan Ṡamūd, misalnya, menolak tanda-tanda terang bukan karena kurang bukti, melainkan karena gengsi berlebihan. Kebenaran dianggap ancaman terhadap dominasi, sehingga kekeliruan dipertahankan demi menjaga wibawa, yang justru didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan citra, bukan keberanian mengoreksi diri.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Pola kedua yang tak kalah licin adalah penyerangan terhadap pembawa risalah melalui framing. Kaum Quraisy, alih-alih mematahkan argumen dengan hujjah jujur, justru menuduh Nabi mengada-ada dan memelintir pesan. Strategi ini efektif untuk menggeser perhatian publik dari substansi ke stigma, membuat kebenaran kalah di ruang persepsi, bukan argumentasi.
Arief Sulistyanto menilai, dua pola kuno ini masih hidup di masa kini, meski dengan bungkus yang berbeda. Dulu berhala dan syair, kini data dipilih-pilih, opini diproduksi, jargon dipoles, dan pencitraan digenjot. Kebenaran yang mengoreksi dianggap mengganggu, kritik diposisikan sebagai ancaman, dan pertanyaan dijawab dengan slogan. Pada tahap ini, kezaliman bukan lagi perbuatan spontan, melainkan sebuah arsitektur yang memoles kesalahan agar tampak benar, sementara kebenaran dibuat tampak merepotkan.
Ironi Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dalam konteks negeri yang kaya, kezaliman ini kerap menjelma dalam pengelolaan sumber daya alam. Narasi “investasi” dan “program pangan” terdengar mulia, namun berpotensi menjadi selimut untuk menutupi pelanggaran sunatullah. Hutan dibuka serampangan, tata ruang dipermainkan, dan penyangga ekosistem diabaikan.
Akibatnya, alam berbicara melalui bahasa yang tak bisa disuap: banjir bandang, longsor, luapan sungai, krisis air, dan rusaknya hulu daerah aliran sungai. Bencana di Sumatra pada akhir November 2025 menjadi cermin pahit, di mana daya rusak membesar ketika lanskap kehilangan pelindungnya. Alam tidak sedang “marah”, melainkan menjalankan hukum sebab-akibat yang tegas, dengan korban pertamanya hampir selalu rakyat kecil.
Pada saat yang sama, wacana pembukaan lahan hutan skala sangat luas, termasuk di Papua, atas nama agenda-agenda besar juga disoroti. Kelestarian sering diperlakukan sebagai catatan kaki. Padahal, kerusakan pada bentang alam sebesar itu bukan sekadar isu lingkungan, melainkan menyentuh ketahanan sosial, kesehatan, ketersediaan air, dan membuka pintu bencana yang lebih dahsyat. Risiko ekologis dialihkan kepada publik, membuat rakyat menanggung penderitaan langsung dan kemiskinan yang diwariskan.
Puncak Kezaliman: Pergeseran Amanah
Di sinilah puncak kezaliman menjadi nyata, bukan hanya merampas uang, tetapi merampas amanah. Amanah bukan sekadar jabatan atau proyek, melainkan tanggung jawab moral untuk menempatkan kekayaan negeri sebagai jalan kesejahteraan rakyat, bukan ladang keuntungan sempit. Amanah juga mencakup tata kelola meritokrasi, menempatkan orang cakap dan bersih pada posisi strategis, bukan sekadar yang dekat dan patuh.
Ketika amanah dipindahkan dari pelayanan menjadi transaksi, sistem akan melahirkan pemimpin yang pandai bertahan, bukan pemimpin yang pandai membenahi. Kezaliman kian gelap ketika kebijakan merusak dibenarkan dengan pembingkaian moral, mendustakan tanda-tanda kebenaran pada alam, sejarah, dan realitas sosial. Publik dibuat bingung agar kekuasaan tidak terlihat keliru, sementara korban diminta bersabar seolah penderitaan adalah kewajaran.
Pertanggungjawaban Moral dan Ilahi
Arief Sulistyanto mengingatkan, ada satu ruang yang tidak bisa dimanipulasi: pertanggungjawaban di hadapan Allah. Perampasan amanah tidak pernah hilang, melainkan berpindah dari catatan manusia ke catatan langit. Di dunia, narasi bisa diatur, namun dalam hisab, yang dinilai bukan niat yang diumumkan, melainkan akibat nyata. Mengatasnamakan investasi atau ketahanan pangan tidak otomatis mensucikan kebijakan bila praktiknya merusak sunatullah, menyingkirkan rakyat, dan memindahkan risiko bencana kepada masyarakat.
Tanda-tanda Allah kini terlalu nyata untuk disangkal. Pertanyaannya bukan apakah tanda itu ada, melainkan apakah kita memilih terus menyangkalnya dengan kebebalan kolektif, menormalkan kerusakan, dan mengulang kesalahan. Jangan sampai bangsa ini berlari mengejar kepentingan sesaat sambil mengabaikan tanda-tanda yang jelas menuju kebinasaan.
Negeri ini tidak kekurangan kekayaan, namun seringkali kekurangan keberanian moral untuk berkata: yang salah harus dihentikan, yang benar harus ditegakkan, dan amanah harus dikembalikan pada tujuan hakikinya, yakni kesejahteraan rakyat dan keadilan yang memuliakan kehidupan. Dusta mungkin menang di panggung, namun ruang hisab tidak mengenal pencitraan. Rakyat boleh dibingungkan, alam tak bisa dibohongi, dan Allah tak bisa dikelabui. Jalan pulang dimulai dari kejujuran: pada data, pada dampak, pada amanah, dan pada korban.