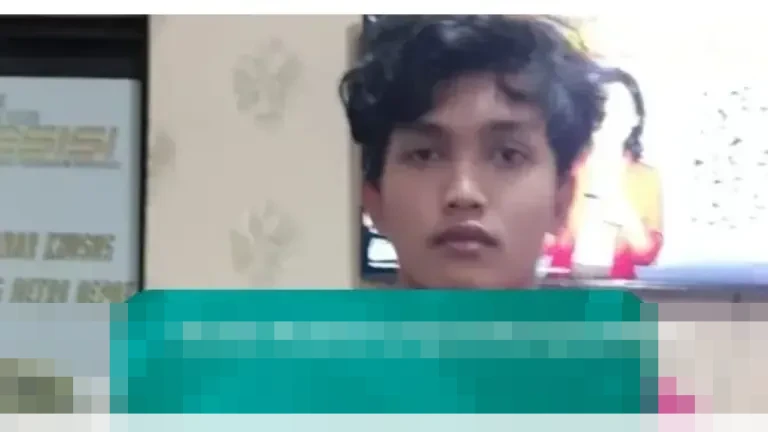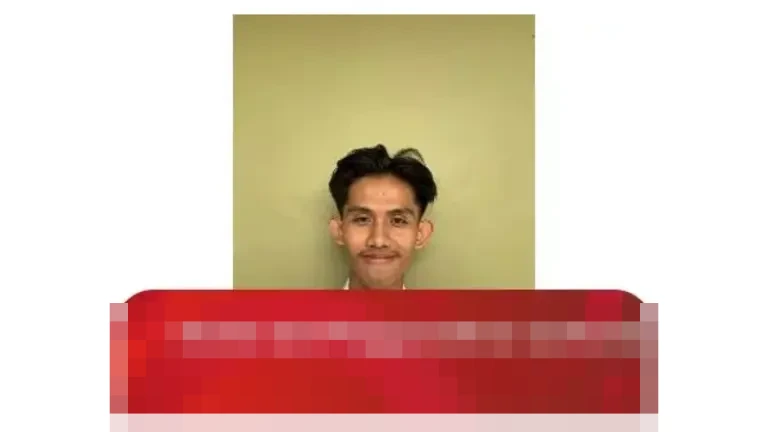Bagi banyak pihak, memenangkan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) seringkali dianggap sebagai puncak perjuangan hukum. Pencabutan izin tambang atau pembatalan izin usaha yang merusak lingkungan kerap dirayakan sebagai kemenangan mutlak.
Namun, di balik euforia tersebut, tersimpan sebuah realitas pahit yang kerap terabaikan: putusan PTUN seringkali hanya mampu “membatalkan kertas” berupa izin, namun gagal “memperbaiki tanah” atau memulihkan lingkungan yang telah rusak.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Pertanyaan krusial kemudian muncul: setelah izin dicabut dan operasional alat berat dihentikan, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab membiayai upaya pemulihan lingkungan yang terlanjur hancur?
Kasus konsesi tambang di Pulau Wawonii menjadi cerminan anomali ini. Ketika izin dibatalkan, perusahaan memang berhenti beroperasi, namun pemerintah tidak memperoleh dana apa pun untuk restorasi, sementara masyarakat tetap harus hidup di tengah sisa-sisa kerusakan alam. Inilah urgensi untuk mendorong evolusi dalam praktik hukum di Indonesia.
Tiga Refleksi Krusial untuk Keadilan Ekologis
Pertama, mengonkretkan prinsip “polluter pays” atau ‘pencemar membayar’ dalam amar putusan. Prinsip ini tidak boleh lagi sekadar menjadi jargon akademis, melainkan harus termanifestasi secara nyata dalam setiap putusan hakim.
Hakim PTUN perlu memiliki keberanian untuk mengeluarkan amar restitutif yang secara tegas mewajibkan Tergugat (Pemerintah) untuk menghukum badan usaha perusak lingkungan agar menyetorkan dana pemulihan ke kas negara melalui rekening khusus.
Kedua, memperluas petitum atau tuntutan oleh pihak penggugat. Kesadaran hukum masyarakat juga harus ditingkatkan. Penggugat tidak cukup hanya meminta pembatalan izin usaha, tetapi harus berani menambahkan petitum yang menuntut ganti rugi atas kerusakan alam yang secara langsung dirasakan oleh rakyat.
Tanpa petitum yang responsif terhadap kerusakan lingkungan, ruang gerak hakim akan terbatas dalam memberikan keadilan ekologis yang utuh.
Ketiga, sinergi kebijakan dan regulasi. Visi perubahan ini membutuhkan dukungan sistemik yang kuat. Kementerian Keuangan perlu segera melegalisasi pembentukan rekening khusus untuk pemulihan lingkungan.
Di sisi lain, Mahkamah Agung melalui Kamar Tata Usaha Negara perlu merumuskan Pleno Kamar yang memberikan ‘gigi’ atau daya paksa bagi putusan lingkungan. Tujuannya jelas: agar putusan memiliki kekuatan hukum yang memaksa pengusaha untuk memberikan kompensasi nyata atas rusaknya ruang hidup warga.
Efektivitas Jalur PTUN dan Kebutuhan Terobosan Hukum
Di tengah maraknya sengketa lingkungan hidup, efektivitas penegakan hukum kita perlu dievaluasi secara jujur. Selama ini, banyak yang menganggap jalur pidana atau perdata sebagai ‘senjata utama’ melawan perusak lingkungan.
Namun, realitasnya menunjukkan bahwa kedua jalur tersebut seringkali memakan waktu yang sangat lama, berbiaya mahal, dan proses pembuktiannya sangat rumit.
Dari perspektif lain, jalur Peradilan Administrasi (PTUN) sebenarnya menawarkan jalan yang lebih efektif. Mengapa? Karena hanya di PTUN instrumen kekuasaan negara berupa izin usaha dapat langsung ‘diputus urat nadinya’ atau dicabut jika terbukti merusak lingkungan.
Meski demikian, pencabutan izin saja tidaklah memadai. Kita membutuhkan terobosan hukum yang lebih berani dan komprehensif.
Para penggugat harus mulai melangkah lebih jauh dari sekadar meminta pembatalan ‘kertas’ izin. Hakim PTUN pun harus berani memposisikan diri sebagai ‘Penjaga Ekologi’.
Artinya, putusan tidak boleh berhenti pada pencabutan izin semata, tetapi harus dibarengi dengan perintah pemberian kompensasi untuk reboisasi dan pemulihan lingkungan secara menyeluruh.
Bayangkan jika setiap gugatan di PTUN menyertakan petitum ganti rugi atas kerusakan ruang hidup. Hal ini akan menciptakan efek jera ganda: izin usaha hilang, dan kewajiban memulihkan alam tetap melekat. Ini adalah cara paling konkret agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan atas hilangnya hak mereka terhadap lingkungan hidup yang sehat.
Sudah saatnya PTUN tidak lagi menjadi peradilan ‘kertas’ yang hanya mengurusi aspek prosedural administratif. Ia harus bertransformasi menjadi benteng terakhir yang memastikan bahwa setiap izin yang merusak alam akan berakhir dengan pemulihan, bukan sekadar pembiaran sisa-sisa kehancuran.
Sebab, hukum yang adil tidak hanya menghukum kesalahan di masa lalu, tetapi juga harus mampu menyembuhkan luka bumi untuk masa depan.