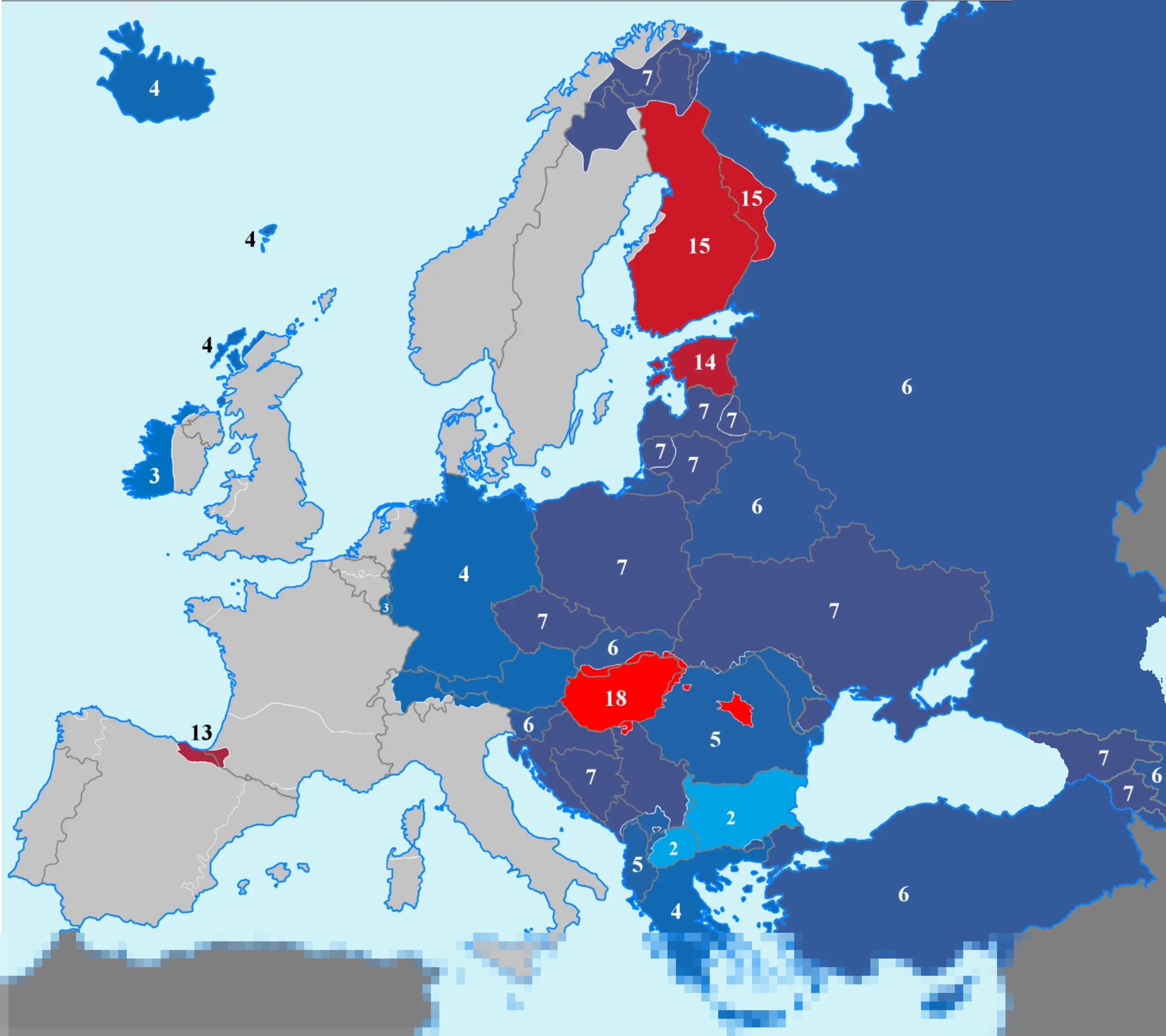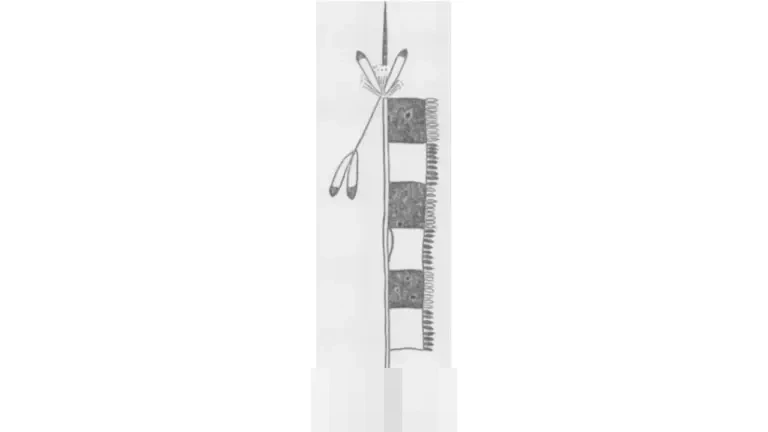Dunia kembali dihadapkan pada tontonan geopolitik yang mencengangkan. Penangkapan figur kunci di Venezuela oleh Amerika Serikat, dengan dalih “narkoterorisme”, bukan sekadar drama kriminal transnasional biasa. Peristiwa ini, yang terjadi pada Senin (5/1/2026) di New York, memicu analisis mendalam mengenai dinamika kekuasaan global.
Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, Probo Darono Yakti, dalam analisisnya di Detik pada Rabu (7/01/2026), secara tajam menyebut insiden ini sebagai manifestasi dari naked power politics, atau politik kekuasaan yang telanjang. Menurut Probo, narasi penegakan hukum yang dibangun Washington hanyalah lapisan legitimasi di balik perebutan kontrol atas cadangan minyak terbesar di dunia.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Tindakan unilateral Amerika Serikat yang menabrak kedaulatan negara lain tanpa mandat PBB ini, menurut Mureks, menegaskan bahwa hukum internasional saat ini tak lebih dari “catatan kaki” bagi kepentingan nasional negara adidaya. Fenomena ini sejalan dengan postulat bapak realisme politik, Hans Morgenthau, yang dalam karyanya Politics Among Nations menegaskan bahwa “kepentingan nasional didefinisikan dalam terminologi kekuasaan” (interest defined in terms of power). Ketika kepentingan vital, seperti keamanan energi, dipertaruhkan, prinsip moral dan hukum positif sering kali dikesampingkan.
Alarm Kedaulatan bagi Indonesia: Dari Minyak ke Nikel
Bagi Indonesia, apa yang terjadi di Caracas bukan sekadar berita mancanegara yang jauh. Ini adalah cermin retak yang memantulkan bayangan masa depan kita sendiri, sekaligus alarm keras bagi para pengambil kebijakan di Jakarta.
Jika Venezuela ditarget karena cadangan minyaknya, Indonesia harus mawas diri dengan posisi strategis sebagai raja nikel dan pemilik mineral kritis dunia. Kebijakan hilirisasi dan resource nationalism yang kini menjadi primadona ekonomi nasional adalah “pisau bermata dua”.
Di satu sisi, kebijakan ini meningkatkan nilai tambah ekonomi dan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya industri kendaraan listrik. Namun, di sisi lain, ia menempatkan Indonesia dalam radar bidikan kekuatan global yang merasa pasokannya terganggu atau dominasinya terancam.
Apa yang diulas Probo tentang Venezuela sejalan dengan Logika Melos yang dicatat sejarawan Thucydides dalam Perang Peloponnesia: “yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah menderita apa yang harus mereka terima”. Kita tidak boleh naif berpikir bahwa “niat baik” hilirisasi untuk kemakmuran rakyat akan selalu disambut karpet merah oleh dunia internasional.
Indonesia harus siap menghadapi era Lawfare, yakni penggunaan hukum sebagai senjata perang asimetris. Hari ini, Venezuela ditekan dengan dalih narkoba. Besok, bukan mustahil Indonesia ditekan dengan dalih isu lingkungan (ESG), standar perburuhan, atau hak asasi manusia yang dipolitisasi.
Isu-isu normatif ini sangat mudah “dikonstruksi” menjadi senjata diplomatik dan sanksi ekonomi untuk memaksa Indonesia membuka keran ekspor mentah atau menyerahkan pengelolaan aset strategis kepada pihak asing.
Ilusi Diplomasi Tanpa “Otot” Pertahanan
Pertanyaan kuncinya adalah, sanggupkah Indonesia menahan tekanan tersebut? Di sinilah letak relevansi pandangan realisme ofensif yang disodorkan John Mearsheimer. Ia menekankan bahwa dalam sistem internasional yang anarki, tidak ada “polisi dunia” yang benar-benar adil. Satu-satunya jaminan keamanan adalah kekuatan sendiri (self-help).
Kasus Venezuela memberikan pelajaran pahit tentang kegagalan deterrence (daya tangkal). Selama bertahun-tahun, Caracas mengumandangkan retorika anti-Barat yang keras. Namun, retorika itu terbukti keropos. Kegagalan Venezuela mendeteksi operasi asing dan mencegah infiltrasi menunjukkan lubang besar dalam kemampuan intelijen dan pertahanan mereka.
Bagi Indonesia, ini adalah sinyal merah. Doktrin diplomasi “Bebas Aktif” tidak bisa berdiri di ruang hampa. Diplomat Indonesia di meja perundingan membutuhkan dukungan kekuatan (hard power) yang kredibel. Tanpa postur pertahanan yang disegani, seperti Angkatan Laut yang mampu mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Angkatan Udara yang menguasai langit, kedaulatan sumber daya alam hanyalah klaim di atas kertas yang rentan disobek.
Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) mahal semata. Belajar dari Venezuela, yang juga memiliki jet tempur canggih buatan Rusia namun tetap tak berdaya, Indonesia membutuhkan pembangunan kapabilitas intelijen yang mumpuni untuk mendeteksi ancaman hibrida. Pertahanan harus mampu mengantisipasi operasi klandestin yang bertujuan mendestabilisasi keamanan dalam negeri sebagai pintu masuk intervensi asing.
Realisme Menghadapi Rimba Global
Apa yang terjadi di Venezuela adalah wake-up call. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tatanan berbasis aturan (rules-based order) yang selama ini dipercaya perlahan sekarat, digantikan oleh logika rimba di mana kekuatan menentukan kebenaran.
Indonesia tidak boleh menjadi pihak yang “menderita” dalam logika Thucydides tersebut. Mempertahankan kedaulatan nikel dan masa depan ekonomi bangsa membutuhkan sinergi total: diplomasi yang cerdik, ekonomi yang mandiri, dan militer yang bertaring.
Kolaborasi sipil-militer harus diarahkan untuk melindungi aset strategis bangsa dari segala bentuk intervensi, baik yang berwujud serbuan militer maupun yang berkedok penegakan hukum internasional.
Pepatah kuno si vis pacem, para bellum (jika mendambakan damai, bersiaplah untuk perang) kini menemukan konteks barunya. Jika ingin berdaulat secara ekonomi, Indonesia juga harus siap secara militer. Karena dalam politik kekuasaan global yang telanjang, kelemahan adalah undangan terbuka bagi agresi.