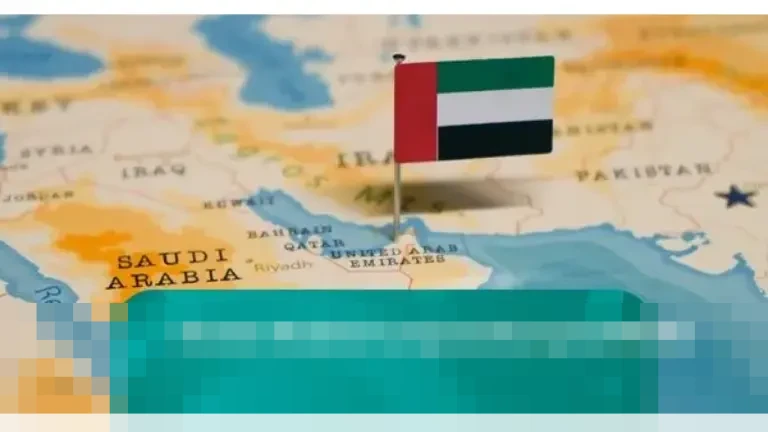Dunia pendidikan tinggi Indonesia kini menghadapi ironi besar. Di tengah gencar-gencarnya pemerintah mendorong universitas meraih predikat kelas dunia (World Class University), fondasi utamanya, yakni para dosen, justru berjuang di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) demi menuntut hak paling dasar: upah yang layak.
Gugatan yang diajukan oleh Serikat Pekerja Kampus (SPK) terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen serta UU Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan sekadar urusan domestik akademisi. Lebih dari itu, gugatan ini mencerminkan retaknya komitmen negara terhadap pembangunan sumber daya manusia.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Bayangkan seorang magister hingga doktor yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menempuh pendidikan, namun setiap akhir bulan harus memutar otak hanya untuk membayar tagihan listrik atau sekadar membeli susu anak. Ini bukan cerita fiksi, melainkan realitas pahit yang dialami banyak dosen di Indonesia.
Kini, melalui SPK, para penjaga gawang intelektual bangsa ini akhirnya “turun gunung”. Mereka melayangkan gugatan judicial review ke MK dengan tuntutan sederhana namun fundamental: Dosen berhak sejahtera.
Gaji Dosen Indonesia: Kalah Jauh dari Negara Tetangga
Selama ini, profesi dosen selalu dibalut dengan narasi “pengabdian”. Namun, narasi ini sering kali disalahgunakan untuk melanggengkan upah rendah. Jika menengok ke negara tetangga, data perbandingan gaji dosen sangat menyedihkan bagi Indonesia.
Akar masalah ini terletak pada ketidaksinkronan regulasi yang menjerat kesejahteraan dosen dalam ketidakpastian hukum. Secara regional, posisi dosen Indonesia berada pada titik yang mengkhawatirkan. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa gaji dosen di Indonesia merupakan yang paling terendah di Asia Tenggara.
Di saat dosen di Malaysia bisa membawa pulang gaji rata-rata Rp18 juta hingga Rp25 juta per bulan, atau di Singapura yang mencapai angka ratusan juta rupiah, banyak dosen di Indonesia, terutama dosen muda dan dosen swasta, yang take home pay-nya masih tertahan di angka Rp2 juta, bahkan ada yang lebih rendah. Angka ini bahkan lebih rendah dari gaji buruh pabrik di wilayah industri tertentu yang sudah memiliki standar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang jelas.
Diskriminasi Status dan “Kasta” Akademik
Gugatan SPK ke MK bukan tanpa alasan hukum yang kuat. Ada beberapa pasal dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang selama ini hanya menjadi “macan kertas” atau aturan yang indah di atas kertas tapi nol dalam implementasi:
- Pasal 14 ayat (1) huruf a: Menyatakan dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- Pasal 15 ayat (1): Menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.
Namun, dalam praktiknya, frasa “di atas kebutuhan hidup minimum” tidak pernah memiliki standar baku yang mengikat secara nasional. Akibatnya, banyak perguruan tinggi memberikan gaji pokok yang bahkan berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR). SPK menilai tidak adanya standar upah minimum khusus dosen nasional menciptakan ruang eksploitasi yang dilegalkan oleh kekosongan hukum.
Lebih jauh lagi, gugatan ini menyoal Pasal 51 UU Guru dan Dosen yang sering kali terbentur dengan implementasi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Terjadi stratifikasi sosial yang tajam antara dosen ASN dan dosen tetap yayasan (swasta). Dosen swasta sering kali memikul beban Tri Dharma yang sama beratnya, namun tanpa perlindungan jaminan hari tua atau tunjangan fungsional yang setara dengan rekan mereka di sektor negeri.
Ketiadaan perlindungan upah yang seragam ini membuat dosen di Indonesia terjebak dalam “kemiskinan struktural”. Bagaimana mungkin seorang dosen bisa fokus melakukan riset mendalam atau menulis di jurnal internasional bereputasi jika ia harus “nyambi” mengajar di banyak tempat demi menutupi biaya dapur?
Dampak Buruk “Dosen Nyambi”
Dampak dari upah rendah ini sangat sistemik. Ketika gaji pokok tidak cukup untuk hidup sebulan, dosen terpaksa melakukan “kerja sampingan”. Ada yang mengajar di banyak kampus sekaligus (taxi driver professor), menjadi konsultan proyek, atau bahkan melakukan pekerjaan di luar bidang akademik.
Akibatnya, kualitas riset menurun, inovasi terhambat, dan mahasiswa kehilangan waktu bimbingan yang berkualitas. Bagaimana kita bisa bermimpi memiliki universitas kelas dunia jika pengajarnya masih sibuk memikirkan cara menyambung hidup dari hari ke hari?
Gugatan SPK ke MK adalah pengingat bahwa janji “mencerdaskan kehidupan bangsa” tidak bisa dilakukan melalui praktik yang tidak adil. Kesejahteraan dosen adalah prasyarat bagi kemandirian bangsa. Jika negara terus abai terhadap tafsir pasal-pasal kesejahteraan ini, maka mimpi Indonesia Emas 2045 hanyalah akan menjadi bangunan megah di atas fondasi yang rapuh.
Mendukung gugatan ini bukan berarti memanjakan kaum intelektual, melainkan bentuk investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dosen yang sejahtera adalah prasyarat mutlak bagi Indonesia yang cerdas dan kompetitif di kancah global. Saatnya kita berhenti menormalisasi kemiskinan di balik jubah akademik.