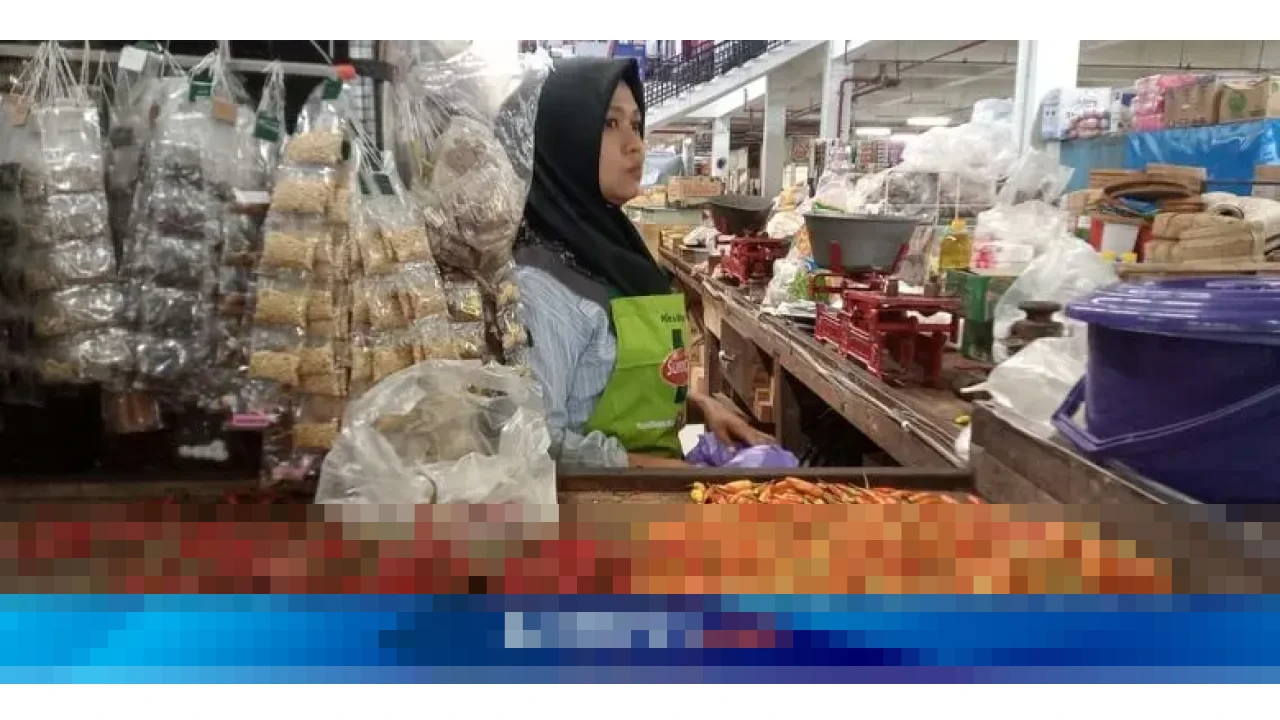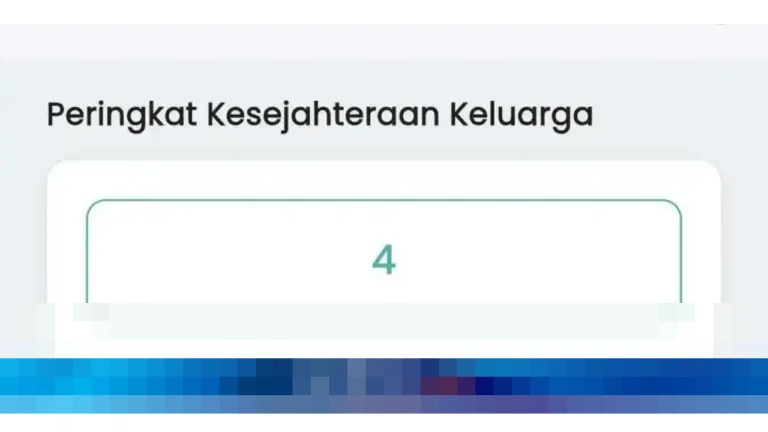Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 109,92. Angka ini, dalam kerangka inflation targeting framework, lazim dianggap optimal bagi stabilitas makroekonomi karena mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga, sebagaimana diungkapkan Mishkin (2018).
Secara statistik, kondisi ini mengindikasikan tekanan harga masih terkendali dan risiko ketidakpastian makro relatif rendah. Namun, bagi banyak rumah tangga, persepsi kesejahteraan tidak selalu sejalan dengan angka resmi. Dalam perspektif subjective well-being economics, kesejahteraan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh indikator makro, melainkan oleh pengalaman konsumsi harian dan tekanan biaya hidup yang dirasakan langsung, menurut Stiglitz, Sen, & Fitoussi (2009).
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar: mengapa belanja harian tetap terasa berat meskipun inflasi dinyatakan aman? Teori cost of living approach menjelaskan bahwa kenaikan kecil pada harga barang esensial dapat menimbulkan tekanan kesejahteraan yang besar, terutama bagi rumah tangga dengan elastisitas pendapatan rendah (Deaton, 1997). Inflasi 2,92 persen ini perlu dibaca sebagai fenomena sosial-ekonomi, bukan semata angka agregat.
Inflasi Terkendali: Antara Teori dan Realitas Rumah Tangga
Dalam teori makroekonomi Keynesian dan New Keynesian Economics, inflasi moderat pada kisaran 2–3 persen dipandang sebagai kondisi ideal karena menjaga ekspektasi inflasi tetap stabil sekaligus mendorong aktivitas ekonomi (Gali, 2015). Inflasi yang terlalu rendah berisiko memicu deflationary trap, sementara inflasi tinggi menciptakan distorsi harga dan ketidakpastian investasi.
Dari sisi kebijakan moneter, inflasi 2,92 persen mencerminkan keberhasilan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga price stability sebagai nominal anchor perekonomian (Blanchard, 2021). Stabilitas ini penting karena ekspektasi inflasi yang terjaga akan memengaruhi keputusan konsumsi, tabungan, dan investasi masyarakat. Namun demikian, teori macro–micro disconnect menegaskan bahwa stabilitas pada level agregat tidak selalu menjamin kenyamanan pada level rumah tangga (Banerjee & Duflo, 2011).
Inflasi yang tampak terkendali secara nasional dapat dirasakan berbeda oleh kelompok masyarakat dengan struktur pengeluaran yang tidak sama. Mureks mencatat bahwa perbedaan ini sering kali menjadi sumber utama ketidakpuasan publik terhadap data ekonomi makro.
Membaca IHK 109,92: Dari Meja Makan hingga Ongkos Harian
IHK 109,92 menunjukkan bahwa secara kumulatif harga barang dan jasa telah meningkat sekitar 9,92 persen dibandingkan tahun dasar. Konsep IHK sendiri dibangun atas pendekatan fixed basket index, yang merepresentasikan rata-rata pola konsumsi nasional (ILO, IMF, OECD, 2020). Tantangannya, rata-rata nasional sering kali menyamarkan variasi antar kelompok pendapatan.
Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, porsi belanja pangan dan energi sangat dominan. Dalam teori inflation inequality, inflasi memiliki dampak distribusional karena kelompok miskin lebih terekspos pada kenaikan harga barang esensial dibandingkan kelompok kaya (Kaplan, Moll, & Violante, 2018). Akibatnya, inflasi yang sama secara statistik dapat terasa jauh lebih berat secara sosial.
Ketika inflasi didorong oleh komoditas kebutuhan pokok, persepsi “hidup makin mahal” muncul meskipun inflasi headline masih rendah. Hal ini sejalan dengan konsep salience effect dalam ekonomi perilaku, di mana konsumen lebih mengingat dan merespons harga yang sering mereka temui dibandingkan indeks rata-rata (Shiller, 2017).
Daya Beli: Ketika Angka Aman Bertemu Realitas Upah
Inflasi 2,92 persen akan terasa ringan apabila pertumbuhan pendapatan riil melampaui inflasi. Teori real income hypothesis menjelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi ditentukan oleh selisih antara pendapatan nominal dan laju inflasi (Mankiw, 2021). Ketika upah tumbuh lambat atau stagnan, inflasi rendah sekalipun tetap menggerus daya beli.
Dari perspektif ekonomi perilaku, persepsi inflasi sangat dipengaruhi oleh harga kebutuhan primer seperti pangan, transportasi, dan pendidikan, bukan oleh indeks statistik agregat (Akerlof & Shiller, 2015). Jika harga-harga tersebut meningkat, kepercayaan konsumen cenderung melemah dan konsumsi tertahan, meskipun indikator makro menunjukkan stabilitas.
Karena itu, teori inclusive growth menekankan bahwa pengendalian inflasi harus diiringi kebijakan pendukung, seperti penciptaan lapangan kerja produktif, penyesuaian upah yang adaptif terhadap produktivitas, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran (OECD, 2019). Tanpa kombinasi ini, inflasi terkendali berisiko menjadi sekadar keberhasilan teknokratis.
Mengapa Inflasi Aman Tetap Perlu Diwaspadai?
Inflasi 2,92 persen bukan alasan untuk berpuas diri. Dalam kerangka welfare economics, stabilitas harga adalah prasyarat, bukan tujuan akhir pembangunan ekonomi (Stiglitz, 2012). Inflasi yang sehat seharusnya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan nyata dan penurunan kerentanan ekonomi.
Bagi masyarakat, inflasi stabil memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan jangka menengah. Bagi dunia usaha, ia menciptakan iklim investasi yang lebih terprediksi. Namun manfaat ini hanya akan optimal apabila pertumbuhan pendapatan riil dirasakan secara luas, bukan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Inflasi 2,92 persen memang angka yang aman. Tetapi rasa hidup yang lebih ringan ditentukan oleh seberapa bersahabat harga dengan pendapatan. Di situlah pekerjaan rumah kebijakan sesungguhnya berada: memastikan stabilitas statistik bertransformasi menjadi kenyamanan ekonomi sehari-hari, karena bagi masyarakat, ekonomi yang sehat bukan hanya inflasi rendah, melainkan rasa cukup yang nyata dari bulan ke bulan.