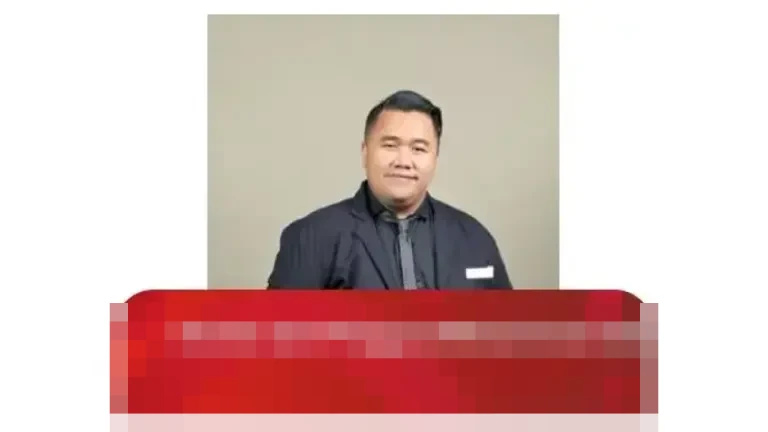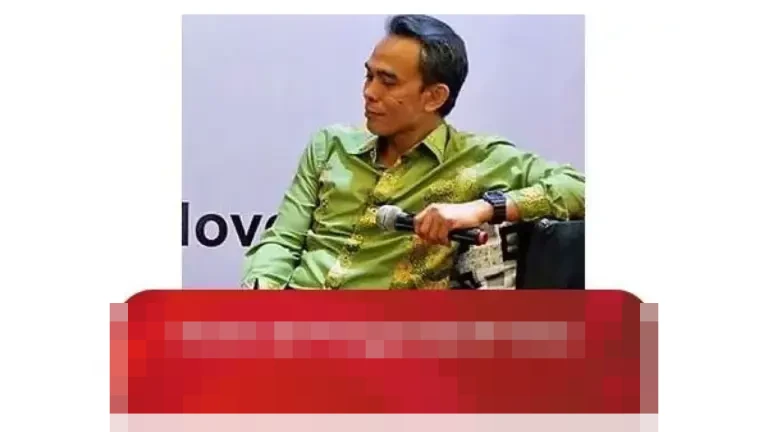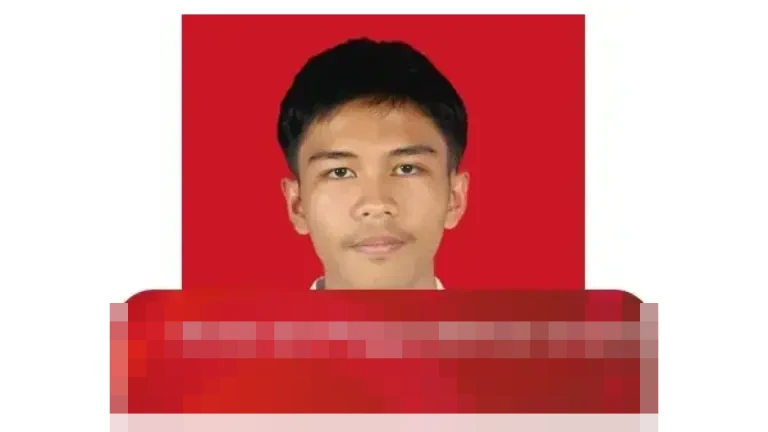Sejumlah dosen melayangkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah hukum ini bukan sekadar menuntut kepastian penghasilan yang layak, melainkan juga membuka kembali perdebatan mengenai krisis makna profesi dosen dalam lanskap pendidikan nasional.
Dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UU Guru dan Dosen, secara normatif disebutkan bahwa dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial. Namun, menurut pantauan Mureks, frasa “di atas kebutuhan hidup minimum” menjadi pangkal persoalan.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Ketidakjelasan indikator operasional serta absennya mekanisme pengawasan yang tegas atas frasa tersebut membuka ruang tafsir yang sangat luas. Dalam praktiknya, kondisi ini kerap merugikan para dosen, khususnya mereka yang mengabdi di perguruan tinggi swasta.
Jarak Wacana dan Realitas
Dari perspektif komunikasi, situasi ini menyoroti jurang lebar antara wacana normatif yang dibangun negara dan realitas material yang dialami para profesional pendidikan. Negara kerap memproduksi narasi bahwa dosen adalah profesi terhormat dan sejahtera.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan banyak dosen menerima penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), dibebani tugas tridarma yang berat, dan tetap dituntut memenuhi standar kinerja akademik yang tinggi. Ketika kebijakan tidak selaras dengan realitas sosial, legitimasi sistem pendidikan pun dipertanyakan.
Peran media dan diskursus publik juga turut memperkeruh masalah ini. Dosen sering kali direpresentasikan sebagai figur idealis, pekerja pengabdian, atau bahkan pelaku “panggilan jiwa”.
Representasi semacam ini, meski bernilai moral, berisiko menormalisasi kerentanan ekonomi yang mereka hadapi. Mureks mencatat bahwa dengan membingkai dosen sebagai simbol pengabdian, pembahasan mengenai hak ekonomi, relasi kerja yang adil, dan perlindungan profesional menjadi terpinggirkan. Dalam kajian komunikasi kritis, kondisi ini dapat dipahami sebagai romantisasi simbolik yang menutupi persoalan struktural.
Gugatan sebagai Titik Balik
Gugatan ke Mahkamah Konstitusi menjadi titik balik krusial. Ini menggeser posisi dosen dari sekadar subjek moral menjadi subjek hukum.
Dosen kini tidak lagi hanya diposisikan sebagai pendidik yang harus berkorban, melainkan sebagai warga negara yang menuntut kepastian hak konstitusionalnya. Langkah ini sekaligus menyingkap kontradiksi dalam wacana pendidikan nasional, di mana pendidikan selalu disebut sebagai investasi masa depan bangsa, tetapi aktor utamanya justru diperlakukan sebagai beban biaya.
Dalam perspektif ekonomi politik komunikasi, bahasa kebijakan yang termuat dalam undang-undang seringkali berfungsi menciptakan kesan keberpihakan tanpa jaminan implementasi konkret. Istilah normatif seperti “kesejahteraan” dan “penghasilan layak” lebih bekerja sebagai retorika legitimasi, bukan sebagai instrumen keadilan yang nyata.
Akibatnya, dosen terpaksa membuktikan hak hidup layaknya melalui jalur hukum, sebuah kondisi yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem pendidikan yang sehat dan berpihak.
Pada akhirnya, gugatan ini melampaui sekadar putusan Mahkamah Konstitusi. Ini adalah momen reflektif bagi bangsa untuk meninjau ulang bagaimana profesi dosen dimaknai.
Apakah dosen diposisikan sebagai aset intelektual yang harus dijaga keberlanjutannya, atau hanya sebagai simbol retoris dalam pidato tentang kemajuan pendidikan? Selama pertanyaan fundamental ini belum terjawab secara konsisten dalam kebijakan dan praktik, krisis makna profesi dosen akan terus berulang.