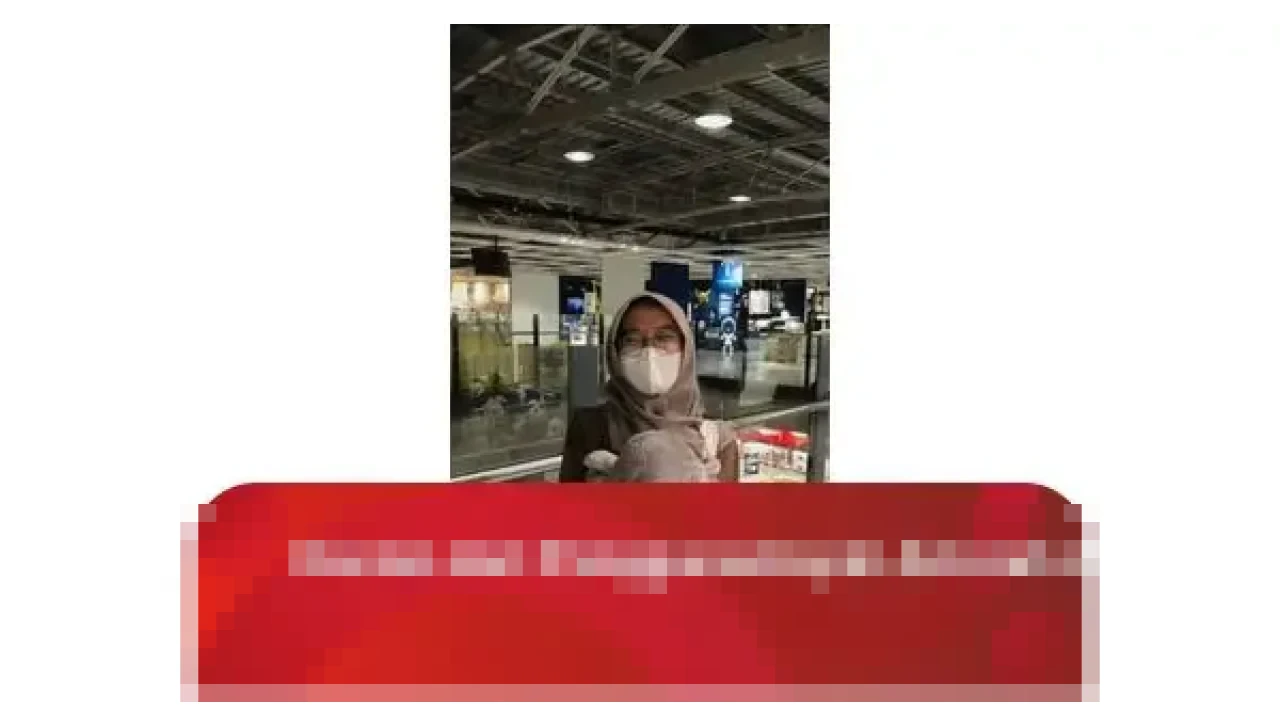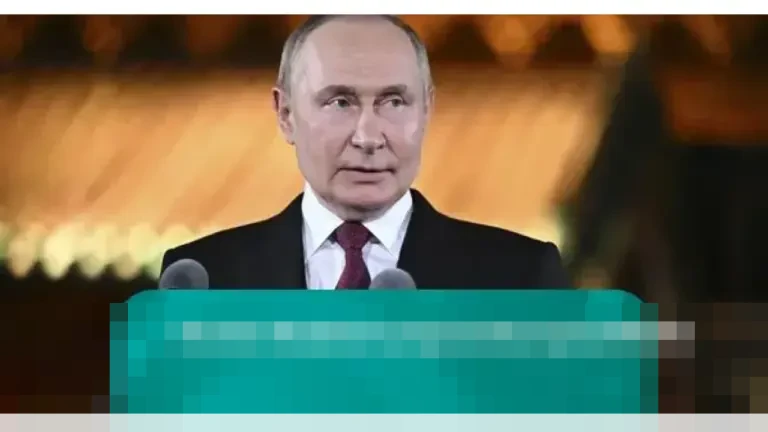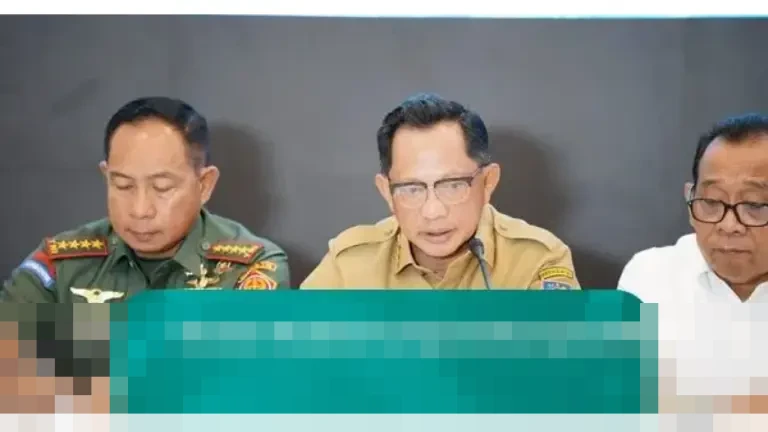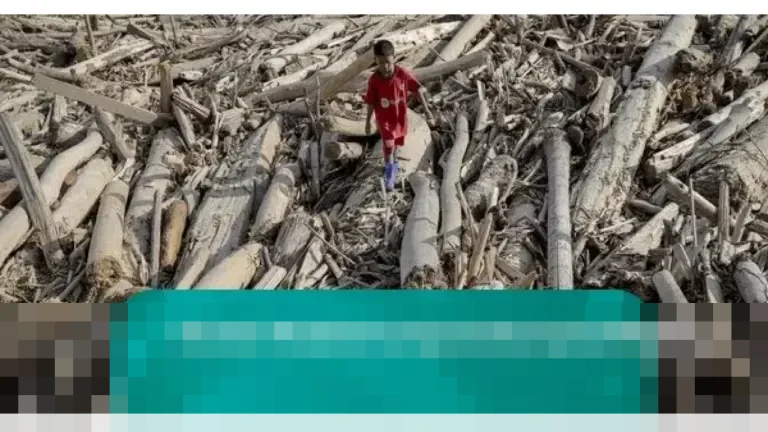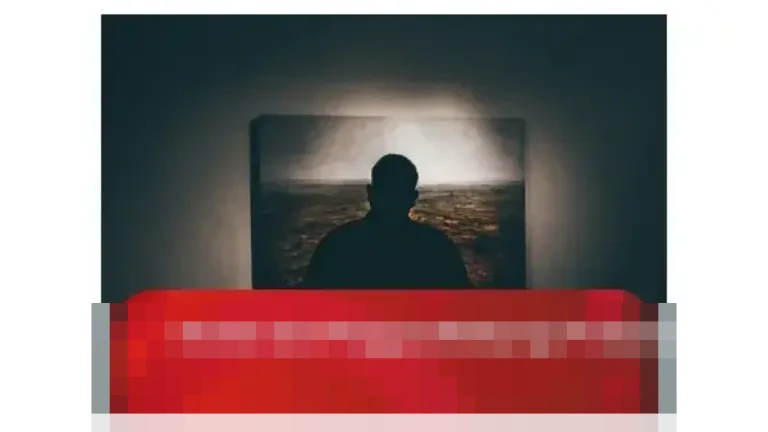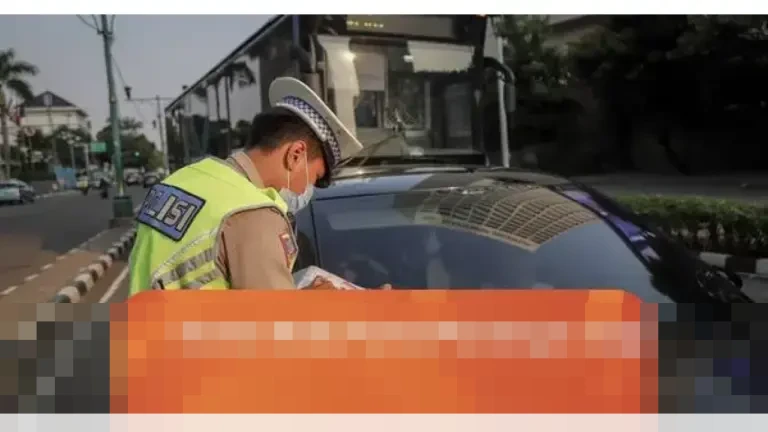Kekerasan sering kali digambarkan sebagai tindakan fisik yang brutal, melibatkan pukulan, senjata, atau api. Namun, dua cerpen Indonesia, “Bagaimana Saya Bertemu Orang yang Telah Saya Eksekusi” karya Era Ari Astanto dan “Merebut Tanah” karya I Putu Supartika, menawarkan perspektif berbeda. Keduanya menunjukkan bahwa kekerasan dapat bekerja secara lebih rapi, tersembunyi, bahkan dianggap wajar dalam masyarakat.
Analisis ini menggunakan teori kuasa dan disiplin dari filsuf Michel Foucault. Menurut Foucault, kuasa tidak hanya dijalankan melalui paksaan fisik. Sebaliknya, kuasa juga bekerja melalui aturan, prosedur, dan sistem yang secara halus membentuk cara berpikir serta perilaku manusia. Individu menjadi patuh bukan karena ancaman langsung, melainkan karena merasa bahwa kepatuhan tersebut adalah hal yang normal dan semestinya.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Kuasa Negara dalam Eksekusi yang Steril
Dalam cerpen “Bagaimana Saya Bertemu Orang yang Telah Saya Eksekusi”, pembaca diajak menyelami dunia seorang eksekutor negara. Tokoh “saya” digambarkan menjalankan tugas hukuman mati dengan rapi dan tanpa banyak pertanyaan. Proses eksekusi disajikan sebagai prosedur teknis yang steril, seolah-olah nyawa manusia hanyalah bagian dari administrasi yang harus diselesaikan.
Melalui lensa Foucault, negara dalam cerpen ini tidak perlu terus-menerus menunjukkan kekerasan secara terbuka. Kuasa negara bekerja melalui disiplin yang terinternalisasi, seperti seragam, protokol, bahasa birokrasi, dan sistem hukum yang baku. Tokoh eksekutor, dalam konteks ini, bukan hanya pelaku kekerasan, melainkan juga korban dari sistem disiplin tersebut. Ia kehilangan ruang untuk berpikir secara moral karena telah dibentuk menjadi alat yang taat. Krisis batin baru muncul ketika ia bertemu kembali dengan orang-orang yang secara administratif telah ia eksekusi, membuka celah bahwa sistem yang terlihat rapi ternyata menyimpan manipulasi dan kebohongan.
Kuasa Adat dalam Perebutan Tanah
Sementara itu, cerpen “Merebut Tanah” menghadirkan bentuk kuasa yang berbeda, yakni kuasa adat. Sudarma berhadapan dengan kekuatan adat yang mengklaim tanah warisan keluarganya. Meskipun ia memenangkan kasus tersebut secara hukum negara, keputusan ini justru memicu amarah komunitas adat. Kekerasan tidak langsung muncul dari individu tertentu, melainkan dari massa yang bergerak atas nama tradisi dan kehormatan bersama.
Dari perspektif Foucault, adat dalam cerpen ini berfungsi sebagai sistem kuasa yang menormalisasi kepatuhan. Warga desa sejak lama telah didisiplinkan untuk percaya bahwa melawan adat adalah kesalahan besar. Oleh karena itu, kekerasan yang dilakukan terhadap Sudarma tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, melainkan sebagai pembelaan terhadap nilai kolektif. Kuasa bekerja melalui rasa takut, tekanan sosial, dan pengawasan komunitas, bukan semata-mata melalui hukum tertulis.
Persamaan Kuasa Negara dan Adat
Jika dibandingkan, negara dalam cerpen pertama dan adat dalam cerpen kedua tampak berbeda, namun keduanya memiliki cara kerja yang mirip. Keduanya menciptakan sistem yang mengatur tubuh, pikiran, dan pilihan individu. Negara melakukannya melalui hukum dan birokrasi, sedangkan adat melakukannya melalui norma dan solidaritas kolektif. Dalam dua konteks tersebut, individu sama-sama kehilangan kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri.
Melalui dua cerpen ini, pembaca dapat menyadari bahwa kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar. Justru kekerasan yang paling kuat sering kali bekerja secara halus, tersembunyi, dan dilegitimasi oleh sistem yang dianggap sah. Dengan pendekatan Michel Foucault, kedua cerpen ini memperlihatkan bagaimana kuasa dapat merampas kemanusiaan tanpa harus selalu menumpahkan darah secara langsung.