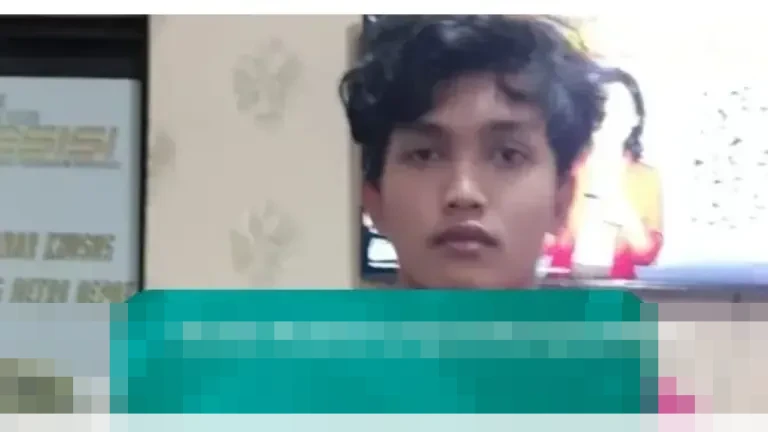Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah selalu menempatkan anak-anak sebagai prioritas utama. Di hadapan masa depan bangsa, setiap kebijakan yang menyentuh gizi anak-anak seolah otomatis dianggap suci. Oleh karena itu, saat MBG diumumkan, publik diminta untuk menanggalkan segala kecurigaan sejak awal, sebab ini adalah tentang gizi dan anak-anak.
Namun, realitas kehidupan sehari-hari memiliki kebiasaan buruk: ia gemar menghitung. Di meja makan masyarakat, seporsi nasi, sebutir telur, sayur bening, dan lauk sederhana jarang mencapai angka Rp10.000. Apalagi jika hidangan tersebut dimasak dalam skala ribuan porsi, dengan bahan baku grosir dan menu yang diseragamkan. Maka, ketika negara menyebut angka Rp10.000 per porsi, publik tidak sedang mencurigai niat, melainkan sedang mengingat harga pasar yang lebih realistis.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Dapur MBG dan Klaim “At Cost”
Dapur MBG secara resmi disebut bekerja dengan prinsip at cost, yang berarti tidak mencari keuntungan, hanya mengganti biaya operasional. Frasa ini terdengar bersih, layaknya laporan keuangan yang dicetak rapi. Akan tetapi, istilah at cost hanya akan bermakna jika operasional dapur tersebut transparan. Jika tidak, frasa itu dapat berubah menjadi mantra administratif yang sah, namun tidak sepenuhnya meyakinkan publik.
Dalam praktiknya, biaya selalu lentur. Biaya dapat ditekan, menu bisa disederhanakan, dan kualitas dapat dinegosiasikan. Setiap rupiah yang tidak masuk ke piring anak-anak akan dicatat sebagai efisiensi. Negara mungkin menyebutnya keberhasilan, sementara publik melihatnya sebagai sisa, dan dapur menganggapnya sebagai napas usaha.
Operasional Saat Libur Sekolah: Pertanyaan Publik
Secara hukum, tidak ada yang salah dengan mekanisme tersebut. Namun, masalah muncul pada suasana yang terbentuk. Ketika program MBG tetap berjalan saat libur sekolah, ketika dapur tetap beroperasi meskipun anak-anak tidak sedang belajar, publik mulai membaca tanda-tanda lain. Seolah-olah program ini tidak boleh berhenti, bukan semata-mata karena anak-anak lapar, melainkan karena ada ekosistem yang tidak bisa kehilangan arus dana, bahkan untuk sehari.
Pada titik ini, dapur tidak lagi terlihat sebagai pelaksana kebijakan sosial, melainkan sebagai unit produksi yang harus terus menyala. Api kompor menjadi simbol keberlanjutan program; jika kompor padam, grafik anggaran pun ikut turun.
Padahal, yang dipersoalkan publik bukanlah keuntungan itu sendiri. Dalam kehidupan normal, setiap kerja layak dibayar. Tukang masak bukanlah malaikat, dan dapur bukan tempat pertapaan. Yang menjadi persoalan adalah ketika keuntungan tersebut disembunyikan di balik bahasa pengabdian. Anak-anak dijadikan wajah depan, dapur bekerja di belakang layar, dan negara berdiri di tengah, berharap semua orang cukup terharu untuk tidak bertanya.
Masyarakat saat ini tidak hanya kenyang nasi, tetapi juga kenyang slogan. Mereka memahami bahwa kebijakan sosial modern sering dijalankan dengan logika proyek, lengkap dengan target, serapan anggaran, dan laporan. Dalam setiap proyek, selalu ada pihak yang akan merugi jika proyek tersebut berhenti.
Maka, prasangka pun lahir, bukan karena masyarakat jahat, melainkan karena sistemnya ambigu. Jika memang dapur memperoleh selisih dari efisiensi, sebaiknya hal itu diungkapkan. Jika ada batas margin keuntungan, bukalah informasi tersebut. Jika kualitas makanan dijaga, perlihatkan standarnya. Kebijakan sosial tidak akan runtuh oleh kejujuran, justru sebaliknya, ia akan runtuh oleh kepura-puraan.
Kepercayaan Publik dan Transparansi
Sebab, publik tidak menuntut negara untuk berhenti memberi makan anak-anak. Mereka hanya ingin tahu: apakah yang benar-benar dijaga itu adalah gizi anak, atau keberlanjutan operasional dapur?
Dalam masyarakat yang semakin terdidik, pertanyaan semacam ini tidak bisa lagi dijawab hanya dengan niat baik semata. Niat baik yang tidak transparan akan selalu kalah oleh satu hal sederhana: hitungan kasar di kepala orang-orang yang terbiasa berbelanja harian. Di sanalah negara diuji, bukan pada programnya, tetapi pada keberaniannya berkata jujur tentang bagaimana program itu bekerja. Karena pada akhirnya, anak-anak memang perlu makan, tetapi kepercayaan publik juga perlu diberi asupan yang layak.