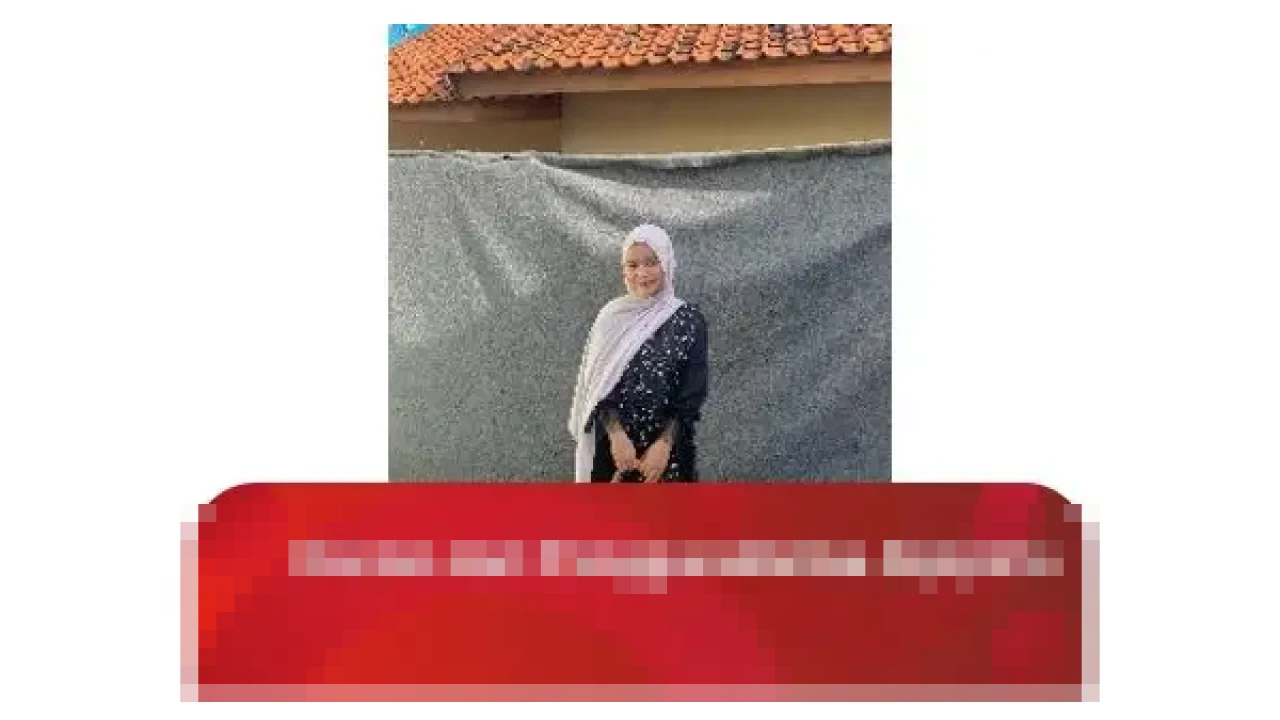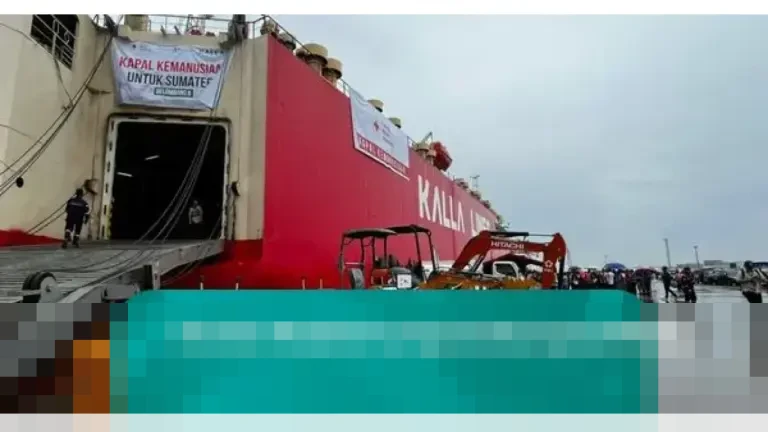Suasana belajar di ruang kelas sekolah dasar (SD) belakangan ini menyisakan sebuah keganjilan. Banyak anak terlihat sangat berhati-hati dalam bersikap, ragu mengangkat tangan, menjawab dengan suara pelan, dan sering memilih diam meskipun memiliki pendapat. Kesalahan kecil seolah menjadi sesuatu yang harus dihindari, bukan bagian dari proses belajar. Padahal, sekolah dasar seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak untuk mencoba dan keliru.
Ketakutan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Mureks mencatat bahwa fenomena ini tumbuh dari kebiasaan yang terus berulang di ruang kelas. Kesalahan sering kali langsung dikoreksi tanpa memberi ruang bagi anak untuk menjelaskan cara berpikirnya. Jawaban salah segera dibenarkan, sementara jawaban benar diberi pujian. Dari situ, anak belajar bahwa yang dihargai bukan proses memahami, melainkan hasil akhir yang tepat. Perlahan, anak mulai menyesuaikan diri dengan cara belajar yang aman: diam, mengikuti, dan tidak mengambil risiko.
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai peran sekolah dasar sebagai ruang belajar yang ramah bagi anak. Anak SD berada pada fase paling wajar untuk melakukan kesalahan. Mereka masih membangun logika, mengenal pola, dan belajar memahami dunia di sekitarnya. Namun, tekanan untuk selalu benar membuat proses belajar terasa kaku dan menegangkan, bahkan sejak usia yang seharusnya dipenuhi rasa ingin tahu dan eksplorasi.
Tekanan untuk “bisa” sejak dini juga mendorong anak lebih mengandalkan hafalan daripada pemahaman. Anak belajar agar tidak salah, bukan agar benar-benar mengerti. Keberanian untuk mencoba perlahan menghilang, tergantikan oleh keinginan untuk aman di hadapan guru dan teman. Dalam kondisi seperti ini, bertanya menjadi risiko, dan diam terasa sebagai pilihan paling selamat.
Yang lebih mengkhawatirkan, rasa takut ini kerap dianggap sebagai kurang percaya diri bawaan anak. Padahal, ketakutan tersebut lebih tepat dipahami sebagai respons terhadap lingkungan belajar yang tidak memberi ruang aman. Anak-anak ini bukan tidak mampu, melainkan terbiasa menahan diri karena kesalahan sering dikaitkan dengan rasa malu atau penilaian negatif. Mereka belajar sejak awal bahwa tampil “aman” lebih penting daripada berpikir jujur.
Orang dewasa, baik guru maupun orang tua, sering kali tanpa sadar memperkuat situasi ini. Pertanyaan anak yang dianggap sepele dijawab singkat. Jawaban keliru langsung dibetulkan tanpa dialog. Proses berpikir anak jarang diberi waktu. Niatnya mungkin agar anak cepat paham, tetapi dampaknya justru membuat anak ragu pada pikirannya sendiri dan enggan mencoba di kemudian hari.
Dampak dari kondisi ini tidak berhenti di bangku sekolah dasar. Anak yang terbiasa takut salah akan membawa sikap itu ke jenjang berikutnya. Mereka tumbuh menjadi siswa yang pasif, enggan berpendapat, dan takut mengambil keputusan. Ketika dewasa, mereka sering dinilai kurang berani atau kurang kritis, tanpa pernah menelusuri akar masalahnya pada pengalaman belajar paling awal.
Jika sejak sekolah dasar anak sudah terbiasa menahan pendapat dan takut keliru, maka sekolah kehilangan salah satu perannya yang paling penting: membantu anak mengenal cara berpikirnya sendiri. Pendidikan lalu berubah menjadi latihan kepatuhan, bukan proses pertumbuhan. Sekolah dasar seharusnya menjadi tempat pertama di mana anak memahami bahwa salah bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian alami dari proses belajar yang manusiawi.