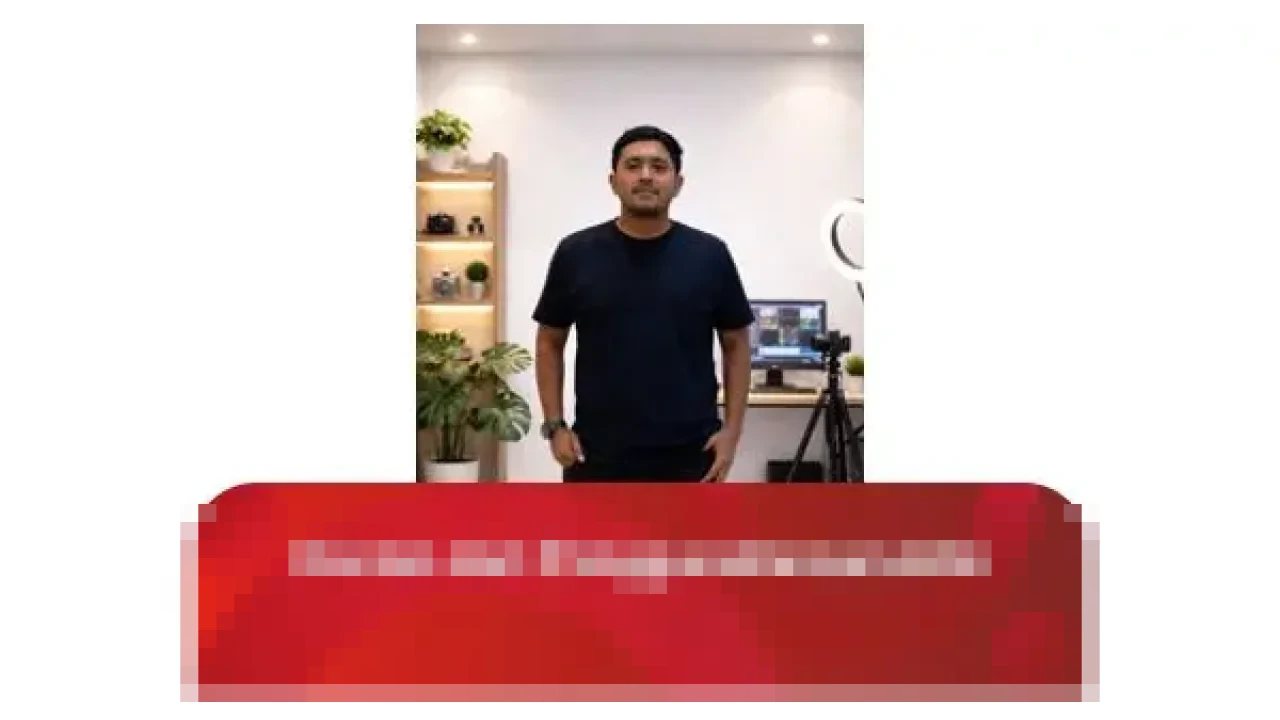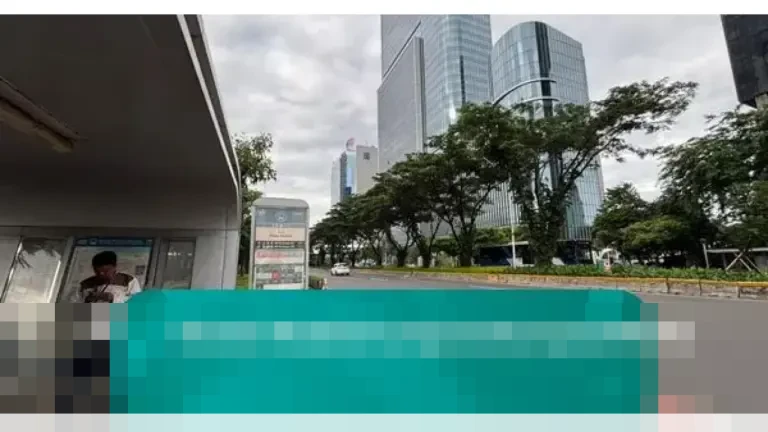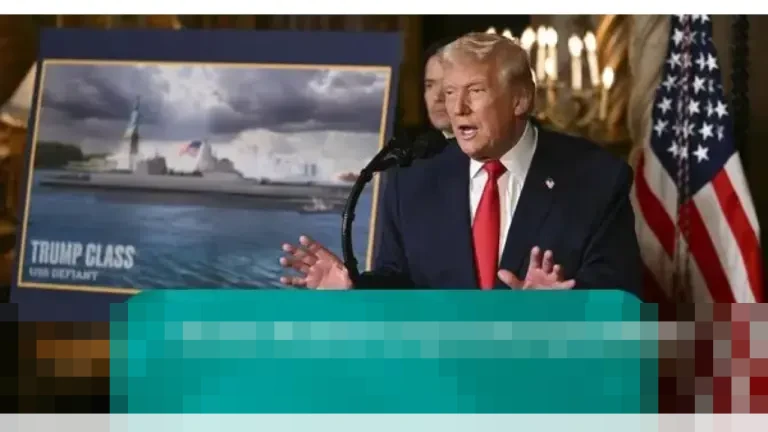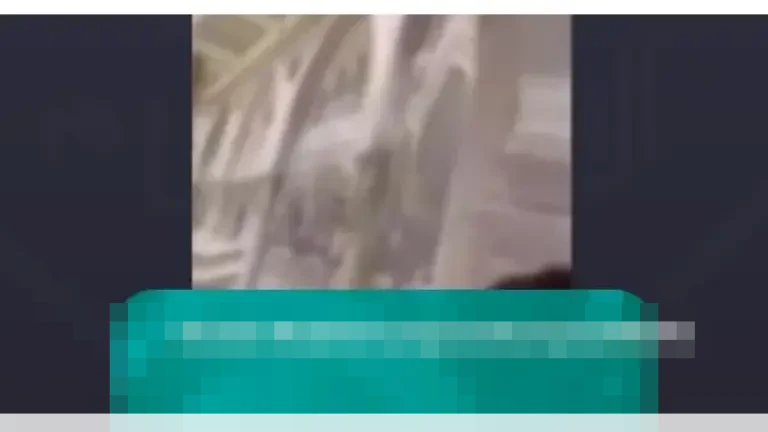Di tengah guyuran hujan subuh yang tak henti dan kegelapan akibat listrik padam, Syamaun, 50 tahun, dengan perlahan menuliskan surat kepada Tuhan. Setiap goresan pena seolah ingin memastikan Sang Pencipta memahami getaran kalimat yang ia titipkan, diiringi firasat buruk yang mulai mengendap seperti lumpur di dasar Sungai Ngop.
Dalam keyakinannya, yang juga dipegang erat oleh warga sekampungnya, hujan adalah salah satu waktu terbaik untuk berdoa. Namun, malam itu, hujan datang tanpa membawa keindahan, justru memicu kegelisahan yang mendalam.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Begitu suratnya selesai ditulis, lampu tiba-tiba padam, menyisakan gelap gulita. Maun meraba-raba dinding, mencari penerang. Di sudut dapur, ia menemukan korek api dan sebuah senter kecil. Kedua benda sederhana itu menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang menelan kampungnya. Di luar, suara hujan menghantam seng rumah seperti kerikil-kerikil kecil yang dilempar dengan amarah.
Dengan cahaya seadanya, Maun mengambil air wudu. Adzan subuh seharusnya sudah berkumandang, tetapi malam itu banyak kemungkinan terjadi: apakah suara muazin kalah oleh gemuruh hujan, atau mungkin muazin sedang membereskan surau yang mulai kebanjiran. Air mulai merembes ke kamar mandi rumahnya.
Maun melihat keluar dari balik jendela kayu. Kampungnya tak seperti biasanya. Biasanya, akan ada satu-dua motor melintas menjelang subuh dan selalu ada warga berjalan menuju surau. Namun pagi itu, seluruh pintu rumah tertutup rapat. Jalanan sepi. Kampung yang dihuni ratusan jiwa itu terasa seperti telah mati.
Hujan terus mengguyur tanpa ampun. Maun yakin beberapa rumah di dekat Sungai Ngop sudah tenggelam. Daerah itu memang langganan banjir, hanya saja kali ini firasatnya lebih gelap dari biasanya.
Beberapa tahun terakhir, pembalakan besar-besaran telah terjadi di hutan Gunung Goh. Perizinan disebut-sebut keluar melalui ‘bawah meja’ para pejabat daerah. Informasi ini baru diketahui Syamaun dari koran yang ia baca beberapa hari sebelumnya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahkan mengutuk keras para pejabat tersebut karena dinilai telah diam-diam mengeluarkan izin pembalakan liar.
Air sudah menutup bagian bawah pintu rumahnya. Ia mengurungkan niatnya untuk salat, khawatir hujan akan menenggelamkan rumahnya. Ia disergap ketakutan. Doa-doa liar berhamburan dari kepalanya.
Di pagi yang masih gelap itu, air hujan datang membawa lumpur, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Air juga membawa kayu-kayu besar berlabel kementerian kehutanan, tercabut entah dari hutan mana, terpotong rapi oleh senso manusia. Air Sungai Ngop meluap. Gelombangnya membawa batang-batang kayu yang menghantam rumah-rumah warga seperti amukan raksasa buta.
Maun berlari tergopoh-gopoh keluar rumah hanya dengan kain sarung kotak-kotak, kaki telanjang, sembari gemetar. Ia terus berdzikir sepanjang hari, air wudhunya masih tersisa. Ia menumpang keselamatan di lantai dua surau, bersama beberapa warga termasuk Pak Kades Samsul, yang akrab disapa Keuchik Son. Dari tempat itu, Maun dan sedikit warga di sana menyaksikan kampungnya luluh lantak.
Teriakan minta tolong terdengar, tetapi tak jelas dari mana. Degup jantungnya seperti dipukul dari dalam. Rumah-rumah saling bertumpukan. Mobil-mobil hanyut. Lembu-lembu mati mengapung dalam lumpur. Maun merasa seolah kiamat telah datang, meski matahari belum terbit dari barat.
Ia salat subuh terlambat. Di lantai dua surau, ia menunaikan salat subuhnya. Di rakaat kedua, saat membaca qunut, ia menangis tersedu-sedu. Maun hidup sebatang kara setelah istrinya meninggal dunia dua tahun lalu. Dia tak memiliki anak dan hidup sendirian. Yang ia takutkan kini hanya kehilangan saudara-saudara dan teman-temannya.
Di tengah isak tangis, ia teringat tiga surat yang ia lipat rapi di saku bajunya. Perlahan, ia membuka satu per satu.
Surat Pertama untuk Tuhan
“Tuhan, pagi ini, saat masih gelap, ada ketakutan yang memenuhi seluruh tubuhku. Pagi ini aku tak melihat jamaah datang ke surau. Azan pun tak terdengar, dikalahkan oleh amukan hujan. Kampungku seperti tak bernyawa…”
Tubuh Maun melemas. Air matanya mengalir tanpa ia cegah. Ia membuka surat kedua dengan tangan gemetar.
Surat Kedua untuk Tuhan
“Tuhan, selamatkan orang-orang yang kusayang. Sanak saudara yang selama ini membantuku. Jangan biarkan mereka hanyut oleh banjir yang bukan salah mereka. Mereka yang serakahlah yang layak dihantam arus itu. Mereka yang menebang hutan, yang mengaku itu demi kemajuan. Mereka yang menertawakan kami saat kami melarang penebangan liar. Kemajuan untuk siapa, Tuhan? Bukankah hidup kami yang semakin menderita? Bukankah mereka wakil kami? Mengapa mereka tak pernah mendengar kami? Mereka lupa janji-janjinya.”
Keuchik Son, kepala desa setempat, menepuk pundaknya. “Sabar, Un. Kita hanya hamba. Semua akan kembali kepada-Nya,” ucapnya menenangkan.
Surat Ketiga untuk Tuhan
“Tuhan, hujan akhirnya benar-benar murka. Hutan lindung tak lagi terlindungi. Kayu-kayu sebesar raksasa menghantam rumah-rumah tak berdosa. Yang tersisa hanya kami, lumpur, kayu, dan tanah tempat kami dilahirkan. Rumah-rumah hilang, bersama cinta yang tumbuh di setiap sudutnya. Hujan bulan Desember mengerikan. Kami mulai takut pada hujan. Bukan berarti kami membencinya. Kami hanya merindukan matahari, hingga kami pulih dari ketakutan ini. Untuk saat ini, kami benar-benar memohon, Tuhan: Kami kalah. Kami menyerah.”
Setelah membaca surat terakhir, Maun menunduk lama. Ia menangis sesenggukan. Hujan mereda, menyisakan lumpur dan gelondongan kayu. Kampung berubah menjadi hamparan puing.
Saat turun dari surau, Maun melihat orang-orang berjalan gontai dengan tubuh dilumuri lumpur. Kampung itu bak negeri zombi. “Maun! Syamaun!” seseorang berteriak dari jauh. “Kampung kita hilang. Orang-orang hilang. Banyak yang mati!”
Maun terduduk. “Ampuni kami, ya Tuhan…”
Di pengungsian, seorang ibu menggendong anaknya yang kehausan. “Belum ada bantuan yang sampai,” ucapnya lirih. Beberapa warga menyaring air lumpur untuk diminum. Pemerintah bergerak lamban. Ratusan nyawa tampak kecil bagi seorang pembunuh. Namun, satu nyawa begitu berarti bagi mereka yang saling mencintai.
Maun duduk, lemah, lapar, tak minum seharian. Namun pikirannya bukan pada dirinya, melainkan pada ibu-ibu yang kehilangan anak, dan anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Banjir tak hanya melanda kampungnya. Berita menyebar bahwa seluruh provinsi dikepung bencana, yang terparah ada di tiga provinsi: di Negeri Serambi Mekkah, di Tanah Batak, dan di Ranah Minang.
Sebentar kemudian, Keuchik Son masuk tenda di pengungsian dan memeluk Maun. “Kampung kita hilang, Un. Rumah kita hilang. Sanak saudara kita hilang. Beberapa sudah ditemukan… dalam keadaan tak bernyawa.” Maun menggigit bibir menahan tangis, tetapi air matanya jatuh juga.
Beberapa hari kemudian, bantuan tak juga datang. Gubernur setempat berkata, “Banyak warga saya yang meninggal bukan karena banjir, tapi karena kelaparan. Ini bencana terparah yang melanda bumi Serambi Mekkah setelah tsunami 2004.”
Di luar tenda pengungsian, warga menengadah ke langit. “Ya Tuhan, tolong sampaikan kepada pemimpin kami, jika mereka tak membawa kami bantuan, kirimkan kain kafan. Biar kami mati dengan terhormat.”
Setelah semua yang terjadi, Syamaun menyadari satu hal: benda-benda di muka bumi ini tak pernah punya niat jahat. Manusia-manusia serakah lah yang menciptakan kejahatan itu. Hujan tak menciptakan banjir, melainkan tangan-tangan manusia yang merusak alam. Lumpur dan gelondongan kayu yang kini berserakan akan menjadi saksi bisu di hadapan Tuhan.