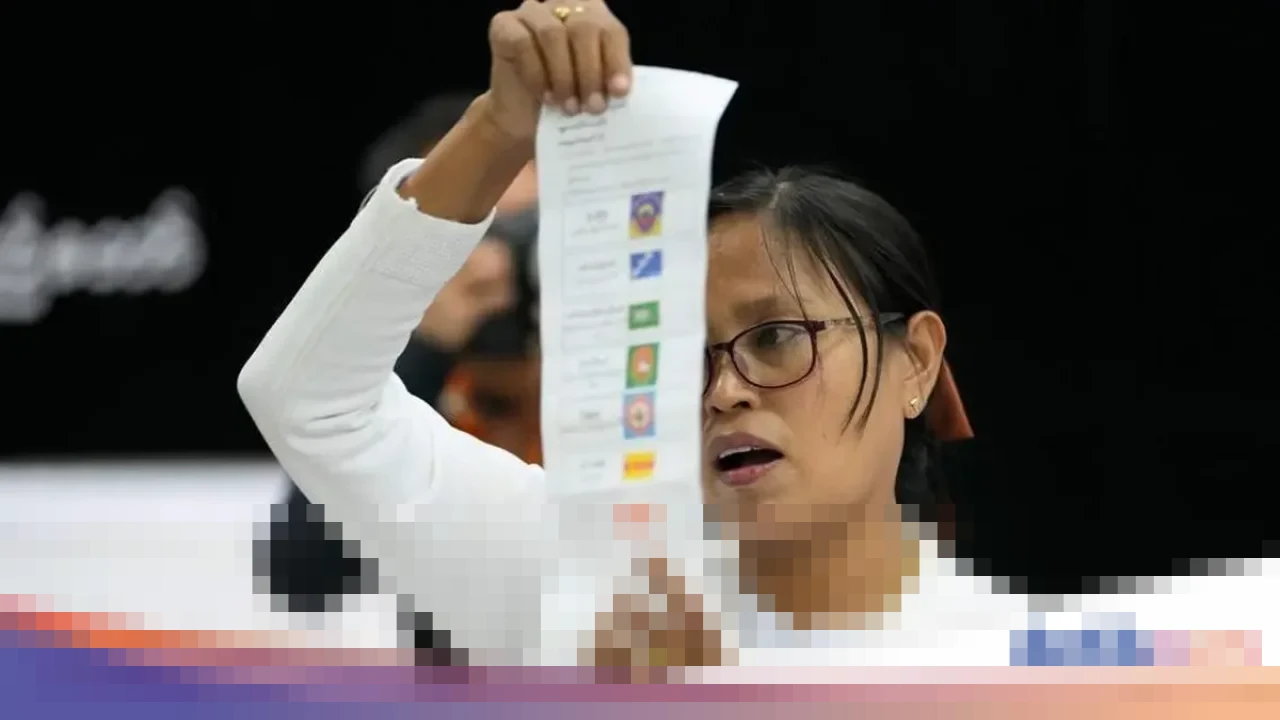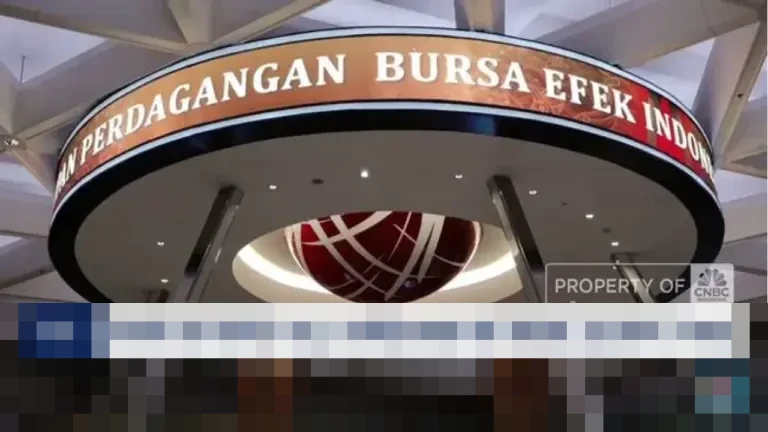Partai pendukung militer di Myanmar dikabarkan telah meraih mayoritas suara dalam putaran pertama pemilihan umum yang diselenggarakan oleh junta. Namun, pemilu ini menuai kecaman internasional dan disebut sebagai upaya militer untuk mengukuhkan kekuasaan di tengah perang saudara yang berkecamuk.
Kantor berita AFP melaporkan perolehan suara tersebut pada Senin (29/12), mengutip seorang sumber. Meskipun junta mengklaim pemilu ini sebagai kemajuan penting, sekitar separuh wilayah di Myanmar tidak dapat berpartisipasi akibat konflik bersenjata yang terus memburuk sejak kudeta 2021.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Partisipasi Rendah dan Kekhawatiran Warga
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di pusat-pusat perkotaan utama Myanmar dibuka pada Minggu (28/12). Namun, tingkat partisipasi pemilih dilaporkan jauh lebih rendah dibandingkan pemilu bersejarah pada 2015 dan 2020. Suasana jalanan juga sepi, berbeda dengan antrean panjang pemilih di pagi hari pada pemilihan sebelumnya.
Seorang perempuan muda di Yangon menolak berkomentar kepada tim DW setelah keluar dari bilik suara. “Maaf, saya tidak ingin berkomentar,” ujarnya. Perasaan hati-hati ini sangat terasa di kalangan anak muda sepanjang hari pertama pemilu.
Pemungutan suara direncanakan berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama telah selesai pada 28 Desember, sementara tahap kedua dan ketiga dijadwalkan pada 11 Januari dan 25 Januari 2026.
Beberapa minggu menjelang pemilihan, sejumlah anak muda mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang dampak jika tidak memilih. “Kami khawatir tentang dampak dari tidak memilih. Apakah ini akan mencegah kami meninggalkan negara atau apakah akan ada pemeriksaan bukti pemilihan di bandara?” kata seorang pria berusia 30 tahun dari Yangon yang meminta namanya tidak disebutkan.
TPS di kota-kota besar justru mengalami peningkatan jumlah pemilih lanjut usia. Perubahan ini berkaitan dengan banyaknya anak muda yang pergi dari Myanmar, sebuah tren yang meningkat akibat penindasan pascakudeta dan pemberlakuan wajib militer oleh junta sejak 2024.
Seorang perempuan berusia 37 tahun, yang juga memilih untuk tidak menyebutkan namanya karena alasan keamanan, memberikan suaranya bersama anaknya. Kepada DW, ia mengungkapkan kelelahan terhadap situasi saat ini. “Saya memilih, hanya untuk berharap ada perubahan setelah pemilu,” ujarnya, menolak berkomentar lebih lanjut.
Kecaman Internasional dan Pemilu “Palsu”
Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan sejumlah negara Barat lainnya telah menolak pemilihan ini, menganggapnya sebagai pemilu “palsu” yang hanya menguntungkan para jenderal militer dan memperparah nasib Myanmar.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam KTT ASEAN pada akhir Oktober 2025 menegaskan, “Sangat jelas bahwa dalam keadaan konflik saat ini dan mengingat catatan hak asasi manusia junta militer… bahwa kondisi untuk pemilihan bebas dan adil tidak ada.”
Setelah kudeta 2021, pemimpin de facto pemerintah demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, ditahan dan dipenjara bersama para pemimpin sipil terpilih lainnya. Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), juga telah dilarang.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPB), sejak 2021, lebih dari 7.630 warga sipil tewas akibat tindakan pasukan keamanan. Selain itu, AAPB melaporkan sekitar 30.000 orang saat ini ditahan dengan tuduhan kasus politik.
Ejaz Min Khant, seorang pakar hak asasi manusia di Fortify Rights, sebuah kelompok hak asasi regional, menyatakan kepada DW, “Agar pemilu dapat dipercaya, para pemimpin oposisi dan anggota parlemen harus dibebaskan dan diizinkan untuk berpartisipasi.” Ia menambahkan, “Sebuah pemilu yang dijalankan secara eksklusif oleh militer tanpa pihak oposisi utama adalah pemilu palsu.”
Selain tidak adanya oposisi, pemungutan suara juga tidak dilakukan di wilayah yang berada di luar kendali militer. Komisi Pemilihan Umum (UEC) yang ditunjuk junta bahkan menambah daftar panjang wilayah yang dikecualikan, dengan sembilan daerah baru ditambahkan sehari sebelum tahap pertama, sehingga total 65 daerah tanpa hak pilih.
Ambisi Min Aung Hlaing dan Klaim “Kemajuan Demokrasi”
Setelah memberikan suaranya di TPS Naypyitaw, pemimpin junta Min Aung Hlaing meyakinkan wartawan bahwa pemilu akan berlangsung bebas dan adil. Namun, seorang pengacara di Yangon yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada DW bahwa masalahnya “bukan sekadar pemilu yang adil atau siapa penyelenggaranya, entah itu militer atau pihak lain.”
“Yang terpenting adalah orang-orang ingin melihat perubahan sekarang, bukan hanya membiarkan keadaan ini terus berlarut-larut dalam keadaan kolaps,” kata pengacara tersebut.
Meskipun beberapa pengamat berharap junta akan melonggarkan pembatasan, banyak yang percaya bahwa pelonggaran hanya akan sedikit dan bertujuan untuk menguntungkan rezim demi mendapatkan keterlibatan dan legitimasi internasional yang lebih besar.
Di luar tempat pemungutan suara, Min Aung Hlaing tampak berusaha meredam ambisi kepresidenannya. “Saya adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan seorang pegawai negeri. Saya tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa saya ingin melakukan hal ini atau itu. Saya bukan pemimpin partai politik,” ungkapnya, menambahkan bahwa potensi kepresidenannya hanya dapat dibahas setelah parlemen menetapkan proses pemilihan presiden.
Media dan pendukung pro-junta mempromosikan pemilu ini sebagai keberhasilan, menampilkan dokumentasi warga yang memberikan suara. Namun, media independen seperti Mizzima News dan Myanmar Now melaporkan adanya tekanan terhadap pegawai pemerintah, personel militer, dan keluarga mereka untuk memilih, serta diminta membuktikan partisipasi.
Pekan lalu, kepala junta memperingatkan bahwa tidak memilih berarti menolak “kemajuan menuju demokrasi.” Di tengah upaya junta untuk terus menjalankan pemilu, konflik di lapangan terus memburuk, dengan militer berusaha merebut kembali wilayah yang hilang dan memaksa kelompok oposisi untuk menyerah.