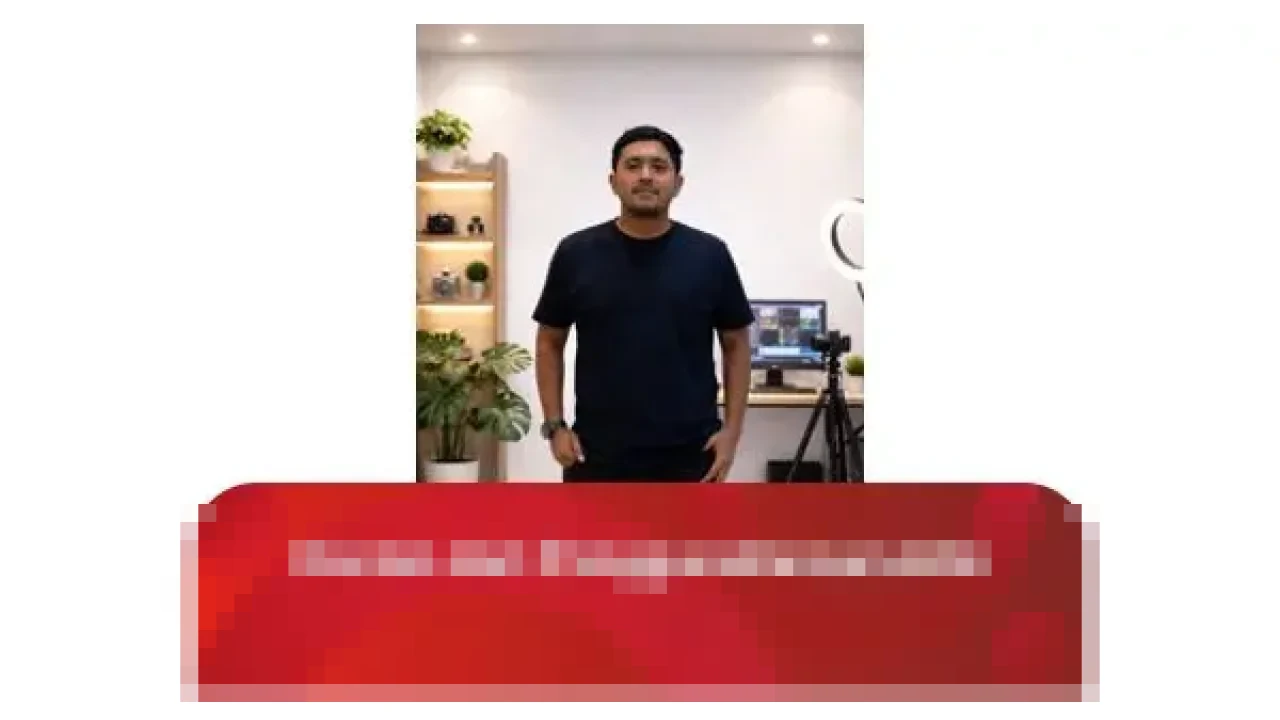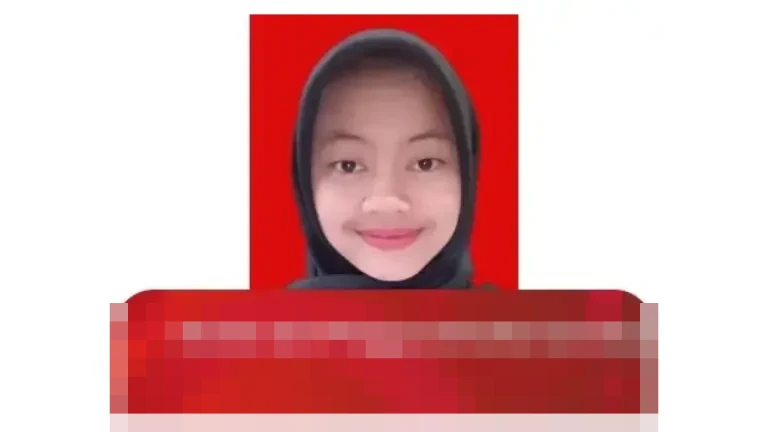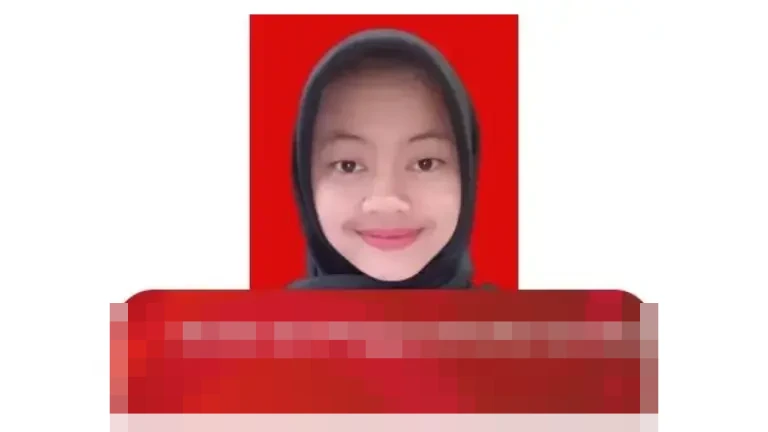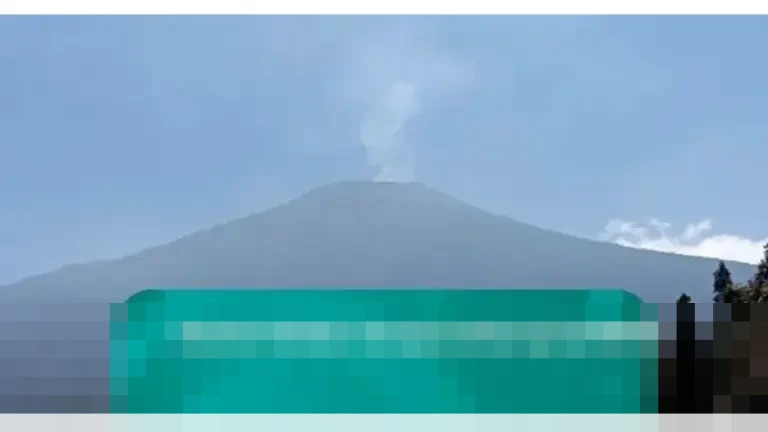Sabtu, 03 Januari 2026, sore itu, Soleh, seorang sopir travel L300, masih setia menanti penumpang di simpang empat ibu kota provinsi. Sudah hampir tiga jam ia mengibas-ngibaskan tangan, berharap ada satu saja penumpang yang mau menuju Kuta Batu. “Setidaknya ada satu penumpang saja untuk ongkos minyak, mobil ini akan langsung berangkat,” gumamnya, bersandar di mobil tua miliknya.
Tak lama, seorang pria muda dengan tas lusuh muncul dari ujung simpang. Mata Soleh langsung awas, sigap menawarkan tumpangan. “Kuta Batu, dik?” panggilnya. Pria itu berhenti, menatap ragu. “Maaf, Pak. Saya nggak punya uang. Di kantong cuma ada dua puluh delapan ribu. Itu pun pemberian teman di penjara.”
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Kata ‘penjara’ membuat kumis Soleh sedikit bergetar, jantungnya berdegup lebih kencang. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Nismuh, menjelaskan bahwa ia baru saja bebas dan ingin pulang ke kampung halamannya, Kuta Simpang, di Ujung Tapak, dekat jembatan balai. Sebuah isu tak mengenakkan telah sampai padanya: kampungnya tenggelam karena banjir.
Soleh terkejut. Ia tahu betul dari berita yang beredar, Kuta Simpang termasuk wilayah terparah dilanda banjir. “Terus… bagaimana kabar mereka sekarang?” tanyanya prihatin. “Saya belum dapat kabar mereka, Pak. Saya hanya berharap anak dan istri saya selamat. Saya rindu mereka,” suara Nismuh bergetar, mengusap matanya.
Melihat keputusasaan di mata Nismuh, hati Soleh tergerak. “Tenang anak muda. Insya Allah anak dan istrimu baik-baik disana. Kalau begitu naiklah, aku akan mengantarmu ke kampung halaman,” kata Soleh seraya tersenyum kecil. Tanpa pikir panjang, ia menekan pedal gas, tak lagi menunggu penumpang lain. Kemanusiaan baginya lebih penting dari segalanya.
“Nama saya Soleh bin Spono,” ia memperkenalkan diri. “Kalau adik sendiri siapa namanya?” Nismuh menjawab, “Baik Pak Soleh. Nama saya Nismuh.” Soleh tertawa kecil, “Jangan panggil pak, panggil bang saja. Gini-gini saya masih muda. Rambut saja yang putih, faktor kebanyakan mikir. Aslinya saya masih berumur nggak lebih 50 nggak kurang 40.”
Nismuh sempat menawarkan uang dua puluh delapan ribu miliknya, namun Soleh menolak. “Tak usah anak muda. Nanti kau bisa pakai uang itu untuk keperluan lain,” jawab Soleh cepat, matanya berkaca-kaca.
Perjalanan Penuh Dering Telepon dan Pengakuan Mengejutkan
Perjalanan satu jam pertama dipenuhi dering telepon yang membuat Soleh kesal dan lelah. Dari agen, rumah, hingga loket, semua menuntut perhatiannya. “Ah kau ini, kenapa baru kau bilang sekarang, aku sudah di jalan pegunungan ini. Kau kasih ke mobil lain saja, aku buru-buru ini,” bentaknya pada agen. Kepada anaknya, ia berpesan, “Halo, Nak. Apa? Mati lampu? Ya sudah malam ini kamu ngaji di rumah saja. Bilang sama mamak, ayah agak telat pulang. Karena harus mengantar penumpang ke Kuta Simpang.”
Setelah menutup telepon, Soleh menghela napas. “Maaf dik, beginilah kerja sopir lintas, dik.” Mobil terus melaju, kali ini sedikit lebih lambat. Beberapa saat kemudian, Soleh teringat sesuatu. Lututnya sedikit bergetar. “Maaf ya, dik. Kalau boleh tahu… kasus apa sampai masuk penjara?” tanyanya, melirik kaca spion tengah.
Tatapannya bertemu dengan rambut awut-awutan dan jenggot lebat Nismuh. Matanya merah, wajahnya kusut, penuh letih. Nismuh menjawab dengan tenang, “Tenang bang Soleh. Sepanjang jalan tadi, beberapa orang juga menanyakan hal yang sama. Saat saya bilang baru keluar penjara, mereka semua berubah jadi takut pada saya.”
Kemudian, dengan suara dikeraskan melawan deras angin sore karena kaca mobil terbuka, Nismuh mengaku, “SAYA MASUK PENJARA karena kasus kurir narkoba. Saya dijebak. Dua tahun setengah vonisnya, tapi saya jalani dua tahun tiga bulan.”
Soleh mengangguk, tetap mendengar. “Kenapa demikian?” timpalnya. Nismuh menjelaskan, “Saya juga menanyakan hal yang sama kepada Kepala Lapas. Kepala lapas bilang saya dibebaskan lebih cepat karena beliau sering lihat saya menangis. Teman-teman satu sel juga bantu. Uang dua puluh delapan ribu itu dari mereka.” Soleh mengangguk-angguk keras, merasa dadanya longgar. Ia tahu, wajah seperti itu tak pandai berbohong. Sebagai sopir travel puluhan tahun, Soleh merasa mudah menilai orang.
“Adik berdoa saja, agar keluarga diberikan keselamatan. Kalau adik ingin istirahat, silahkan tarik kursi itu agak ke belakang,” kata Soleh.
Kemanusiaan di Tengah Genangan Banjir
Tiga kabupaten telah dilalui tanpa hambatan. Sore berganti malam. Setelah melewati tikungan tajam, Soleh memperlambat laju mobilnya karena lima puluh meter di depannya ada genangan air setinggi lutut. Tiba-tiba Nismuh membuka pintu mobil. Soleh hendak mencegatnya, namun pandangannya tertuju pada seorang perempuan renta bertubuh bungkuk yang berdiri di tepi jalan, kebingungan antara menyeberang atau tetap di tempat. Arus sungai tak jauh dari sana cukup deras dan berbahaya.
Banyak orang di tepi jalan hanya menatapi nenek itu, tak ada yang memberi bantuan. Nismuh datang, memberi isyarat kepada pengemudi lain untuk memperlambat laju. Tanpa ragu, ia menolong nenek itu menyeberang, membawanya ke tempat yang lebih tinggi, dekat masjid.
Setelah kembali ke mobil, Soleh berkata, “Gila kamu dik, salut saya sama kamu, tak pantas orang seperti kamu berada di penjara. Negara ini memang kacau masalah hukum. Ibarat kata, pisau di atas, alah lupa saya.” Nismuh membenarkan, “Tumpul ke atas tajam ke bawah bang.” Soleh menimpali, “Nah, itu maksud saya.”
Mobil kembali melaju, menerobos genangan air. Pengalaman mobil tua milik Soleh berhasil melalui rintangan itu. Hujan masih terus mengguyur, angin malam bertiup kencang. Dalam gelap, Soleh melirik kaca spion. Nismuh terlihat kelelahan, wajahnya dipenuhi putus asa, kekecewaan, dan penuh harapan. Matanya terus berkaca-kaca, menahan tangis.
Soleh sebenarnya ingin bertanya banyak tentang hidup Nismuh, perjuangannya di penjara, keadilan, dan nasib orang kecil. Namun, ia hanya tersenyum kecil. Pertanyaannya terasa tak ada artinya, sebab Nismuh sudah lebih dulu terlelap.
Sesaat kemudian, suasana terasa lengang. Soleh menarik napas panjang, prihatin pada Nismuh, juga pada anak dan istrinya yang keberadaannya masih menjadi tanda tanya. “Bagaimana jika seandainya anak dan istrinya terbawa banjir? Bagaimana jika pria malang ini tak bisa lagi melihat senyum anak istrinya lagi,” seruan batinnya menyeruak, mengingat obrolannya dengan anaknya beberapa jam lalu.
Mata Soleh menyorot jalanan dengan tatapan tajam yang fokus, membayangkan perasaan Nismuh. Dada Soleh ikut bergemuruh, napasnya tak beraturan. Klakson sebuah truk yang hendak menyalip membangunkan Nismuh. “Sialan! Kau mau kami mati?!” bentak Soleh dari dalam mobilnya. “Kenapa, Bang?!” tanya Nismuh, membuat Soleh tersadar telah mengganggu tidurnya. “Nggak apa-apa dik, mobil besar itu main serobot saja.”
Titik Terang di Kuta Simpang
Soleh melirik arloji di lengan kirinya, masih tersisa empat jam lagi untuk sampai ke tujuan. Mobil sudah mulai memasuki kawasan bencana, akan melewati tiga titik lokasi banjir sebelum tiba di Kuta Simpang. Selama perjalanan di kawasan bencana itu, Nismuh mulai banyak diam. Pandangannya tertuju pada kondisi pemukiman warga di kiri dan kanan jalan nasional yang dihantam banjir bandang.
Di sela itu, Nismuh sempat bercerita bahwa ia menikah dengan istrinya tahun 2021 pasca korona, teman satu kelas saat SMA. Setahun menikah, tahun 2022 mereka dikaruniai seorang putri cantik. Namun, setahun umur putrinya, nasib sial menimpanya yang membuatnya harus berakhir di dalam sel.
Sebelum memasuki kawasan Kuta Simpang, Soleh sempat berhenti di salah satu warung makan. “Nggak apa-apa, ini saya yang bayar,” ucap Soleh, membuat Nismuh kembali berterima kasih atas kebaikan sopir itu. Singkatnya, mobil telah memasuki Kuta Simpang. Suasana mencekam, lampu mati di seluruh penjuru. Soleh mengurangi laju mobil.
“Rumah adik di kecamatan apa?” tanya Soleh. “Di Ujung Tapak, sebelum jembatan, bang. Tapi nggak papa-papa turunkan saya di Masjid Jamik saja bang. Kata orang di warung makan tadi, warga Desa Ujung Tapak mengungsi di Masjid Jamik. Mudah-mudahan anak dan istri saya ada disana.”
“Oh siap adik,” sambut Soleh. Desa Ujung Tapak berada persis di samping sungai, ditempati warga miskin. Ribuan lahan sawit ditanam di sana, namun menurut Mureks, hanya sepuluh persen warga yang menikmati hasilnya, selebihnya oligarki. Jika musim hujan tiba, air pasti naik ke rumah warga. Kali ini, untuk pertama kalinya banjir terparah terjadi, menenggelamkan apa yang ada.
Soleh tak sanggup lagi melirik kaca spion mobilnya, sebab tak sanggup mendapati wajah Nismuh yang menahan air mata. “Agak cepat, Bang,” pinta Nismuh ketika mereka mendekati jalan masuk ke Desa Ujung Tapak. “Saya mau mencari anak dan istri saya.”
Soleh menekan pedal gas sedikit lebih keras, menerbangkan lumpur di bagian belakang ban mobilnya. “Bang Soleh, bagaimana cara abang pulang, sementara kota abang sudah lewat.” Nismuh bertanya. “Tak usah adik pikirin saya, saya hanya berdoa anak dan istrimu ada di pengungsian.” “Aamiin bang,” sambut Nismuh cepat-cepat.
“Terima kasih, Bang. Tidak usah masuk, disini saja, nanti mobil abang susah keluar. Hanya Allah yang akan membalas kebaikan abang.” Ucapan Nismuh di pintu gerbang masuk Masjid Jamik tak digubris oleh Soleh. Ia ingin berbuat baik kepada penumpangnya yang malang itu. Ternyata Soleh tak sanggup membendung air matanya yang sengaja ia tutupi sepanjang jalan, dan tetap berusaha menghibur penumpangnya itu.
Nismuh mulai berjalan tertatih-tatih memasuki pekarangan Masjid Jamik. Tapi siapa sangka, seorang perempuan dan seorang anak kecil berlari ke arahnya. Nismuh membuka lebar tangannya, memeluk kedua perempuan yang sangat ia cintai. Tangisnya pun pecah. Dia meraba-raba pipi anak dan istrinya, mencium mereka.
Di ujung jalan, Soleh menyaksikan semuanya. Air matanya jatuh. Dia menangis tersedu, merindukan anak dan istrinya di rumah. Lalu, dia memutar setir mobil, membunyikan klakson. Nismuh, istri dan anaknya melambai tangan ke arahnya. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya, Soleh merasa benar-benar berguna sebagai manusia.